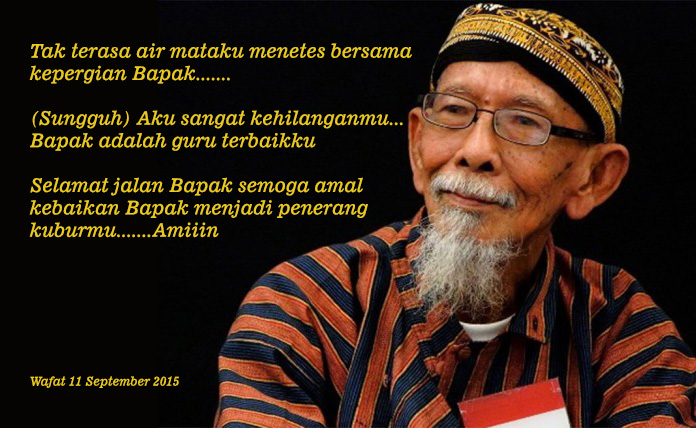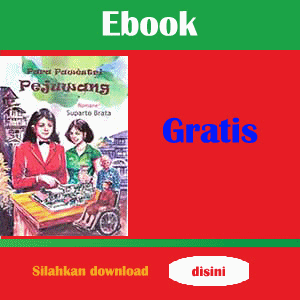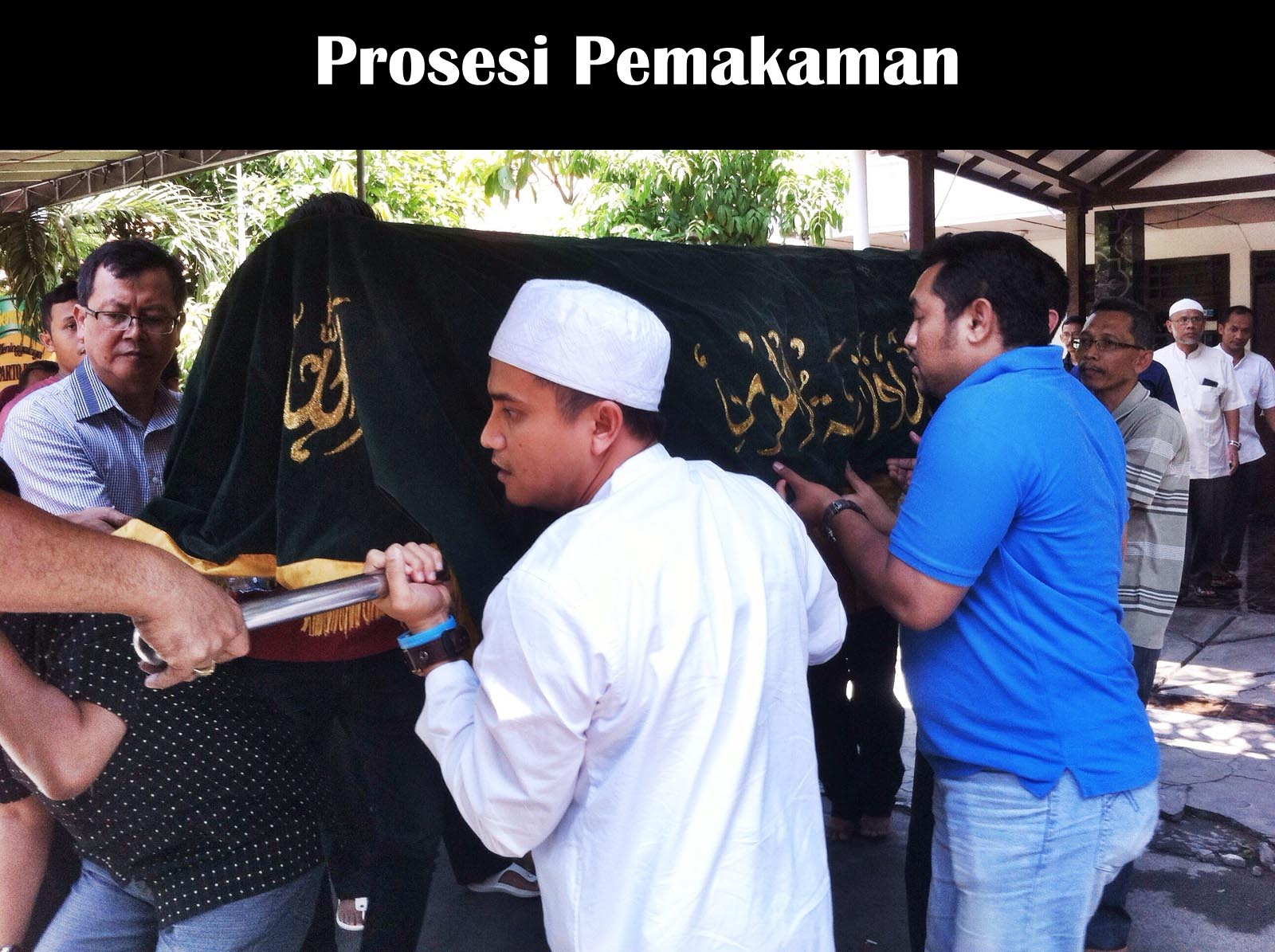CITRA WANITA JAWA
CITRA WANITA JAWA
DALAM NOVEL DONYANE WONG CULIKA
Karya Suparto Brata
Judul buku: DONYANE WONG CULIKA (novel bahasa Jawa, 538 halaman), karya Suparto Brata, Penerbit: NARASI Jl. Jawa D-10 Perum Nogotirto II Yogyakarta 55292, Telp: (0274)620879, (0274)625743, Fax. (0274)625743; cetakan I 2004.
*
Teks sampul belakang luar: Iki crita Jawa. Critane wong Jawa, cara Jawa, rasa Jawa, pikiran Jawa, ing Tanah Jawa Abad 20. Iki critane wong Jawa ing desa, ing sawah, ing kutha, ing omah kampung, ing loji, ing hotel, ing guest-house, ing kraton. Iki crita panguripane Sabar, kusir dhokar, Wongsotukiran sing gugontuhonen, Nini Sali randha tuwa tanpa keluwarga, Barman si bakul klapa, Painem bocah kuru ngeyeyet cacingen, Dalimin sing setya tuhu marang bendarane, Kariya Mentes sing sambene ngobong bata, Den Darmin kang idealis, Ki Pratignya dhalang wayang, Ndara Kanjeng Jodi wong ningrat kang ngoyak-oyak katresnan, Jumilah prawan desa kang Gerwani, Sangkarku niyaga seniman Lekra, Ndrajeng Manik putri kraton, Ndara Jemba putri tanpa bapa, Sastra Kentrung sing wis wuta, Nyi Lurah Badrakirana waranggana kraton, Santinet bakul jarit kriditan, Bonet si mahasiswa. Lan akeh maneh. Iki critane wong Jawa jaman Landa, jaman perjuwangan nglawan Landa, jaman Yogyakarta Ibu Kota RI, jaman Nasakom, lan jaman Orde Anyar. Iki critane wong Jawa, pakulinane, watake, rasa-rumangsane, pikirane, pakartine, solah-bawane, pakaryane, sandhang-pangane, budayane, agamane, jamane, negarane, sejarahe, bumine, kahanan alame, nasibe, jantra uripe lan mbokmenawa ramalane. Crita iki diracik nganggo basa Jawa ngoko, basa sastra sing standar nalika jamane crita rerekan iki dumadi..
Andaikata kita menyusun sebuah antologi Sastra Nusantara Klasik, kita muat tulisan-tulisan Hamzah Fansuri, Hasan Mustapa, Ranggawarsita dan penulis-penulis lain yang klasik. Tetapi kalau kita menyusun antologi Sastra
*
Sayang sekali, buku-buku bahasa Jawa karya Suparto Brata, termasuk Donyane Wong Culika, tidak diizinkan diterjemahkan dalam bahasa
*
Email Arpeni Rahmawati, mahasiswi FBS UNY
*
Komentar Drs. Tito S. Budy (Pemimpin Umum Majalah GENTA, Sragen): Bagi saya buku bermutu atau tidak, bisa dilihat kalau diterjemahkan dalam bahasa asingnya (bukan bahasa aseli buku itu). Kalau dalam buku terjemahannya laris populer, maka buku tadi berkualitas sebagai bacaan dunia. Buku-buku karangan Herry Porter, Karl May, Karen Armstrong, Ahmad Tohari, laris populer dalam buku terjemahannya bukan bahasa aselinya, maka saya nilai itu buku yang berkualitas. Begitu pula buku sastra Jawa. Kalau buku sastra Jawa yang diterjemahkan dalam bahasa lain (jadi buku) mampu bersaing (terbaca laris) dengan buku-buku bahasa Indonesia atau asing, maka buku sastra Jawa tadi memang berkualitas. Karya-karya Suparto Brata, terutama Donyane Wong Culika (menurut pengarangnya arti judul itu Negerinya Orang Curang), saya yakin mampu menjadi bacaan sastra dunia kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya). Kalau pun sekarang belum ada orang asing yang berminat menterjemahkannya dalam bahasa mereka, (DWC sudah beredar di Belanda, Australia, Amerika, Prancis, Jerman), untuk menduniakan DWC seyogyanya ada dari pihak penggemar sastra Jawa menjadikan DWC obyek studi terjemahan ke bahasa asing, entah itu dilakukan oleh pihak pribadi, swasta, instansi pendidikan bahasa asing, atau bahkan pemerintah Indonesia. DWC dalam bahasa asing bukan saja pustaka berbahasa asing itu, melainkan cerita karakter dan sejarah orang Jawa sejak zaman Kraton Surakarta sampai zaman Orde Baru dipandang dari berbagai aspek kehidupan (dan kejujuran seorang pengarang) tapi bukan buku antropologi, melainkan dikemas dalam bentuk novel, sehingga pembacanya tidak terbatas pada para akademisi saja, juga terbaca oleh umum mulai dari kanak-kanak sampai ke kakek-nenek. Buku Donyane Wong Culika (Negerinya Orang Curang) perlu dipromosikan jadi khasanah pustaka dunia. (diceritakan 8 November 2008 dalam perjalanan ke Rutan Wonogiri).
*
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna melengkapi gelar Sarjana Sastra Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
CITRA WANITA JAWA DALAM NOVEL
‘DONYANE WONG CULIKA’
KARYA SUPARTO BRATA
(Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra)
Skripsi tersebut telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret pada tanggal 10 Januari 2008.
Pada skripsi itu Citra Wanita Jawa yang diulas terdapat pada (BAB IV, PEMBAHASAN, huruf C. Analisis Sosiologi Sastra), penguraian penelitian tentang:
1. Perwujudan Perjuangan Wanita dalam Novel DWC,
2. Perwujudan Citra Wanita dalam Novel DWC, yang diperinci lagi menjadi
a. Citra Wanita dalam Keluarga,
b. Citra Wanita dalam Masyarakat,
c. Citra Wanita yang Lemah terhadap Nafsu Birai sebagai
Sifat Turun-menurun. (huruf vet dari penulis).
Sesuai dengan judul, tulisan ini akan mengutip beberapa uraian contoh penelitian dalam skripsi tersebut serba sedikit, utamanya pasal Citra Wanita dalam Keluarga, Citra Wanita dalam Masyarakat, Citra Wanita yang Lemah terhadap Nafsu Birahi sebagai Sifat Turun-menurun untuk memberi gambaran CITRA WANITA JAWA DALAM NOVEL ‘DONYANE WONG CULIKA’, setidaknya menurut penelitian ilmiah yang diajukan dalam skripsi yang telah teruji. Dalam kutipan juga ditambahkan catatan penulis agar masalahnya menjadi lebih jelas. Kata tambahan ditulis dalam kurung, diakhiri dengan pen. (….. pen).
Selain itu juga akan dikutipkan serba sedikit dari: Amanat, yang dipetik dari BAB IV huruf B. Analisis Struktural Novel DWC, dan seperti yang diamanatkan dalam skripsi ini dikutipkan juga BAB V PENUTUP, A. Kesimpulan dan B. Saran, agar hasil penelitian ini juga diapresiasi sebagai ilmu kesastraan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan mendunia.
*
PERWUJUDAN CITRA WANITA DALAN NOVEL DONYANE WONG CULIKA
Gambaran mengenai citra wanita Jawa yang terungkap dalam novel DWC meliputi peran-peran yang disandangnya dalam keluarga, peran dalam masyarakat dan gambaran wanita-wanita yang lemah dalam menguasai nafsu birahi sebagai sifat turun-menurun. (Skripsi. h.187).
c. Citra Wanita dalam Keluarga.
Wanita memiliki kodrat sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak-anaknya sebagai generasi penerus, sehingga dapat disebutkan bahwa tidak mungkin akan hadir generasi penerus tanpa kehadiran seorang ibu. Madusari adalah seorang ibu yang memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya, yakni Pratinah. Ia adalah pembuka jalan bagi pendidikan hidup yang mendasar. Melalui seorang ibu, anak-anak akan belajar sopan santun lebih banyak sebelum menuju tatanan hidup yang lebih komplek lagi. Dalam kehidupan keluarga di Jawa biasanya anak-anak sejak sebelum lahir sampai umur remaja akan lebih dekat dengan ibu. Peran orang tua sangat penting sekali dalam mendidik anak sejak dini. Dalam novel DWC karya Suparto Brata dikisahkan bahwa Madusari sebagai seorang ibu, dia sangat menyanyangi anaknya, Pratinah. Seperti yang tergambar pada kutipan berikut: (Skripsi. h.188)
MADUSARI sebagai orang tua tidak selamanya mengikat anak, suatu saat mereka akan hidup lepas dari orang tuanya. Selama masih dalam asuhan, orang tua harus disampaikan secara langsung, namun bisa melalui cerita-cerita ataupun canda tawa lewat obrolan antara orang tua dan anak. Hal tersebut terungkap dalam kutipan berikut.
Kutipan:
Wiwit cilik, isih cilik banget, isih dadi suson, terus dadi kelon, sabanjure nganti bisa mlayu lan sekolah, Pratinah tansah diemong kanthi dipituturi, didongengi, diura-urakake dening ibune. Sadurunge krungu kabare donya panguripan, Pratinah
Terjemahan:
Dari kecil, masih kecil sekali, masih dalam susuan, kemudian dalam buaian, selanjutnya sampai bisa berlari dan sekolah, Pratinah selalu diasuh dengan dinasehati, diberi cerita, dinyanyikan oleh ibunya. Sebelum mendengar kabar dunia kehidupan, Pratinah sudah mendengar dahulu alunan suara ibunya, berita yang disampaikan ibunya, nasihat untuk bekal hidup kelak.
Madusari sebagai orangtua tidak selamanya mengikat anak, suatu saat mereka akan hidup lepas dari orangtuanya. Selama masih dalam asuhan, orangtua hendaknya selalu memberikan nasihat-nasihat mengenai kehidupan. Nasihat tidak harus disampaikan secara langsung, namun bisa melalui cerita-cerita ataupun canda tawa lewat obrolan antara orangtua dan anak. Hal tersebut terungkap dalam kutipan berikut:
Kutipan:
Pancen ora bisa ngawasi bocah sarana dicancang kaya mentas tuku pitik anyar, ben ora ilang. Kepriyea wae Pratinah mesthi kudu duwe kebebasan lunga menyang endi-endi. Minangka pengawasane, minangka tali panyancange ngawasi bocah, yakuwi ngomong. Crita. Mituturi. Mituturi nanging aja wujud mituturi langsung, aja awujud srengen. Aja! Mituturi sing awujud crita, crita guyon-guyon, crita tepa palupi. Ah, ya kaya crita ing buku kae, lo! Crita kang nyenengake ngukur pribadine bocah dadi kuthuk, nurut, miturut. Crita kuwi sing dienggo nyancang, sing dienggo ngawasi polahe bocah! (DWC, h. 303).
Terjemahan:
Memang tidak bisa mengawasi anak dengan cara diikat seperti baru saja beli ayam baru, agar tidak hilang. Bagaimanapun juga Pratinah harus mempunyai kebebasan pergi ke manapun. Sebagai pengawasannya, sebagai tali pengikatnya memantau anak, yaitu berbicara. Bercerita. Menasihati. Memberi nasihat tetapi jangan berujud menasehati langsung, jangan begitu tegang. Jangan! Memberi nasihat yang berupa cerita, cerita jenaka, bercerita suri tauladan. Ah, seperti di buku itu, lho! Cerita yang menyenangkan memahat pribadi anak menjadi dewasa, menurut, patuh. Cerita itu yang dipakai untuk mengikat, yang dipakai untuk memantau gerak-gerik anak!
Madusari berusaha menjadi sosok ibu yang baik bagi Pratinah. Sebagai seorang ibu, Madusari sangat menyayangi putri semata wayangnya dan selalu memberi pendidikan yang baik bagi Pratinah. Meskipun Madusari menyimpan masa lalu yang kelam, dia tidak ingin masa kelamnya itu diketahui oleh puterinya. Dia ingin masa lalu yang pernah ada dalam hidupnya disimpan rapat-rapat. Dalam perannya sebagai ibu dari Pratinah, Madusari tetap berada pada peran yang sesuai dengan aspek biologisnya, yaitu mengasuh, mendidik, serta memelihara anaknya.
Novel DWC juga mengungkapkan sosok wanita dalam kehidupan keluarga yang ikut berperan mengatur kehidupan rumah tangga, hal tersebut dapat diketahui dari kutipan berikut:
Kutipan:
Pujere nalar lan alur uripe keluwarga Ki Dhalang Pratig pancen ana sing wadon. Madusari kuwi sanajan tata laire luruh lan pratingkahe klebu klemak-klemek, nanging kekarepane kenceng lan akas. Sing dientha lan diranggeh dhuwur. Lan keluwargane suyut kabeh, suyut sing ngajeni (DWC, h.372)
Terjemahan:
Arah dan pemikiran kehidupan keluarga Ki Dalang Pratig memang berada pada istrinya. Madusari itu meskipun sifat lahirnya lembut dan tingkahnya halus, tetapi keinginannya kuat dan keras. Yang menjadi harapan dan cita-citanya tinggi. Dan keluarganya mendukung semua, mendukung dan menghargai.
Data tersebut menunjukkan bagaimana seorang istri ikut dan berperan aktif dalam kehidupan berumah tangga atau keluarga, bahkan terlihat Madusari tampak mendominasi gerak keluarganya. Wanita tidak hanya bekerja di belakang saja, namun dengan terbukanya ruang gerak memungkinkan untuk lebih memperlebar peran mereka dalam suatu keluarga.
b. Citra Wanita dalam Masyarakat.
1. Bidang Pendidikan.
Tokoh wanita Jawa yang berperan dalam bidang pendidikan tergambar pada diri TUKINEM (dalam novel DWC karya Suparto Brata), sebagaimana terungkap dalam kutipan berikut:
Kutipan:
Mula banjur teken ikatan dinas, mlebu sekolah guru B ing Sala. Ikatan dinas saasramane pisan. Marga Tukinem klebu bintang sekolah, nalika dibenum dadi guru dheweke wenang milih enggon. Milih bali menyang kandhange dhewe. Dadi guru ing Jenar, cedhak omahe ing Margasari (DWC, h.210).
Terjemahan:
Maka kemudian menandatangani ikutan dinas, masuk sekolah guru B di Sala. Ikatan dinas berikut asramanya sekalian. Karena Tukinem termasuk bintang sekolah, ketika diangkat menjadi guru, dirinya berhak memilih tempat. Memilih kembali ke daerahnya sendiri. Menjadi guru di Jenar, dekat rumahnya di Margasari.
Data di atas menunjukkan Tukinem telah mengabdikan diri dalam bidang pendidikan dengan menjadi seorang guru kontrak di desanya. Hal tersebut jelas telah membuktikan perannya secara aktif di bidang Pendidikan.
2. Bidang Ekonomi.
Beberapa tokoh wanita dalam novel DWC karya Suparto Brata telah menunjukkan perkembangan perannya dalam bidang ekonomi Hal ini diperlihatkan pada tokoh TUKINEM yang berkata kepada suaminya Sukardi untuk selalu berusaha agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Tukinem menegaskan bahwa semua pekerjaan hendaknya dikerjakan dahulu sebelum menginginkan hasil yang besar. Seperti pada kutipan berikut:
Kutipan:
“Apa-apa kuwi dicoba dhisik. Diawaki, ditandangi, dilakoni dhisik. Aja durung-durung
Terjemahan:
”Segala pekerjaan itu dicoba dulu. Dipahami, dikerjakan, dilakukan dahulu. Jangan sebelumnya sudah diputuskan tidak bisa berhasil dikerjakan karena tidak logis. Sudahlah, selogis-logisnya pemahaman manusia, Tuhan bisa membuat yang tidak logis menjadi kenyataan. Tuhan selalu bisa membuat keadaan, membuat yang tidak logis bagi pemahaman manusia menjadi logis, maka jangan terburu-buru memutuskan dengan cara mengedepankan pikiran manusia. Sepintar-pintarnya manusia masih pinter Tuhan. Maka apa-apa yang belum tentu itu dikerjakan dahulu, hasilnya tetap kabur atau menjadi kenyataan, baru berkatalah kamu! Katakanlah setelah kamu lakukan, kamu usahakan!” Tukinem pernah berkata seperti itu yang dicatat oleh Sukardi.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa semua hal atau pekerjaan jangan terlalu cepat diputuskan, semuanya harus dikerjakan terlebih dahulu. Hasil dan semua yang akan terjadi sudah diatur oleh Tuhan, manusia hanya berhak menjalani saja, sebab semua hasil dan kemungkinan yang menurut manusia mustahil bisa dengan mudah terjadi atas kehendak-Nya. Hal tersebut telah menunjukkan peranan wanita di sektor ekonomi, dijelaskan bahwa Tukinem mengatakan kepada Sukardi untuk selalu berusaha dan berpasrah diri kepada Tuhan. Tukinem juga menegaskan bahwa untuk tidak terlalu cepat memutuskan sebelum berusaha.
Kutipan:
Apamaneh bareng rumangsa kecukupan. Tukinem ada-ada ngedegake toko ing latar ngarep omahe wongtuwane, kahanan ekonomine Wongsotukiran sabrayat sangsaya becik. (DWC, h. 207).
Terjemahan:
Apalagi setelah merasa kecukupan. Tukinem berinisiatif mendirikan warung di halaman rumah orangtuanya, keadaan ekonomi Wongsotukiran sekeluarga semakin baik.
Kutipan di atas jelas mengungkap aktivitas Tukinem dalam hal memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi. Selanjutnya dalam novel DWC karya Suparto Brata menggambarkan sosok SANTINET sebagai wanita Jawa yang datang dari daerah, telah berperan juga dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang terungkap dalam kutipan di bawah ini:
Kutipan:
Ing Jakarta penggaweane Santinet sing pokok ngiderake barang sembet kridhitan ing kantor-kantor lan omah gedhongan.
Terjemahan:
Di Jakarta pekerjaan Santinet yang pokok menawarkan barang-sandang cara kriditan di kantor-kantor dan rumah gedongan. Sudah mempunyai pelanggan banyak, dan daerah operasionalnya sudah bisa dijadwal. Hari Senin ke daerah Kebayoran Baru. Rabu di Thamrin. Jumat di sekitar Lapangan Banteng. Begitu seterusnya.
Tokoh lain yang menunjukkan perannya di bidang ekonomi dalam novel DWC karya Suparto Brata yakni PRATINAH. Setelah perkenalannya dengan dokter yang bernama Steffy Tjia, Pratinah berusaha untuk mendekati dr. Steffy Tjia, dan pada akhirnya dia berhasil menjadi simpanan dari dokter tersebut.
Pratinah berusaha mencapai tujuan hidupnya dengan bekerja, menjual keahliannya bernyanyi dan menari rasanya cukup bagi Pratinah. Nyanyian Pratinah ternyata membawa berkah pada dirinya. Pratinah segera diajak pentas keliling kafe-kafe di Jakarta oleh Melcheor Hutubessy yang kebetulan mempunyai grup band. Dengan penghasilan yang lumayan Pratinah menjalaninya dengan senang hati. Saat itu Pratinah telah terikat kontrak dengan seorang manajer kafe, yaitu Mr. Cheng Hoo. Sejak itu Pratinah kembali berkumpul dengan kelompok musik Melcheor Hutubessy, termasuk Agnes yang pandai menari, keliling kafe dan club di Jakarta.
Kutipan:
“Eee, Pratinah kowe, ya? O, Allaaah,
Terjemahan:
“Eee, kamu Pratinah, ya? O, Allaaah, sudah kuintip dari dalam rumah, siapa kok ada nona-nona tersesat ke sini! Toblaaas, toblas-toblas! Aduuuh, mengapa rambutmu kamu sasak seperti ini, membuat aku tak tahu siapa kamu! Sini-sini-sini, Anak Cantik! Kamu memang benar-benar cantik saat ini. Caramu berpakaian itulah yang aku jadi tak kenal kamu! Sekarang apakah kamu sudah menjadi menantunya Pak Menteri? Sudah terlaksana betul sekarang kamu mengencingi Ibu Kota Negara Jakarta, ya! Jaman sudah kacau kamu masih cantik menjadi Ratu Ayu, tidak mau terluka tidak mau hidup miskin, tidak mau derajatmu turun!”
Kutipan di atas menunjukkan sikap mandiri dalam diri Pratinah. Mandiri dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi yang tidak tergantung pada orang lain. Sebagai seorang yang mandiri, wanita harus memiliki pola pikir yang dipergunakan sebagai penimbang dalam membuat keputusan. Kemandirian yang dimaksud bukan berarti berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain, sedangkan segalanya bisa berjalan dengan baik, selaras dan seimbang apabila terjalin kebersamaan. Perjuangan tidak harus dicapai melalui bantuan dari suami atau orang lain, melainkan wanita juga harus memiliki kemampuan, motivasi, tujuan dan keyakinan terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi.
3. Bidang Hukum.
Novel DWC karya Suparto Brata menempatkan tokoh wanita memiliki persamaan di bidang hukum. Dalam kriminologi, teori-teori yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku kejahatan laki-laki, dialihkan kepada wanita sebagai suatu pemikiran yang datang kemudian. Tidaklah mengejutkan bila ditemukan bahwa wanita tidak cocok dengan model-model tersebut. Apabila kita ingin mengerti keanekaragaman kehidupan wanita, kita perlu mendengarkan penuturan wanita mengenai pengalaman-pengalaman mereka sendiri (Jane C. Ollenburger dan Helen A.Moore, 1996;278). Hal ini dilukiskan pada tokoh TUKINEM, dia adalah sosok yang sangat sadar akan bahaya laten komunis. Dibuktikan pada kekhawatirannya akan kemunculan kembali Kasminta dari pelariannya. Tukinem berusaha untuk menjauh dari sosok Kasminta, supaya dia dapat terhindar dari kasus yang akan melibatkan dirinya bila dia terbukti dekat dengan Kasminta. Seperti yang diungkapkan pada kutipan berikut:
Kutipan:
“Kasmin! Kok Kasminta!
Terjemahan:
“Kasmin! Kok Kasminta! Sudah jelas! Lihat saja surat-surat yang disimpan yang ditinggal olehnya di langit-langit rumahnya. Telah menunjukkan kalau dia itu penganut agama komunis! Orang komunis itu tidak perlu didekati, kecuali kalau kita memang orang kumunis! Tingkah lakunya seperti itu. Jika orang yang tidak menganut komunis, berarti musuh komunis, harus dilawan sampai hilang dari muka bumi!”
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tukinem sangat membenci paham komunis, dan membuat dirinya benci kepada Kasminta yang juga seorang komunis. Dia memiliki pemikiran seperti itu, semata untuk menghindar dari kasus-kasus hukum yang akan terjadi pada diri dan keluarganya bila dia menjalin kedekatan dengan Kasminta yang seorang eks-komunis. Pemaparan tersebut telah menunjukkan akan persamaan hukum di antara kaum wanita. Seorang wanita juga harus memiliki kesamaan di semua bidang termasuk bidang hukum. Wanita berhak mendapat perlakuan yang adil, meskipun dalam kenyataannya masih sering terlihat adanya pelanggaran hak-hak wanita atas hukum..
Tokoh selanjutnya yakni MINTARTI, seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan karena trauma masa lalu. Dia mengalami depresi berat karena ayahnya yang dibantai oleh PKI. Melihat kondisi tersebut, Kasminta mencoba untuk memanfaatkan kondisi Mintarti demi kepentingannya, yaitu memfitnah Sukardi. Mintarti yang terganggu jiwanya tidak menolak bahkan Kasminta di mata Mintarti dikiranya sebagai Susmanta, mantan kekasihnya. Tindakan Kasminta yang telah memperdaya Mintarti tersebut dapat digolongkan sebagai misogynist cultural system yaitu suatu sistem budaya yang membenci wanita. Misogyny dapat didefinisikan sebagai sikap membenci wanita. Konsekuensi dari masyarakat misogynist ialah menjauhkan wanita, khususnya wanita dilindungi, serta menahannya di rumah-rumah para pelindung mereka, di belakang pintu terkunci. Akibat dari budaya kekerasan yang dilestarikan oleh struktur hukum dan sistem peradilan pidana, wanita hidup dengan suatu tingkat ketakutan yang konstan. Joan Smith, dalam bukunya Mysogynies mencerminkan kepercayaan kebudayaan misogynist secara keseluruhan:
Diskriminasi serta pencemaran nama dan kekerasan yang diderita wanita
bukanlah kebetulan historis, tetapi berkaitan dengan manifestasi dari
kebencian ini, berada dalam suatu budaya yang tidak hanya bersifat
sekses, tetapi kadang-kadang mematikan wanita. Misogyny memakai
banyak samaran, mengungkapkan dirinya sendiri dalam bentuk-bentuk
yang berlainan, yang didiktekan oleh kelas, kekayaan, pendidikan, ras,
agama dan faktor-faktor lainnya. Namun, karakteristik utamanya adalah
sifatnya yang dapat merembes (dalam Jane C. Ollenburger dan Helen A.
Moore, 1996;230).
Berkembangnya jaman menuntut keterbukaan dan kebebasan gerak wanita dalam berbagai bidang, ternyata berdampak pula pada kejahatan yang ditimbulkan oleh wanita itu sendiri.
Kutipan:
“La, ya, kono! Kerja bakti sing tandang wong wedok-wedok, wonge Gerwani. Dalan dikapling-kapling, diwenehi plakat, ditancepi gendera, watune dikeruki, ditumpuk, jare mengkone arep dikleler,ditata sing rata. Éé, bareng
“Jumilah? Jumilah kancakula?”
“La thik ora! Saiki dadi pimpinane Gerwani. Ngono aku krungu kabare jare dalan iki arep disetum didandani DPU ora oleh. Herr! Malah Bupatine didemonstrasi. Ora oleh nyetum dalan iki.”
“Sing mboten ngangsali sinten?”
“Ha ya Jumilah sak balane. Wedoka kae wong politik-taktik, kok, kae. Wani nglurug rame-rame nyang ngarepe Pak Bupati!” (DWC, h.361)
Terjemahan:
“Iya, itu! Kerja bakti yang dilakukan perempuan-perempuan anggota Gerwani. Jalanan dikapling-kapling, ditempeli papan bertulisan, ditancapi bendera, batunya diambil, ditumpuk, katanya akan disebar, dipasang merata. Éé, ketika sudah sore, jalan tidak semakin baik, timbunan batu tadi dibawa untuk mengurug halaman Singaranu. Lha yang memberi komando Jumilah.”
“Jumilah? Jumilah temanku?”
“Siapa lagi! Sekarang menjadi pemimpin Gerwani. Konon aku mendengar, katanya jalan ini akan diperbaiki DPU, diperkeras dengan digilas selender, tidak boleh. Herr! Bahkan Bupatinya didemonstrasi. Tidak boleh memperbaiki jalan ini.”
“Siapa yang melarang?”
“Ya Jumilah dan rombongannya. Meskipun perempuan tetapi berpolitik-taktik, kok, dia itu. Berani beramai-ramai menyerbu ke hadapan Pak Bupati!”
Kutipan di atas mengungkapkan keterlibatan wanita Jawa yang melanggar hukum negara. Tokoh Jumilah, meskipun dari masyarakat pedesaan Jawa, dirinya telah larut dalam suasana politik yang membuatnya terjebak dalam jeratan hukum. Hal ini tidak lepas dari kebebasan dan keterbukaan gerak kaum wanita dalam masyarakat, namun sangat disayangkan masih saja ada yang memanfaatkannya tidak sesuai dengan norma, yang pada akhirnya wanita-wanita itu harus berurusan dengan hukum.
4. Bidang Sosial-Budaya.
Tokoh-tokoh wanita dalam novel DWC karya Suparto Brata memiliki latar belakang budaya Jawa yang kuat. Berjalannya cerita membawa pembaca dalam menemukan kebudayaan modern, sebagaimana yang mewarnai perjalanan hidup Pratinah. Pratinah adalah anak Madusari yang merantau ke
Novel DWC karya Suparto Brata memberikan gambaran wanita yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang tradisi. Gambaran wanita tersebut mencerminkan adanya dialektik antara nilai-nilai lama yang dianggap sakral dan bernilai luhur sehingga harus dipertahankan dan nilai-nilai baru atau modern yang menginginkan adanya perubahan terhadap tatanan atau nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan kemajuan dan perubahan zaman.
PRATINAH merupakan sosok yang mewakili wanita modern. Walau dia dilahirkan dalam keluarga yang begitu kental dengan tradisi Jawa, namun ia memiliki pemikiran yang maju. Pratinah secara fisik sangat cantik juga sangat supel dan mudah bergaul dengan orang lain disertai dengan pemikiran yang maju. Pergaulan tersebut membuat setiap orang tertarik untuk memperhatikan tingkah lakunya.
Kutipan:
Ing gedhung dansahan kono Pratinah gampang banget golek mangsan kang nekakake dhuwit byukbyukan. Racake babe-babe sing kepengin sinau dansah, keturahen dhuwit, nanging satemene iya madik-madik golek wong ayu kaya Pratinah kuwi. Yen bisa kencan karo Pratinah rumangsane kasil ngrebut katresnane wong ayu becik-becik. Dijak kencan, dipacari nganti pirang-pirang dina, kencane ing kamar hotel gedhe, utawa ing bungalow ing pegunungan. Mesthi wae metu wragat kang ora sithik. Wong lanang royal wedokan ngono
Terjemahan:
Di gedung dansa itu kPratinah mudah sekali mencari mangsa yang mendatangkan uang banyak. Biasanya bapak-bapak yang ingin belajar dansa, kelebihan uang, tetapi sebenarnya juga diam-diam mencari wanita cantik seperti Pratinah itu. Kalau bisa kencan dengan Pratinah mereka merasa berhasil merebut cinta wanita baik-baik. Diajak kencan dipacari sampai beberapa hari, kencannya di kamar hotel besar, atau di bungalow di pegunungan. Sudah pasti keluar biaya yang tidak sedikit. Laki-laki royal perempuan seperti itu sudah tidak peduli berapa keluarnya biaya. Dan Pratinah tidak bodoh, yang seperti itu juga untuk membiayai hidupnya.
Kutipan yang ditunjukkan di atas menggambarkan bahwa Pratinah yang telah dirasuki kebudayaan modern mulai menampakkan penyimpangannya dalam pergaulan hal itu terlihat ketika dia selalu mencari lelaki untuk diajaknya bercumbu, lalu dia akan mendapatkan uang dari laki-laki yang ingin belajar menari dansa dengannya. Pratinah ternyata adalah seorang pelatih dansa.
Kutipan:
Nalika kuwi Pratinah lagi dikon ngajari dansah keluarga Mawikare, keluarga Kawanua ing laladan Jalan Wijaya. Omahe gedhe magrong-magrong, mebele apik, ruwangane amba, dienggo ajar dansah kobet, platarane iya bawera, mobil bisa mlebu-metu, mangku lurung gedhe, kenceng, sepi, ing laladan kutha anyar. (DWC, h.421).
Terjemahan:
Ketika itu Pratinah sedang disuruh mengajari dansa keluarga Mawikere, keluarga Kawanua di kawasan Jalan Wijaya. Rumahnya besar dan megah, mebelnya bagus, ruangannya luas, dipakai belajar dansah cukup, halamannya juga luas, mobil bisa keluar-masuk, menghadap ke jalan raya, lurus, sepi di daerah
Kutipan di atas menunjukkan bahwasanya wanita Jawa juga mempunyai peranan yang penting dalam Perwujudan citra wanita sebagai seorang yang berperan aktif dalam dunia seni budaya ditampilkan dalam novel DWC karya Suparto Brata, tidak lain juga merupakan pencerminan dari aktivitas berkesenian para wanita di dalam masyarakat yang terjun di dunia seni. Dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas berkesenian khususnya kaum wanita di masyarakat tetap ada. Adanya tuntutan persamaan hak antara wanita dan laki-laki, Pratinah menginginkan perubahan pada diri wanita. Wanita harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, namun di sisi lain Pratinah mencerminkan sikap sebagai wanita modern yang keterlaluan, yaitu menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan
Wanita dalam masyarakat Jawa hendaknya juga mendapat penghargaan yang layak, dari mereka pulalah akan lahir generasi penerus bangsa. Banyak sudah kisah para wanita Jawa jaman dahulu yang ikut berperan dan berjasa terhadap negaranya. Kutipan di bawah ini juga mengungkap kembali hal tersebut.
Kutipan:
Satemene bale somah nganti negara, kuwi moncer mblerete ora bisa ora, gumantung uga lelabete wong wadon. Lelabete wong wadon ora kena disepelekake. Kliru yen wong Jawa nyebut wong wadon kuwi kanca wingking, swarga nunut neraka katut. Anggepan kaya ngono kang ateges nyepelekake wong wadon, malah bisa njungkelake rumahtanggane utawa negarane. Bisa kuwalat karo wong wadon. Madusari percaya yen akeh wong wadon Jawa sing jiwane kaya Tribuwana Tungga Dewi, kaya Madusari barang ngono. Gedhe lelabuhane marang pasrawungan urip ing sapadha-padha, gawe luhure bangsa lan manungsa (DWC, h.304).
Terjemahan:
Sebenarnya rumah tangga sampai negara, itu terang redupnya tidak bisa tidak, bergantung juga kepada peran wanita. Peran wanita tidak bisa disepelekan. Salah kalau wanita Jawa disebut wanita itu sebagai teman mumbuntut, ke surga ikut, ke neraka juga ikut bagaimana laku lelaki. Pandangan seperti itu bisa meruntuhkan rumah tangga atau negaranya. Bisa kuwalat terhadap wanita. Madusari percaya bahwa banyak wanita Jawa yang jiwanya seperti Tribuwana Tungga Dewi, seperti halnya Madusari yang juga begitu. Besar perannya terhadap pergaulan hidup sesama, membuat luhurnya bangsa dan manusia.
Demikian uraian mengenai peran wanita bila dilihat dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Seperti yang telah ditunjukkan pada tokoh Pratinah sebagai seorang wanita yang tangguh dan kuat. Perantauannya di
c. Citra Wanita yang Lemah dengan Nafsu Birahi
Sebagai Sifat Turun-menurun.
Masa lalu Madusari pernah terlibat masalah dengan laki-laki, ketika ibunya melarikan Madusari yang menginjak remaja dari Gusti Mas Pamorkaton. Hal ini disebabkan bahwa Madusari akan diambil isteri oleh Gusti Mas Pamorkaton bersamaan dengan Ndarajeng Manik. Hal itu tidak lepas dari apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ndara Siti ibunya sendiri.
Kutipan:
Madusari kelingan nasibe dhewe. Uga isih cilik mengkono
Terjemahan:
Madusari teringat nasibnya sendiri. Juga ketika masih kecil sudah tersandung dengan laki-laki! Gusti Mas Pamorkaton! Ketika itu dirinya sudah perawan, sudah beranjak remaja, rasanya sudah lebih tua dari Pratinah itu. Sebenarnya dirinya tidak sepenuhnya tahu, siapa Gusti Mas Pamorkaton itu. Belum kenal bergaul benar. Mendadak ada pertemuan yang memutuskan Ndara Jemba (nama Madusari ketika bocah. Pen.) dijadikan tambahan harus ikut dinikahi Gusti Mas Pamor. Ndrajeng Manik senang, ibunya juga senang, tetapi Ndara Jemba harus bagaimana? Tidak bisa merasakan. Mendadak ia memergoki ibunya sendiri, Ndara Siti, terlihat di bilik tempatnya sedang tersedu-sedu karena ya permasalahan laki-laki Gusti Mas Pamorkaton itu! Dan selanjutnya nasib Ndara Jemba menjadi tidak karuan, disingkirkan oleh ibunya melesat jauh sampai Jogja. Hidup sendirian!
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Madusari (yang nama kecilnya Ndara Jemba, pen) teringat akan perjalanan hidupnya. Ketika masih kanak-kanak dirinya sudah menerima kenyataan bahwa dia tidak memiliki ayah, hanya berdua dengan ibunya yaitu Ndara Siti, dan mengabdi pada keluarga Kusumapraba di Baluwerti keraton Surakarta Hadiningrat. Madusari beranggapan ibunya Ndara Siti mempunyai kisah yang memalukan sehingga harus dirahasiakan kepada semua orang, termasuk juga kepada anaknya sendiri, Ndara Jemba alias Madusari.
Kutipan:
Terus, lungane saka Nyogja uga marga crita katanggore karo wong lanang! Ah, kuwi macan gege ana sing nguthik-uthik, ana sing ngilik-ilik. Srimadu kaya macan gege, lagi nganggur, lagi leyeh-leyeh, ditiliki, diinguki, diithik-ithik dening Saksana sing ngobarake nafsune. La bareng ketubruk, diladeni….! Ah, dheweke kisinan tenan! Lali! Kentir kepengin ngicipi ngrasakake adrenge nafsu birai. Edan! Kenapa kok nglakoni mengkono! Ketiwasan! Kepregok thokleh dening Ndaramas Jodi. Mangka satemene dheweke
Terjemahan:
Kemudian, perginya dari Jogja juga karena cerita terbenturnya dengan laki-laki! Ah, itu harimau sedang berjemur santai ada yang mengganggu, ada yang mengkili-kili. Srimadu seperti harimau berjemur santai, sedang melamun-lamun, sedang istirahat, ditengok, dicumbu-rayu oleh Saksana yang mengobarkan nafsunya. Tergiur dilayani….! Ah, malu! Ia lupa, terlena! Terhanyut ingin mencicipi gairah nafsu birahi. Gila! Mengapa hal seperti itu dilakukannya! Terlanjur! Tertangkap basah oleh Ndaramas Jodi. Sedangkan sebenarnya dirinya sudah terikat akan menjadi istri Ndaramas Jodi Hargadiningrat itu! Srimadu malu sekali. Lari terpontang-panting ketakutan! Malu, kecewa, marah! Kehilangan akal. Seketika pergi lari dari masyarakat pergaulannya di Keraton Ngayogyakarta. Pergi tertatih, lagi-lagi karena persentuhannya dengan laki-laki. Kata kasarnya, permasalahan pejantan!
Madusari sadar, bahwa kisah hidupnya juga melewati hal yang sangat memalukan, yaitu ketika berselingkuh dengan Kapten Saksana karena tidak kuat menahan nafsu birahinya. Dapat dikatakan Madusari tersandung masalah lelaki, karena keturunan dari ibunya, Ndara Siti? Dan anaknya, Pratinah, juga akan tergoda laki-laki Guru Kardi? Oh, harus dihindarkan. Dipisah, dijauhkan. Pratinah masih terlalu kecil!
Beberapa kutipan di atas menunjukkan bahwa ibunya Ndara Jemba alias Madusari, yaitu Ndara Siti, sebelumnya juga tersandung dengan masalah laki-laki, sehingga Ndara Siti melahirkan Ndara Jemba tanpa bapak. Perempuan melahirkan anak, tentu karena hubungan dengan laki-laki. Pada bagian lain Ndara Siti pernah bercerita tentang seorang Putra Dalem yang belum sunat, namun hanya sebatas begitu saja yang diketahui Madusari alias Ndara Jemba. Kini (setelah Madusari hidup di desa dan punya anak perawan Pratinah) Madusari menebak-nebak bahwa Putra Dalem itulah yang berhubungan dengan ibunya. Putra Dalem yang belum sunat itu adalah Gusti Mas Pamorkaton, ternyata setelah berhubungan, bisa menghasilkan jabangbayi. Jabangbayi yang tidak punya bapak. Ya dirinya, Ndara Jemba alias Madusari! Makanya ketika ada keputusan bahwa dia akan dinikahi Gusti Mas Pamorkaton, ibunya segera menyingkirkan dari Baluwerti kraton Surakarta Hadiningrat ke Keraton Jogyakarta.
Dan Madusari, kini ibunya Pratinah, sadar bahwa dirinya juga dalam pelarian setelah kepergok ketahuan terjebak dalam perselingkuhan dengan Kapten Saksana ketika masih dalam lingkungan Keraton Jogyakarta. Padahal dirinya sudah dipertunangkan dengan Ndaramas Jodi Hargadiningrat.
Pada bagian akhir cerita ketika Pratinah hidup di
*
Demikianlah problema hidup yang dialami beberapa tokoh wanita Jawa dalam novel DWC yang mempunyai kelemahan terhadap nafsu birahi sebagai sifat turun-temurun, yaitu terperosoknya mereka dalam berhubungan dengan laki-laki. Ndara Siti punya anak Ndara Jemba alias Madusari tanpa bapak, Madusari selingkuh dengan Saksana. Pratinah anak Madusari juga diprawani oleh Saksana.
Permasalahan wanita yang tersandung dengan laki-laki, dan juga wanita yang terlena karena menuruti nafsu birahi, terasa sekali mengikuti beberapa tokoh wanitanya, yaitu NDARA SITI, MADUSARI dan PRATINAH. Cerita tersebut berhubungan dengan sifat atau bawaan turun-menurun warisan dari wanita-wanita pendahulunya.
Kutipan:
“Emoh! Aku ki dudu lonthe! Emoh
“Oom! Ngundanga aku Oom Son! Huah-ha-ha! Kon sugih kok ora gelem! Hiya, priye? Tutugna kandhamu! Sugih, dhuwit akeh, senenge nang endi? Hua-ha-ha!” (DWC, h.464).
Terjemahan:
“Tidak! Aku ini bukan pelacur! Tidak mau menerima uangmu hanya karena tidur seperti ini. Meskipun kamu bayar satu juta, aku tidak mau!” gertak Pratinah dalam hati. Hanya dalam hati. Yang terucap irama dan bunyinya lirih, “Sugih, arta kathah, niku senenge teng pundi, ta, Paklik?”
“Oom! Panggillah aku Oom Son! Hua-ha-ha! Disuruh kaya kok tidak mau! Iya, bagaimana? Lanjutkan bicaramu! Orang kaya, uang banyak, senangnya di mana? Hua-ha-ha!”
Kutipan di atas dapat diperoleh gambaran, bahwa Pratinah sekarang, tidak lagi mengejar uang semata namun lebih ingin menikmati nafsu birahinya. Hal tersebut tidak lain karena
Kutipan:
Pratinah seneng banget nglakonake sandiwarane dadi wadon ndesa sing sajak isih murni. Dheweke ngreti yen kancane kencan iki bisa mudal-mudal nepsu biraine yen diladeni dening bocah ndesa sing sajak durung pengalaman. Pratinah dhewe ketarik karo tingkah lanang sing kerasukan nafsu setan kaya mengkono mau. Sak ora-orane karo Oom Son iki. Pratinah ora bakal lali pengalamane kang sepisanan. Pengalaman kang aji banget, sengsem banget. Saben wong wadon mesthi ora tau lali karo sacumbana kang sepisanan. Saiki Pratinah kepengin mbaleni pengalaman mau! Kepengin kerasukan kaya biyen kae. Ngrasakake hardaning birai. (DWC, h. 463)
Terjemahan:
Pratinah senang sekali melakukan sandiwara menjadi wanita desa yang terlihat masih murni. Dirinya mengerti kalau teman kencannya ini bisa bergejolak nafsu birahinya kalau dilayani anak desa yang terlihat belum berpengalaman. Pratinah sendiri tertarik dengan tingkah laki-laki yang kerasukan nafsu setan seperti itu, setidak-tidaknya dengan Oom Son ini. Pratinah tidak akan lupa pengalamannya yang pertama kali. Pengalaman yang sangat berharga sekali, berkesan sekali. Setiap perempuan pasti tidak akan lupa dengan hubungan badan yang pertama kalinya dengan laki-laki. Sekarang Pratinah ingin mengulangi pengalaman tadi! Ingin kerasukan seperti dulu itu. Merasakan gejolak birahi.
Berdasarkan sikap Pratinah yang ditunjukkan di atas, menunjukkan bahwa Pratinah telah benar-benar dikuasai oleh nafsu birahi untuk merasakan berbagai sensasi hubungan lawan jenis. Semua uraian di atas menerangkan kembali bahwasanya kurangnya pengendalian diri terhadap nafsu birahi oleh beberapa tokoh wanita, yang sebenarnya mereka masih dalam satu garis keturunan. Mobilitas yang dilakukan oleh kaum wanita memang akan membawa berbagai permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan wanita itu sendiri.
Perwujudan dari citra wanita Jawa seperti yang ditampilkan dalam novel DWC karya Suparto Brata disimpulkan adanya fenomena-fenomena wanita dalam masyarakat. Wanita dengan berbagai peranannya mengharuskan mereka bertahan hidup dalam masyarakatnya, sehingga mereka harus bekerja atau mencari nafkah, tentu saja hal itu bukan suatu peran yang mudah melainkan merupakan peran yang harus dijalaninya. Begitu pula dengan gambaran wanita yang tidak memiliki keturunan, serta citra wanita yang lemah terhadap nafsu birahi sebagai sifat turun-menurun, tidak membuat mereka berhenti dalam menjalani aktivitasnya. Mereka tetap menjalani kehidupannya meski kenyataannya sangat pahit. Hal tersebut juga menunjukkan adanya eksistensi wanita sebagai seorang yang mandiri. Demikianlah gambaran perwujudan citra wanita Jawa dalam novel DWC karya Suparto Brata.
*
AMANAT
Pengarang biasanya menyampaikan pesan atau amanat tersebut pastilah dapat bermanfaat dalam kehidupan. Karena pengarang dalam menciptakan karya sastra tak lepas dari kehidupannya sehari-hari yang dialaminya. Mengingat pengarang adalah merupakan bagian dari anggota masyarakat, dan pengarang tinggal di lingkungan masyarakat. Maka tak heran jika banyak karya sastra berupa cerbung, cerpen, atau pun novel kebanyakan mengangkat tema yang diambil dari kehidupan masyarakat dan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini amanat atau pesan pengarang sangat penting sekali disampaikan kepada pembaca agar pembaca atau peminat karya sastra dapat mengambil hikmah dari karya sastra tersebut. Pengarang karya sastra biasanya menyampaikan amanatnya mengenai berbagai hal tentang hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat.
Kutipan:
“Apa-apa kuwi dicoba dhisik. Diawaki, ditandangi, dilakoni dhisik. Aja durung-durung
Terjemahan:
“Segala sesuatunya itu dicoba dulu. Dipahami, dikerjakan, dilakukan dahulu. Jangan belum apa-apa sudah diputuskan tidak bisa terjadi. Sebab tidak logis. Sudahlah, selogis-logisnya pemahaman manusia, Gusti Allah bisa membuat yang tidak logis menjadi kenyataan. Gusti Allah selalu bisa membuat kenyataan, membuat yang tidak logis menurut kepahaman manusia menjadi logis, maka jangan terburu-buru memutuskan dengan cara mengedepankan pikiran manusia. Sepintar-pintarnya manusia masih pintar Gusti Allah. Maka apa-apa yang belum tentu itu kerjakan dahulu, hasilnya tetap kabur atau menjadi kenyataan, baru berkatalah kamu! Katakanlah hasilnya setelah kamu melakukannya, kamu telah mengusahakannya!” Tikinem pernah berkata seperti itu yang dicatat oleh Sukardi.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa semua hal atau pekerjaan jangan terlalu cepat diputuskan, semuanya harus dikerjakan terlebih dahulu. Hasil dan semua yang akan terjadi sudah diatur oleh Tuhan, manusia hanya berhak menjalani saja, sebab semua hasil dan kemungkinan yang menurut manusia mustahil bisa dengan mudah terjadi atas kehendak-Nya.
Seorang wanita hendaknya selalu menjaga hubungan pergaulannya dengan laki-laki, yang dimaksud di sini adalah hubungan
Kutipan:
Ndara Siti tansah ngandhani sing ngati-ati srawung karo para priya lan pangeran bangsawan ing kana. “Tansah elinga karo unen-unen wangsalan ing lelagon gendhing: Parabe Sang Marabangun, sepat domba Kali Oya, aja dolan lan wong priya, gurameh nora prasaja, Ndhuk. Sing ngati-ati, sing waskitha!” Sing dituturi mengkono mung anake dhewe, Ndara Jemba. Dene Ndrajeng Manik,
Terjemahan:
Ndara Siti selalu menasihati agar berhati-hati bergaul dengan para lelaki dan para pangeran di
Manusia hidup di dunia ini sebagai bagian dari masyarakat, hendaknya saling tolong menolong antarsesamanya. Semua perbuatan akan lebih berguna bagi kepentingan yang lain kalau dilakukan secara ikhlas dan dilandasi kesadaran tentang peran dan kewajibannya di masyarakat. Masyarakat akan mencatat peran tersebut sebagai suatu pengabdian yang tulus dan akan sangat dihargai dalam masyarakat itu sendiri. Kutipan di bawah ini menyatakan cerita Sukardi tentang Sastradirun yang telah banyak berjasa bagi kehidupan masyarakatnya.
Kutipan:
Pancen, Sukardi ngarani Sastradirun sing kawentar dadi Petruke Sriwedari jaman semana kaleksanan nggayuh urip kang lebda utama. Nyatane nalika matine sing nglayat wong sak Sala jejel riyel melu bela sungkawa. Titikane uwong ngaurip begja kemayangan yakuwi yen ing akhir uripe, nalika sedane, dilayat dening wong akeh. Mratandhani anggone urip biyene
Terjemahan:
Memang, Sukardi menyebut Sastradirun yang terkenal menjadi Petruknya Sriwedari jaman itu tercapai meraih hidup yang berguna dan utama. Nyatanya ketika meninggalnya yang melayat orang se Sala berdesakan ikut berbela sungkawa. Tandanya orang hidup beruntung itu kalau di akhir hayatnya, ketika meninggal, dilayat oleh orang banyak. Menandai hidupnya dulu sudah membuat kebaikan persaudaraan dengan manusia lainnya, sudah memberikan pengabdian hidup kepada sesama manusia, sudah berguna terhadap pergaulan di dunia. Nyatanya ketika meninggal banyak yang merasa kehilangan, dan memperlihatkan bela sungkawanya ikut melayat jenasahnya.
Amanat berikut menyampaikan kepada pembaca bahwa hendaknya suatu pekerjaan dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, benar-benar menguasai bidangnya. Dengan kata lain suatu profesi atau pekerjaan tadi menjadi pegangan utama dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan untuk selanjutnya berguna bagi masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan yang diharapkan, haruslah diikuti pengorbanan dan kerja keras.
Kutipan:
“Yen kowe kepengin dadi dhokter, ya kudu sekolah sing tenan. Kudu lulus universitas. Pendheke kowe kudu wani rekasa sinau nggethu sadurunge bisa nyekel lan methik kasil pakaryanmu kang mantep. Iling-ilingen kuwi. Lan, tandhesna ing batinmu pesenku iki: yen kowe dadi tani, ya dadia tani sing jempolan, yen kowe dadi dhokter, ya aja dadi dhokter sing tembre-tembre angger lulus pamulangan luhur wae, nanging dadia dhokter sing peng-pengan, sing kukuh anggonmu kepengin ngabdi marang manungsa sapadha-padha. Dadia apa wae kudu sing paling jempol, saora-orane paling aji tumrap masyarakat sakupengmu. Kanthi mengkono kowe bisa urip ing tataran masyarakat dhuwur ing ngendi wae uripmu, ing desa, ing kutha, ing njaban negara…..!” (DWC, h. 287).
Terjemahan:
“Kalau kamu ingin jadi dokter, ya harus sekolah yang sungguh-sungguh. Harus lulus universitas. Pendeknya kamu harus berani berjuang belajar sungguh-sungguh sebelum kamu memegang dan memetik hasil karyamu yang mantap. Selalu ingatlah akan hal itu. Dan landasilah ingatanmu dengan pesanku ini: kalau kamu jadi petani, ya jadilah petani yang jempolan, kalau kamu jadi dokter, ya jadilah dokter yang hebat, jangan dokter yang sembarangan asal lulus pendidikan tinggi saja, melainkan jadilah dokter yang baik, yang kokoh keinginanmu mengabdi kepada sesama manusia. Menjadi apapun harus yang paling jempol, setidak-tidaknya yang paling berguna bagi masyarakat sekelilingmu. Dengan begitu kamu bisa hidup paling dihargai di tataran masyarakat manapun kamu berada, di desa, di
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya selalu ingat dan berbakti kepada-Nya. Mengingat Tuhan salah satunya dengan berdoa, menumpahkan segala permohonan kepada-Nya. Setiap manusia mempunyai keyakinan yang berbeda-beda tentang Ketuhanan, begitu juga hubungan manusia dengan Tuhan bersifat pribadi, artinya hanya individu itu sendiri yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Setiap individu berhak berpegang dengan keyakinan yang diyakininya. Untuk berhubungan dengan Tuhan tidak harus meniru orang lain, namun tidak boleh juga menghina cara orang lain.
Kutipan:
“Kowe pancen ora tau oleh dhidhikan agama. Pendhidhikan sangu uripmu sing paling akeh ya saka aku, lan aku ya mung bisa ndhidhik kowe sabisa-bisaku. Dadi kowe nyenyuwun marang Gusti Allah ora sah niru carane wong liya. Nanging ya aja nyacad carane wong liya. Caramu ya caramu pribadi, ya sabisa-bisamu, sing pokok kowe percaya marang Gusti Allah Kang Mahatunggal. Yen prekara urip ing alam donya, kowe perlu golek kanca srawung, goleka kanca sing saakeh-akehe, goleka mitra kang tresna ing sapadha-padhane ngaurip, padha ngrasakake susah lan bungah bareng-bareng. Ora sah bengkerengan rebutan rejeki, marga angger tansah dioyak, ora sah nganggo regejegan, rejeki kuwi mau bakal tinampa adil manut jatah murwate dhewe-dhewe. Yen prekara suwarga, kowe ora sah ngajak-ajak kanca, ora sah sekuthon karo wong liya, ora sah nyambat wong liya, sowan lan ngadhepa dhewe marang Sing Gawe Urip. Marga iki prekara batin, prekara kang ora kasat mata, prekara jiwa dudu raga, prekara gegayutanmu karo Pangeranmu, anggonmu sowan bisa sawayah-wayah, bisa ing sakedhep netra, bisa sarana tapa utawa pasa patang puluh dina patang puluh bengi, bisa ing ngendi papan, bisa nganggo sadhengah cara, lan ora perlu seksi utawa kanca Sing paling kokbutuhake mung sowanmu madhep Gusti Allah Kang Mahawikan Akarya Jagad mligi kuwi mantep, ijen, lan dudu ragawi.”(DWC, h.340).
Terjemahan:
“Kamu memang tidak pernah memperoleh pendidikan agama. Pendidikan bekal hidupmu yang paling banyak ya dariku, dan aku juga hanya bisa mendidik kamu semampuku. Jadi kamu memohon kepada Tuhan tidak usah meniru caranya orang lain. Tetapi juga jangan mencela cara orang lain. Caramu ya caramu pribadi, juga semampumu, yang penting kamu percaya kepada Tuhan Yang Mahatunggal. Kalau masalah hidup di dunia, kamu perlu mencari teman bergaul, carilah teman sebanyak-banyaknya, carilah mitra yang menyayangi sesama hidup. Bersama-sama merasakan susah dan senang bersama-sama. Tidak usah berkelahi berebut rezeki, sebab kalau terus saja dikejar, tidak usah memakai cara kotor, rezeki tadi akan jatuh adil menurut bagiannya masing-masing. Kalau masalah surga, kamu tidak usah mengajak teman, tidak usah bersekutu dengan orang lain, tidak usah mengeluh minta bantuan orang lain, datang dan menghadaplah sendiri kepada Yang Membuat Hidupmu. Sebab ini perkara batin, perkara yang tidak kasat mata, perkara jiwa bukan raga, perkara hubunganmu dengan Allahmu, caramu menghadap bisa sewaktu-waktu, bisa dalam sekejap mata, bisa dengan cara bertapa atau berpuasa empat puluh hari empat puluh malam, bisa di segala tempat, bisa dengan segala cara, dan tidak perlu saksi atau teman. Yang paling kamu butuhkan hanyalah menghadapmu kepada Gusti Allah Sang Mahakarya Jagad Seisinya itu mantap, secara diri pribadi, dan bukan ragawi.”
*
A. KESIMPULAN
1. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai analisis struktural, serta analisis sosiologi sastra yang terdapat dalam novel DWC karya Suparto Brata. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Dilihat dari aspek struktural karya sastra, dalam novel DWC karya Suparto Brata tema yang diangkat pengarang adalah kelicikan. Kemudian mengenai amanat yang berhubungan dengan tema adalah semua kebaikan dan keburukan perbuatan yang dilakukan manusia di kemudian hari tentu akan menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Sedang alur yang digunakan adalah alur campuran yang secara garis besar alur dalam novel DWC mungkin progresif, tetapi di dalamnya betapapun kadar kejadiannya, sering terdapat adegan-adegan sorot balik. Demikian pula sebaliknya. Latar yang dipakai meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Terdapat beberapa tokoh dalam novel DWC karya Suparto Brata, sedangkan hanya ada beberapa tokoh sentral wanita dalam novel ini, yaitu Pratinah dan Tukinem. Tokoh laki-laki misalnya Kasminta dan Guru Kardi digunakan sebagai sarana mengalirnya cerita atau mendukung alur cerita. Tokoh laki-laki yang bernama Kasminta digunakan sebagai sarana tegangan cerita, adapun untuk perwatakan tokohnya terungkap melalui dimensi fisik, penampilan psikis, serta aspek sosiologis para tokohnya.
2. Dilihat dari aspek sosiologi sastra, diungkapkan mengenai permasalahan sosial yang diangkat dalam novel DWC karya Suparto Brata utamanya permasalahan-permasalah sosial yang berhubungan dengan keadaan zaman sekarang, yang diinterprestasikan sebagai zaman edan, di mana dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang “culika” licik, curang. (Donyane Wong Culika = Negerinya Orang Curang, pen.) Berjalannya cerita membawa ke berbagai permasalahan para tokohnya, namun kembali kepada judul penelitian ini yang mengangkat citra wanita Jawa yang di dalamnya mendiskripsikan segala bentuk gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian mengenai wanita. Ada tiga hal yang berkaitan dengan citra wanita Jawa dalam novel DWC yakni mengenai perwujudan perjuangan wanita Jawa, pewujudan citra wanita Jawa dalam novel DWC karya Suparto Brata yang meliputi citra wanita dalam keluarga dan masyarakat serta citra wanita yang lemah terhadap nafsu birahi sebagai sifat turun-temurun. Perjuangan hidup tokoh wanita dalam novel DWC telah memberi gambaran bahwasanya mereka berhak memperjuangkan kehidupan mereka sendiri. Adapun citra wanita dalam keluarga, di dalamnya telah ditunjukkan bahwa yang membedakan antara pria dan wanita adalah kodrat. Hal ini diterangkan bahwa seorang wanita memiliki kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan yakni mengurus rumah tangga, di sisi lain juga terdapat perwujudan citra wanita Jawa dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan yang digambarkan pada sosok Tukinem. Wanita dalam keluarga tanpa keturunan hendaknya tidak menjadi obyek yang selalu disalahkan. Citra wanita Jawa dalam masyarakat digambarkan menjadi empat hal yaitu masalah keterlibatan mereka dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Terbukanya ruang gerak yang lebar bagi wanita Jawa membawa keterlibatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Perwujudan gambaran atau citra wanita yang terakhir adalah citra wanita yang lemah terhadap nafsu birahi sehingga sifat turun temurun, digambarkan melalui tokoh Pratinah dan Madusari. Mereka sebenarnya wanita-wanita yang tangguh dan kuat memperjuangkan hidup dan hak-haknya, namun sangat disayangkan lemahnya mereka terhadap pengendalian nafsu birahi. Penelitian yang dilakukan terhadap karya sastra berbentuk novel Jawa ini berusaha mendiskripsikan unsur-unsur struktur novel dan eksistensi dari citra wanita Jawa di dalamnya, sebagaimana teruangkap dalam kesimpulan di atas.
B. SARAN
Berpijak dari kesimpulan yang telah diuraikan, selanjutnya akan ditampilkan beberapa saran sebagai berikut:
Penelitian terhadap novel DWC karya Suparto Brata masih sangat terbatas, permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini masih berkutat di seputar permasalahan sosial mengenai citra wanita Jawa, sehingga dimungkinkan untuk dilanjutkan, yang sudah barang tentu dari sudut pandang yang lain atau analisis yang berbeda agar mampu memberikan masukan mengenai aspek-aspek penting lainnya dalam novel DWC karya Suparto Brata.
Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kemajuan kepada penikmat atau pembaca sastra dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam kehidupan dan harus dihadapi dengan lebih arif serta bijaksana untuk ke depannya.
Pendekatan yang dipakai dalam analisis terhadap novel DWC karya Suparto Brata adalah tinjauan sosiologi sastra. Diharapkan nantinya akan ada penelitian lain yang dapat terus dilakukan untuk meneliti novel karya Suparto Brata dengan pendekatan yang berbeda dari sudut pandang yang lebih menarik mengenai aspek-aspek penting lainnya.
Diharapkan apa yang telah dipaparkan lewat penelitian mengenai novel ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun pecinta sastra, khususnya sastra Jawa.
*
Dipaparkan, dikutip dan disunting oleh Suparto Brata
***
De Bloedige Maandag
Hari Senin yang berdarah-darah. Di WC Balai Pemuda Surabaya terdapat ceceran darah hingga menggenangi lantainya.
Bacalah
MASIH ADAKAH NILAI-NILAI
KEJUANGAN & KEPAHLAWANAN BANGSA?
Akhir Desember 2008