Wong Jawa Ilang Jawane
Makalah pada seminar
WONG JAWA ILANG JAWANÉ
(Balai Soedjatmoko Solo & House of Danar Hadi 14 Juni 2009)
Menurut cerita Ibuku, saya lahir di Centrale Burgere Ziekenhuis (CBZ) Surabaya, hari Sabtu Legi, bulan Sawal tahun Jé. Itu diucapkan tiap kali. Ketika saya masuk sekolah, ketika saya umur 7 tahun, ketika jadi pelajar, ketika saya nikahan. Pernah juga tiap hari Sabtu Legi dibikinkan sesajen ketan 3 warna, dan kembang setaman. Itu kata Ibu. Dongenge Sibu. Sedikit demi sedikit saya selidiki, saya lalu mengerti, bahwa saya dilahirkan di RSUP Surabaya, tanggal Masehinya 27 Februari 1932. Penyelidikan lebih lanjut, hari itu juga lahir seorang bayi perempuan, yang kemudian hari jadi perempuan cantik jelita dan termasyur, yaitu Elizabeth Taylor. Sejarahnya lebih lanjut, CBZ itu adalah yang sekarang menjadi Surabaya (Delta) Plaza. Sebuah plaza di tengah Kota Surabaya.
Dengan saya tuliskannya “dongeng” Ibu saya itu, (juga saya tulis pada beberapa bukuku), maka “dongeng” itu diketahui oleh masyarakat sekarang, oleh pembaca bukuku. Menjadi abadi, dapat ditelusuri setiap saat. Padahal, kalau tidak saya tulis, “dongeng” Ibu itu, tempat-tempat yang ditunjukkan Ibu, saksi-saksi dalam “dongeng” Ibu, hilang musna.
Segala apa yang saya alami, saya lihat, saya dengar, saya rasakan, yang merupakan riwayat hidup dan budaya serta peradaban masyarakat yang terlibat, akan lenyap tak terketahui lagi. Tetapi karena saya tulis, menjadi karya tulis buku, maka dapat diketahui oleh orang-orang generasi selanjutnya. Padahal, sampai hari ini, umur saya 77 tahun, saya telah menulis banyak buku, saya jadi pengarang, penulis cerita, atau istilah elitenya sasterawan. Saya telah menulis sastera.
Menurut Goldmann (1977;99) karya sastra yang sempurna adalah karya sastra yang didasarkan atas keseluruhan kehidupan manusia, yaitu pengalaman subjek kreator (pengarang) sebagai warisan tradisi dan konvensi. Sastra menyajikan kehidupan, dan kehidupan tersebut sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subjektif manusia. Ada kesamaan antara sosiologi dengan sastra sehingga teks sastra dapat dikaji melalui pendekatan sosiologi (Wellek & Warren, 1989;109).
Tidak saya pungkiri, bahwa sebanyak itu buku yang saya tulis, sebagian besar saya kutip dari pengalaman saya, apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, yang terkesan jelas di ingatan saya. Padahal hidup saya mengarungi zaman Belanda, zaman Jepang, Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, zaman perjuangan kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang. Tentu saja ditambah pengetahuan dari bacaan saya. Justru dari pembacaan itu awalnya saya jadi punya keterampilan dan kegemaran menulis. Kalau begitu, dengan kegemaran saya membaca buku dan menulis buku, saya sudah “mengabadikan” dan “mempertahankan” warisan tradisi dan konvensi sosial budaya masyarakat zaman-zaman yang saya lalui. Yaitu zaman dengan budaya masyarakatnya orang Jawa. Saya dilahirkan sebagai orang Jawa, ketika kecil hidup di lingkungan bangsawan, di Kota Kerajaan Surakarta Hadiningrat, diperlakukan dan bertingkahlaku cara Jawa, berbicara bahasa Jawa, membaca dan menulis bahasa Jawa. Banyak suka-dukanya yang saya lakoni, namun setelah lampau dan kini kukenang, maka kehidupan saya itu sangat indah. Sayang sekali zaman bergeser, keindahan yang kualami tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Tata kota, peradaban, bahkan bahasa Jawa, yang sekarang kukenang begitu indah, sudah tidak trend lagi untuk digunakan. Alangkah sayangnya. Karena rasa sayang itulah mungkin, barangkali, saya selalu ingin menuliskan kisah-kisah kehidupan yang saya saksikan, saya alami, saya ketahui, dalam sastra Jawa dan sastra Indonesia, atau karya tulis buku..
Pernah, dalam waktu yang panjang, saya berpikir, bahwa hidup saya ini sarwa kebeneran. Kebetulan saya lahir sebagai orang Jawa. Bangsawan. Hanya orangtua tunggal (ibu) yang tidak punya warisan kekayaan maupun ketrampilan. Kebetulan Ibu mengajakku hidup di Sragen (desa). Kebetulan disekolahkan di Sekolah Angka Loro yang pelajaran membaca dan menulisnya bahasa Jawa huruf Hanacaraka. Kebetulan sebagai Ibu dan saya yang hidup berduaan di desa, malam hari ngeloni saya dengan membaca buku macapat Wong Agung Menak. Kebetulan di sekolah itu pelajaran membaca buku dan menulis halus diajarkan tiap hari sejak kelas 1 hingga kelas 5. Kebetulan murid kelas 4 diwajibkan pinjam buku di perpustakaan, dan diuji buku tadi dibaca atau tidak. Kebetulan Jepang datang. Kebetulan ibu melamar jadi PRT di Surabaya. Kebetulan saya hidup di zaman Revolusi. Kebetulan saya menangi zaman Orde Lama di Surabaya. Kebetulan langka buku bahasa Indonesia terbit, sehingga saya cari buku bacaan bahasa Inggris. Membacanya susah payah, tapi kok kebetulan bukunya ada di lowakan. Kebetulan terbit majalah Kisah, Siasat, Mimbar Indonesia yang saya mampu berlengganan dan belajar menulis sastra di situ. Kebetulan saudara sepupuku yang berlengganan Panjebar Semangat menyuruh saya ikut sayembara menulis cerita sambung di majalah bahasa Jawa. Kebetulan dengan berbekal bacaan saya bahasa Inggris saya membacai cerita detektip, dan saya cakkan di bahasa Jawa hebat sekali. Ya, kebetulan, kebetulan, kebetulan sebagaimana kodratnya.
Tapi kemudian saya berubah. Karena kegemaran saya membaca buku dan menulis (buku), bukanlah kodrat. Saya di sekolah diajari, dibimbing, dibiasakan setiap hari, dibudayakan membaca buku dan menulis (buku). Jadi, kebudayaan saya membaca buku dan menulis buku sehingga sampai sekarang berusaha mengembangkan sastra Jawa sebagai bacaan dunia, harus saya capai dengan latihan-latihan. Pengalaman, weruh lan krungu, memang kodrat. Tetapi membaca dan menulis, bukan kodrat. Harus ada pembelajarannya, latihannya, memberbudayakannya. Akhirnya, pengalaman hidup saya itu tidak kebetulan, ora sarwa kebeneran, karena saya raih dengan pencapaian juga, yaitu pelajaran membaca buku dan menulis (buku) yang terus-menerus tiap hari selama 12 tahun sekolah dasar. Maka ungkapan sarwa kebeneran itu jadi kersaning Allah.
Sampai umur 77 tahun ini, saya mendapat tiga hadiah terbesar dari Allah, yaitu (1) sehat wal’afiat (2) bebas memilih, (3) mempu membaca buku dan menulis buku. Menyadari akan hal itu, maka tiga hadiah besar tadi saya anggap sebagai amanah, harus ibadhah, dan Alhamdulillah barkah. Setidaknya dengan anggapan seperti itu saya wajib menulis buku, yang menceritakan hal-hal yang berkenaan dengan pengalaman hidup saya, yaitu saya sebagai orang Jawa, lahir di Jawa, bergaul dan berbahasa Jawa, dan bercita-cita sastra Jawa jadi bacaan dunia, riwayat serba Jawa jadi perpustakaan dunia. Dengan dipustakakan segala yang Jawa, maka Jawa tidak hilang dari dunia, melainkan abadi dan mungkin sekali malah bertkembang. Dinasorus mati beribu tahun yang lalu diketahui kehidupannya karena meninggalkan fosil, manusia Jawa mati 100 tahun yang lalu dapat ditilik gerak sosial kehidupannya karena meninggalkan tulisan-tulisan pada buku. Misalnya karya tulis buku Ranggawarsita.
Untuk mengetahui Serbajawa yang saya alami dan ketahui yang saya kutip dalam buku-buku karya tulis saya, berikut saya kutipkan riwayat singkat keberadaan saya:
1932 lahir di Surabaya, sebagai anak nomer 8. Karena waktu saya lahir Bapak yang sudah diikuti oleh Ibu selama itu (sampai lahir anak ke 8 ) tidak punya tempat tinggal dan tidak punya pekerjaan, maka umur 6 bulan saya dibawa Ibu pulang ke habitatnya. Yaitu di Istana Jayaningratan. Eyang Putri Gusti Jayaningrat, adalah adik Eyang Putri saya, Eyang Putri Prajasuwarna (Prajasuwarna adalah suami yang kedua). Eyang Gusti punya putra putri Bu Gusti (Suryabrata), Eyang Putri punya anak Ibu saya. Sejak kecil Bu Gusti dan Ibu bertempat tinggal di Jayaningratan. Maka ketika umur 6 bulan dibawa ke Surakarta, saya dibawa ke habitat Ibu, Jayaningratan, hidup di sana.
1932-1936 di Jayaningratan. Meskipun sekecil itu, saya ingat Dalem Jayaningrat itu bentuknya bagaimana, ada pintu gerbangnya yang dilalui kereta kuda, pintunya besar, kalau ditutup masih ada pintu kecil yang bisa dilalui orang. Di halaman yang luas ada pohon sawo kecik. Di halaman belakang ada pohon duwet gentong, disebut gentong karena buahnya besar-besar. Di sekeliling istana dialiri serokan yang airnya mengalir kebiru-biruan. Ada kakus umum untuk para abdi dalem terletak di sudut belakang barat-laut, bentuknya terbuka hanya dengan diberi atap. Para yang buang hajat bisa buang hajat berjemaah sambil omong-omong. Bukan hanya benda mati budaya yang terkesan, tapi juga tingkah laku manusianya. Saya ingat misalnya, kalau duduk bersila yang benar, kaki kanan di depan. Menghadap para bangsawan harus laku-dodok. Kepada Ibu saya harus berbahasa Jawa krama, bahasa ngoko hanya kepada orang yang sedrajat atau lebih rendah derajatnya dari saya.
1936-1937 karena Kanjeng Pangeran Jayadiningrat wafat, maka Eyang Gusti (garwanya) beserta keluarga seluruhnya (termasuk Eyang Putri, Ibuku dan saya) pindah ke rumah menantunya (suami Bu Gusti) yaitu Kanjeng Pangeran Suryabrata di Gading Kulon 121. Saya sudah lebih tua, lebih banyak yang saya alami, lihat, dengar. Bentuk bangunannya di depan ada tembok setinggi 4 meter, ada pintu gerbangnya bercat hitam dua tempat, di barat dan timur. Di sebelah barat ada rumah loteng yang digunakan untuk surau. Di sebelah timur ada rumah loteng yang katanya (saya tidak pernah lihat) untuk gudang senjata. Di sebelah depannya tembok pinggir jalan raya ada halaman, ada sederet pohon kelapa. Ibu dan saya dapat kamar di belakang, menghadap halaman yang ada sumurnya di sebelah timur. Saya pernah sakit mata hingga tidak bisa melihat sama sekali (bèlèken). Ke mana-mana digendong Ibu. Dan digoda oleh ndrajeng-ndrajeng putra putri Kanjeng Pangeran Suryabrata. “Siapa aku?” Saya lempar dengan roti yang sedang saya makan, “Ndrajeng Sarwosri! Ndrajeng Ambar!”. Meskipun akhir tahun Ibu menetapkan hidupnya pindah ke Sragen mengikuti anjuran kakak iparnya (mbakyunya Bapak) dalam usaha merapatkan diri ke keluarga suami (Bapak), tetapi sampai zaman Jepang Ibu masih sering mengajak saya pergi ke Istana Suryabratan, cukup dewasa saya mengetahui kehidupan di Suryabratan. Kanjeng Pangeran Suryabrata dibuang ke Ambon oleh Sinuwun X, makanya selama hidup di Suryabratan yang saya ketahui hanya istri-istri serta putri-putrinya saja. Putra lakinya hanya seorang, Ndaramas Teguh.
1937-1941, bersama Ibu seorang menempati rumah di Pasar Kebo Sragen. Ibu mengikuti saran iparnya (Bu Pus) bertempat tinggal di Sragen, ternyata Bu Pus bersama anaknya (Saparas) pindah rumah ke Pati. Hidup sendiri bersama Ibu yang tidak punya keterampilan apa-apa, saya masuk sekolah desa (Sekolah Angka Loro di Sragen Wetan). Hidup bermain dengan anak-anak desa, ya ikut angon kambing, mandi di sungai, mencari cengkerik malam hari di kebun orang, nonton wayang semalam suntuk. Kehidupan cara desa waktu itu saya alami benar-benar. Dari Pak Guru di sekolah saya tahu hidup para petani waktu itu dihargai dua sen per hari per jiwa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana para gadis-gadis desa memocok tebu (memilih ruas tebu yang mulai tumbuh tunasnya untuk ditanam), mereka itu digaji sehari dua sen. Saya menunggui mereka, karena ruas tebu yang dibuang, boleh diambil oleh anak-anak (termasuk saya) dan dimakan. Malam hari, Ibu mengantar tidur saya dengan tiduran membaca macapatan (dinyanyikan) buku Wong Agung Menak, saya ikut menyemaknya. Pada sepenggal cerita harus ganti tembang, Ibu seringkali tebak-tebakan, dengan kalimat akhir dari penggalan cerita terdahulu, maka tembangnya harus ganti tembang apa. Tembang cerita berikutnya selalu dibikin sandi dari tembang yang ceritanya berakhir. Misalnya akhir tembang cerita akhir ada kalimatnya ‘kemambang kèli’ maka penggalan cerita barunya digubah tembang Maskumambang.
1941-1942, karena suasana mau perang mulai terasa, misalnya di kampung-kampung diadakan latihan menyelamatkan diri dari bahaya bom dari udara, lampu harus padam, dan lain-lain, Ibu ketakutan. Bingung karena tidak ada lagi sanak saudara yang bisa dingèngèri, maka Ibu melamar pekerjaan jadi PRT pada Bupati Sragen, KRT. Mr. Wongsonegoro. Ibu dan saya masuk ke Dalem Kabupaten. Ibu menjadi pengasuh (emban) Ndrajeng Sri Danarti, putri ke 4 yang sudah sekolah di SMP di Solo, sedang saya menjadi batur Ndaramas Tripomo, yang sekolah di ELS (Europeesche Lagere School) Sragen. Ke mana pun Ndaramas Tri pergi, saya harus ikut. Karena Ndaramas Tri ini nakal sekali, maka saya sering berontak, lebih baik seharian pergi dari Dalem Kabupaten. Pagi berangkat sekolah (Angka Loro) langsung tidak pulang sampai malam hari, yang saya perkirakan tidak bakal ketemu dengan Ndaramas Tri. Saya lebih suka bermain-main dengan teman-teman lama di Pasar Kebo. Seringkali tidak makan seharian siang hari, karena ya tidak ada orang yang memberi makan. Tapi pulang di Dalem Kabupaten, Ibu pasti sudah menyiapkan makanan yang enak-enak, yang diperoleh dari lorotan (sisa-sisa makanan) keluarga Ndara Kanjeng. Misalnya bakmi, panggang ayam, buahnya durian dibakar, mempelam. Makanan yang bergisi. Suasana lain, setelah jadi baturnya Ndaramas Tri sudah agak mereda, damai, yaitu suasana membaca majalah dan buku. Waktu itu saya sudah kelas 4, di sekolah sudah ada wajib pinjam buku perpustakaan sekolah, dan Gusti (Nyonya) Wongsonegoro suka menyuruh saya pinjam-pinjam buku sekolah, sedang Ndrajeng Tanti, (putri ke 5) yang juga sekolah di ELS Sragen juga suka sekali membaca buku, hingga suasana baca-membaca buku menjadikan kegairahan saya. Persahabatan saya dengan Ndrajeng Tanti menjadi lebih akrap karena sama-sama suka membaca buku dan didiskusikan bersama. Dan karena Mr. Wongsonegoro menyewa post-trommel, kotak yang berisi majalah-majalah tiap minggu diganti, maka saya mulai mengenal bahasa Belanda. Ndrajeng Tanti dengan semangat sering menterjemahkan cerita-cerita di majalah bahasa Belanda tadi.
1942-1945, Jepang masuk, akhirnya Mr. Wongsonegoro dipindahkan jadi Fuku Syucokan di Semarang. Sebelum Mr. Wongsonegoro dipindahkan ke Semarang, Ibu sudah keluar dari Dalem Kabupaten, dan lalu melamar jadi PRT pada Ndrajeng Sarwosri (putra putrinya Suryabratan) yang menjadi istri Mas Soeharto Suryohartono di Surabaya. Alasan Ibu, ikut Mr. Wongsonegoro sudah tidak nyaman lagi (suasana pendudukan Jepang, menekan kehidupan di Dalem Kabupaten Sragen), dan ingin mendekat ke pihak Bapak yang punya saudara di Surabaya (Bu Lik Wibisono di Gersikan Surabaya) dan Bapak masih berkutat di daerah Jawa Timur (Malang, Sidoarjo, Probolinggo). Selain saudara dari Bapak, kakak saya R.M.Soewondo (anak nomer 4 usianya 10 tahun lebih tua daripada saya ~ wafat di Bandung tanggal 15 Juni 2009, selagi saya pulang dari Seminar di Solo ini ke Surabaya) konon sudah bekerja. Jadi Ibu ingin tidak lagi selalu menjadi PRT, tapi berumahtangga sendiri dengan puteranya (saya dan Mas Wondo). Sebagai anak PRT, saya di Surabaya sekolah di SR.Moendoeweg, sekolahnya anak-anak kampung. Maka saya segera akrap dengan anak-anak kampung Surabaya. Menggunakan bahasa Surabaya, melakukan apa yang dialami oleh anak-anak kampung Surabaya, tapi juga terkendali sebab saya tetap ikut bergaul serumah dengan keluarga bangsawan Jawa (puteri Kanjeng Pangeran Suryabrata).
Begitulah kehidupan saya berlanjut (untuk cermin kehidupan saya di Surabaya zaman Jepang, kunjungi www.supartobrata.com Surabaya no Monogatari). Tetap bergaul dengan “rakyat rendahan” Jawa, tapi juga terkendali karena berasal dari bangsawan Jawa. Nilai-nilai budaya rendahan juga saya alami, saya saksikan, saya lihat dan saya dengar, (mencari pocokan tebu, mandi di kali, ikut andhokan merpati, tahu caranya ramai-ramai minum towak, biasa mendengarkan dan terlibat dialog bahasa Surabayan). Tapi juga pergaulan dengan keluarga di rumah yang ningrat dan sopan, misalnya bicara kepada siapa harus krama atau ngoko, memanggil seseorang pun harus disebutkan panggilannya yang sesuai drajatnya dilihat dari sudut pandangnya. Saya selalu memanggil nama orang lain pakai awalan Mas, Mbak, Bu, Pak, Jeng, Dhimas, Nakmas, Ndrajeng, Ndaramas. Ini mendarah daging saya sebagai orang Jawa. Semua saya lakukan tanpa kesukaran ataupun keberatan apa pun.
Pendeknya baik riwayat hidup saya sebelum ke Surabaya, maupun setelah jadi orang Jawa dewasa hingga tua, tata kehidupan saya tetap berorientasi mau pun terlibat langsung denganwong Jawa, di Tanah Jawa, pada keluarga ningrat maupun rendahan. Semua penuh tantangan dan kegembiraan kalau sudah berhasil dilewati. Dan nyatanya saya kini hidup sampai tua, meski zaman terus bergeser, peralatannya untuk hidup kian beraneka dan canggih untuk menopang kehidupan. Tetapi segala peradaban hidup sepanjang umurku yang Jawa, yang saya kenang dengan rasa keindahan dinamika kehidupan dengan cara mengalami sendiri, menyaksikan, menonton dan mendengarkan, itu semua akan lenyap tanpa ada bekasnya. Apalagi orang-orangnya (pelaku budaya) juga berganti. Dengan berkembangnya teknologi, membeludaknya pengaruh global, yang semuanya tadi untuk merangsang kehidupan masa kini, yaitu mengecap kehidupan masa kini dengan cara-cara kodrati, (menggunakan cara indrawi: melihat, mendengar, merasa,) maka segalanya akan lenyap ketika zaman bergeser, ketika generasi berubah. Segalanya hanya untuk dinikmati pada zaman yang berlaku. Setelah zaman berlalu, lenyaplah semua peradaban yang dirasakan dengan cara kodrati, dengan cara indrawi melulu. Kalau pun yang mengalaminya bisa menceritakan pengalamannya dengan cara indrawi (bercerita dengan suara mulut atau gerakan isyarat tangan) itu hanya sebagai “dongeng” saja. Tidak bisa ditularkan kepada orang lain apalagi generasi lain.
Kehidupan yang saya alami di Jayaningratan, di Suryabratan, wujud rumah bangsawan Jawa, pergaulan sosial bangsawan Jawa, seperti yang saya “dongengkan” di acara ini, sudah lenyap. Hanya jadi “dongeng”. Mendengar ceritaku ini sekarang bisa membayangkan bagaimana rumah bangsawan Jawa zaman itu, dan bagaimana pergaulan orang-orang Jawa ketika itu, tetapi begitu Saudara-saudara pergi dari ruang acara ini, yah, semua hanya jadi “dongeng”. Saudara-saudara tidak bisa menceritakan persis seperti cerita saya tadi kepada orang lain. Maka lenyaplah gambaran kehidupan orang Jawa zaman yang saya alami.
Untunglah, sejak masuk sekolah, sejak kelas 1 sampai seterusnya, saya diajari menikmati kehidupan tidak dengan cara inderawi melulu, melainkan (ini yang paling penting dalam sistem pendidikan bangsa dan dalam hal mentransfer budaya!) dengan membudayakan membaca buku dan menulis buku. Dengan kebudayaan saya membaca buku dan menulis buku, apa yang saya alami dalam hidup saya sebagai orang Jawa, segala peradaban dan kesaksian saya tidak semuanya lenyap. Dengan saya tuliskan (pada buku) pengalaman saya hidup sebagai orang Jawa, maka meskipun zaman bergeser, orangnya ganti-ganti, budaya Jawa yang kualami itu masih bisa dirasakan. Tidak lenyap. Dan bisa dibaca lewat karya tulis bukuku (artinya orangnya yang ingin tahu juga harus punya budaya membaca buku, biarpun dia orang asing, bukan orang Jawa. Kalau orangnya tidak punya budaya membaca buku, ya karya tulis bukuku itu sia-sia). Dan kalau mau melestarikan, atau bahkan mengembangkan kembali, dengan membaca buku orang tidak saja bisa membayangkan (menikmati) masa lampau, tapi juga bisa berimajinasi merancang hidup masa depan dengan bekal-bekal kehidupan masa lampau. Bisa merancang masa depan bangsa Jawa dengan bekal peradaban bangsa Jawa masa lampau. Karya tulis buku pengalaman saya masa lalu bisa digunakan untuk merekonstruksi masa depan yang lebih baik. Membaca buku dan menulis buku adalah kiat hidup modern, kiat hidup untuk menengok masa lampau, dan bisa digunakan sebagai bahan perbaikan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Setidaknya dengan “dongeng” saya jadikan karya tulis buku, saya sudah mengabadikan serbasedikit dari kehidupan saya sebagai orang Jawa. Ini sudah pasti berguna untuk masa kini dan mendatang. Entah digunakan untuk sekedar mengenang zaman dulu, atau memberikan rangsangan untuk menyusun masyarakat Jawa yang akan datang. Karena itu saya yakin (dan sudah banyak buktinya) menulis buku dan membaca buku adalah kebudayaan yang memperpanjang umur manusia. Dan kalau yang dibaca dan ditulis tentang bangsa Jawa, maka kebudayaan Jawa pun akan panjang umurnya. Tidak lenyap.
*
Saran:/
Kalau dalam seri seminar “Wong Jawa Ilang Jawane” ini ada maksud untuk mencari identitas tentang bangsa Jawa, saya kira dengan menuliskan “dongeng” saya menjadi karya tulis buku, saya sudah “berhasil” mempertahankan agar “Wong Jawa ora ilang Jawane”. Meskipun ini hanya sedikit dari usaha yang besar (seri seminar). Sedikit karena apa? Karena suku bangsa Jawa yang menulis pengalamannya pada buku sedikit, dan yang membacanya juga sedikit. Bagaimana bisa urun lebih besar, kalau 95% orang Jawa tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku? Dan menurut gejalanya, dengan berkembangnya teknologi modern yang lebih memanjakan penggunaan indrawi (terutama melihat dan mendengar, radio, TV, telepon, HP), presentase orang Jawa tidak berbudaya membaca buku dan menulis buku meningkat naik menjadi lebih dekat lagi ke 100%. Kian engganlah bangsa Jawa belajar berbudaya membaca buku dan menulis buku. Sebab, melihat dan mendengar itu kodrat, tidak usah diajari orang bisa menikmati penglihatan dan pendengaran. Sedang membaca buku dan menulis buku itu bukan kodrat, untuk menjadikan kiat hidup harus belajar terus-menerus dulu, harus berbudaya dulu, baru bisa digunakan untuk menikmati kehidupan.
Dengan membludaknya alat-alat yang memanjakan kodrat, membuat orang jadi enggan belajar untuk menikmati kehidupan dengan susah payah harus belajar dulu. Kalau menonton TV sudah tahu nikmatnya tanpa harus belajar. Lain dengan mengemudikan mobil. Harus belajar dulu, harus dewasa dulu. Begitu juga penikmatan hidup lain misalnya pemain piano, pemain bulu tangkis. Harus ada alatnya, harus ada latihannya mempergunakan alat itu. Baru bisa menikmati setelah lancar berlatih. Apalagi membaca buku dan menulis buku. Untuk bisa menikmati latihannya bukan hanya sebulan (mengemudi mobil) atau setahun (main piano), melainkan harus dilatih tiap hari selama paling tidak 12 tahun usia dini. Mengapa kian lama presentase tidak-berbudayanya orang Jawa membaca buku dan menulis buku menanjak ke angka 100%? Karena di sekolah selama 12 tahun usia dini, sekarang tidak ada pelajaran membaca buku dan menulis buku yang dilatih setiap hari ketika masuk kelas. Syaratnya masuk sekolah, asal bisa membaca a-b-c, masuk. Tapi selanjutnya tidak dibudayakan membaca buku dan menulis buku. Maka setelah lulus sekolah SMA, anak-anak bangsa Jerman rata-rata telah membaca 32 judul buku, anak bangsa Belanda 30 buku, anak Rusia 12 buku, anak New York 32 buku, anak Swiss 15 buku, anak Jepang 15 buku, anak Singapura 6 buku, anak Malaysia 6 buku, anak Brunai 7 buku, anak Indonesia 0 buku (penelitian Drh Taufik Ismail 1996).
Nah, sebenarnya untuk mempertahankan agar “Wong Jawa ora ilang Jawane” yang dimaksud dengan seri seminar ini, salah satunya tiru saja cara saya mengabadikan budaya Jawa. Yaitu perbanyak saja manusia Jawa yang menulis buku dan membaca buku, terutama buku-buku bahasa Jawa. Caranya memperbanyak orang Jawa berbudaya membaca buku dan menulis buku bagaimana? Berlatih (dengan guru) membaca buku dan menulis buku tiap hari selama paling tidak 12 tahun usia dini (dari klas 1 SD – klas 12 SMA). Dengan begitu, lulus SMA putera Indonesia sudah bisa mencari ilmu sendiri secara mandiri, tidak tergantung pada lulus UNAS yang hendak meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Contonya, Ayip Rosidi, bisa hidup berbakti menyemarakkan bahasa daerah tanpa mengantongi ijazah.
Berbudaya membaca buku dan menulis buku bukan saja berguna untuk mempertahankan agar “Wong Jawa ora ilang Jawane”, melainkan juga bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa.
Coba, perhatikan uraian berikut ini:
Anjing dan kucing (binatang) , untuk mencapai kenikmatan hidupnya (kawin, makan) menggunakan insting. (Binatang: + insting).
Manusia (purba), untuk mencapai kenikmatan hidupnya, menggunakan insting (panca indra) dan alat (making tool animal). Seorang petani bisa menanam padinya di sawah dengan subur setelah dia melihat dan mendengar cara menanam padi tetangganya (indrawi) lalu mencangkul sawahnya (pakai alat pacul). Supaya bisa hidup (mendapat pekerjaan) seseorang harus menjadi sopir taksi (melihat dan mendengar), maka ia berlatih nyopir mobil sebulan, sudah lancar, dia dapat hidup dengan nyopir taksi (alatnya mobil). Seseorang ingin hidup dengan main musik (melihat dan mendengar), maka ia harus belajar main piano selama setahun, akhirnya ia pun menikmati hidup dengan main piano (alatnya piano). Pendeknya untuk mendapat pekerjaan (menikmati hidup) manusia harus menggunakan (terampil) alat. (Manusia purba: insting + alat)
.
Anjing dan kucing, untuk mencapai kenikmatan hidupnya, tidak pernah menggunakan alat apa-apa. Maka dari itu kalau manusia mencapai kenikmatan hidupnya tidak menggunakan alat apa-apa, ia sama dengan anjing dan kucing. Mencapai kenikmatan hidupnya hanya dengan indranya saja. Contoh orang yang menikmati hidup tanpa menggunakan alat yaitu: pelacur, maling, kawin-cerai dengan orang kaya, pembunuh. (Meskipun di sini, akal juga berperan serta pada manusia-manusia tadi).
Tetapi, dengan hanya mahir mempergunakan alat saja, orang tidak bisa menjadi dosen, insinyir, hakim, dokter (profesi modern). Sebab untuk menikmati hidup dengan profesi modern, ada tambahan syarat lagi: harus berbudaya membaca buku dan menulis buku. Tidak mungkin orang (meskipun kuliah) menjadi dokter, tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku (hanya mendengarkan kuliah melulu = melihat dan mendengar = kodrat indrawi) bisa jadi dokter.
Manusia (modern): untuk mencapai kenikmatan hidupnya berlaku rumus: (Manusia modern: insting + alat + membaca buku dan menulis buku).
Jadi membaca buku dan menulis buku adalah kiat hidup modern.
Kapankah membaca buku dan menulis buku menjadi kiat hidup manusia, sehingga disebut modern? Sejak filosof Yunani Plato (428-347 S.M) mendirikan sekolah filsafat yang dinamai Academus, sesuai dengan pahlawan legendaris Athena. Karenanya sekolah itu dikenal sebagai Akademi. Dan sejak itu beribu “akademi” didirikan di seluruh dunia. Plato adalah murid Socrates. Socrates (470-399 S.M) adalah tokoh yang paling banyak menyiarkan ilmunya dalam seluruh sejarah filsafat, sehingga dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa selama hampir 2500 tahun ini. Socrates banyak menyiarkan pemikiran filsafatnya hanya melalui pidato-pidatonya (bersuara, didengarkan, indrawi). Juga ketika dia mengadakan pembelaan atas hukuman mati minum racun oleh peengadilan, hanya dipidatokan. Baik pemikiran filsafatnya maupun pidato pembelaannya menjadi misi kemanusiaan yang tersebar di seluruh dunia hingga berabad-abad karena ditulis oleh Plato setelah kematian Socrates. Plato menuliskan pidato pembelaan Socrates pada buku Apologi. Di samping Apologi, Plato juga melestarikan (ditulis jadi buku) seluruh karya utama Socrates (yang dipidatokan, diucapkan secara indrawi) ~ misalnya kumpulan Epistles dan kira-kira 25 Dialog filsafat yang pernah didiskusikan dan dipidatokan Socrates. Kita bisa mendapatkan karya-karya ini (berupa buku) sekarang berkat tindakan Plato menuliskannya jadi buku yang bisa dibaca dan dipelajari sejak Plato mendirikan akademi. Kalau tidak jadi buku dan dibaca pada buku, apa manfaat filsafat Socrates yang diuraikan secara lisan demi untuk menata kehidupan manusia ~ kebenaran, etika, kebaikan dan kejahatan ~ masa depan yang ideal? Socrates tidak pernah menuliskan apapun, meskipun banyak orang sebelumnya melakukan (menulis). Muspra! Buku, ditulis dan dibaca, itulah kuncinya memperbaiki kehidupan manusia masa depan.
Baik Yesus, maupun Socrates adalah conto tokoh yang penuh teka-teki, juga bagi rekan-rekan sezaman mereka. Tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya, maka terpaksa kita mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka menentang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Dan akhirnya, aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Yesus dan Socrates tidak menuliskan sekalimat tentang ajaran-ajarannya. Plato menyelamatkan dan mengembangkan ajaran Socrates dengan cara menuliskannya jadi buku. Lucas, Mateus, Markus dan Johanes menyelamatkan, mengabadikan, menyiarkan dan mengembangkannya dengan menulis ajaran Yesus jadi Kitab Injil.
Muhammad juga tidak menulis sekalimat pun aktivitasnya. Agama Islam berhasil disiarkan dan banyak pemeluknya hingga masyarakat sekarang lewat pembacaan Al-Qur’an yang ditulis dan dikumpulkan oleh Zaid bin Tsabit, yang sejak umur 12 tahun menjadi “sekretaris” Rasulullah, menulis wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Wahyu tertulis itu merupakan bait-bait Al-Qur’an. Al-Qur’an tidak pernah dibukukan secara utuh pada zaman Nabi SAW. Namun ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tulisan-tulisan Al-Qur’an yang berserakan dikumpulkan dan disatukan. Zaid bin Tsabit yang diperintahkan oleh Abu Bakar yang menyetujui usul Umar bin Khattab, memimpin kodifikasi Al-Qur’an yang semula tulisan lepas-lepas berserakan itu.
Satu contoh lagi, bahwa untuk memenuhi kemakmurannya, manusia modern selain kodrat indrawinya serta menggunakan alat, juga harus membaca buku dan menulis buku. Misi Socrates disiarkan lewat Apologi, Epistles, misi Yesus lewat Kitab Injil, misi Muhammad lewat Al-Qur’an. Semua berhasil diabadikan, disiarkan, dipeluk, dianut dipercaya lewat tulisan buku dan dibaca intensip pada buku.
Contoh yang lain yang tulisannya pada buku mempengaruhi dianut dan dipercaya masyarakat luas adalah (sekedar contoh) buku tulisan Karl Marx (1818-1883 Das Capital 1867), Adolf Hitler (Meinkamf), Charles Darwin (1809-1882, The Descent of Man, 1871, The Origin of Species, 1859), Sigmund Freud (1856-1939, Libido Sexualita, apa yang kita kerjakan desakan dari seks), Sir Isaac Newton (1642-1727 teori gravitasi, tentang jatuhnya apel), Dale Cornegie (How to Win Friends and Influence People), Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Karen Armstrong ( A History of God), Thomas Stamford Raffles (The History of Java), Ranggawarsita, R.A.Kartini, Tan Malaka, Bung Karno, Sutan Syahrir, Himawan Soetanto (Yogyakarta 19 Desember 1948), Nurcholis Madjid, Mario Teguh, Andrea Hirata. Siapa pun yang membaca bukunya dengan intensif pasti mendapatkan tambahan ilmu, dan dengan tambahan ilmunya tadi dirinya tentu lebih siap menghadapi zaman karena banyak akal dan daya upaya berprakarsa. Takdirnya berubah daripada sebelum membaca buku-buku tadi. Tetapi kalau sepanjang hidupnya tidak membaca buku sama sekali, orang akan hidup sebagaimana kodrat-fitrah-alamiahnya. Yaitu bodoh. Miskin. Ketinggalan zaman. Maka berbudaya membaca buku dan menulis buku, adalah kiat hidup modern. Berbudaya membaca buku berpotensi mengubah takdir menjadi yang lebih baik.
*
Manusia modern (yang punya kiat berbudaya membaca buku dan menulis buku) telah dimulai sejak Pluto (428-347 S.M.) mendirikan sekolah filsafat Academus. Kalau suku bangsa Jawa yang hidup sekarang ini tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku, maka manusia tadi adalah orang kuna atau premitif yang hidup di zaman modern. Hidup ketinggalan zaman 25 abad (4 abad S.M + Abad 21 kini).
Untuk memuaskan hidupnya tiap makhluk rumusnya:
Binatang (insting-kodrati);
Manusia primitif (insting-kodrat-indrawi + menggunakan alat);
Manusia modern (insting-indrawi + menggunakan alat + membaca buku dan menulis buku)
Berbudaya membaca buku dan menulis buku mutlak menjadi kiat hidup modern. Sebab dengan berbudaya membaca buku dan menulis buku, manusia bisa mengubah takdirnya, yaitu bisa menjalani profesi modern (jadi guru, dokter, insinyir, professor, sastrawan). Kalau tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku mulanya hanya bisa jadi petani dengan cangkulnya (hidup zaman dulu), atau sopir taksi dengan mobilnya (hidup zaman sekarang tetapi pengetahuannya kuna). Rumusnya: (kodrat-indrawi + menggunakan alat). Tidak bisa jadi dokter, hakim, insinyir, sastrawan, karena tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku, yang rumusnya (kodrat-indrawi + menggunakan alat + berbudaya membaca buku dan menulis buku).
Agar berbudaya membaca buku dan menulis buku tidak saja mencerdaskan manusia Jawa yang hidup modern pada zaman modern, tetapi juga menjadi “Orang Jawa ora ilang Jawane”, maka sebaiknya diperbanyak penerbitan buku-buku bahasa Jawa. Terutama di sekolah di mana anak-anak Jawa belajar membaca buku dan menulis buku, di sana harus tersedia banyak buku bahasa Jawa, dan pengajaran membaca buku selama 12 tahun juga dengan diajarkan pembacaan buku bahasa Jawa.
Demikianlah sekelumit saran, bagaimana agar “Wong Jawa ora ilang Jawane”. Semoga bisa diterima dan dilaksanakan. Amin.
Surabaya, 5 Juni 2009.

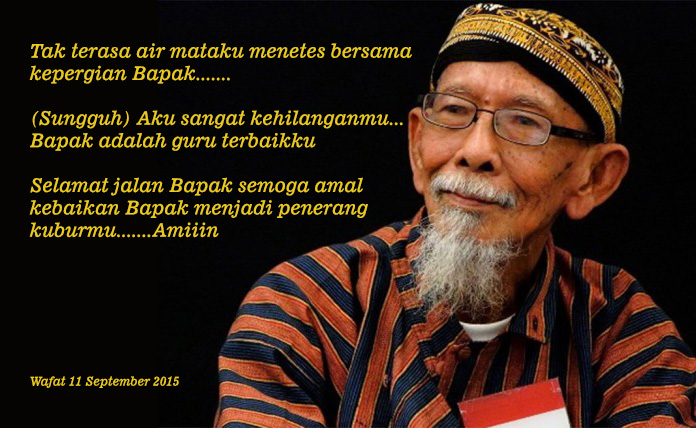



































Dahsyattt!
Dperbolehkan untuk mengambil isi ceritanya Eyang ?
sarujuk…
apek tenaaaan
Kulanuwun,
Weleh weleh andharane kangmas Suparto iki dawa banget. Kamangka saiki iki aku lagi neng paran, dadi ora isa jenak leh ku maca. Mengko wae nek wis tekan omah takwacane maneh.
Nuwun, Young_kong Wongso Lo.
Weelllaaaaadalaaah …. Maca seratane Pak “PENI” Suparto ki — embuh cerkak, novel, roman, makalah, esaay — rumangsaku kok pada: nggregetne, lucu, megelke, mangkelke, wasis, pinter, ….. Yen dikeparengake mbiji, karya Pak Suparto sing apik dhewe, kandel dhewe, dakwaca bola-bali ora mboseni, yaiku: “Donyane Wong Culika”.
Sukses Pak Suparto, mugi tansah pinaringan sehat seger waras, supados nyerat terus, berkarya senantiasa. AMien
D. Jupriono
Fakultas Sastra, Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya
Nuwun sewu nderek ngangsu kawruh bab babagan jawi pak..
Ndherek pitaken punapa asma Jayaningrat punika nunggak semi? awit eyang kula ingkang rumiyin asma Gajah Talana utawi Jayaningrat, lajeng kagungan putra Ky Hanggawijaya/Djayawinata/Jayaningrat I (putra mantu HB I) ingkang sumare ing Srumbung Magelang (saking Raden Sunu Agustriyanto, trah Projosuwiryo, Temon , KP, DIJ)