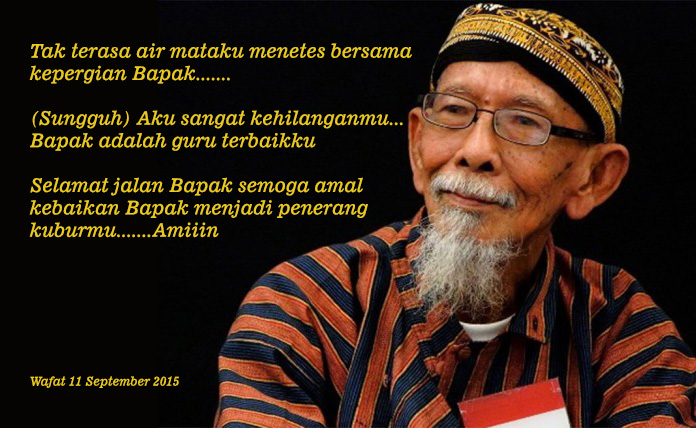Riwayat Hidup Suparto Brata
Tulisan ini saya temukan di Hardisk Bapak yang baru saja saya copy pada tanggal 21 Agustus 2016 dari Adik saya Neo Semeru Brata, yaitu sebuah pengantar untuk buku berjudul HARI JADI KOTA SURABAYA, 682 tahun Sura Ing Baya, barangkali bermanfaat bagi yang memerlukan.
KATA PENGANTAR DARI PENGARANG
Buku ini jelas buku sejarah Kota Surabaya. Tetapi bukan buku pelajaran sejarah dan bukan buku teks sejarah secara akademis yang menuntut pembuktian adanya situs, prasasti, artefak, dokumen dan semacamnya. Ini buku sejarah Kota Surabaya sebab yang ditulis adalah pengalaman hidup penulisnya, yaitu pengalaman hidup saya, Suparto Brata. Yang saya tulis adalah kesaksian saya, apa yang saya ingat, yang pernah saya rasakan, saya lihat, saya dengar, baik saya dengar sendiri maupun saya dengar dari cerita orang lain, dan juga ditambah pemikiran saya, pengetahuan saya dari membaca buku. Apa yang saya saksikan, saya dengar dan pemikiran saya tadi belum tentu benar menurut faktanya, mungkin hanya ilusi, dan mungkin sangat sepele, sangat tidak penting untuk diketahui pembaca, namun karena pernah kecanthol pada ingatan saya, maka terus saya tulis di buku ini. Penting dan tidak penting untuk orang lain, namun terus kuingat ketika menulis buku ini, dan tidak akan diketahui orang lain kalau tidak saya tulis. Jadi ya saya tulis saja. Dan itu fakta sejarah.
Jadi menulis buku ini sebenarnya saya mendongeng pengalaman saya hidup di Surabaya.
Karena saya menulis ingatan saya, menulis pemikiran saya, maka lebih sering saya menulis perincian sebab dan akibat sesuatu persoalan. Saya tulis apa yang saya lihat pada waktu awal dan saya uraikan apa selanjutnya yang saya lihat kemudian hari. Bentuk tulisan saya jadi cerita uraian sesuatu yang saya lihat awalnya sampai saya lihat akhirnya bagaimana. Jadi pada buku ini saya tidak bercerita secara kronologis kejadian yang saya lihat awal kehidupan saya dari waktu ke waktu, secara urut sampai akhir hidup saya ketika menulis buku ini, sebagaimana biasanya buku sejarah ditulis.
Meskipun begitu, saya menulis buku ini memang bertujuan menulis buku sejarah Kota Surabaya, di mana saya secara runtut hidup dari bocah dulu, lalu dewasa, lalu tua, lalu menulis buku ini. Maka seharusnya urut-urutan ceritanya juga harus begitu supaya pembaca juga bisa membayangkan bagaimana kejadian-kejadian di Kota Surabaya menurut kronologis waktunya. Tapi kalau saya tulis seperti itu, konteks sebab dan akibatnya jadi kurang jelas. Mungkin pembaca hanya tahu kejadian demi kejadian masa lampau begitu saja, tidak mempelajari atau menyimpulkan sejarah sebab dan akibatnya. Padahal buku sejarah tulisan saya ini sangat memberi kesan dan pesan soal sebab dan akibat yang terjadi, yaitu yang saya saksikan waktu dulu itu, akibatnya baru kentara saat sekarang karena saya menyaksikan juga kejadian atau keadaannya yang kemudian itu, dan baru sekarang bisa saya tulis. Dengan kesan dan pesan seperti itu, sekalipun itu hanya kesimpulan saya seorang, mungkin kesimpulan tadi tidak benar, namun selain pembaca tahu sejarah peristiwanya, dari sejarah sebab akibat tadi pembaca juga bisa mengambil manfaat untuk menyusun kehidupan di Surabaya masa yang akan datang. Akibat yang jelek, tolong dihindari untuk lelakon yang akan datang, akibat yang baik bolehlah ditiru demi perbaikan hidup di Surabaya masa depan. Betapa pun sejarah adalah peristiwa masa lalu, jadi pelajaran masa kini, untuk mengunstruksi kehidupan masa depan. Tanpa mengetahui sejarah masa lalu, orang mengunstruksi masa depan secara membabi buta, dan sangat mungkin melakukan lagi dan lagi kesalahan-kesalahan dan kegagalan hidup masa lampau. Melakukan berulang kesalahan perbaikan hidup berarti memperbaiki cara hidup yang sia-sia. Pasti bukan keinginan para pembaca yang akan menjalani hidup di Surabaya masa depan.
Menceritakan secara kronologis memang juga memperjelas waktu-waktu kejadian. Supaya gampang para pembaca mengingat kronologis kejadian yang saya alami di Surabaya, maka berikut saya sampaikan dulu riwayat hidup saya. Di situ saya catatkan tahun-tahun kehidupan saya, agar jelas kejadian yang saya tulis ini saya alami ketika apa, zaman apa dan suasananya bagaimana, tahun berapa.
Mudah-mudahan riwayat hidup secara kronologis di mana saya berada ini sangat menolong pembaca membayangkan yang terjadi di Surabaya dari tahun ke tahun secara kronologis juga. Dan itulah sejarah Kota Surabaya dari waktu ke waktu.
Saya mulai menulis cerita ini tahun 2011, menjelang peringatan hari jadi Kota Surabaya yang ke 718, 31 Mei 2011. Merupakan kegiatan saya untuk memperingati hari jadi kota kelahiranku Surabaya secara personal. Tapi oleh karena banyaknya kesibukan lain, penulisan ini tidak juga selesai-selesainya. Kalau kemudian terbit menjadi buku seperti ini, saya sangat berterima kasih kepada Penerbit, dan bersyukur Alhamdulillah. Semoga buku ini sangat berguna seperti apa yang saya amanatkan.
Sebenarnya, menulis cerita Surabaya Zaman Jepang begini sudah pernah saya lakukan pada bulan Mei 1983. Tulisan tadi dimuat bersambung di suratkabar Jawa Pos tanggal 30 Mei – 21 Juni 1983, selama 20 hari. Seperti biasanya tulisan yang dimuat di koran tadi saya kliping. Aman jadi dokumen saya. Namun, pada tahun 2005, saya ingin merayakan hari jadi Kota Surabaya secara pribadi dari nurani saya. Cara merayakan hari jadi Kota Surabaya secara peribadi maupun bersama begitu sering saya lakukan. Biasanya berwujud tulisan, saya siarkan di suratkabar, atau malahan tulisan yang berwujud buku sebagai dokumen. Yang berwujud buku misalnya buku berjudul HARI JADI KOTA SURABAYA, 682 tahun Sura Ing Baya, saya kerjakan demi membantu tugas yang diemban Kolonel Laut Dokter Sugiyarto Tirtoatmojo dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 31 Mei 1975. Secara peribadi juga pernah saya buatkan novel untuk memperingati Hari Jadi Kota Surabaya, yaitu novel berjudul Saputangan Gambar Naga, (PT.Grasindo Jakarta, 2003) untuk memperingati 700 tahun Hari Jadi Kota Surabaya. Nah, tahun 2005, muncul keinginan tiba-tiba merayakan Hari Jadi Kota Surabaya. Tidak sempat menulis buku. Maka kliping koran Jawa Pos Surabaya Zaman Jepang saya gunting-gunting menjadi buku kecil, saya fotocopy sebanyak 10 jilid. Agar berupa buku, wajah sampulnya saya beri tulisan Katakana, di bawah saya tulisi EDISI SURABAYA USIA 713 TAHUN. Buku kecil tadi habis saya berikan kepada orang-orang atau pejabat yang saya kira berperhatian dengan sejarah Kota Surabaya.
Beberapa tahun selanjutnya perhatian saya pada hal-hal yang lain. Tahun 2010 saya baru sadar bahwa tulisan dokumen Surabaya Zaman Jepang yang pernah dimuat di Jawa Pos dulu sudah tidak ada lagi di kliping saya. Buku kecilnya juga sudah habis saya bagikan. Padahal saya sedang ingin menulis tentang Kota Surabaya yang saya ketahui sejarahnya. Saya sedang menulis Nama-nama Jalan Kota Surabaya 1942. Yaitu nama jalan sebelum Balatentara Dai Nippon datang di Surabaya. Nama-nama jalan yang dibuat oleh pemerintah Gemeente Soerabaia itu masih lengkap terpampang di setiap ujung potongan jalan yang saya saksikan pada zaman Jepang. Itu yang sedang saya tulis. Tapi jadi geragapan menyadari dokumen tulisanku Surabaya Zaman Jepang tidak saya miliki lagi. Maka penulisan buku Nama-nama Jalan Kota Surabaya 1942 saya hentikan, beralih menggali lagi dokumen Surabaya Zaman Jepang. Tetapi karena tidak mungkin lagi menulis secara urut seperti yang pernah saya tulis di Jawa Pos, maka penulisan baru Surabaya Zaman Jepang jadinya seperti buku ini. Saya tulis dengan banyak ingatan yang muncul, dan yang saya alami tahun-tahun selanjutnya, maka akhirnya saya putuskan bebas merdeka menulis apa saja yang teringat di benak saat menulis buku ini.
Namun, karena inspirasinya dari kehilangan dokumen Surabaya Zaman Jepang, maka buku ini tetap saya juduli Surabaya Zaman Jepang.
Ada lagi alasannya mengapa saya juduli Surabaya Zaman Jepang. Sebab pada zaman Jepang tahun 1942 itulah saya kembali dan mulai menetap di Surabaya dalam umur yang cukup jelas mempunyai ingatan, pikiran, kesan kenangan dan sebagainya. Sangat indah kalau ditulis.
Mari, kita mulai menyemak riwayat hidup saya.
*
Riwayat para leluhurku.
Saya dilahirkan di Surabaya Plaza hari Sabtu Legi 19 Sawal 1862, tahun Jawa Jé, (1350 Hijriah), sama dengan 27 Februari 1932. (Tapi di KTP/ijazah tertulis 16 Oktober 1932, ngawur ketika untuk penulisan di ijazah SMP 1950). Waktu saya lahir tahun 1932, Surabaya Plaza masih merupakan Centrale Burgelijk Hospital (CBZ) atau Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Saya merupakan anak ke-8 dari pasangan Bapak-Ibu saya, R.Soeratman Bratatenaja – R.A.Djembawati (anak ke-8 berarti Bapak dan Ibu telah berjodohan setidaknya lebih dari 16 tahun), namun hanya anak nomer 4 (R.M.Soewondo) yang bertahan hidup. Anak yang lain meninggal ketika masih bayi. Sedang antara saya dengan anak nomer 4 jaraknya 10 tahun. Kakak lahir 1922.
Leluhurku dari pihak Bapak.
Pada waktu saya dilahirkan, Kakak saya disekolahkan di Rooms-Katholiek HIS di Semeroestraat di Malang, diasramakan dan dibeayai oleh kemenakan ayah bernama Saparas, yang merasa berhutangbudi kepada ayah; dengan begitu pembeayaan hidup Kakak tidak bergantung kepada ayah. Menurut cerita Ibu, tahun-tahun kelahiran Kakak adalah zaman jaya-jayanya pasangan Bapak dan Ibu. Bapak bekerja sebagai keurmeester atau ‘mantri kewan’ (1920-1924), yaitu pejabat pemeriksa kesehatan hewan yang mau disembelih, gajinya dari pemerintah besar. Bapak dan Ibu menempati rumah besar di Jalan Jasem Sidoarjo. Selain Ibu, di rumah Jasem Bapak juga menanggung hidup ibunya (Eyang Putri), tiga orang adik-adiknya (Paklik Suyit, Bulik Sri, Paklik Har), seorang kemenakannya (Mas Saparas) yang sudah dewasa. Mas Saparas ini putera dari mbakyunya Bapak, bernama R.A.Wiryopuspito (Budhe Pus).
Waktu itu (1922-an) Budhe Pus mengikuti suaminya hidup di Krapyak, Pasar Kebo, Sragen. Rumah di Pasar Kebo ini saya dan Ibu pada tahun 1937-1941 bertempattinggal.
Saudara Bapak yang tidak ikut Bapak (1922-an) selain Budhe Pus, ada lagi Bulik Tiyah, adik Bapak. Bulik Tiyah menikah dan ikut suaminya seorang bangsawan (Ndara Bei) di Kauman Solo. Anaknya Bulik Tiyah, Ndrajeng Ties, oleh Ndara Bei dikawinkan dengan seorang laki-laki tua tetapi kaya, berumah di Kemlayan Solo. Tahun 1950 nanti saya dan Ibu pernah mondok di Kemlayan situ.
Selain Budhe Pus dan Ndrajeng Ties yang nanti penting dalam hidup saya adalah Bulik Sri. Bulik Sri yang ketika perawannya ikut Bapak di Jasem Sidoarjo kemudian bekerja jadi perawat di CBZ (Rumah Sakit Simpang Surabaya), ketemu jodohnya, yaitu Raden Mas Wibisono yang sedang praktek jadi dokter muda. Perjodohan ini kemudian berhasil membuat rumah cukup besar di Gresikan gang 2 nomer 23 Surabaya. Baik Paklik Wibisono maupun rumah Gresikan gang 2 nomer 23 Surabaya ini akan menggores kehidupan saya yang saya tulis di buku ini.
Keluarga Bapak di Jasem Sidoarjo (1920-1924) dikerubuti oleh keluarga dari Bapak. Mereka itu manja. Ibunya Bapak (Eyang Putri) yang ikut berumah di Jasem Sidoarjo banyak permintaan untuk membeayai keluarganya. Sedang Ibuku tersisih dan tertindih di antara keluarga pihak Bapak tadi. Misalnya untuk merayakan pernikahan Bulik Sri (1921), Paklik Suyit minta dibelikan mobil untuk mengangkuti para tamu dari Solo ke Surabaya. Dituruti oleh Bapak. Kata Ibu mobil tadi minta beaya banyak, karena Paklik Suyit tidak tahu tehnik mengoperasikan mobilnya. Eyang Putri minta agar Bapak membeayai seorang kemenakannya (Mas Saparas = cucu Eyang Putri) disekolahkan jadi dokter. Karena pembeayaan keluarga berat, Bapak memakai uang jawatannya. Maka Bapak dipecat dari pekerjaannya. Jatuh miskin. Kemenakan (Mas Saparas) yang disekolahkan jadi dokter tidak bisa melanjutkan studynya. Kemenakan ini gagal jadi dokter. Tapi berhasil bekerja jadi sipir penjara besar di Sragen (kota orangtuanya, Budhe Pus). Masih jejaka kedudukan Mas Saparas jadi sipir bui cukup tinggi, dapat rumah dinas, kaya. Karena merasa berhutangbudi disekolahkan Bapak sampai tingkat mahasiswa, tahu Bapak jatuh miskin, Mas Saparas lalu ganti membeayai Kakak (R.M.Soewondo) bersekolah. Kakak diasramakan di Sekolah Katholik di Malang selama 10 tahun (1930-1940), yaitu sejak kelas satu HIS (setingkat SD, 7 tahun tamat) hingga lulus MULO (setingkat SMP, 3 tahun tamat).
Kakak R.M.Soewondo lulus MULO tahun 1941. Keluar asrama sekolah di Malang, Kakak ikut buliknya (Bulik Sri, adik Bapak yang sudah menikah dengan R.M.Wibisono berumah di Gersikan gang 2 nomer 23) di Surabaya, dan dikursuskan tehnik radio tetap dibeayai oleh Mas Saparas. Selesai kursus setahun dapat ijazah, Kakak R.M.Soewondo dapat pekerjaan di Marine Ujung Tanjungperak, tempat pangkalan Angkatan Laut Belanda di Surabaya. Bekerja belum lama di bagian radionya kapal-kapal, Jepang datang mendarat di Surabaya. Kakak masih tetap dipakai sebagai pekerja di Marine Ujung Tanjungperak, meskipun kepemilikannya jadi punya Kaigun, Angkatan Laut Jepang (1942-1945). Tapi tahun 1944 Kakak keluar dari Marine Ujung, pindah bekerja pada Jawa Denki Jigyo-sya (jawatan listrik) di Gemblongan Surabaya.
Waktu saya lahir di Surabaya 1932, Bapak sedang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal tetap, dan hidup mencari pekerjaan di sekitar daerah Gupermen (pemerintahan Belanda) di Jawa Timur.
Leluhurku dari pihak Ibu.
Karena Bapak tidak punya pekerjaan, maka Ibu membawa saya yang masih bayi umur 6 bulan ‘pulang’ ke rumah besar (istana) Gusti Kanjeng Pangeran Hario Djajadiningrat di Gajahan Surakarta Hadiningrat. Waktu kanak-kanak dulu Ibu hidup di situ ikut Buliknya, yaitu isteri GKPH Djajadiningrat. R.Ay.Djajadiningrat adalah adik Nenekku (R.Ay.Projosuwarno). R.Ay.Djajadiningrat dan Nenek R.Ay.Projosuwarno adalah putera-putera dari GKPH Kusumabrata II, istananya juga di Gajahan Solo, tapi sebelah timur dekat Alun-alun Kidul. Sedang istana GKPH Djajadiningrat di Gajahan sebelah barat.
Nenek R.Ayu.Projosuwarno menikah dua kali. Yang pertama dengan Eyang Wirasaraya punya rumah di Kedunglumbu Solo. Lahir seorang anak perempuan, yaitu Ibuku. Berpisah dengan Eyang Wirasaraya, Eyang putri menikah dengan R.M.Projosuwarno. Dan Ibuku sejak kecil dititipkan pada Buliknya hidup bermain sampai dewasa di istana GKPH.Djajadiningrat.
Tahun 1932-1937 saya ikut Ibu di Istana Djajadiningratan.
Karena Bapak tidak punya pekerjaan dan tempattinggal tetap di Surabaya, maka Ibu memutuskan pulang ke Solo, ke istana GKPH Djajadiningrat di mana sewaktu kecil hingga perawan Ibu hidup berbahagia berkumpul sesama keluarga besar seleluhur. Tapi Ibu kini ‘pulang’ ke sana bawa bayi, Ibu bukan kanak-kanak lagi. Teman sepermainan Ibu juga sudah dewasa dan tidak di sana lagi. Di rumah besar itu, Ibu dan saya (bayi umur 6 bulan) hanya menumpang tempat saja. Artinya bisa dapat kamar tempat tinggal, tidak usah menyewa, karena masih keluarga seleluhur. Sandang pangan harus cari sendiri. Kebetulan Ibu mendapat harta warisan dari Kakek (R.M.Ng.Wirasaraya). Menurut cerita Ibu, Kakek R.M.Ng. Wirasaraya dan Nenek R.Ay. Projosuwarno sudah berpisah cerai sejak Ibu masih bocah, makanya Ibu sewaktu bocah ikut Buliknya di Djajaningratan, terpisah dari Kakek yang hidup berumah di Kedunglumbu Solo. Warisan Ibu didapat dari Kakek R.M.Ng.Wirasaraya. Selain barang-barang rumah tangga seperti bokor, almari, dan sebagainya, rumah dan pekarangannya di Kedunglumbu Solo itu juga diwariskan kepada Ibu dan adik tiri Ibu, yaitu Bulik Doeri Darmosaroyo. Putera Kakek R.M.Ng. Wirasaraya memang hanya dua orang puteri itu.
Ibu sejak kecil diperlakukan sebagai puteri bangsawan di istana Djajadiningratan, tidak punya keterampilan untuk hidup mandiri. Ketika ‘pulang’ ke istana Djajadiningratan (1932) membawa saya, bayi umur 6 bulan juga tidak dapat bekerja yang mendapatkan penghasilan apa-apa. Maka hidup membesarkan saya sejak bayi hanya dengan menjuali barang-barang warisan yang Ibu peroleh dari Kakek Wirasaraya. Tentu saja harta warisan itu akhirnya habis.
Dalam usaha membesarkan saya seorang diri, Ibu selalu berusaha mendekati untuk bersatu kembali dengan Bapak. Berkali-kali pada zaman Belanda saya diajak Ibu meninjau ke Surabaya, ke tempat-tempat keluarga atau bekas kenalan, termasuk ke kampung Jasem Sidoarjo di mana Bapak-Ibu pernah hidup berjaya. Semua peninjauan itu dengan maksud untuk bergabung kembali membangun kehidupan rumah-tangga bersama Bapak. Namun tidak berhasil.
Tahun 1937-1941 saya ikut Ibu berumah sendiri di Pasar Kebo Sragen.
Sebelum harta warisan dari Kakek habis, Ibu mendekat kepada Budhe Pus di Sragen, di mana Mas Saparas (putranya Budhe Pus) yang masih bujang punya kedudukan tinggi sebagai sipir di Rumah Penjara Besar di Sragen. Ibu keluar dari istana Pangeran Djajaningratan pindah menempati rumah Budhe Pus di Kampung Pasar Kebo di Sragen 1937. Waktu itu saya sudah umur 5 tahun. Rumah Budhe Pus di Pasar Kebo Sragen adalah rumah tembok satu-satunya di desa Krapyak Sragen waktu itu. Ibu dan saya menempati rumah tembok itu berdua saja, sebab Budhe Pus ikut menempati rumah dinas Mas Saparas di daerah sekitar Rumah Penjara Besar Sragen. Untuk pendekatan yang kekal terhadap keluarga Bapak, Ibu bahkan menjual tanah dan rumah warisannya di Kedunglumbu Solo kepada adiknya Bulik Doeri Darmosaroyo, uangnya dibelikan rumah dan pekarangan tetangga samping rumah Budhe Pus di Kampung Pasar Kebo di Sragen. Dengan memiliki rumah dan pekarangan di situ, maka Ibu akan selalu dekat dengan Budhe Pus (iparnya). Ibu dan saya tetap menempati rumah tembok milik Budhe Pus, sedang rumah-rumah di pekarangan baru milik Ibu disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rumah-rumah gedeg dipetak-petak, sewanya amat murah, tiap petak dua sen per hari.
Namun usaha Ibu mendekati keluarga Bapak dengan cara itu juga sia-sia. Sebab tahun 1940 Mas Saparas dipindah pekerjaan jadi sipir di penjara di Kota Pati. Budhe Pus ikut pindah ke Pati. Ibu dan saya tetap tertinggal berumah tembok milik Mas Saparas di Krapyak, Pasar Kebo, Sragen. Berduan saja. Ibu tidak punya penghasilan lain selain menjuali barang warisan dari Kakek. Hasil persewaan rumah gedeg tidak mungkin untuk menghidupi kami. Sedang saya sudah bersekolah, di Sekolah Angka Loro di Sragen Wetan. Tahun 1940 ketika Mas Saparas pindah ke Pati, saya sudah kelas 3. Tentu saja Ibu panik dengan keadaan seperti itu. Seorang putri bangsawan hidup berdua saja dengan anaknya umur 8 tahun di desa, tanpa penghasilan! Mau usaha apa, agar tidak meninggalkan Sragen? Sebab harta warisannya berupa pekarangan ada di Sragen, dan saya sudah terlanjur bersekolah Angka Loro (sekolah yang paling rendah zaman itu) di Sragen. Untuk memperpanjang hidupnya karena barang-barang peninggalan Kakek kian menipis, Ibu menggadaikan kain-kain batik miliknya, dan hutang uang kepada Cina Mindring, dan mencoba membuka warung pecel di rumah sendiri. Banyak kerabat Ibu yang mencela, putri bangsawan kok jualan nasi pecel! Dan memang usaha Ibu tidak jalan.
Selama 1937-1941 itu saya hidup sangat bebas bermain sebagai bocah desa umur 5-9 tahun: bermain layangan seharian, mencari cengkerik malam hari, adu cengkerik siang hari, makan tebu di sawah, mandi di sungai, ikut menggembala kambing, mendengarkan omongan cabul, diadu berkelahi sesama teman. Bebas bas bermain keluar rumah. Ibu tertinggal sendiri di rumah, tidak bisa melarang kebebasan saya. Tapi pagi hari masuk sekolah, pasti saya jalani.
Dalam usaha Ibu yang gagal mendapatkan penghasilan dan gagal mendekati keluarga Bapak, menjalani hidup kesendirian di desa begitu sangat rentan. Tidak ada kerabat yang mau menolong. Maka akhirnya Ibu melamar pekerjaan jadi batur (pembantu rumah tangga) pada Bupati Sragen, Mr. Raden Mas Tumenggung Ario Wongsonagoro. Diterima oleh isteri Ndara Bupati. Dan amanlah kehidupan kami berdua. Menjadi batur, kami berdua mendapat penginapan di rumah Bupati, tidak sendirian berdua saja di pekarangan desa, dan juga dapat makan kenyang.
Tahun 1941-1942 saya ikut Ibu menjadi batur di rumah Bupati Sragen.
Sebelumnya Ibu tidak kenal sama sekali dengan keluarga Bupati Sragen itu. Ibu diterima sebagai emban (pengasuh khusus) putri Bupati yang sudah remaja (anak nomer 4), Raden Ajeng Sridanarti, sedang saya menjadi pengasuh putranya yang bernama Raden Mas Tripomo (anak nomer 6). Sridanarti sudah sekolah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, perguruan yang lebih berkembang dari sekolah rendah = SMP) di Solo karena di Sragen belum ada MULO, berangkat pagi pulang sore naik keretaapi. Ibu tetap di rumah Bupati. Sedang adik-adiknya masih sekolah di ELS (Europeesche Lagere School = sekolah rendah untuk bangsa Eropa) di Sragen.
Batur terjemahan sesungguhnya adalah budak. Tapi mengikuti zaman sekarang lebih diperhalus menjadi ‘pembantu rumah tangga’ disingkat PRT. Hidup jadi batur sebenarnya memang jadi budak. Kemerdekaannya betul-betul ditindas oleh majikannya. Apa segala perintah majikannya harus dituruti. Itu yang terjadi awal mula saya jadi batur Raden Mas Tripomo. Merdeka hanya waktu belajar ke sekolah, saya sekolah di sekolah Angka Loro Sragen Wetan, beliau sekolah di ELS tengah kota, pulang sekolah saya harus ikut ke mana saja R.M.Tripomo bergerak. Ya main layang-layang, belajar sepeda, berkelahi, saya harus ikut dan membela R.M.Tripomo. Tapi hak saya ikut main tidak ada. Belajar sepeda ya hanya suruh mendorong saja. Saya jadi tidak kerasan. Maka tiap kali berangkat sekolah, saya atidak pulang ke rumah bupati. Saya melanjutkan bermain di kampung lama, Pasar Kebo. Di sana ketemu lagi dengan teman-teman lama, bermain bebas. Senang sekali. Satu hal yang tidak kudapat. Ibu tidak ada di rumah Pasar Kebo, jadi juga tidak ada yang beri saya makan. Seharian bermain di Pasar Kebo saya tidak makan. Baru berani pulang ke rumah bupati, kalau kira-kira R.M.Tripomo sudah tidur. Seringkali saya pulang setelah malam hari. Berjalan sendiri di malam gelap dari Pasar Kebo ke rumah bupati. Sebenarnya saya juga takut gelap, takut jadi-jadian seperti cerita orang, takut penyamun. Tapi ya harus saya lakoni, supaya saya bisa bertemu Ibu dan tidur di dekat Ibu. Lewat depan rumah yang dijaga oleh polisi, pasti ditegur, anak umur 8 tahun seorang diri masuk rumah bupati. Bertemu Ibu, Ibu pasti menyiapkan makanan. Makanan sisa-sisa makanan keluarga Sang Bupati. Meskipun namanya sisa-sisa, tapi enak dan bergizi. Ada mi, daging, nasi putih, buah. Lebih mewah daripada kalau yang masak Ibu di Pasar Kebo dulu.
Kurang beruntungnya saya hidup bebas begitu, saya jatuh sakit. Sakit malaria tropika. Pagi hari terasa sehat-sehat saja, berangkat sekolah, jam 10 setelah istirahat pertama, badan merasa demam amat sangat. Seringkali harus disuruh pulang oleh Pak Guru. Kalau sudah demam begitu seringkali apa yang sudah saya makan pagi itu keluar dari mulut. Tumpah di kelas. Saya langsung disuruh pulang. Sering juga selama pelajaran sekolah tidak demam. Pulang sekolah saya pun bermain ke Pasar Kebo. Main di sana tiba-tiba demam. Saya pun tidur di emper rumah teman saya. Sampai demamnya berakhir. Atau malam hari tiba, saya dengan masih merasa demam harus pulang ke rumah bupati. Akhirnya saya tidak kuat lagi, tidak pergi ke sekolah, tidur saja di mana Ibu bisa menemani saya. Akhirnya saya sembuh juga, dan terbebas dari perbudakan R.M.Tripomo. Saya bebas bermain apa saja di rumah bupati, tidak lagi harus mengikuti R.M.Tripomo. Saya ikut belajar menari dan menabuh gamelan. Bergaul dengan putra-putri bupati yang lain juga bebas. Tapi jadi istimewa bergaul dengan Raden Ajeng Tanti, mbakyunya R.M.Tripomo. Istimewanya beliau suka sekali membaca buku, dan saya disuruh mendengarkannya. Semula memang dibacakan untuk didengarkan anak-anak yang lain juga, tetapi kemudian hanya saya yang suka mendengarkan cerita buku yang dibacanya. Banyak sekali buku bahasa Jawa tulisan latin yang saya sewa dari perpustakaan sekolah maupun swasta yang kami nikmati berdua untuk membacanya. Peristiwa pembacaan buku itu menjadi salah satu pergerakan jiwa saya untuk menyenangi membaca buku. Suasana itulah gerakan jiwa saya awal mulanya.
Selain merasakan perbudakaan, sakit malaria tropika yang sangat payah, kegairahan membacai buku, ada lagi yang mengubah kejiwaan saya, yaitu datangnya Balatentara Dai Nippon ke Indonesia. Perang terjadi. Mr.Wongsonegoro sebagai cendikiawan tentu saja semula melawan kedatangan Dai Nippon. Kedudukan beliau dipersoalkan. Akhirnya bahkan beliau diangkat jadi Fuku Syutjokan (wakil residen) di Semarang. Saya dan para keluarga Sang Bupati merasakan benar bagaimana kerasnya pemerintahan Balatentara Dai Nippon awal mula di Sragen.
Pindah ke Semarang ikut keluarga Mr.Wongsonegoro Ibu tidak mau. Ingin mendekat lagi kepada Bapak. Hidup sendiri di Sragen tidak mungkin lagi. Maka diputuskan pergi saja ke Surabaya. Di Surabaya Ibu melamar jadi PRT keponakannya, yaitu Raden Ayu Sarwosri. R.Ay.Sarwosri adalah istri Mas Suharto Suryohartono, waktu itu rumahnya di van Stipriaan Luciusstraat 31 Surabaya, sedang melahirkan putra ke 3 laki-laki, dinamai Kusno Hartowo. Ibu menjadi pengasuh bayi tadi. Saya ikut Ibu pindah ke Surabaya, sekolahku pun dipindah ke Sekolah Rakyat di Jalan Mundu, sekolah dengan nama Kokumin Gakkõ di Moendoeweg Surabaya. Dari sinilah nanti saya memulai cerita tentang Surabaya pada zaman Jepang (1942-1945). Pada waktu itu kakak saya R.M.Soewondo sudah bekerja di Marine Ujung, pondok di rumah Bulik Sri, Gersikan gang 2 nomer 23 Surabaya. Bapak tidak di Surabaya, konon menjadi penjaga tambak milik Kaji Umar di Sidoarjo. Bapak sudah kawin lagi dengan perempuan di desa sana. Pendekatan Ibu tampaknya sia-sia. Tapi Ibu sudah punya harapan bisa hidup dengan kakak R.M.Soewondo kelak kemudian hari.
Tahun 1942 saya ikut Ibu menjadi PRT di van Stipriaan Luciusstraat 31 Surabaya.
Tahun 1942 Jepang mendarat di Pulau Jawa. Ibu mengajak saya pindah ke Surabaya, mengabdi pada keponakannya Raden Ayu Sarwosri (cucu Pangeran Djajadiningrat) yang sudah menikah dengan Raden Suharto Suryohartono. Mas Suharto bekerja sebagai sekretaris Kabupaten Surabaya, kantornya di Gentengkali, rumahnya di Van Stipriaan Luciusstraat nomer 31 Surabaya.
Tahun 1944-1945 saya mondhok di rumah Pak Broto di Karangmenjangan Surabaya.
Mas Suharto Suryohartono akhir tahun 1944 diangkat jadi Wedono di Krian, bersama keluarganya pindah ke Krian. Ibu tetap ikut ke Krian. Saya dan Mas Darkiman mondok di kerabat Solo, Ibu Subroto, di Kampung Karangmenjangan, sebelah timur dari gedung Rumah Sakit Karangmenjangan. Saya melanjutkan sekolah di Canalaan 121, tiap hari pergi-pulang sekolah berjalan kaki, kaki telanjang. Sementara itu kakak R.M.Soewondo pindah pekerjaan. Keluar dari Marine Ujung Surabaya, pindah bekerja di Jawa Denki Jigyo-sya, perusahaan Listrik di Gemblongan Surabaya.
Tahun 1945-1947 saya, Ibu dan kakak R.M.Soewondo mengungsi di Probolinggo.
Pada Perang 10 November 1945, dalam ancaman hujan peluru dari darat, laut dan udara, berbondong-bondong orang Surabaya lari mengungsi keluar kota, dengan membawa barang sekuatnya dan sebisanya. Bingung, tujuannya tidak menentu, asal segera keluar dari Kota Surabaya saja terlepas dari ancaman maut ultimatum Komandan Pasukan Sekutu di Jawa Timur, Mayor Jendral E.C.Mansergh. Dalam keadaan seperti itu saya bersama Ibu dan Kakak R.M.Soewondo, bertiga lari mengungsi ke Probolinggo. Sekilas ada niatan juga mendekati tempat Bapak berada. Konon Bapak bekerja di pabrik karung Asko di Probolinggo pimpinan Bapak Mochammad Saleh, mantan kenalan Bapak-Ibu ketika dulu hidup berjaya. Kakak R.M.Soewondo oleh jawatannya (Listrik Gemblongan) pernah ditugaskan di Probolinggo, dan ketemu Bapak. Maka ketika ribut-ribut mengungsi keluar dari Surabaya Ibu, Kakak, dan saya menuju ke Probolinggo. Ketika kami datang di Probolinggo ternyata Bapak sudah meninggal dunia. Probolinggo kota sangat asing bagi kami bertiga. Kami mengungsi tidak punya tujuan lain, maka kami diizini Pak Moch.Saleh menempati bekas rumah Bapak, di Kampung Mangunharjo dekat pabrik karung Asko tempat Bapak bekerja dulu. Kami bertiga membentuk keluarga sendiri. Kakak mendapatkan pekerjaan di Djawatan Listrik & Gas, Ibu menjadi jurumasak di rumah, dan saya membantu-bantu di rumah sambil meneruskan sekolah. Kami mengungsi di Probolinggo 1945-1947, saya bersekolah dari kelas VI SR, sampai naik kelas II SMP.
Tahun 1947-1949 saya lari ke Sragen, lepas dari pendudukan tentara Belanda.
Ketika Belanda menyerbu kota-kota di daerah Jawa Timur Juli 1947, keluarga saya bubar. Kakak meninggalkan rumah kami di Probolinggo Kampung Mangunharjo pergi ke Surabaya entah di mana (takut sama pendudukan tentara Belanda), Ibu pergi ke Jasem Sidoarjo ikut membantu Haji Rokhayah yang mengusahakan makanan juadah iyas. Haji Rokhayah kenalan lama Ibu ketika masih jaya di Sidoarjo dulu. Tidak mungkin saya ikut Ibu. Saya mengembara ke pedalaman (tidak mau hidup di daerah penjajahan Belanda) sampai di Sragen dan Solo.
Tahun 1949 saya ke Surabaya, bersama Ibu dan kakak di Gresikan 2/23 Surabaya.
Baru kemudian tahun 1949 saya kembali ke Surabaya ketika Yogyakarta sebagai Ibu-Kota Republik Indonesia telah diduduki oleh tentara Kerajaan Belanda (19 Desember 1948). Saya berkumpul lagi dengan Kakak dan Ibu, dan membentuk rumah tangga bertiga lagi. Kami menempati rumah Paklik Wibisono di Gersikan II nomer 23. Rumah itu kosong ditinggal mengungsi sekeluarga ke Madiun. Kosong ditinggal ngungsi rumah tadi dalam keadaan pintu-pintu serta kusennya sudah hilang, pekarangannya ditumbuhi ilalang. Ilalang saya babat, pintu-pintu kami carikan tutupnya. Pagar sekeliling pekarangan kami bangun.
Keadaan kami seperti waktu di Probolinggo. Kakak R.M.Soewondo bekerja di pabrik radio PT.Philips di Ngagel. Ibu juru masak di rumah. Saya semula menganggur, tapi kemudian bisa masuk sekolah di Middelbare School (setingkat SMP) di Jalan Kalianyar Wetan. Sekarang gedungnya jadi Sekolah Petra. Dalam waktu setahun itu (1949-1950) gedung sekolah saya berpindah dua kali, pertama pindah ke Polackstraat (Sulung Sekolahan, gedung sekolah saya sekarang jadi bangunan masjid Kantor Gubernur), dan pindah lagi ke Tempelstraat (Jalan Kepanjen). Tahun 1950 namanya diubah jadi SMPN 2 Jalan Kepanjen 1 Surabaya.
Kemudian ketika keluarga Paklik Wibisono datang tahun 1950, keluarga saya (Ibu dan kakak) bubar lagi. Kakak dikirim study oleh PT.Philips ke Eindhoven Negeri Belanda selama 6 tahun. Karena rumah Gersikan sudah kembali ke pemiliknya, maka Ibu yang menganggur tak punya penghasilan lebih baik pergi dari rumah itu, dan paling bisa ya mencari kehidupan kembali ke keluarga besar bangsawan Surakarta di Solo. Sudah berumur 18 tahun belum lulus SMP, maka saya memaksa diri meneruskan sekolah di Surabaya hingga lulus. Banyak teman yang seusia saya bertahan bersekolah di SMPN 2 Surabaya situ 1950 seperti saya.
Saya boleh tetap tidur di Gersikan, tapi beaya hidup harus saya tanggung sendiri. Kebetulan waktu itu saya berkenalan dengan teman sesekolah yang rumahnya di Setro, pagi-pagi sebelum masuk sekolah mengedarkan koran Jawa Pos yang pabriknya di Kembang Jepun. Semula sering berangkat dan pulang bersama ke sekolah. Namanya Muslimin. Saya diajak Muslimin ikut jadi loper koran Jawa Pos. Saya mau. Mendapat jatah mengedarkan koran Jawa Pos di daerah Ampel. Hasil jadi loper itulah yang saya gunakan untuk membeayai hidup saya selama meneruskan bersekolah di SMPN 2 Jalan Kepanjen Surabaya tahun 1950.
Karena keadaan perang begitu, sekolah saya terhambat-hambat. Waktu kembali ke Surabaya 1949 sempat tidak bersekolah, tapi akhirnya bersekolah di Middelbare School di Polackstraat, lalu sekolahnya dipindah ke Tempelstraat, sekolah mana kemudian menjadi SMPN 2 Surabaya. Saya lulusan pertama sekolah di SMPN 2 Jl. Kepanjen Surabaya 1950, bersama Kadaruslan (terkenal dengan nama Cak Kadar, yang tahun 2005-2011 memimpin Pusura), Wardiman Djojonegoro, yang kemudian hari pernah jadi Menteri Pendidikan Indonesia.
Tahun 1950-1952 saya berusaha ikut Ibu kembali di Solo.
Tahun 1950 saya lulus SMPN 2 Jalan Kepanjen Surabaya, masuk ke SMAN 2 Kompleks Wijayakusuma. Saya masih boleh mondok di rumah Paklik Wibisono di Gresikan, tapi harus mencari kehidupan sendiri. Termasuk pembayaran sekolah. Pelajaran sekolah maupun pembeayaan sekolah sangat berat bagi saya. Tidak bisa lagi saya menjadi loper koran. Selain mengerjakannya membutuhkan waktu hingga mengganggu waktu belajarku, juga hasilnya tidak mungkin untuk membeayai hidupku, termasuk membayar sekolah. Karena kesulitan hidup, akhirnya saya putuskan saya menyusul Ibu saja hidup di Solo. Hidup bersama Ibu mungkin lebih baik keadaannya. Belum cukup setahun saya bersekolah di SMAN 2 Kompleks Wijayakusuma Surabaaya, saya minta pindah ke Solo.
Di Solo saya sempat tidak bisa bersekolah, karena kepindahan saya pada pertengahan tahun ajaran. Sekolah-sekolah SMA sudah penuh. Ternyata kehidupan Ibu di Solo juga sangat tidak memadai. Tidak punya rumah sendiri, terpaksa mondok-mondok ke tempat saudara. Penghasilan Ibu hanya diperoleh karena buruh membatik. Itupun karena Ibu sudah tua, membatiknya dibawa ke rumah. Penghasilannya sangat minim.
Tahun ajaran baru 1951 saya baru dapat bersekolah di SMAK di Nonongan yang dibuka baru. Sekolah ini kemudian bernama SMAK St.Joseph. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan senang hati. Namun pembayaran sekolah saya tetap tidak bisa lancar, karena penghasilan Ibu tidak memadai. Akhirnya saya memutuskan diri minta pindah sekolah Katholiek di Surabaya, tetapi tujuan utama saya pindah ke Surabaya mencari kehidupan atau pekerjaan. Mencari pekerjaan di Surabaya lebih gampang daripada di Solo.
Ikut Ibu di Solo tidak punya pekerjaan yang memadai, maka saya kembali ke Surabaya, mencari pekerjaan, 1951.
Sejak tahun 1951 dan selanjutnya saya bertempat tinggal di Surabaya.
Ditolong oleh Paklik Wibisono bekerja di Rumah Sakit Kelamin di Jalan Dr.Soetomo Surabaya, saya cari rumah pondokan gratis di rumah Pak Kir Jalan Jasem 19 Sidoarjo. Berangkat dan pulang bekerja mengayuh sepeda dari Jasem Sidoarjo ke Jalan Dr.Soetomo Surabaya.
Saya tidak kerasan dengan pekerjaan saya, terutama karena tidak ada mesin ketik di kantor, maka ketika ada iklan membutuhkan operator teleprinter yang harus dikursus dulu selama satu tahun, saya melamarnya dan berhasil pada pekerjaan itu. Bekerja sebagai operator teleprinter Kantor Telegrap Surabaya sejak tahun 1952-1960. Saya mencari pondokan berpindah-pindah di Kota Surabaya sejak itu.
Tahun 1960-1967 saya pindah pekerjaan dari Kantor Telegrap ke Perusahaan Dagang Negara Jaya Bhakti, bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi 1957. Tahun 1962 saya menikah dengan Rara Ariyati, juga karyawan PDN Jaya Bhakti. Tahun 1967 Direktur Utamanya Bp. Soehardiman, menyuruh semua karyawan PDN Jaya Bhakti harus jadi anggota Golkar. Saya dan istri tidak mau, jadi keluar dari pekerjaan.
Tahun 1967 saya mengarang buku diterbitkan oleh Kho Ping Hoo di Solo.
Dan berusaha dagang kapok, kulak di Surabaya (PT Kapok) dijual ke Bandung.
Tahun 1969-1988 saya menjadi pegawai Pemkot Surabaya, sampai pensiun.
Berbagai pekerjaan telah saya tempuh: menjadi operator teleprinter, pegawai Perusahaan Dagang Negara, pedagang kapok, pengarang roman, wartawan freelancer, pegawai pemkot, pensiun 1988. Sepanjang kurun waktu itu saya juga menikah, punya anak, membesarkan anak, membangun rumah dan seterusnya, saya tetap bertempat tinggal di Surabaya.
Menjalani hidup dengan beraneka zaman geger seperti itu menjadi suatu pengalaman yang indah ketika saya menjalani hidup pada waktu ini. Sejak isteri saya meninggal dunia 2002, saya sebagai kepala keluarga sudah selesai, anak-anak saya empat orang sudah punya jodoh, punya anak, punya pekerjaan, tempat tinggal, dan hidup masing-masing mandiri, tidak saling tergantung kepada sesama saudara. Namun oleh Gusti Allah saya masih Diberi tiga anugerah utama istimewa, yaitu (1) Hidup sehat, (2) Bebas memilih, tidak dipenjara, tidak tergantung pada instansi/orang lain, (3) Diberi kemampuan membaca buku dan menulis buku. Ketiga anugerah utama tadi saya anggap amanah, yang harus saya ibadahkan, dan sebagai barkah. Maka sisa-sisa hidup saya saya gunakan untuk melaksanakan amanah Allah tadi. Salah satunya sisa waktu hidup saya ini saya manfaatkan untuk menulis buku. Menulis buku antara lain tentang kenangan hidup saya yang mengalami pancaroba peralihan zaman yang dahsyat karena melampaui Perang Dunia II, namun dengan Kehendak Allah saya bisa lolos hidup sampai sekarang, menjadi pengalaman yang indah kalau dikenang sekarang. Dari kegemaran membaca buku dan kemampuan menulis cerita, pengalaman dan kesaksian saya masa-masa lalu menjadi bahan penulisan yang amat beragam tentang kehidupan zaman, alias sejarah. Senang dan sengsara, jatuh dan bangkit melakoni hidup zaman perjuangan, zaman Jepang, menjadi kenangan yang indah, tidak bakal dinikmati oleh generasi anak-cucuku. Saya tuliskan cerita-cerita pengalamanku, agar generasi anak-cucuku juga dapat merasakan jatuh-bangkit hidup yang dialami generasiku. Dengan harapan yang jelek jangan terulang terjadi pada generasi anak-cucuku, yang baik agar dijadikan contoh teladan, sehingga hidup mereka menjadi lebih baik daripada kehidupan zaman generasi saya. Cerita sejarah, bukanlah cerita masa lalu, melainkan juga cerita masa kini dan masa harapan ke depan. Sebaiknya dipelajari dan diketahui oleh para putera bangsa yang akan menjalani hidup pada masa kini dan masa depan.
Cerita Surabaya Zaman Jepang ini, waktu saya kirimkan ke penerbit supaya dijadikan buku, semula akan saya ubah disesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman tahun akhir-akhir ini. Namun, beberapa penggemar dan ahli sejarah menganjurkan agar diterbitkan jadi buku seperti sebagaimana waktu saya menulis cerita ini (2011). Agar pemikiran saya waktu itu tetap tertulis apa adanya saat itu. Tidak berubah dan ditandai pemikiran waktu itu, juga menjadi tonggak sejarah, saran mereka. Maka dengan segala kerendahan diri naskah buku garapan tahun 2011 ini saya kirimkan ke penerbit. Tentu saja cerita ini pengalaman diri pribadi, sangat amatir, barangkali banyak penggambaran yang tidak benar maupun kurang tepat. Tapi saya tulis dengan jujur waktu menulis tahun 2011 ini.
Demikianlah pengantar buku ini. Seperti yang saya sebut awal cerita, maksud penulisan cerita ini merupakan persembahan saya dalam memperingati hari jadi Kota Surabaya yang ditetapkan tanggal 31 Mei 1293, secara perorangan, sehingga tiap pada setiap tahun para warga Surabaya bisa mengingat keadaan Kota Surabaya pada zaman Jepang, dengan cara membaca buku ini. Penulisan buku ini timbul dari pemikiran sendiri, tidak didasari oleh pesanan apa pun dan dari siapa pun juga. Semoga bermanfaat.
Dirgahayu Kota Surabaya, 31 Mei 1293 sampai sepanjang masa.