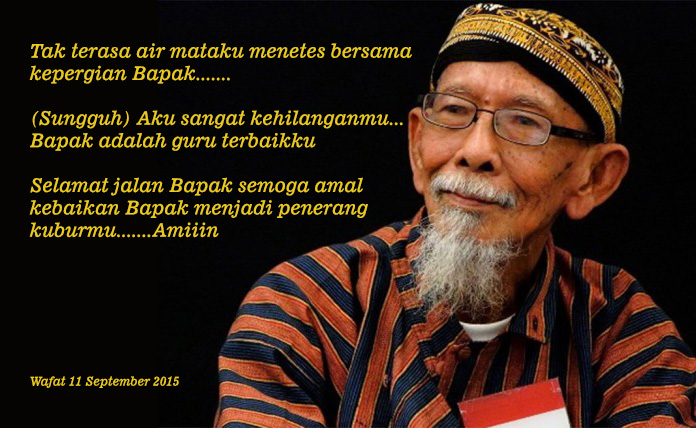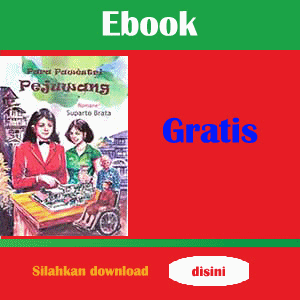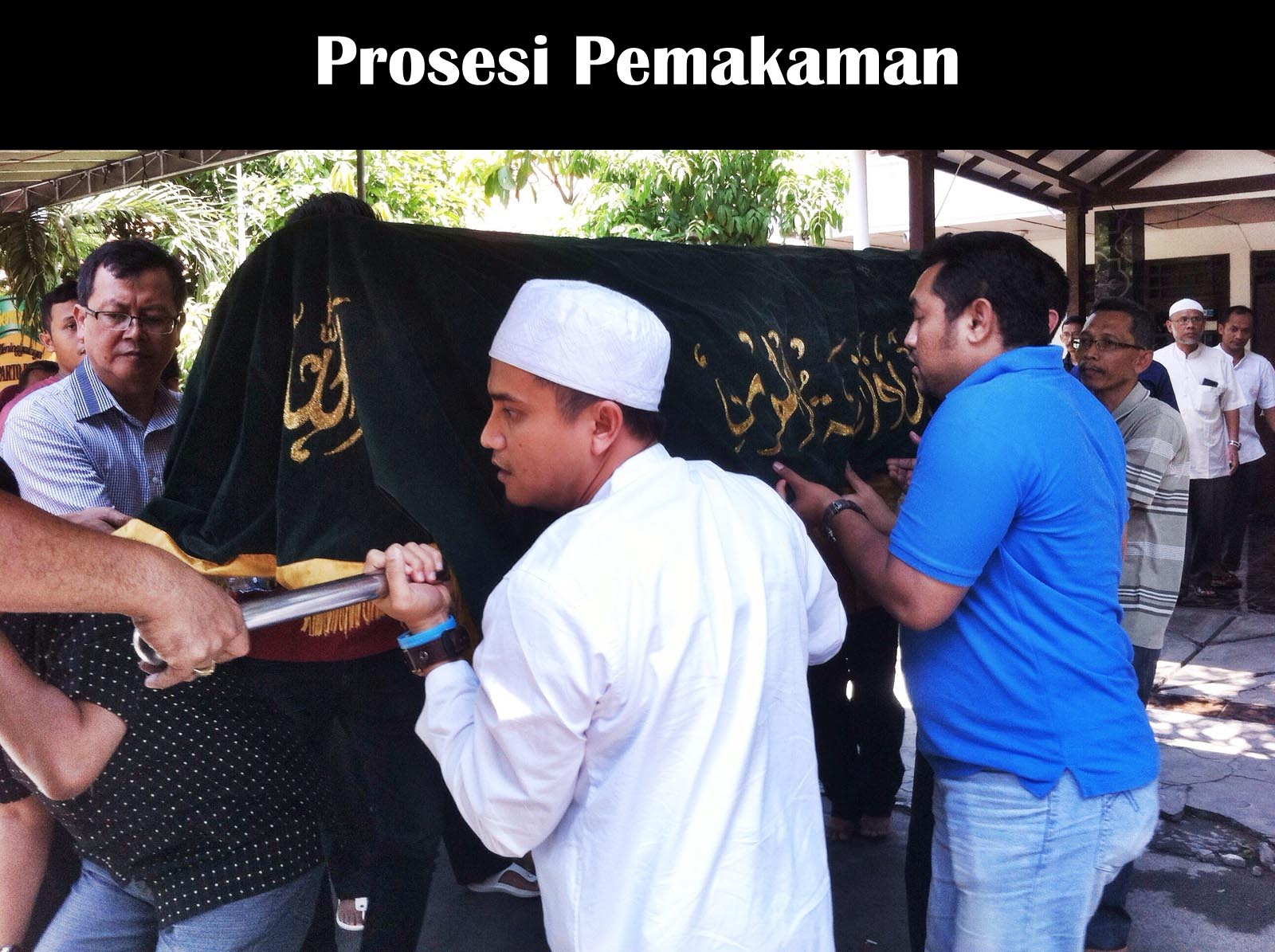CATATAN NOVEMBER/DESEMBER 2008
SOLIDARITAS PENGARANG SASTRA JAWA
Jumat/Sabtu 7/8 November 2008.
Jumat 7 November saya berangkat ke Bungurasih jam 12 siang. Bertemu dengan Mbak Trinil dan Mas Djoko Prakosa, dan akhirnya Mas Bonari. Bis patas brangkat jam 14.00, sampai di Masjid Raya Sragen jam 20.00, dijemput Mas Tito. Kami ditampung tidur di rumah Mas Tito. Kata Mas Tito, nanti Siti Aminah dengan suami dan anaknya juga datang dari Yogya, tapi akan diinapkan di hotel saja. Setelah Siti datang, diantar ke hotel, saya ikut mengantar. Saya, Mas Djoko, Mas Bonari dan Mas Tito diskusi di rumah Mas Tito tentang berbagai macam utamanya tentang sastra Jawa dan para sastrawannya sampai jam 1 malam, di bagian atas rumah Mas Tito di Puro Asri Blok D4 Sragen. Bagian atas rumah itu dibikin seperti warung, ada bangku, kursi, meja dengan makanan-minuman ringan di atasnya, serta langit biru memayunginya..
Sabtu 8 November, seperti biasa saya bangun jam 03.30. Turun ke bawah, Mbak Trinil, Mas Djoko dan Mas Tito sudah siap di depan rumah. Ketika matahari terbit, saya, Mas Djoko, diantar Mas Tito menjemput Siti Aminah, tetapi dengan mengitari Kota Sragen atas permintaan saya. Mas Tito menggali pengalaman saya ketika hidup di Sragen, seperti yang mengilhami cerpen saya: Lelakone Si Lan Man, dan novel Nona Sekretaris. Jadi dari Puro Asri kami ke utara, menyeberang rel sampai di Pegadaian ada perempatan. Dulu bukan perempatan, tapi pertigaan. Belok ke barat, lewat Kuwungsari, ke kanan, lewat Cantel, terus ke abatoir (pemotongan hewan), belok ke timur, melalui jembatan yang dulu namanya Kreteg Abang, sampai di perempatan, belok ke kanan lagi sampai di Pasar Kebo. Di sinilah habitatku ketika masih kecil. Selama perjalanan saya kisahkan riwayatku di Sragen dengan tempat-tempat yang kami lalui itu. Bekas-bekas rumahku dan tempat dahulu saya bermain, sudah jejal dengan bangunan rumah. Tidak ada lagi sela pekarangan luas atau kebun-kebun. Ujung jalan Krapyak Pasar Kebo ini bercabang dua, dipilih yang ke kiri, melewati sekolah saya, yang dulu pernah dijadikan terminal bis. Dari situ lalu belok ke timur, menjemput Siti Aminah dan suaminya.
Mas Tito ini sukses hidupnya jadi pemborong. Juga menjadi penerbit majalah Pendidikan dan Keluarga GENTA. Berkembangnya usahanya dia ingin mendirikan percetakan, sudah beli tanah di dekat rumahnya. Rencananya dia akan menerbitkan buku, termasuk melamar buku-buku saya. Di rumahnya yang sekarang, ada ruangan khusus untuk perpustakaan. Dia menyimpan semua buku karanganku, dan tiap halaman depan minta tandatanganku.
Sekira jam 08.00 kami berangkat ke Wonogiri. Di mobil Mas Tito ada kami yang dari
Sampai di Rumah Tahanan Wonogiri sekitar jam 11 siang. Di situ Mas Cipto dosen Uness Semarang sudah ada. Dan rombongan dari Triwida (Mas-mas Narko, Tiwiek, Jarot, Sumono, dll) juga sudah menanti. Kami, para pengarang sastra Jawa, mau membezuk Mas Ruswardiatmo. Di
Mas Ruswardiatmo adalah penilik sekolah di Kabupaten Wonogiri, sudah pensiun. Pada APBD 2003 Wonogiri, ada anggaran untuk pembelian buku sekolah. Sebagai petugas, Mas Rus membeli buku-buku itu dari penerbitan Balai Pustaka. Oleh Balai Pustaka Mas Rus dapat fee. Mas Rus tidak mau menerima fee itu, maka dipesankan dijadikan tambahan jumlah buku saja. Tapi ternyata jumlah buku tambahan itu tidak ada. Jadi Mas Rus dituduh korupsi, karena jumlah buku tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan. Belum disidang dan diputus, namun ancaman hukumannya sekian tahun penjara dan mengembalikan denda sekian milyar rupiah. Pada hal, selama hidup Mas Rus jadi guru, terlalu jujur, dibenum jadi penilik tapi belum serah-terima jabatan juga tidak mau menempati kursinya, rumah yang ditempati sekarang ya rumah warisan kakeknya dulu, dibangun sedikit demi sedikit hingga merupakan rumah yang sekarang ditempati (di Solo). Hidupnya sangat sederhana, sebagaimana hidupnya seorang guru yang baik, kudu digugu lan ditiru. La kalau tidak bisa melunasi hukumannya, maka rumah warisan itu akan disita. Jadi, apa darma bakti Mas Rus sebagai pendidik untuk hidupnya itu, bukan dihargai jasanya, melainkan harus dibayar dengan hukuman penjara dan harta warisannya. Apa Mas Rus tidak menceritakan bahwa tidak menerima uang fee itu? Sudah, tetapi ujar jaksa, pendek kata negara dirugikan sekian juta rupiah, kalau tersangka tidak mau menerima uang itu, ya salahnya sendiri.
Mas Tito menyebutkan bahwa perkara Mas Rus itu berbalikan dengan pepatah Jawa kuna yang selama ini jadi pedoman hidup: Becik ORA ketitik, ala ORA ketara.
Pertemuan hanya dibatasi selama 15 menit. Setelah batas waktu sipir mengingatkan harus bubar. Saya memberi buku-buku karangan saya: Dom Sumurup Ing Banyu, Lelakone Si lan Man, Emprit Abuntut Bedhug, Jaring Kalamangga, Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem. Mas Rus senang sekali, sebab bisa untuk membunuh waktu. Dia sudah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Wonogiri, agar di rutan diselenggarakan perpustakaan. Saya bilang kepada teman-teman yang belum baca buku-buku saya itu, bisa membaca buku saya tadi dengan gratis, tidak usah bayar. Yaitu datanglah kepada Mas Rus, pinjam di tempatnya. Kami pun potret-potretan, dan berpisah.
Teman-teman Triwida langsung pulang lewat Ponorogo. Kami sisanya lewat Solo. Setelah singgah makan siang di Mi Gading, kami pun menuju terminal. Berangkat dengan bus patas dari Solo jam 14.00, kami katutan Siti Aminah yang terus melanjutkan perjalanan ke
*
KAMPUNG
Senin, 10 November 2008
Harian Jawa Pos memperingati 63 tahun Hari Pahlawan dengan memuat kejadian di kampung-kampung
Cak Kadar menyayangkan, banyak peringatan Hari Pahlawan salah kaprah. Peringatan diisi dengan hiburan. Juga disayangkan pada kampung-kampung atau tempat
Sore hari Pak Budi Darma SMS saya, apa sudah baca Metropolis Jawa Pos hari ini. Kampung2 ingkang dados ajang perang 10 November 45, menika saged dados novel enggal panjenengan. Saya jawab, Wo, kula aturi mbikak domain kula. Petualangan Sabarudin langkung hebat ing 10 November. Lalu ditanggapi lagi: Domain panjenengan kados pundi? Sabarudin cariyosipun Pak Gatut Kusuma sasampunipun 10 Nopember. Lalu saya beritahu domain saya www.supartobrata.com .
*
KEPAHLAWANAN DI ERA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Rabu, 12 November 2008.
Selagi ingat dan sempat, saya pergi ke Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh FISIP Unair siang hari, dalam rangka peringatan Dies Natalis Ke-54 Universitas Airlangga. Di layar mimbar jelas ditulis temanya:
Korporasi Patriotik atau Patriotik Korporate?
Kepahlawanan di Era Corporate Social Responsibility
Moderator: Drs. Suko Widodo, Msi
Pembicara: Yenny Zannuba Wahid (The Wahid Institute)
Rahma Ida, PhD (FISIP Unair).
Mungkin karena masih di sekitar Hari Pahlawan, awal acara banyak pertanyaan semisal: Apakah arti pahlawan? Siapakah pahlawan masa kini? Apakah Amrozi Cs pahlawan atau apa? Ditujukan kepada Yenny Wahid.
Meskipun mengaku agak bingung untuk menjawab tema di layar mimbar, Yenny Wahid dengan banyak senyum canda menjawab: Pahlawan adalah mereka yang memalingkan diri untuk memperhatikan kepada orang lain, yang meringankan beban, yang memberi pekerjaan, memberi kepuasan kepada orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah apapun agamanya. Sekarang ini orang Islam banyak, tetapi banyak yang tidak Islami. Banyak yang menderita kemiskinan, bukan miskin duniawi melainkan miskin rokhani. Tiap orang punya hati nurani yang bisa menjadikan dia pahlawan, tetapi seringkali terkubur oleh kegiatannya sehari-hari. Patriotisme sangat mendasar untuk bangkit, tetapi seringkali negara tidak memberi keamanan sehingga sistemik menghambat. Waras, seorang kurban lumpur Lapindo yang menerima bantuan uang begitu banyak, merasa itu bukan haknya, dia mengembalikan uang itu. Waras seorang pahlawan, karena dia antidiskriminasi.
Dengan bicara canda begitu, sidang banyak diwarnai dengan tertawa.
Kalau zaman perjuangan 1945, jadi pahlawan itu gampang, karena musuhnya hanya satu. Belanda. Kalau sekarang? Kalau PKB? “Kalau saya, musuhnya juga jelas: Muhaimin! Cobalah bayangkan. Gus Dur membangun sebuah rumah besar. Keponakannya disuruh menempati salah satu biliknya yang di depan, yang nyaman, diberi AC segala. La kok tidak terima. Inginnya menguasai rumah besar itu seluruhnya…!”
Menjawab pertanyaan apa yang dikerjakan Mbak Yenny ketika menjadi penasihat SBY dan bedanya menjadi penasihat Gus Dur, pada SBY cukup banyak penasihat yang handal sehingga sarannya kurang sempat diterima, sedangkan kalau dengan Gus Dur dia bisa berdialog lebih sering. Gus Dur memang cacad fisiknya, tapi paling sehat rokhaninya, ujar Mbak Yenny. Pernah ketika Gus Dur jadi presiden menggalang kerjasama ekonomi bersama Jepang, Korea Selatan, Cina, India dan Indonesia, untuk menjadikan pasar bersama. Waktu itu Amerika dan Eropa jadi gentar. Sebab yang digaet Gus Dur adalah negeri-negeri yang paling banyak penduduknya, menjadikan pasar yang hebat. Kalau menolak produk atau modal dari luar dan mengonsumsi barang buatannya sendiri, hancurlah sudah pasar ekonomi dari Amerika dan Eropa.
Tentang kepahlawanan di era Corporate Social Responsibilty (CSR) bukan tanpa pertimbangan isu tentang CSR tersebut disorot. Saat ini memang banyak perusahaan yang sudah melaksanakan CSR hanya karena memenuhi UU. Dengan kata lain, tanpa didasari kepedulian mendalam terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Mbak Yenny UU telah mengharuskan perusahaan mengeluarkan 1,5 persen keuntungannya untuk diberikan kepada masyarakat. Pemberian itu merupakan bentuk kepedulian sosial. Program tersebut tentu perlu didukung. Hanya, pemerintah semestinya juga tidak lepas tangan.
Rachma Ida, berbicara dengan cerdas mengenai tema, terutama CSR yang dalam Islam disamakan dengan zakat, sebenarnya sudah harus jadi sosial budaya, sedangkan dengan UU ini keuntungan perusahaan dipaksakan (1,5% keuntungan diserahkan kepada masyarakat). Di negara lain, yang begitu sudah lumrah. Rachma menyebutkan beberapa pentolan nama perusahaan dunia yang telah melaksanakan CSR yang telah jelas memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Kata Rachma, seharusnya CSR itu berupa program yang tepat guna dan bertujuan menyejahterakan masyarakat. Artinya, tidak asal telah melaksanakan CSR. Karena itu, diperlukan kesadaran perusahaan. “Dengan begitu, image perusahaan di masyarakat juga akan meningkat.”
*
NPWP
Biasanya (tercantum dalam akte perjanjian penerbitan buku) royalty buku diberikan dan dilaporkan kepada saya (pengarang) tiap 6 bulan sekali, yaitu periode Januari-Juni, dan Juli-Desember. Laporan itu misalnya begini:
Perhitungan Royalti periode Juli-Desember 2006.
Nama pengarang, judul buku & perhitungannya: Aurora Sang Pengantin yang laku 10 exp; Saputangan Gambar Naga, (10% X 43 X 41,800) 179,740; Mencari Sarang Angin (10% X 147 X 97,900) 1.439.130. Jumlah 1.618.870; dipotong PPh Ps 23 15% = 242.831. Jumlah yang dibayarkan (kepada pengarang) 1.376.040.
Selain lampiran perhitungan royalti tadi, disertakan pula BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 lembar ke-1 yaitu lembar untuk wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Departemen
Tapi, menurut pangalaman saya, meskipun sudah tertulis dalam akte perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan pengarang, tidak semua penerbit dengan setia atau tepat waktu memberi laporan demikian. Bahkan ada penerbit yang sama sekali tidak memberi laporan dan juga tidak memberi royalti.
Lalu, andaikata pengarang tadi tidak memergoki buku cetakan ke-3 karangannya di
Penerbit yang saya jadikan contoh laporan kepada saya tadi adalah penerbit buku saya yang secara rajin mengirim laporan kepada saya. Namun, saya maklumi, kalau perhitungan royaltinya seperti berikut penerbit tadi enggan juga mengirimkan lembar laporan:
Pada Agustus 2007, saya menerima laporan dari penerbit saya yang sama bunyinya begini: Bersama ini kami sampaikan perhitungan royalti atas buku Bapak yang berjudul sebagai berikut:
Periode berikutnya (Juli s/d Desember 2007) saya tidak terima laporannya. Namun pada November 2008 saya dapat edaran dari penerbit saya itu sebagai berikut:
Dengan hormat. Berhubung dengan Perubahan UU Pajak Penghasilan yang akan ditetapkan per Januari 2009, dimana salah satu ketentuan perubahannya adalah bagi Wajib Pajak Penerima Penghasilan (khususnya untuk PPh 23 yaitu Penghasilan atas Royalti), yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi 100% dari tarif normal.
Atas perubahan UU Pajak tersebut, kami mohon bagi Bapak/Ibu yang belum memiliki NPWP dapat mengurus pembuatannya di Kantor Pajak terdekat sesuai dengan alamat KTP masing-masing. Apabila sudah memiliki NPWP, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengirimkan fotocopy NPWP tersebut yang kami perlukan untuk proses pembayaran royalti periode Juli-Desember 2008 dan selanjutnya. Kami mohon fotocopy NPWP dapat diterima paling lambat tanggal 30 November 2008.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Ingin memenuhi permintaan penerbit tadi, Kamis tanggal 13 November 2008, saya mengurus NPWP ke Kantor Pajak terdekat rumah saya, yakni di daerah Mangga Dua Surabaya. Naik angkutan
Formulis permohonan saya diterima, saya diberi tanda terima untuk mengambil kartu NPWP esok harinya. Dianjurkan pagi hari benar-benar, agar dapat nomor antrian kecil, menunggunya panggilan ke konter tidak lama (karena hanya mengambil kartu). Saya menanyakan apa yang harus saya kerjakan selanjutnya? Tiap bulan sebelum tanggal 20 saya diharuskan datang ke Kantor Pajak, menyampaikan laporan penghasilan saya. Caranya, saya harus mengisi laporan itu pada lembar formulir
Keesokan harinya pagi-pagi benar saya pergi ke Kantor Pajak. Dapat nomer antrian 02. Ketika dipanggil ke konter dan telah menerima kartu serta Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak, saya bertanya, karena royalti dari penerbit buku biasanya diberikan 6 bulan sekali, apakah saya bisa datang ke kantor pajak melaporkan/mengisi Surat Setoran Pajak tiap 6 bulan atau setahun sekali? Tidak boleh. Harus tiap bulan sebelum tanggal 20. Bukankah tidak setiap bulan saya menerima royalti, bukti apa yang harus saya cantumkan dalam SSP ? Ya ditulis saja NIHIL dalam kolom Jumlah Pembayaran Terbilang. Apakah harus saya sendiri yang datang? Boleh suruhan orang lain, atau diposkan. Tapi, bukankah saya harus mengisi formulir SSP ? Bagaimana saya dapat SSP ? Ya ketika menyetor pajak (menyerahkan SSP yang telah terisi) bisa mendapat blangko formulir SSP. Berarti tidak mungkin saya poskan. Suruhan orang juga tidak mungkin, sebab saya tidak biasa menyuruh orang lain.
Jadi, apa kesimpulan dari pengurusan NPWP untuk penghasilan kepengarangan saya? Jelas penghasilan kepengarangan saya tidak dipotong pajak lebih tinggi 100% dari tarif normal. Yaitu kalau tiap bulan sebelum tanggal 20 saya pergi ke Kantor Pajak menyetorkan SSP. Tetapi, seperti surat-surat pemberitahuan dari penerbit yang saya terima (saya tulis di atas), selama tahun 2006, 2007 dan sampai November 2008, saya tidak menerima royalti karena buku saya tidak laku. (Penjualan buku 0). Jadi, kalau tahun 2009 nanti berlaku UU Pajak Penghasilan dan royalti dari penerbitan buku saya nihil seperti tahun-tahun sebelumnya, penghasilan saya sebagai pengarang nihil, dan saya harus tiap bulan sebelum tanggal 20 naik angkutan kota pulang-pergi ke Kantor Pajak Rp 6.000,00. Setahun 12 X Rp 6.000,00 = Rp 72.000,00. Sebagai pengarang yang bukunya terbit, saya harus bayar setidaknya Rp 72.000,00 setahun.
*
PENGHASILAN DAN KEBERHASILAN MENGARANG
Sebenarnya sudah sejak awal saya tahu bahwa kepengarangan saya tidak bisa dijadikan penghasilan pokok hidup saya. Dimulai dari awal sekali, yaitu tahun 1950. Waktu itu saya umur 18 tahun, tetapi belum lulus dari SMP. Kakak yang selama perang (mengungsi) 1945-1950 menafkahi saya dan ibu dikirim perusahaan tempat ia bekerja (Philips) tugas belajar ke
Tulisan saya baru berhasil diterbitkan oleh majalah pada tahun 1952, setelah saya bekerja di Kantor Telegrap Surabaya yang menerima saya dengan ijazah SMP. Saya hidup dari gaji pegawai negeri, bukan dari mengarang. Tetapi tidak berhenti mengarang. Dan karangan yang dimuat di majalah mendapat honorarium. Saya bahkan membeli mesin ketik sendiri, untuk meleluasakan kegiatan saya mengarang di rumah. Saya menyewa rumah sendiri (Rangkah 5/23B), seorang diri di rumah (1953-1962, 1956 Ruba’i Katjasungkana ikut mondok di rumah sewa saya). Pada periode itu saya sempat bekerja di Kantor Telegrap (bertukar jadwal dinas dengan teman sejawat, saya bekerja jam 13.00 – 19.00 terus) sambil sekolah di SMAK St.Luis (masuk sekolah jam 07.00-13.00), sempat menulis cerita/artikel/berita di majalah dan koran, bahkan menulis novel (Tak Ada Nasi Lain, 1958), mulai menulis cerita bahasa Jawa dan menghasilkan cerita-cerita bersambung di Panjebar Semangat. Giat menulis segala macam artikel (sastra, tari, musik, pendidikan, olah raga). Berita dan ulasan tentang Sayembara Tari Serampang 12 di Surabaya 1958 beserta fotonya, hampir semua koran dan majalah di Surabaya memuat artikelku yang berbeda-beda jenis beritanya diterbitkan oleh koran Surabaya (Harian Umum, Surabaya Post, Trompet Masyarakat, majalah Gelora, Tanahair, Duta Masyarakat). Tulisan saya baik fiksi, berita maupun artikel segala macam, juga dimuat di majalah di
Dari gaji dari Kantor Telegrap saja, dan kegiatan penuh semangat saya menulis di koran
Meskipun hidup berumah tangga dengan anak isteri kecukupan, saya tidak berhenti menulis. Karangan-karangan saya, lebih-lebih cerita panjang (novel) terus mengalir diterbitkan. Ketika itu
Ketika buku saku bahasa Jawa sedang boom di masyarakat (1966-1968), isteri saya ikut ke redaksi Djaja Baja dan bertemu dengan Pak Tajib. Oleh Pak Tajib isteri saya dibisiki bahwa karangan-karangan saya banyak pembacanya, andaikata itu dijadikan buku, tentu laris. Isteri saya tanya-tanya kalau membuat buku, kira-kira biayanya berapa. Pak Tajib mengatakan sekian-sekian, dan sanggup menyuplai kertasnya (kertas CD jatah Djaja Baja). Waktu pulang saya goncengkan sepedah, di Jalan Kapasan isteri saya minta diturunkan. Dia menuju ke toko mas, dan melucuti kalung dan cincinnya, dijual. Dan akan menerbitkan karangan-karangan saya jadi buku dengan modal penjualan perhiasannya itu. Begitulah akhirnya, bekerja sama dengan Pak Tajib buku-buku cerita bahasa Jawa saya terbit. Saya dan isteri saya yang mencari percetakan, mengawal pengangkutan kertas, mencari pelukis, mencari izin penerbitan buku ke DPKN (polisi). Kalau buku bahasa Jawa waktu itu yang terbit dan laris adalah buku saku (selembar kertas
Pertama-tama menawarkan buku, Kadurakan Ing Kidul Dringu, (buku sudah saya bayar lunas di percetakan dan saya bawa ke rumah) saya tawarkan di kios buku di terminal Jembatan Merah (kami lalui kalau kami bekerja ke Kantor Djaya Bhakti). Bertemu dengan kios buku Munir. Semula Munir minta 10 jilid. Rumah saya sempit, ada setumpuk buku di situ, jadi lebih sempit. Karena tidak tahu ke mana lagi saya harus menjual, maka saya pasang iklan di Minggu Pagi Jogya. Klise gambar samak iklan juga saya buatkan. Harga iklan cukup mahal, tapi tetap saya tempuh. Dan pesanan buku lewat pos-wisel pun mulai datang, tidak tersangka ada yang dari luar Pulau Jawa. Dan ternyata untuk menguangkan penerimaan wisel di kantor pos, saya harus punya badan hukum perusahaan penerbitan, karena saya menggunakan nama Penerbit Ariyati. Jadi, untuk bisa mengambil uang pos-wisel, kami harus membuat akte badan hukum penerbitan ke notaris. Kami pun mengusahakan pendirian CV Ariyati. Entah berapa minggu kemudian, Munir datang ke rumah. Buku yang ada di rumah diborong, dibayar kontan.
Dari pengalaman itu selanjutnya saya menerbitkan buku-buku Kadurakan Ing Kidul Dringu (percetakan intertype di Jl. Karet), Emprit Abuntut Bedhug (percetakan intertype di Kapasan), Pethite Nyai Blorong (percetakan Jl. Karet). Gambar tentu Teguh Santosa. Waktu itu pembuatan gambar berwarna harus menggunakan 4 macam klese. Karena akan banyak buku yang mau saya terbitkan, maka saya pesan gambar-gambar dari Teguh Santosa. Mas Teguh Santosa hanya memberi gambar hitam-putih, nanti yang membuat berwarna pabrik klise. Sesudah pesanan gambar datang (langsung saya bayar), naskah dan gambar saya bawa ke DPKN untuk mendapatkan izin diterbitkan jadi buku dari polisi. Setelah itu baru saya masukkan ke percetakan. Setelah percetakan setuju, baru gambar-gambar saya buatkan klisenya. Semua saya kerjakan sendiri di antara tetap bekerja sebagai karyawan PDN Djaya Bhakti, seringkali bersama isteri, naik sepedah goncengan. Malah isteri saya punya inisiatif minta Direktur PDN Djaya Bhakti memasang iklan di buku kami, dan berhasil penerbitan buku ditambah penghasilan dari pemasangan iklan dari kantor kami.
Mencetakkan buku lewat percetakan intertype memerlukan waktu yang lama, maka saya berusaha mencari percetakan lain.
Tapi usaha penerbitan buku bahasa Jawa ini terhenti ketika diadakan rasia oleh polisi
Usaha saya menerbitkan buku bahasa Jawa mati kutu. Padahal waktu itu, saya dan isteri saya sudah terlanjur keluar dari karyawan PDN Djaya Bhakti. Keluar bukan karena ingin mengandalkan usaha penerbitan buku basa Jawa sebagai mata penghasilan pokok. Tetapi karena pada tahun 1967, semua karyawan PDN Djaya Bhakti harus masuk Soksi. Kami tidak mau, jadi keluar dengan uang pesangon masing-masing Rp 50.000,00.
*
Hari-hari sebelumnya, ketika penerbitan buku bahasa Jawa lancar, selain ke Lauw Solo, saya mengirimkan naskah cerita bahasa Jawa ke CV Gema Solo, milik Kho Ping Hoo. Waktu itu cerita silat Kho Ping Hoo juga sedang membeludak, formatnya juga sama dengan buku saku bahasa Jawa. Ternyata naskahku diterbitkan jadi buku saku oleh Kho Ping Hoo, yaitu Patriot-Patriot Kasmaran dan Lintang Panjer Sore. Tidak seperti saya mencetakkan buku ke Lauw, yaitu saya mendapat kiriman buku hasil cetakannya dan saya ikut menjual buku tadi, melainkan Kho Ping Hoo memberi honorarium saja (Rp 600,00 tiap naskah) dan saya tidak perlu ikut menjualkan buku tadi. Kho Ping Hoo menulis
Karena janji tadi, ketika keluar dari pekerjaan di PDN Djaya Bhakti, dengan semangat saya akan mengarang sebagai mata pencarian pokok saya. Saya di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari bersama isteri dan anak-anak, seperti mencuci pakaian, menyapu rumah dan semacamnya. Selesai itu, mengetik cerita. Waktu itu masih mengurusi penerbitan buku sendiri, ya kadang-kadang tanya ke percetakan, buku saya bagaimana.
Tiap bulan dua kali saya mengirimkan naskah ke Kho Ping Hoo, à 40-50 halaman ketik folio, yang tengah bulan naskah cerita satu jilid selesai, yang akhir bulan merupakan cerita seri bersambung berkelanjutan. Tiap naskah saya kirim, saya segera terima HR (atau royalti?) Rp 600,00. Itu mencukupi benar, karena harga beras Rp 30,00 per kilogram. Waktu itu saya punya dua orang anak, saya tidak bekerja cari uang apa pun kecuali mengetik karangan di rumah, terutama untuk dikirim ke Kho Ping Hoo. Tetapi tidak bisa bertahan lama. Sebab naskah ceritaku yang seharusnya bisa sebulan terbit dua buku (saku) cerita silat, ternyata tidak terus diterbitkan jadi buku oleh Kho Ping Hoo. Jadi honorarium tetap saya terima tiap saya kirim naskah, tetapi tidak diterbitkan jadi buku. Berarti saya menerima gaji buta. Honorarium yang saya terima bukan dari hasil (laba) penjualan buku. Maka hubungan dengan Kho
Tapi pekerjaan ini terlalu susah. Artinya saya harus banyak berkeliaran di
Karena sudah jelas isteri saya untuk bertahan mencari kehidupan di Surabaya, dan dengan modal uang untuk penerbitan buku maupun berdagang kapok tidak mungkin, tetapi saya lebih mengandalkan menjual tulisan saya ke suratkabar dan majalah (menjadi wartawan free-lancer), maka agar modal yang kami miliki tidak hilang percuma, kami belikan tanah di dekat rumah milik yang menyewakan rumah saya, dan kelebihan uangnya kami gunakan untuk membangun rumah di situ, yang akhirnya menjadi rumah Rangkah 5/25A. Pembangunan rumah itu, karena dikerjakan sedikit demi sedikit, memakan waktu 1968-1971. Februari 1971 baru kami tempati, itupun lantainya masih tanah, temboknya belum dipelur, daun pintunya hanya pada kamar-kamarnya.
Waktu itu Mas Basuki Rachmat dan Mas Farid Dimyati yang dulunya wartawan/redaktur majalah/suratkabar di Surabaya dan juga seniman drama/sastra, pada membantu Walikota Surabaya Orde Baru R. Soekotjo. Walikota mau menerbitkan majalah (Gapura). Tahu saya di rumah, mereka mengajak saya menjadi redaktur dan pengelola majalah Gapura. Saya pun masuk kantor Walikota
Meskipun pekerjaan sebagai pegawai Humas yang harus meliput kegiatan Walikota dan DPRD cukup sibuk, Walikota Orde Baru yang mengubah kota besar jadi kota metropolis, kegiatannya tidak hanya di siang hari dan di dalam kota, namun dengan pegang mesin ketik di kantor, saya sempat mengarang dengan lancar. Mengarang cerita pendek dan cerita sambung, bahasa Indonesia dan Jawa. Khusus yang bahasa Jawa punya saluran kekuasaan (membantu Mas Bas sejak dahulu), maka kerja penulisan cerita, berita, dan artikel apa saja lebih leluasa dan produktif. Hingga cerita sambungnya di majalah Djaja Baja dari punya saya, ke punya saya lagi. Dlemok-dlemok Ireng, Dom Sumurup Ing Banyu, Jemini cerita sambung yang berturut-turut dimuat di Djaja Baja. Saya sempat pula mengirimkan cerita sambung ke majalah Panjebar Semangat, Luwih Becik Neraka. Sedang tulisan-tulisan bahasa Indonesia, panjang atau pendek, cerita sambung atau hanya berita atau artikel, muncul di
Apalagi “keahlian” saya sebagai pekerja seni dan menulis dibutuhkan untuk mengerjakan suatu proyek, misalnya menjadi pengurus Dewan Kesenian Surabaya, menjadi tim penulisan Master Plan Surabaya 2000, meliput sejak awal dan penulisan buku penelitian Hari Jadi Kota Surabaya, menjadi tim penulisan sejarah perjuangan 10 November 1945 di Surabaya, menjadi tim penulisan sejarah pers Jawa Timur, menjadi tim penulisan Panglima-panglima Brawijaya. Sungguh penghasilan saya mencukupi.
Meskipun begitu, menulis karangan tidak bisa lepas dari kehidupanku. Dalam tahun-tahun sibuk itu di bidang penulisan saya masih dapat hadiah karena penulisan saya tadi. Misalnya dapat hadiah buku Inpres (Damar Wulan, diterbitkan Gramedia Jakarta, Jaring Kalamangga diterbitkan Bina Ilmu Surabaya), meraih Juara Harapan menulis roman di Dewan Kesenian Jakarta, cerita sambung saya dimuat di Kompas (Surabaya Tumpah Darahku), Hadiah I penulisan buku seni untuk mahasiswa dari Dep.Dikbud Jakarta (Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa).
Orde Baru berlangsung terus, Walikota Surabaya berganti-ganti dari R. Soekotjo, Soeparno, Muhadji Widjaja, Dokter Purnomo Kasidi semua TNI, dan pembangunan terus berlanjut. Gedung Walikota yang baru pun dibangun, Bagian Humas pun mendapat ruangan yang layak, serta masuk pegawai-pegawai baru yang pendidikannya sarjana, maka menduduki pangkat dan jabatan lebih tinggi daripada saya. Dengan perluasan seperti itu, maka pekerjaan mengikuti tim-tim pembangunan yang semula saya ikuti, diambil alih oleh tenaga muda, dengan segala ceperan penghasilannya. Misalnya memotret moment-moment pembangunan yang dulu saya jadikan ceperan penghasilan dengan menjual foto (baik ke suratkabar, maupun ke perorangan ~ misalnya kepada Pak Camat ketika terjepret foto dekat dengan Walikota, foto mengikuti peninjauan DPRD ke Karangkates, DPRD menjemput dwaja Kota Surabaya ke Solo) setelah saya ajarkan memotret kepada petugas baru, dikuasai oleh mereka. Tapi lebih dimanfaatkan lagi oleh tenaga muda itu. Dulu saya menjual foto (untuk penghasilan ceperan) hanya selembar dua lembar, oleh mereka menjadi satu-dua album. Bahkan ada tenaga Humas, meskipun titelnya sarjana, memotret Pak Sutran Bupati Trenggalek ketika rapat dengan Gubernur Jawa Timur, dikumpulkan jadi satu album, dibawa sendiri ke Trenggalek untuk dijualnya. Betul-betul penghasilan ceperan yang diusahakan dengan maksimal.
Sedang saya, karena kalah pangkat dan kalah muda, dikembalikan khusus sebagai pengelola majalah Gapura, karena bisa menulis di majalah ini (dari pegawai Humas) hanya saya dan Farid Dimyati. Berbeda dengan memotret yang bisa segera saya ajarkan kepada tenaga baru Humas, kepandaian menulis tidak bisa dialihkan kepada mereka. Saya tidak perlu pergi ke luar kantor, duduk manis di pojok ruangan kantor, menghadapi mesin tulis, cukuplah. Pekerjaan mengelola majalah Gapura (terbit sebulan sekali) dari mencari/menulis isinya sampai mengurus percetakan dan peredaran, secara rutin selama sebulan bisa saya selesaikan dalam seminggu. Kalau ada kegiatan di luar tugas dinas
Meskipun mencari penghasilan ceperan dari proyek-proyek pembangunan
Pada tahun 1980-an, Bapak Budi Darma mengritisi para pengarang/penulis sastra
Pada tulisan Pak Budi Darma lainnya (saya lupa di mana) tentang kepengarangan, suatu karya (sastra) yang baik yang indah tentulah tercipta dari orang yang berbakat seni (sastra). Bakat seninya besar. Namun suatu hasil karya bisa saja tercipta dari seorang yang bakat seninya hanya 15%-20%, selebihnya dari etos kerjanya. Hasil karya yang begitu kualitas seninya tidak seindah orang yang berkarya mengandalkan bakatnya, tapi berkat etos kerjanya menghasilkan produk yang berlimpah. Meskipun tulisan tadi tidak khusus dialamatkan kepada saya, tetapi sepertinya sayalah yang dijadikan contoh soal. Dan saya senang dijadikan contoh soal oleh Pak Budi Darma. Keberhasilan kepengarangan saya dan keproduktivitasan hasilnya lebih cenderung memburu kesenangan berkreativitas bebas. Penghasilan saya mengarang tidak tertandingi oleh teman sejawat saya yang berebutan mencari rezeki ceperan dari pekerjaan dinasnya. Tetapi pekerjaan tulis-menulis pun nilai sastranya tidak sebagus atau tersohor seperti karya sastra yang indah-indah.
Saya memang tidak suka berebutan memburu rezeki (mengikuti pasar). Oleh karena itu, meskipun pada periode puluhan tahun itu ada proyek buku Inpres untuk kanak-kanak (yang dibeayai oleh Unesco) yang imbalannya mengiurkan (naskah/dummi yang disetujui oleh dewan juri dari Dikbud, untuk SD bukunya 80.000 exp, untuk SMA 20.000 exp dibeli oleh pemerintah untuk disiarkan ke perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia). Saya ikut penataran/lokakarya tentang buku kanak-kanak apa yang diinginkan oleh pemerintah (Dikbud), diselenggarakan selama 7 hari di Cipayung, dan 7 hari lagi pada jarak waktu sebulan berikutnya dengan membawa hasil karyanya buku kanak-kanak untuk didiskusikan (tahun 1976). Dari proyek buku Inpres ini banyak sekali pengarang (atau sebelumnya bukan pengarang) dan penerbit (yang sebelumnya bukan penerbit) yang tiba-tiba menjadi kaya raya karena bukunya lolos putusan juri dan bukunya dibeli oleh pemerintah. Saya yang telah ditatar tentunya bisa menghasilkan karya buku kanak-kanak demikian. Namun saya tidak giat memburu menciptakan karya buku kanak-kanak. Mengarang buku untuk bacaan kanak-kanak bukan kesenanganku mengarang cerita. Hanya dua judul buku untuk SD (Oh, Surabaya diterbitkan Bina Ilmu Surabaya dan Damar Wulan diterbitkan Gramedia Jakarta), dan satu judul untuk SMA (Jaring Kalamangga diterbitkan Bina Ilmu Surabaya) buku saya yang mendapat Inpres. Saya lebih suka mengarang sesuka hati, bebas, tidak terikat pesanan. Dan hasilnya karya-karya yang……tidak menganut selera pasar. Tidak menghasilkan banyak uang.
Anak-anak saya, keempatnya tentulah mengalami sekolah SD, SMP, SMA pada tahun-tahun periode buku Inpres itu. Namun tidak seorang pun pernah membaca buku pinjaman dari sekolahnya. Keempat anak saya suka membaca buku, karena tiap hari gajian mereka saya giring ke Toko Buku Gramedia di Jalan Basuki Rakhmat untuk memilih buku masing-masing. Mereka kenal buku-buku seri
Sekarang Orde Baru sudah selesai. Zaman Reformasi sudah berjalan sekian tahun. Namun pendidikan putera bangsa di sekolah, masih banyak yang sama dengan sekolah lakon Laskar Pelangi. Lebih-lebih tentang pembelajaran membaca buku. Membaca buku dan menulis buku adalah sarana hidup modern. Semua pekerjaan yang modern pasti disaranai dan diprasaranai penerbitan buku, penulisan buku dan pembacaan buku. Dan pembudayaan membaca buku adalah pada umur-umur dini, atau umur-umur 12 tahun sekolah dasar. Di negara maju (Belanda, Jepang, ~ di mana pada zamannya saya ikut mengenyam pendidikannya) sekolah dini 12 tahun adalah sistem membudayakan anak manusia membaca buku dan menulis buku. Di sekolah itulah anak manusia dibudayakan membaca buku dan menulis buku. Tidak di tempat dan waktu lain. Di zaman Belanda dan Jepang (1938-1945) saya dan teman segenerasiku belajar membaca buku dan menulis buku juga di sekolah, tidak di tempat dan waktu lain. Tapi di luar sekolah, kami tidak menonton TV atau main playstation, bermain di alam bebas, juga seringkali membaca buku bukan belajar, melainkan stimulan rangsangan menikmati isi buku (bukan paksaan), seperti anak sekarang menikmati nonton TV. Orang Jepang, yang untuk menjadi cerdas dan pandai harus membaca buku, dan untuk membaca buku harus hafal huruf kanji paling tidak 2000 gambar, tidak mungkin mereka setelah jadi mahasiswa tiba-tiba menghafal huruf begitu banyak. Tentu menghafalkannya huruf kanji diangsur dari sejak dini, selama 12 tahun belajar di sekolah dasar. Kalau melewati 12 tahun umur sekolah anak mereka tidak dididik/dibudayakan membaca dan menulis huruf kanji (membaca buku), tidak mungkin orang Jepang itu menjadi cerdas. Orang Jepang yang tidak hafal 2000 huruf kanji, mana bisa membaca buku? Dan karena tidak membaca buku, ya bodoh. Bukan di Jepang, begitu juga yang saya alami pada sekolah Angka Loro zaman Belanda (1938-1942). Klas satu, membaca buku dan menulis buku (huruf Jawa), kelas dua membaca buku (Siti Karo Slamet), kelas tiga buku bacaan kelas (dibaca di kelas bersama-sama) Koentjoeng Karo Bawoek, Panggelar Budi, Kembang Setaman jilid I, Matja Titi Basa Lan Tjarita.
Yang saya tidak habis pikir, bagaimana kinerja para guru dinilai selama ini? Tidak adakah semacam performance appraisal yang menjamin performa guru selalu termonitor, terkoreksi, dan terkembangkan secara sistemik?
Sangat disayangkan bila dinas pendidikan tidak punya performance appraisal yang efektif. Selain menghambat peningkatan kualitas guru, jenjang karir guru mungkin jadi tidak jelas. Guru yang ideal dari sisi teknis dan psikologis tidak terpantau. Kalaupun ada sertifikasi, kualifikasi guru-guru seperti guru kelas anak saya itu rasanya tidak meningkat. Yang ada cuma kenaikan di atas kertas. Sebab, tidak ada tindak lanjut kontinu.
Ketersediaan dan kapasitas asesor juga perlu diperhatikan. Bukan rahasia lagi, problem utama peningkatan mutu guru adalah jumlah guru yang terlalu banyak. Sehingga, sulit menaksir kemampuan mereka secara intens dan kontinu.
Apalagi, kapasitas asesor pun dipertanyakan. Sebab, pengawas sekolah umumnya adalah mantan kepala sekolah yang dianggap berprestasi. Sekali lagi, karena tak berkarir dari sekolah negeri, saya kurang paham soal kategori atau standar apa yang membuat seorang kepala sekolah dianggap berprestasi. Apakah karena nilai unas sekolahnya selalu bagus? Karena siswanya selalu juara Olimpiade?
Dengan asumsi belum ada performance appraisal terintegrasi dalam jenjang karir seorang guru, bagaimana generasi guru yang sudah melampaui jenjang kepala sekolah dan sekarang menjadi pengawas? Dari segi kemampuan tertib administratif, mereka mungkin sangat berpengalaman. Tapi, bagaimana paradigma kependidikan? Pernahkah mereka menerapkan student centered (pembelajaran berbasis pada siswa)? Jangan-jangan mereka tak beda dengan guru kelas anak saya itu? (Rendra Prihandono, Wakil Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia, di Metropolis Jawa Pos, Jumat 5 Desember 2008).
Dengan sistemik kami harus pinjam buku di perpustakaan sekolah dan terkontrol, baru kelas 4 sekolah Angka Loro (sekolah untuk anak desa), kami sudah membacai buku banyak sekali, baik huruf Hanacaraka maupun Latin, baik bahasa Jawa maupun bahasa Melayu. Sebelum saya naik kelas 5, Jepang datang. Dan berbagai tingkat sekolah yang semula berbeda-beda (Angka Loro 5 tahun tamat, HIS 7 tahun tamat) diubah sama rata, yakni SR 6 tahun, SMP (dulunya MULO) 3 tahun, SMT (dulunya ada HBS 5 tahun, AMS 3 tahun) 3 tahun. Dijumlah menjadi sistem sekolah dini 12 tahun.
Tahun 1996, Taufik Ismail meneliti para lulusan SMA (12 tahun pendidikan dini) di berbagai negara. Ternyata lulusan SMA Indonesia telah membaca nol buku. Oleh laporan tadi, maka Taufik Ismail mendapat grand untuk mengupayakan minat baca pada putera bangsa di sekolah. Begitu perhatiannya badan dunia untuk mencerdaskan anak manusia menyaranai mereka membaca buku dan menulis buku, tetapi pendidikan bangsa
Tetapi kalau ilmu hanya ditampung dari pengalaman atau pertemuannya dengan guru, hanya berdasarkan kodrat indrawi melihat dan mendengar, akan gampang terlupakan. Contoh soal, ketika saya menghadiri Kuliah Tjokroaminoto untuk Demokrasi dan Kebangsaan di Unair Rabu 12 November 2008. Ketika sidang sedang berlangsung, Mbak Yenny Zannuba Wahid mengurai pendapatnya dengan canda, santai, mengena sasaran, hingga suasana sidang banyak tertawa serta banyak peserta bertanya: “Siapakah pahlawan sekarang ini? Apakah Amrozi Cs itu pahlawan atau apa?” Semua terjawab dengan jelas, pakai contoh-contoh yang memikat. Namun, begitu selesai sidang, apa yang diperoleh para peserta? Kenangan sekejap, dan terlupakan. Bahkan para penanya pun lupa apa jawaban Mbak Yenny. Sebab mereka tidak merekamnya dengan catatan tertulis. Apalagi setelah sebulan dua bulan dari peristiwa itu.
Untung saya tulis di web saya, sehingga yang tidak hadir pun bisa menampung ilmu yang diucapkan oleh Mbak Yenny Zannuba Wahid ketika itu, meskipun tidak selengkap yang saya saksikan. Ya, kembali lagi, menyerap ilmu harus disaranai dengan membaca (buku) dan menulis (buku), itulah tuntutan kehidupan modern. Jadi, peristiwa mendengarkan ceramah Mbak Yenny itu segera saya tulis. “Don’t lose your ideas, quickly write them down!” ungkapan itu saya temukan pada tisu J.CO Donuts & Coffee di Mega Mall Bekasi (lebih terkenal dengan Giant Bekasi, karena tulisan Giant begitu besar dan strategis).
Selasa 9 Desember 2008, saya mengantar cucu (6 tahun) yang disertai ibunya (anak saya nomer 2) dari Bekasi pergi melihat Museum Geologi di Bandung, dengan travel Xtrans Bekasi-Cihampelas berangkat jam 09.30. Kami datang jam 07.30, oleh Xtrans belum diterima, harus menunggu 15 menit sebelum pemberangkatan. Untuk menunggu waktu sampai jam 09.15 kami sarapan dulu di J.CO Donuts & Coffee di dekat Xtrans, dan menemukan ungkapan yang sangat menyokong penghayatan saya tentang membaca (buku) dan menulis (buku) itu. Apa yang diungkap dalam tulisan itu sudah saya laksanakan semenjak saya di bangku sekolah di SMP zaman RI perjuangan, yaitu tatkala teknik rekaman suara belum ada. Dan berlanjut ketika saya suka cari berita/wawancara untuk ditulis di majalah atau koran. Untuk mengingat tentu saya bikin orek-orek tulisan (karena sistem rekaman suara belum zaman). Juga ketika mendengarkan ceramah Mbak Yenny, karena saya tidak punya alat perekam suara, maka saya catat orek-orek sendiri.
Jadi bukan saya saja penganjur TULISKAN IDEMU, bahkan institusi sekapasitas J.CO Donuts & Coffee pun menganjurkan demikian. Yang paling penting adalah putra bangsa
Saya mengantar cucu naik Xtrans Bekasi-Cihampelas 09.30, dan kembali dari Bandung Xtrans Cihampelas-Bekasi 17.30. Selama di Bandung, selain puas dengan melihat Museum Geologi, belanja oleh-oleh (makanan ringan) di Pasar Baru, sempat juga mampir ke rumah kakak di Hegarmanah Wetan. Kakak saya adalah yang tahun 1950 dikirim oleh NV. Philips ke
Banyak yang menanyakan, di manakah buku Inpres yang dibeayai oleh Unesco dan disebarkan di sekolah dasar dulu itu? Mengapa tidak berfungsi menjadi sarana pendidikan membaca buku di sekolah?
Perpustakaan Umum, Oase di Tengah Tingginya Angka Buta Huruf dan Kemiskinan
HARUS MENCICIL BACAAN TIAP HARI KARENA TAK MAMPU SEDIAKAN PASFOTO
“Pemerintah
Kalau ada dana, Ndiaye berencana menyebarluaskan perpustakaan ke 16 distrik di Pikine. “Banyak orang yang sebenarnya tertarik membaca. Tapi, mereka tak punya cukup uang untuk transportasi menuju ke perpustakaan di sini,” katanya.
Sayang memang rencana Ndiaye hingga kini baru sebatas obsesi. “Tak ada dana, tak ada buku,” ujarnya. (cuplikan berita Jawa Pos, Kamis 4 Desember 2008).
Di mana buku Inpres yang dibiayai oleh Unesco dan disebarkan di sekolah dasar di
Pak Arifin, direktur penerbit Bina Ilmu di Surabaya, pernah mengeluh kepada saya, untuk menagih buku Inpres yang telah dikirimkan ke daerah, penerbit harus punya tanda terima yang sah dari bupati/walikota daerah setempat. Itu sulit sekali meskipun buku telah dikirimkan ke
Jadi, niat baik Unesco mengadakan proyek buku perpustakaan di sekolah SD itu, ternyata tidak bisa mencerdaskan putera bangsa selama bertahun-tahun itu. Tidak ada seorang pun ketika proyek Inpres itu berlangsung terobsesi seperti Papa Buba Ndiaye, terutama di kalangan pimpinan bangsa, yang memfungsikan perpustakaan adalah prasarana mencerdaskan putera bangsa. Oleh karena itu proyek Inpres buku kanak-kanak itu muspra. Bahkan sampai sekarang, usaha membudayakan putera bangsa membaca buku dan menulis buku pada usia sekolah 12 tahun sebagai sarana utama mencerdaskan putera bangsa pun diabaikan. Pemerintah
Depdiknas Bakukan Program PAUD
“Ini upaya menebus kesalahan masa lalu, di mana selama puluhan tahun kita mengabaikan PAUD,” terang Mendiknas Bambang Sudibyo saat membuka Seminar dan Lokakarya Nasional PAUD di Institut Pertanian
Menurut Bambang, kecerdasan secara komprehensif meliputi kecerdasan otak kiri atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan otak kanan atau kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetika, dan kinestika. “Karena 80 persen potensi kecerdasan komprehensif anak dapat dipacu agar berkembang secara pesat dan optimal pada masa usia dini, sisanya 20 persen dikembangkan setelah usia 8-20 tahun,” ujarnya.
Meski PAUD menjadi level penting dalam proses pendidikan, Bambang menolak adanya pembelajaran yang memaksa anak-anak usia dini menerima pelajaran membaca, menulis, dan berhitung (huruf tebal dari pengutip). Bagi dia, hal terpenting dalam PAUD adalah pemberian stimulan (rangsangan) kepada anak. Anak yang besar dan berkembang dalam lingkungan yang kaya stimulan, kecerdasan otaknya berkembang lebih sempurna.
Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengatakan, untuk mewujudkan sistem PAUD yang baik, pemerintah bersama Bappenas dan sektor terkait mulai 2009 mengembangkan sistem PAUD yang holistik dan integratif. “Dalam sistem ini, semua jenis stimulan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan kecerdasan anak akan dipadukan dalam satu sistem layanan yang utuh,” tuturnya. (kutipan berita Jawa Pos, Kamis 27 November 2008).
*
Dengan rumah tangga berpenghasilan cukup demikian, isteri saya berkeinginan pindah ke rumah baru. Ikut-ikutan para tetangga dan teman sejawat yang pada membeli rumah dan menempati rumah di perumahan baru, bukan rumah perkampungan lama seperti Rangkah. Setelah mencari berbagai pembangunan perumahan, akhirnya saya tawarkan perumahan YKP, real estate yang dimiliki oleh Pemkot. Yang caranya memperoleh peminat harus menabung dulu, setelah cukup jumlahnya separo lebih dari harga rumah, dapat pembagian rumah. Selanjutnya sisa harga rumah bisa diangsur tiap bulan hingga lunas untuk umum 80 kali, untuk pegawai negeri 100 kali. Saya punya tabungan Rp 4 juta, untuk pembelian rumah seharga Rp 12 juta, rumah termurah di YKP dengan luas tanah 200 m2, bangunan rumah type 70. Isteri saya punya warisan sawah di Ngombol, yang waktu itu digarap oleh mbakyunya, yang menghasilkan setahun (2 kali panen) Rp 70,00. Kadang-kadang hanya dilapuri sawahnya puso. Jadi isteri saya berkehendak menjual saja sawah-sawah warisan itu. Saudara-saudaranya pada mengingatkan sawah warisan kok dijual, pada melarang. Tetapi isteri saya tidak mengatakan menjual sawah warisan, melainkan memindahkan warisan itu dari desa ke
Setahun menjelang pensiun kami pindah ke rumah YKP RL-I-C 17 Surabaya. Waktu itu anak sulung telah lulus Unibraw, masih mencari pekerjaan, anak kedua (perempuan, lulusan Widya Mandala) sudah bekerja di Alun-alun Perak, nomer tiga dan bungsu masih di SMAN 5 Surabaya.
Mengingat keberhasilan saya yang melebihi teman-teman sejawat yang pangkatnya maupun jabatannya lebih tinggi, dan merasa kelebihan saya itu adalah kegiatan dan keterampilan saya menulis cerita, maka dengan perasaan bergelora saya menyongsong hari pensiun saya (1988) sebagai masa depan yang bebas merdeka. Saya tidak mencari pekerjaan apa-apa lagi, akan mengandalkan keterampilan saya mengarang cerita. Jadi keluar dari pekerjaan dinas pemkot (pensiun), gelora hati saya seperti tahun 1967 ketika keluar dari PDN Jaya Bhakti, akan mengandalkan mengarang sebagai mata penghasilan pokok.
Uang pensiun saya Rp 121.000,00, ternyata persis dengan cicilan pelunasan rumah tiap bulan. Jadi, setelah ambil uang pensiun di kantor pemkot, langsung menyeberang jalan ke kantor Perumahan YKP membayar cicilan rumah, pulang tidak membawa uang apa-apa. Di rumah, seperti yang saya rencanakan, yang saya kerjakan hanyalah mengetik karangan. Waktunya bebas, saya atur sendiri. Pernah juga semalam suntuk tidak berhenti mengetik, pagi harinya saya jalan-jalan melihat-lihat rumah tetangga, kembali ke rumah anak-anak sudah bangun, tetapi ada sesuatu pekerjaan rumah tangga yang tidak beres. Isteri saya marah-marah, “Pagi-pagi sudah keluyuran, tidak mau membereskan rumahnya dulu….!” Dengan bekerja tidak mengenal waktu begitu, saya berhasil memasukkan cerita bersambung saya di
Kegiatan kumpul-kumpul sastrawan bahasa Jawa juga masih saya ikuti. Waktu itu kami menyelenggarakan pertemuan sastra Jawa bekerja sama dengan LIA, kami mendatangkan pembicara Esmiet (Banyuwangi), Tamsir AS (Tulungagung), Arswendo Atmowiloto (Jakarta), JFX Hoery (Bojonegoro). Setelah acara di LIA, saya, Mas Tamsir, Mas Hoery (mereka menginap di rumah saya) diajak Mas Wendo ke hotelnya, untuk membicarakan sesuatu, kira-kira kelanjutan dari acara di LIA tadi. Mas Esmiet tidak ikut kami, karena dia menginap di rumah puteranya atau menantunya di
Begitulah akhirnya, saya dan isteri pindah ke Yogya, Mas Hoery, isteri dan anaknya juga pindah ke Yogya. Kami diberi keleluasaan penuh di bidang keredaksian (merekrut wartawan, mengadakan pelatihan, mendatangkan pakar kewartawanan, membuat/menerbitkan dummi tiap minggu) untuk menyelenggarakan penerbitan tabloid bahasa Jawa Praba. Antara lain saya rekrut Sandra (asal Blitar yang sudah saya lamar jadi calon menantu untuk administrasi). Dan Ardini Pangastuti asal Tulungagung, anggota Sanggar Triwida (sastra Jawa) untuk redaktur. Mereka juga harus tinggal di Yogya. Sedangkan tata usaha dan administrasi/keuangan diatur oleh pihak Kompas. Pemimpin Perusahaan Bu Roesilah, Keuangan Mas Agung Prasetya.
Dengan keadaan seperti itu, bereslah sudah urusan rumah tangga saya. Kami bekerja mulai Desember 1989, sampai Januari 1991. Berhenti dan bubar, karena tidak dapat izin terbit (SIUPP) dari Menteri
Keredaksian dan percetakan Jawa Anyar berjalan setahun, dipindah ke Kompleks Jawa Pos, Karah Agung 45 Surabaya.
Dalam kurun waktu saya dipindah ke Yogya, Solo dan kembali ke
Saya tidak tahu, penghasilan dan keberhasilan saya ini karena kemampuan saya mengarang, atau karena kemampuan saya yang lain. Kalau dulu kemampuan tadi sebagai pns, sekarang sebagai buruh? Namun, waktu itu kegiatan saya mengarang cerita tidak berhenti. Novel Gadis Tangsi yang semula saya ajukan ke redaksi Kompas, lama tidak ada jawaban, saya sodorkan ke Jawa Pos ketika saya direkrut ke Surabaya, langsung dimuat Jawa Pos sebagai cerita sambung. Baru dimuat sekali, saya dapat
Anak saya (yang masih jadi tanggungan) nomer tiga akhirnya lulus. Dia ditawari jadi dosen di ITS, menolak, cari kerja sendiri (lewat iklan koran Kompas) dapat di Honda
Karena kian ringan beaya rumahtangga saya, saya ingin mencurahkan tenaga dan pikiran menulis cerita bebas, tidak terikat oleh institusi lain, maka saya mengundurkan diri dari menjadi redaktur Jawa Anyar.
Jelas bahwa saya berhasil membina rumah tangga saya, anak-anak saya semua bisa hidup mandiri. Mereka memang tidak menjadi penulis sastra seperti saya, mereka titel kesarjanaannya Insinyir, artinya bakat IPA-nya lebih mendukung keberhasilan mereka. Saya sendiri waktu sekolah di SMP dan SMA menempuh bagian B, IPA, dan angka IPA saya bagus. Tapi terpaksa meniti karya dengan menulis, dan berhasrat sekali menulis cerita, karena terpaksa harus cari penghasilan karena waktu mengakhiri pendidikan di SMP tidak ada yang membiayai hidup saya. Dan ternyata hidup saya selanjutnya, bahkan sejak waktu itu, penghasilan saya bukan dari menulis, melainkan dari pekerjaan lain. Jadi, saya sangat setuju dengan cerminan Pak Budi Darma, bahwa bakat saya menulis sebenarnya hanya 15%-20%, hanya karena saya tidak mau kalah itu saja yang membuat saya terus menulis. Sebanyak itu tulisan saya, tidak satu pun yang pernah diterbitkan ulang dari penerbit yang sama, dan tidak pernah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Bukankah itu pertanda bahwa nilai kesastraan saya rendah? (Novel-novel Suparto Brata yang bercorak hiburan dengan tema percintaan tak terhitung jumlahnya dalam bahasa Jawa. Juga menulis novel dengan corak silat.
Begitu pula penghasilan dan keberhasilan saya mengentas anak-anak saya menjadi orang-orang yang mandiri, mendapatkan pekerjaan yang bagus, bisa membangun rumah sendiri yang besar, tidak ketinggalan dengan cara kehidupan modern. Saya tidak pernah mengarahkan mereka harus menempuh pendidikan apa. Namun saya hanya membacakan buku cerita ketika mereka masih belum bisa membaca, menggiring mereka ke toko buku tiap habis gajian, dan menyuruh mereka mengetik dengan sistem 10 hari ketika mereka pertama kali memegang mesin ketik. Anak saya ke-empatnya semua mengetik dengan 10 jari. Meskipun sekarang dengan adanya HP dan PDA mereka mengetik dengan satu ibu jari, tetapi kepandaian mengetik dengan 10 jari seperti yang saya jalani hingga saya bisa menyetor karangan 40-50 halaman tiap dua minggu ke Kho Ping Hoo, masih ada hubungannya dengan kebanggaanku menjadi penulis buku cerita. Dan teman-teman sejawat anak-anak saya masih terkagum-kagum menyaksikan anak-anak saya mengetik dengan 10 jari. Di sini bisa dicatat, bahwa sekalipun orang tidak mencari nafkah dengan hanya melulu menulis cerita, tetapi menggunakan mesin ketik sebagai alat bantu penciptaan orang untuk lancarnya menulis dengan secara yang benar, benar-benar mendorong orang selalu menggunakan alat tadi untuk memacu lancarnya pekerjaannya tadi.
Begitu dengan alat bantu lain ciptaan manusia untuk keperluan lancarnya pekerjaan lain, kalau dilakukan dengan benar, akan menolong mengerjakan keperluan hidup dengan lancar, dengan hasil yang maksimal. Misalnya mobil. Kalau diperlakukan dengan semestinya dan benar, maka akan menjadi alat pengangkutan yang lancar, aman, berhasil, dan orang akan terus suka mengendarai mobil. Kadang-kadang, kalau mencari pekerjaan untuk hidup sulit, mengendarai mobil dengan baik dan benar itu bisa digunakan untuk mencari nafkah juga.
Itu pulalah yang saya pahami keterampilan saya mengetik dengan 10 jari, dan hal itu juga saya ajarkan kepada anak-anak saya. Itu pulalah apa yang saya ajarkan kepada semua anak-anak saya. Pergunakanlah mesin ketik secara benar. Pergunakanlah kamera foto secara benar. Nyetellah TV yang benar, ditonton yang benar. Maka hasilnya akan maksimal. Keempat anak saya (tiga laki-laki, satu perempuan) semua mengetik 10 jari, semua dapat mengendarai mobil dengan baik. Meskipun bukan untuk mata pencaharian, keterampilan mereka menggunakan alat-alat ciptaan manusia tadi bisa mempermudah hidupnya.
Begitu pula pendidikan membaca buku dan menulis buku. Mengetik 10 jari, mengendarai mobil, membaca buku dan menulis buku, semua itu bukan kodrat. Untuk mempergunakan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal harus ada perkenalan dengan alat, dan pelatihan mempergunakannya. Dan pelatihan menggunakan alat yang paling baik dan benar agar mencapai hasil yang maksimal adalah sewaktu pertamakalinya berkenalan dengan alat tersebut. Kalau berkenalan alat tersebut lalu dibimbing caranya menggunakan yang baik dan benar, maka selanjutnya orang akan menggunakan alat tersebut dengan cara yang benar, tidak tahu atau kikuk kalau menggunakan cara yang tidak benar. Perkenalkanlah cara menggunakan alat yang baik dan benar pada perkenalan alat yang paling awal.
Untuk mengetik 10 jari, sejak anak saya pegang mesin ketik pertama kalinya langsung saya bimbing mengetik 10 jari hingga mereka menggunakan alat tadi secara baik dan hasilnya maksimal. Begitu pula membaca buku dan menulis buku. Bukan kodrat. Harus ada perkenalan, dan pelatihan. Sebaiknya semenjak dini, seperti halnya anak saya pertama kali pegang mesin ketik. Kalau mengetik atau mengemudikan mobil, dilatih sebulan dua bulan sudah mahir. Tetapi kalau membaca buku dan menulis buku dibutuhkan latihan berapa waktu? Agar mahir dan berbudaya, ya selama sekolah dini 12 tahun itu, di mana dia mengenal buku bacaan yang pertama kalinya. Dan seperti halnya ketika mereka belajar mengetik, akhirnya berbudaya mengetik dengan 10 jari, dan tidak bisa mengetik dengan cara yang lain, maka begitu juga terhadap buku. Mereka seterusnya mempergunakan buku sebagai alat bacaan dan membaca buku sebagai kebiasaan. Mereka berbudaya membaca buku, dan memperlakukan buku dengan bagaimana fungsi sebaiknya, yaitu dibaca, dinikmati dengan membacanya. Budayakanlah dari awal! Jangan diabaikan! Membaca buku dan menulis buku adalah sarana utama mencerdaskan bangsa, sedang ilmu yang lain-lain adalah muatan ilmu bukan sarana penyerapan ilmu. Meskipun muatan ilmu diberikan, kalau sarana penyerapan ilmunya tidak dibudayakan, ya ilmunya tidak tertampung. Muatan ilmu yang diberikan merojol terlupakan, tidak mencerdaskan putera bangsa. Karena itu untuk mencerdaskan bangsa, sarananya harus dibina paling dulu sebaik mungkin, yaitu membaca buku dan menulis buku harus dibudayakan, harus dilatih tiap hari selama paling tidak 12 tahun masa sekolah dini. Tanpa sarana budaya membaca buku dan menulis buku, maka muatan ilmu seluruhnya yang diajarkan akan terlupakan setelah lampau, dan kecerdasan (bangsa) tidak terkuasai.
Membaca buku dan menulis buku adalah sarana penyerapan ilmu, karena itu juga menjadi sarana kehidupan modern. Untuk hidup modern harus punya profesi, profesi apa saja yang modern pasti disaranai membaca buku dan menulis buku. Profesi yang pelakunya tidak disaranai membaca buku dan menulis buku tentulah profesi kuna atau tradisional, dan pelaku yang tidak berbudaya membaca buku dan menulis buku akan terpuruk pada profesi kuna yang kian sulit untuk pengembangan hidup modern, sulit mencari penghasilan dengan profesi hidup modern, akhirnya menjadi pengangguran. Tidak mampu mendapat pekerjaan di zaman hidup modern, hidup zaman sekarang.
*
Kalau mau jujur, penghasilan saya mengarang tidak pernah bisa saya handalkan menjadi mata pencarian pokok. Tapi saya terus saja tidak berhenti menulis (buku) cerita. Buku saya tidak pernah dicetak ulang oleh penerbit yang sama. Ketika buku saku bahasa Jawa boom saya tidak ikut-ikutan giat menerbitkan buku saku. Ketika Inpres buku kanak-kanak bisa menjadikan pengarang dan penerbitnya kaya raya, saya tidak berpesta ria ikut serta. Ketika buku dengan judul “Cinta” berkobar, saya tidak menirunya. Dan ketika cerita bahasa Jawa tidak mendapat honor yang besar, saya tetap saja menulis dalam bahasa Jawa. Menilik semua itu, menerima keuntungan finansial bukanlah tujuan utama saya mengarang cerita. Oleh karena itu, menerima penghargaan seperti misalnya Hadiah Sastera Asia Tenggara di Bangkok, hadiah sastra Rancagé, meskipun sebagai simbul keberhasilan saya mengarang cerita, setelah menerima hadiah tersebut, saya tidak berhenti menulis cerita. Menerima hadiah atau penghargaan bukanlah pencapaian terakhir kepengarangan saya. Saya tetap menulis cerita bahasa Jawa, dan bahkan saya pacu untuk menghidangkan buku bahasa Jawa yang (saya usahakan) bisa digemari oleh pembaca sastra Jawa. Meskipun hadiah Rancagé, hadiah tertinggi sastra Jawa saat ini, sudah saya capai tiga kali.
Ketika saya menerima Hadiah Rancagé 2005 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, menyambut kemenangan saya, saya menyitir tulisan Mary Higgins Clark, wanita penulis detektif Amerika yang dijuluki Agatha Christie era 80-an, “Kalau kamu kepingin hidup bahagia setahun menangkanlah kuis, kalau kamu kepingin hidup bahagia selama hidup tekunilah pekerjaanmu selamanya”. Saya ingin bahagia selamanya, jadi ya tidak berhenti mengarang cerita.
Mengarang/menulis cerita bahasa Indonesia sampai kini masih saya kerjakan (antara lain saya menulis di web juga dengan bahasa
Kalau kita ingin agar traddisi membaca buku bahasa daerah tidak terputus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan buku untuk dibaca. Karena pemerintah telah puluhan tahun tidak membuktikan niatnya ke arah penyediaan buku bacaan bahasa daerah, hal itu harus dilakukan oleh pihak swasta. Cara penerbitan yang dilakukan selama ini, yaitu secara con amore dan KKN, tidak dapat diharapkan sehingga jalan yang terbuka adalah menyelenggarakan penerbitan secara profesional. Secara profesional artinya harus dilakukan oleh penerbit yang sadar bahwa usahanya adalah mengejar keuntungan yang akan diraihnya secara halal dari para pembeli bukunya. Artinya bukan dengan cara KKN dengan para pejabat yang berwenang membeli buku secara besar-besaran. Pembelian buku oleh pemerintah secara besar-besaran ternyata tidak menjamin buku itu akan sampai ke tangan konsumennya. (Ayip Rosidi, dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2003 di Balai Bahasa Yogyakarta, 25 Oktober 2003).
Apa yang begitu jauh saya lakukan (perjuangkan) dengan menerbitkan buku bahasa Jawa sampai kini, sebenarnya mengingatkan saya pada nasihat Mochtar Lubis. Tahun 1970-an beberapa ceritapendekku dimuat oleh koran Indonesia Raya, pimpinan Mochtar Lubis. Dia menulis tentang menerbitkan korannya, sebagai suatu perjuangan membangun negara dan mencerdaskan bangsa (Indonesia Raya pernah dibreidel pada zaman Orde Lama, dan Mochtar Lubis dipenjara oleh rezim komunis PKI, sementara Pramudia Ananta Tur berjaya menulis di Bintang Timur dan rubrik Lentera di Harian Rakjat, menghujat musuh kaum komunis/PKI. Maka dari itu Mochtar Lubis yang pernah mendapat hadiah Magsaysay dari Pilipina mengembalikan hadiah itu ketika Pram pada akhirnya juga mendapat hadiah Magsaysay), “Perjuangan menuntut sacrifice, bukan sekedar usaha mengajar laba”. Sama,
Saya juga ingat penamaan Pak Budi Darma terhadap diri saya. Saya ini pengrajin sastra, tidak bedanya dengan pengrajin ukiran kayu Jepara, atau pemahat batu arca Muntilan. Maksudnya pengrajin, mencari nafkah dengan apa yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan hanyalah mengukir kayu, ya pekerjaan itu saja yang dilakukan. Saya masih lebih beruntung, karena selain pengrajin sastra, membuat cerita dan menerbitkannya jadi buku, saya masih bisa menjadi pedagang kapok, wartawan bebas, menjadi pns. Ini berkat keberhasilan saya mengubah takdir atau nasib, yaitu berkat pembudayaan atas diri saya membaca buku dan menulis buku ketika belajar 12 tahun pada usia awal sekolah zaman Belanda dan zaman Jepang. Andaikata saya tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku, pasti nasib saya seperti pengrajin ukiran Jepara atau pembatik Pekalongan. Mereka hidup menerima takdir, takdir sebagai orang yang tidak diubah nasibnya, tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku. Nasib atau takdir saya sebagai pengrajin berubah bisa hidup dengan cara lain atau usaha lain. Namun saya tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan pengrajin, yaitu pengrajin menulis cerita. Menulis cerita jadi bagian dari darah hidupku, menulis cerita jadi bagian sarana kesehatanku. Kalau saya tidak melakukannya, sebagian darah hidupku terhenti, kesehatanku berkurang.
Dan karena mengarang cerita itu suatu usaha yang memberi keuntungan, maka dikenakan pajak. Itulah yang diamanatkan dengan keharusan kepemilikan NPWP. Saya sekarang sudah punya NPWP, tetapi usaha saya mencari keuntungan dengan mengarang masih nihil. Malah kalau tiap bulan sebelum tanggal 20 harus naik angkutan
***