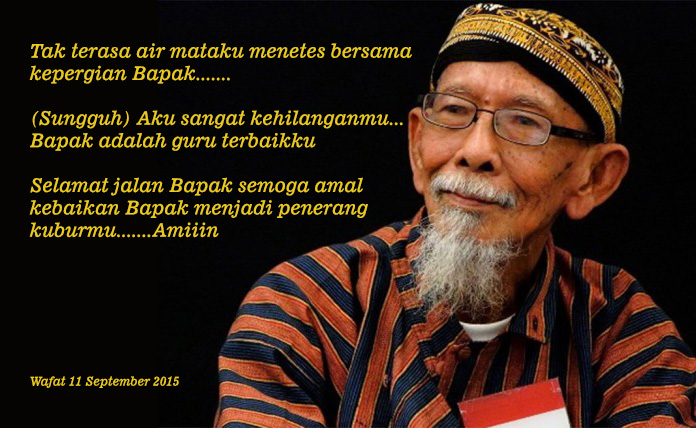Meet Suparto Brata

I met this extraordinary person few weeks ago. Born on the February 27th, 1932, R.M. Suparto Brata is a man of letters. Often, he writes novels and short stories in Javanese. It makes him known as a Javanese literary writer. This is not a popular option in Indonesia, because mostly people don’t buy books written in Javanese. It’s a local language here.
Due to realistic condition of Javanese books selling, Suparto had to face many rejection letters from publishers. “Some of them even made me believe that they would publish my long story, which in fact then, they don’t,” he told me and laughed.
So, occasionally Suparto funded his own book printing. He is just too stubborn to give up. Here are several of his about 140s books:
* Tanpa Tlacak
* Aurora
* Emprit Abuntut Bedhug
* Kadurakan ing Kidul Dringu
* Kerajaan Raminem
* Katresnan kang Angker
* Asmarani
* Pethite Nyai Blorong
* Dom Sumurup ing Banyu
* Nyawa 28
* Tretes Tintrim
* Gadis Tangsi
* Lara Lapane Kaum Republik
* Sanja Sangu Trembela
* Mahligai di Ufuk Timur
* Saputangan Gambar Naga
* Lintang Panjer Sore
* Jaring Kalamangga
* Kamar Sandi
* Garuda Putih
* Nglacak Ilange Sedulur Ipe
* Ngingu Kutuk ing Suwakan
* Donyane Wong Culika
* Saksi Mata
* Lelakone Si lan Man
Suparto Brata had been awarded the Rancagé three times. And in 2007, he earned the South-East Asia Write Award 2007 from SEA Write Award Organizing Committee (Bangkok, Thailand). This man just wants to see that people all over the world read the fine Javanese literary, one day. Suparto lives in such idealism. And I lift my hat for that.
* * *
Lebat sekali hujan malam itu. Padahal malam-malam sebelumnya terasa kering. Kalau saja tak ada janji dengan seorang begawan Sastra Jawa, tentu saya lebih memilih meringkuk di kamar yang hangat. Tapi, untung juga saya memutuskan tetap berangkat ke rumah pemenang Hadiah Rancagé 2000, 2001 dan 2005 yang juga peraih South-East Asia Write Award 2007 ini.
Sebelumnya, kami hanya bertegur sapa lewat email. Itu pun jarang. Bertatap muka? Apalagi! Baru pertama ini. Namun ternyata sambutan seorang Suparto Brata pada saya seperti seorang kawan lama.
Raden Mas Suparto Brata lahir di Rumah Sakit Simpang Surabaya (sekarang Surabaya Plaza), 27 Februari 1932. Senior sekali. Tapi jika Anda perhatikan, ternyata hanya suaranya yang bergetar dimakan usia. Selebihnya, dia terlihat sebagai sang penakluk umur: sehat walafiat, energik, memiliki memori kuat hingga mampu menceritakan detail peristiwa-peristiwa zaman Belanda.
Aktivitas sebagai penulis pun tetap jalan, seperti mengarang di pagi hari, membaca di siang hari, mengedit tulisan, merawat blog dan menjawab email-email. Pak Parto, demikian sapaan akrabnya, bahkan mampu melumat naskah novel saya setebal 142 halaman spasi tunggal, plus menuliskan komentar panjang-lebarnya, cuma dalam tiga hari!
Passion duda beranak empat ini pada dunia tulis memang luar biasa. Saat buta huruf masih mewabah di Indonesia, Suparto kecil sudah menggemari kegiatan baca-tulis. Mulai SMA dia sudah mengirim cerita-cerita untuk media, meski terus ditolak. Waktu itu menjadi penulis benar-benar tidak bisa diandalkan.
Apesnya lagi, dia harus keluar dari SMAK Nonongan Solo, Jawa Tengah, lantaran sang ibu tak sanggup membayar SPP. Suparto remaja pun pergi dari Solo ke Surabaya naik sepeda angin, dengan semangat mencari pekerjaan.
“Aku kerja pertama tahun 1951,” kenangnya. “Di Rumah Sakit Kelamin, Jl. Dr. Sutomo Surabaya. Tapi nggak kerasan, Mas, karena nggak ada mesin tik untuk mengarang, hahaha.”
Maka begitu ada iklan lowongan operator teleprinter di kantor telegraf, Suparto langsung melamar. Dan diterima, meski harus dikursuskan mengetik 10 jari dulu selama setahun. Karena sudah dapat gaji tetap selama kursus, Suparto memutuskan melanjutkan studinya. Dia lulus SMA tahun 1957.
Selama bekerja di kantor telegraf itu, Suparto mulai mengirim karangannya dalam ketikan yang rapi, tidak lagi dalam tulisan tangan. Satu karyanya pun dimuat majalah Aneka. Sebuah titik terang!
Lalu, “Untuk mengikuti perkembangan Sastra Indonesia, aku mulai langganan majalah Siasat dan Mimbar Indonesia. Sekaligus sesekali mengirimkan karangan ke sana,” kisahnya. Prosedurnya sama: karangan tersebut mulanya ditulis tangan pada kertas bekas. Lalu pagi sebelum kursus dimulai, dia mengetiknya di kantor.
Hasilnya menggembirakan. Nama Suparto Brata tercetak di Siasat (pimrednya saat itu Rosihan Anwar), Mimbar Indonesia (pimrednya H.B. Yasin), Garuda, dan lain-lain.
Namun persahabatannya dengan Sastra Jawa baru terjalin saat membaca majalah Panjebar Semangat. Merasa tertantang, Suparto pun memberanikan diri membuat dan mengirimkan cerpen berbahasa Jawa dengan nama pena Parto Printer.
Beruntung, cerpen spekulasi itu langsung dimuat pada April 1958.
Di tahun itu juga, Suparto berhasil menyelesaikan naskah novel pertamanya, Tidak Ada Nasi Lain. Karya setebal 600-an halaman ini belum pernah diterbitkan dalam bentuk buku, tapi kelak pada tahun 1990 dimuat sebagai cerbung di harian Kompas.
Setahun kemudian, Parto Printer juga berhasil menggondol juara I untuk sayembara penulisan cerita bersambung (cerbung) yang diselenggarakan Panjebar Semangat. Artinya, Suparto sukses mengalahkan pengarang favorit di ranah Sastra Jawa saat itu, Any Asmara.
Di tahun 1960, sastrawan Jawa yang menguasai bahasa Belanda dan Inggris ini pindah kerja ke Perusahaan Dagang Negara Djaya Bhakti. Di sana, “Aku jauh lebih makmur daripada saat di kantor telegraf dulu. Jam kerjaku jadi 08.00-16.00.” Catat juga, Suparto menemukan jantung hatinya di perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi itu. Mereka lalu menikah pada tahun 1962.
Tapi tahun 1967, Presdir Djaya Bhakti mewajibkan semua karyawannya masuk Soksi (embrio Partai Golkar). Suparto dan istri menolak. Mereka pun keluar. Suparto sudah berbulat tekat untuk menjadi penulis purnawaktu.
Ironisnya, di periode itulah dia menyadari betapa tulisan berbahasa Jawa sulit diterima masyarakat, bahkan untuk masyarakat Jawa sendiri.
Makanya, “Nulis cerita silat saja,” saran Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo. Kakek dari Desta Club 80’s itu tidak asal bicara. Kala itu cerita silat memang jadi primadona, baik di koran, majalah, komik, maupun buku stensilan.
Suparto manggut-manggut. Dia mulai produktif menulis cerita-cerita silat berbahasa Indonesia untuk disetor pada Kho Ping Hoo. Diterbitkan atau tidak, penulis fiksi bersetting tanah China dan Jawa itu selalu memberi honor pada Suparto.
Namun ketika karya Suparto yang tidak diterbitkan semakin banyak, dia memilih berhenti. Bukan karena kecewa, melainkan lantaran merasa tidak enak memakan gaji buta.
Telepon rumah berdering.
Suparto menghentikan penuturannya untuk menerima telepon itu. Saya tak tahu pasti, sepertinya itu dari wartawan, atau penerbit. Mereka berbincang tentang buku-buku.
Saya menghempaskan diri ke punggung sofa ruang tamu. Lalu menengok ke luar. Hujan yang tadinya deras tampaknya mulai menggerimis. Pamit ah, rencana saya. Tak enak bertamu sampai jam 10 malam begini.
Tapi setelah menerima telepon, Pak Parto malah mengajak saya ke kamar sekaligus ruang kerjanya. Bagaimana saya bisa menolak keramahan itu? Di lain sisi, saya penasaran juga, apakah kamar seorang sastrawan besar sama berantakannya dengan kamar saya.
Ternyata benar. Hahaha.
Kamar berukuran 7×4 meter itu menyimpan 140-an buku Suparto yang telah diterbitkan, juga buku dari penulis lain, biasanya buku-buku langka. Tampak satu lemari dan dua meja yang berisi buku, komputer, printer, dan beberapa naskah kuno yang dia peroleh dari teman-temannya di Eropa atau Amerika. Naskah-naskah itulah yang menjadi bahan riset penulisan buku-bukunya.
Dokumen-dokumen kuno itu plus daya ingat yang kuat sebagai pelaku sejarah menjadikan Suparto Brata salah satu pakar sejarah Surabaya. Meskipun dia lebih berfokus pada fiksi. Saya jadi menyesal, kenapa saat menulis Pemuja Oksigen yang bersetting Surabaya, saya tak sempat mengobrol dulu dengan beliau. Pasti bisa lebih banyak eksplorasi dalam novel thriller itu.
“Sastra tidak dilahirkan untuk majalah atau koran,” ucap Suparto, membuyarkan lamunan saya. Kalau sastra hanya untuk media, lanjutnya, ia akan terbonsai oleh ruang. Sastra yang berserakan semacam itu akan sulit diarsipkan, paling-paling hanya bisa dikliping. Tanpa catatan di perpustakaan nasional maupun internasional (ISBN), susah dirunut riwayatnya.
“Sastra semestinya berbentuk seperti ini,” terang Suparto sambil menunjuk buku-buku di kamarnya.
Namun bagaimana dengan keengganan penerbit, baik swasta maupun pemerintah, terhadap Sastra Jawa yang tidak berbau duit? Cerita Jawa di surat kabar, tabloid atau majalah saja kian langka! Kehadiran Hadiah Rancagé yang diprakarsai Ajip Rosjidi untuk dua kategori, pejuang sastra dan pengarang yang menerbitkan buku sastra daerah, pun belum mampu melumasi seretnya penerbitan Sastra Jawa.
Suparto tidak terhalang oleh itu. Banyak jalan menuju Roma. Tatkala menerbitkan novel Donyane Wong Culika (2005), dia patungan dengan penerbit di Jogjakarta. “Total biaya untuk 1.000 eksemplar adalah 16 juta rupiah. Nah, aku urun 8 juta. Bukunya laris, Mas. Tahun 2008 sudah ludes. Beredar sampai Belanda dan Amerika. Itu membuat namaku semakin dikenal secara internasional sebagai pengarang Sastra Jawa.”
Tapi, banyak juga buku yang belum balik modal sampai sekarang. Bukan masalah. Toh, “Yang penting terus ada buku yang meramaikan khasanah Sastra Jawa. Ini agendaku tiap tahun, Mas. Bahkan di tahun 2010 ini, insya Allah ada lima judul yang diterbitkan dengan cara patungan begitu.”
Suparto Brata hanya ingin kelak Sastra Jawa dipunwaos tiyang sadonya. Barangkali sastrawan daerah memang harus militan seperti ini. Saya geleng-geleng. Beruntungnya Sastra Jawa memiliki seorang Suparto Brata.
Malam pun kian larut.
Hujan sudah reda, meski langit masih merah mendung. Saya akhirnya benar-benar pamit, dan pulang sambil membawa banyak ilmu.
Diambil dari Tulisan Brahmanto Anindito di warung fiksi.