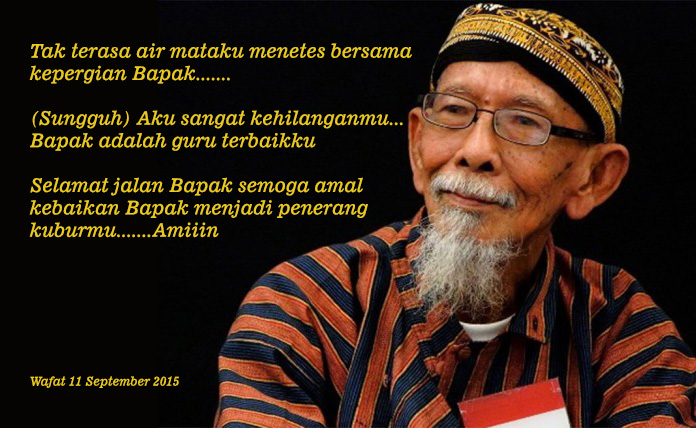SEMANGAT NASIONALISME TOKOH TEYI DALAM NOVEL GADIS TANGSI KARYA SUPARTO BRATA DI ANTARA MASYARAKAT MULTIKULTUR**)
Ade Husnul Mawadah
ABSTRAK
Bangsa Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari sejarahnya sebagai bangsa jajahan Belanda. Pada tahun 1596 dipimpin oleh Houtman dan de Kyzer, Belanda datang dan menjajah Indonesia, kemudian mengakui kedaulatan Republlik Indonesia pada 27 Desember 1949. Selama itulah (±350 tahun) Belanda telah melakukan banyak hal di Indonesia, di antaranya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Hal itu tentu saja sangat mempengaruhi pembentukan mentalitas masyarkat Indonesia sebagai rakyat jajahan Belanda.
Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda menarik sejumlah pihak untuk meneliti dan menuliskannya sebagai sebuah catatan sejarah. Pada zaman itu, Indonesia yang heterogen telah menjadi wilayah yang multikultural. Budaya Barat dan Timur saling bersentuhan selama lebih dari 350 tahun. Selain sejarahwan, sejumlah sastrawan Indonesia pun tertarik untuk menuliskan kondisi masyarakat Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda, salah satu di antaranya adalah Suparto Brata dengan novel Gadis Tangsi.
Novel Gadis Tangsi karya Suparto Brata adalah gambaran kehidupan sebuah tangsi yang multikultur pada zaman kolonialisme Belanda. Barat (Belanda) dan Timur (Jawa Bangsawan dan Jawa Wong Cilik) digambarkan dalam relasi kuasa yang terstuktur dan stereotip yang ditanamkan secara turun-temurun sehingga menjadi mitos dalam masyarakat tersebut. Teyi, tokoh utama Gadis Tangsi, berasal dari golongan masyarakat kelas bawah memandang relasi kuasa dan stereotip tersebut secara positif. Ia berusaha menaikkan kelas sosialnya dengan membangun identitas diri menjadi individu yang nasionalis di antara masyarakat multikultur. Semangat, kemauan, dan peluang yang terbuka lebar telah berhasil meletakkan dirinya pada kelas manapun di lingkungan tangsi tersebut. Teyi berhasil menunjukkan semangat nasionalismenya sebagai perempuan Indonesia, sehingga ia bisa dihargai dan diterima di semua golongan dalam wilayah multikutur tersebut.
Kata Kunci: Kolonialisme, Relasi Kuasa, Konstruksi Mentalitas, Nasionalisme.
1. Pendahuluan
Bangsa Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari sejarahnya sebagai bangsa jajahan Belanda. Pada tahun 1596 dipimpin oleh Houtman dan de Kyzer, Belanda datang dan menjajah Indonesia, kemudian mengakui kedaulatan Republlik Indonesia pada 27 Desember 1949. Selama itulah (±350 tahun) Belanda telah melakukan banyak hal di Indonesia, di antaranya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Hal itu tentu saja sangat mempengaruhi pembentukan mentalitas masyarkat Indonesia sebagai rakyat jajahan Belanda.
Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda menarik sejumlah pihak untuk meneliti dan menuliskannya sebagai sebuah catatan sejarah. Pada zaman itu, Indonesia yang heterogen telah menjadi wilayah yang multikultural. Budaya Barat dan Timur saling bersentuhan selama lebih dari 350 tahun.
Selain sejarahwan, sejumlah sastrawan Indonesia pun tertarik untuk menuliskan kondisi masyarakat Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Beberapa di antaranya telah menuliskannya dalam bentuk fiksi. Sebut saja Pramoedya Ananta Toer dengan novel tetralogi Pulau Buru, Pandir Kelana (R.M. Slamet Danusudirdjo) dengan novel Merah Putih Golek Kencana, dan Suparto Brata dengan Gadis Tangsi.
Pertumbuhan yang sangat pesat dalam dunia sastra di Indonesia dewasa ini telah menarik perhatian sejumlah penerbit untuk menerbitkan karya sastra yang berlatar zaman kolonialisme tersebut. Salah satunya adalah Penerbit Buku Kompas. Dari sejumlah karya sastra yang diterbitkannya, Penerbit Buku Kompas menerbitkan novel Gadis Tangsi karya Suprapto Brata.
Gadis Tangsi adalah novel yang bercerita tentang seorang gadis bernama Teyi yang hidup di lingkungan Tangsi Lorong Belawan pada masa kolonialisme Belanda. Pada masa itu, Belanda memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia. Di lingkungan tangsi tersebut, terdapat orang-orang Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik .
Oleh karena itulah, tangsi menjadi sebuah wilayah yang multikultural. Barat diwakili oleh Belanda, sedangkan Timur diwakili oleh Jawa Bangsawan dan Jawa Wong Cilik. Barat dan Timur memiliki perbedaan dalam hal relasi kuasa. Relasi kuasa di antara ketiga golongan itu sengaja disusun melalui pembagian kekuasaan dan wewenang dalam struktur militer Belanda.
Timur diwakili oleh dua golongan yang sangat bertolak belakang. Jawa Bangsawan digambarkan sebagai orang kaya, berpendidikan formal, terikat oleh nilai-nilai ketat, dan sopan, sedangkan Jawa Wong Cilik digambarkan miskin, tidak berpendidikan formal, hidup dalam norma-norma yang sangat longgar, dan tidak sopan dalam hal berbicara maupun bertingkah laku. Oleh karena itulah, golongan Jawa Bangsawan memiliki kedudukan dan wewenang yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Wong Cilik. Jawa Bangsawan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Belanda. Seperti yang dipaparkan oleh Susetyo (2002) pada zaman kolonialisme Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Golongan pribumi (inlander) diberi status yang paling rendah, kecuali pribumi bangsawan yang diberi status seperti Eropa.
Selain masalah relasi kuasa, novel ini juga menghadirkan stereotip-stereotip orang Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik. Stereotip tersebut diperlihatkan melalui dialog-dialog tokoh, sikap dan perilaku tokoh, pekerjaan tokoh, dan jabatan tokoh dalam masyakat di Tangsi Lorong Belawan dan sekitarnya pada zaman pemerintahan Belanda.
Masing-masing golongan saling mengomentari satu sama lain. Komentar-komentar yang dilontarkan secara eksplisit mengarah pada stereotip golongan-golongan tersebut. Bagaimana Jawa Bangsawan memandang Belanda, Jawa Wong Cilik memandang Belanda, Jawa Bangsawan memandang Jawa Wong Cilik, dan sebaliknya membentuk stereotip tentang masing-masing golongan. Stereotip-stereotip tersebut diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi mitos yang berkembang di masyarakat tangsi. Misalnya, stereotip tentang perempuan Jawa yang lembut dan sopan telah berkembang menjadi mitos bahwa laki-laki akan lebih menyukai perempuan yang lembut dan sopan sehingga anak perempuan tidak boleh berbicara dan bertindak kasar agar disukai laki-laki.
Relasi kuasa dan stereotip yang berkembang di masyarakat Tangsi Lorong Belawan ditanggapi secara positif oleh Teyi, tokoh utama novel tersebut. Ia memelajari budaya Jawa Bangsawan sampai bisa menjadi perempuan tangsi yang bersikap dan berperilaku seperti perempuan bangsawan., berlatih bahasa Belanda hingga mahir berkomunikasi dengan orang-orang Belanda, tetapi tetap hidup dalam budaya asalnya, yaitu budaya Jawa tangsi dengan nilai-nilai yang longgar.
Tulisan ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa dan stereotip Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik di lingkungan Tangsi Lorong Belawan pada masa kolonialisme Belanda dan pengaruhnya terhadap konstruksi mentalitas tokoh Teyi dalam novel Gadis Tangsi karya Suparto Brata.
II. Pembahasan
A. Relasi Kuasa
Pada zaman kolonialisme Belanda di Indonesia, Tangsi Lorong Belawan di Sumatera Utara yang menjadi latar novel Gadis Tangsi telah menjadi lingkungan yang multikultur, yaitu lingkungan yang menjadi wadah interaksi antara Barat dan Timur. Lingkungan multikultur yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, yang hidup bersama dan saling berinteraksi, tanpa meninggalkan ciri khas budayanya masing-masing (Watson, 2006).
Di dalam masyarakat tangsi tersebut terjalin relasi kuasa antara Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik. Relasi kuasa tersebut terjadi karena adanya ketidaksejajaran pangkat, materi, dan pendidikan. Seperti yang dipaparkan Edward Said dalam studinya mengenai Orientalisme (2001) bahwa hubungan antara Barat dan Timur adalah hubungan kekuatan, dominasi, dan hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks. Hubungan tersebut dapat membentuk relasi kuasa antara Barat sebagai penjajah dan Timur sebagai terjajah.
Hubungan relasi kuasa antara Barat dan Timur dalam Gadis Tangsi diperlihatkan melalui struktur kepemimpinan militer Belanda. Belanda menduduki urutan pertama sebagai komandan tertinggi yang dijabat oleh Anthonie van Heffleen. Urutan selanjutnya adalah Kapten Sarjubehi yang berasal dari golongan Jawa Bangsawan, dan urutan terendah adalah orang-orang dari golongan Jawa Wong Cilik yang bekerja sebagai serdadu Belanda dengan pangkat parajurit.
Perbedaan kekuasaan (pangkat) tersebut juga memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Komandan Belanda dan Kapten Jawa Bangsawan tinggal di sekitar tangsi, tetapi berada terpisah dari pemukiman keluarga prajurit. Wilayah pemukiman mereka oleh masyarakat tangsi disebut Kampung Landa. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar dengan perabotan mewah yang tertata rapi, memiliki pembantu, dan memiliki anjing penjaga. Di antara keduanya pun masih terlihat memiliki perbedaan dalam tingkat ekonomi. Komandan Belanda berada pada tingkat lebih tinggi dibandingkan Kapten Jawa Bangsawan. Komandan Belanda memiliki fasilitas mobil pribadi bersama sopir pribadi (hlm.65), sedangkan Kapten Jawa Bangsawan (Kapten Sarjubehi) hanya memiliki sepeda mahal untuk bekerja. Jika Kapten Sarjubehi hendak pergi bersama istrinya, ia akan memesan sado yang paling bagus (hlm. 203).
Tingkat perekonomian paling rendah ada pada prajurit yang dimasukkan dalam golongan Jawa Wong Cilik. Para prajurit dan keluarganya tinggal di pemukiman tangsi. Rumah mereka berdempet-dempet rampat dengan dua kamar saja. Kamar mandi dan dapur berada di ujung rentetan rumah yang digunakan secara umum. Tempat tinggal mereka seperti barak-barak di pengungsian. Setiap tanggal lima, mereka mendapatkan kupon extra voeding, yaitu makanan tambahan dari gudang Belanda. Mereka mendapatkan makanan tambahan itu dengan cara mengantri panjang dan berdesakan.
Para prajurit tersebut adalah orang-orang Indonesia, yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Bagi mereka, Belanda bukan sebagai penjajah bangsanya, melainkan penolong keluarganya. Terjadi simbiosis mutualisme di antara kedua golongan tersebut. Belanda memberikan mereka rumah tinggal, gaji, dan pendidikan kemiliteran, sedangkan mereka memberikan dirinya (jiwa dan raganya) untuk kepentingan Belanda sebagai prajurit militer Belanda. Belanda menjadi penguasa “hidup” mereka. Hal itu menunjukkan bahwa pada masa itu Barat juga menjadi penguasa bagi Timur dalam masalah ekonomi.
Selain pangkat dan materi, relasi kuasa juga terbentuk karena adanya ketidaksejajaran tingkat pendidikan formal. Belanda yang menjadi penguasa pada saat itu, menjadi golongan yang paling terhormat. Orang-orang Belanda adalah orang-orang berpendidikan formal. Golongan bangsawan sebagai golongan masyarakat pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah-sekolah Belanda sebagai bentuk politik Etis bagi kaum elite Indonesia sehingga mereka menjadi orang terpelajar dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Belanda (Ricklefs, 2001: 329). Oleh karena itulah, mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari Belanda.
Perlakuan istimewa Belanda terhadap Jawa Bangsawan, tidak semata-mata karena mereka berbeda dari pribumi golongan Wong Cilik dalam hal pendidikan formal, tetapi juga karena kepentingan politik Belanda di daerah mereka, daerah jajahan Belanda. Secara politik, golongan bangsawan adalah golongan terpelajar yang dapat membantu Belanda dalam memperkuat kuasanya di negara jajahannya. Seperti yang diungkapkan oleh Anderson (2001: 174) bahwa mereka, golongan bangsawan terpelajar tersebut dijadikan pejabat-pejabat kolonial lokal pada masa penjajahan Belanda.
B. Stereotip Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik
Masyarakat Tangsi Lorong Belawan yang multikultur sangat membuka munculnya stereotip, yakni seperangkat penilaian dari kelompok lain dalam hubungannya dengan ingrup dalam situasi terkini (Smith,1999 dalam Pitaloka, 2004). Stereotip tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif.
Stereotip orang Belanda, orang Jawa Bangsawan, dan orang Jawa Wong Cilik pada novel Gadis Tangsi diperlihatkan secara eksplisit, melalui komentar tokoh-tokohnya dan secara implisit melalui sikap dan perilaku tokoh-tokohnya.
Dalam kehidupan masyarakat multikultur di Tangsi Lorong Belawan terjalin interaksi sosial. Proses interaksi sosial tersebut menimbulkan penilaian-penilaian di antara mereka. Belanda memberikan penilaian pada golongan bangsawan, bangsawan menilai wong cilik, wong cilik menilai Belanda, dan sebaliknya. Penilaian tersebut menimbulkan stereotip tentang Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik. Stereotip-stereotip tersebut ditanamkan secara turun-temurun sehingga menjadi mitos yang berkembang di masyarakat tersebut.
1. Stereotip Belanda
Melalui komentar tokoh-tokohnya orang Belanda digambarkan sebagai orang yang tegas dan berwibawa. Orang Belanda juga dianggap paling baik, cakap, dan pandai. Hal itu terlihat pada tentara Belanda peniup terompet. Terompet yang ditiup tentara Belanda sangat merdu dan enak didengar. Berbeda dengan terompet yang ditiup prajurit dari golongan Jawa Wong Cilik, tidak nyaring dan terdengar sumbang. Kutipan berikut ini merupakan bentuk stereotip positif orang Belanda dari sudut pandang Jawa Wong Cilik.
“Nah, terompet pertama sudah berbunyi. Waktu bangun telah tiba. Itu bunyi terompet tiupna Landa Dawa. Begitu nyaring, iramanya teratur, halus, dan panjang. Landa Dawa memang jago meniup terompet. Berbeda dengan tiupan Sudarmin, misalnya, yang bunyinya terasa tersengal-sengal, patah-patah, dan sering kali hilang tiba-tiba” (hlm.1).
Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa yang tinggi derajatnya. Jika berbahasa Belanda, ia akan diterima di kalangan kelas atas. Pedagang-pedagang pun akan menyambut dan melayani hangat ketika pembeli mampu berbahasa Belanda, seperti pada kutipan berikut ini.
“Alangkah hebatnya kalau aku juga bicara bahasa Belanda dengan pemilik tokoyang matanya sipit itu. Mau membeli apa saja bisalangsung bicara dengannya. Aku beli boneka tentu ia akan melayani dengan menghormat santun.”(hlm.208).
Selain itu, bergaul dengan bangsa Belanda memiliki citra yang baik. Ketika Teyi mampu berbahasa Belanda dan berbicara bahasa Belanda dengan lancar, komandan Belanda tertegun dan memandang baik pada Teyi. Begitu juga pandangan dari orang Jawa golongan Wong Cilik. Mereka menganggap Teyi sebagai seseorang yang terhormat karena mampu berbahasa Belanda dan dapat berkomunikasi dengan orang Belanda. Teyi mampu menaikkan derajatnya sebagai golongan bawah setelah ia mampu berbahasa Belanda dan mampu dengan lancar bekomunikasi dengan orang Belanda. Misalnya, ketika Teyi memberitahukan perihal sakitnya Putri Parasi pada keluarga Belanda, mereka langsung mengerti apa yang dikatakan Teyi dan langsung memberikan bantuan.
Mampu berbahasa Belanda juga dianggap sebagai orang pintar. Pandangan tersebut muncul dari golongan Jawa. Misalnya, pada tokoh adik sepupu Putri Parasi yang bersekolah di sekolah Belanda, Raden Mas Kus Bandarkum. Cakrawalanya menjadi semakin luas. Begitu juga halnya dengan Putri Parasi. Ia sebagai perempuan ningrat yang tinggal dan dibesarkan di lingkungan keraton, pola pikirnya menjadi berubah setelah sekolah di sekolahan Belanda. Ia berkeinginan besar untuk keluar dari keraton yang sangat mengikat hidupnya.
Selama perjalanan cerita, stereotip orang Belanda sebagian besar bersifat positif. Stereotip negatif orang Belanda dari sudut pandang Jawa Wong Cilik yang dipaparkan pada cerita awal terhapus dengan peristiwa-peristiwa yang disampaikan pada cerita berikutnya. Ada ambivalensi penilaian Wong Cilik terhadap Belanda yang terlihat pada gambaran sikap dan perilaku Belanda. Misalnya pada kutipan berikut ini.
…. Tetapi anak-anak dan perempuan tangsi umumnya sangat takut dengan Ndara Tuan Belanda, karena kerja orang Belanda hanya mengusut perkara dan memberi hukuman.
Orang Belanda badannya besar, matanya siwer, bahasanya asing, dan sikapnya tak pernah ramah… (hlm.2).
Stereotip negatif tersebut sangat bertentangan dengan gambaran sikap dan perilaku pada cerita selanjutnya. Orang-orang yang berada di sekitar orang Belanda memberikan pujian pada Belanda. Mereka sangat hormat, segan, dan takut pada Belanda. Sebagai penjajah di wilayah itu, Belanda bukanlah sosok yang jahat, tetapi sebaliknya. Mereka mau membantu Putri Parasi saat sakit. Bahkan, saat Teyi diserahkan ke kantor polisi karena dikira hendak mencuri di toko Cina, komandan Belanda tak segan-segan mengantarnya pulang dengan menggunakan mobil pribadinya setelah terbukti bahwa Teyi tidak bersalah. Hal itu jelas bertolak belakang dengan anggapan bahwa orang Belanda tidak ramah dan kerjanya hanya mengusut perkara dan memberi hukuman.
Pandangan anak-anak dan perempuan tangsi tentang Belanda tersebut terjadi karena stereotip tentang Belanda telah ditanamkan secara turun-temurun di masyarakat tangsi sehingga menjadi mitos. Mitos tersebut membentuk prasangka buruk di pikiran mereka tentang Belanda sehingga mereka merasa takut jika berhadapan dengan Belanda.
2. Stereotip Jawa Bangsawan
Golongan pribumi yang berasal dari golongan Jawa Bangsawan diperlihatkan sebagai golongan pribumi yang pandai, sopan, santun, dan sangat menjunjung tata karma dalam menjalani hidup. Perempuan dari golongan ini ditampilkan sebagai perempuan yang sangat patuh pada sosok laki-laki, yaitu ayah dan suami. Dalam pola pikirnya, tampil cantik dan bersikap sopan adalah salah satu cara memunculkan daya tarik untuk menarik kaum laki-laki. Stereotip perempuan Jawa Bangsawan yang diwakili oleh Putri Parasi ini telah menjadi mitos di masyarakat tangsi. Misalnya, Stereotip tentang perempuan Jawa yang lembut dan sopan telah berkembang menjadi mitos bahwa laki-laki akan lebih menyukai perempuan yang lembut dan sopan sehingga anak perempuan tidak boleh berbicara dan bertindak kasar agar disukai laki-laki.
Kapten Sarjubehi yang berasal dari golongan Jawa Bangsawan dianggap sebagai sosok yang gagah, pintar, dan bersifat baik. Ia dipercaya Belanda untuk menggantikan Kapten Depries. Bagi penduduk tangsi, Kapten Sarjubehi dianggap sebagai sosok yang ramah. Setiap kali bertemu dengan bawahannya, ia tak segan menyapa. Begitu juga ketika ia hendak meminta Teyi untuk menemani istrinya, ia tak segan-segan datang langsung ke rumah Teyi dan mengutarakan niatnya baik-baik pada orang tua Teyi. Kapten Sarjubehi juga tergolong laki-laki yang sabar. Ia dengan sabar menghadapi ibu Teyi (Raminem) yang berbicara kasar padanya dan dengan rendah hati ia mau meminta maaf pada keluarga Teyi karena telah lancang meminta Teyi. Peristiwa itu terjadi sampai dua kali, namun Kapten Sarjubehi tidak marah. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai laki-laki yang setia menemani istrinya yang sakit, meskipun pada akhirnya ia segera menikah lagi setelah kematian istrinya. Berikut ini adalah kutipan stereotip petinggi Jawa Bangsawan yang dibandingkan dengan petinggi Belanda dari sudut pandang Raminem (Jawa Wong Cilik).
“Untung yang memergoki komandan Jawa. Masih ada sabarnya. Kalau Ndara Tuan Kapten Depries mungkin kita dilararang berjualan pisang goreng sama sekali.” (hlm.36).
Perbandingan dalam kutipan di atas menggambarkan stereotip yang bertolak belakang antara petinggi Jawa Bangsawan dengan petinggi Belanda. Kehadiran sosok Jawa Bangsawan di tataran petinggi Belanda dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi Wong Cilik karena petinggi Jawa Bangsawan dinilai tidak setegas petinggi Belanda. Anggapan tersebut sesungguhnya dapat bermakna negatif, yaitu petinggi Jawa tidak tegas, sedangkan petinggi Belanda sangat tegas dalam memberlakukan peraturan.
3. Stereotip Jawa Wong Cilik
Orang-orang yang masuk dalam kategori Jawa Wong Cilik adalah orang-orang yang tinggal di tangsi sebagai prajurit Belanda dan keluarganya. Mereka berasal dari Jawa Tengah yang merantau ke Medan, Sumatera Utara, untuk menjadi serdadu Belanda. Salah satu dari mereka adalah Ayah Teyi, Wongsodirjo.
Keluarga para prajurit Belanda itu digambarkan sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan formal dan hidup dalam nilai-nilai yang sangat longgar. Kata-kata kotor sering kali mereka ucapkan, perselingkuhan, seks bebas di kamar mandi umum, persaingan untuk menjadi gundik Kapten Sarjubehi, rumah tangga yang tidak harmonis, malas bekerja, anak-anak yang liar, pembicaraan tentang seks yang fulgar, perjudian, dan mabuk-mabukan menjadi warna-warni kehidupan penduduk tangsi.
Stereotip tentang perempuan tangsi juga cukup menonjol pada novel ini. Keinginan Raminem (Ibu Teyi) untuk mendidik Teyi menjadi perempuan yang berbeda dari anak-anak tangsi lainnya, yang cenderung malas dan lebih suka bermain-main saja, menjadi sarana pemunculan stereotip tentang perempuan tangsi.
“Kalau simboknya mendidik Teyi dengan kekerasan, paksaan, tekanan, ancaman, aku akan memberikan pendidikan dengan kegembiraan, kesukarelaan, sesuka hatinya, semampunya, dan sesempatnya.” (hlm.132).
Pemikiran yang disampaikan Putri Parasi tentang mendidik Teyi tersebut merupakan stereotip perempuan tangsi dalam mendidik anaknya. Kekerasan, paksaan, tekanan, dan ancaman adalah cara dalam mendidik anak bagi seorang ibu dari kalangan bawah. Stereotip lain tentang masyarakat tangsi adalah pada kutipan berikut ini.
“Dasar anak tangsi! Anak kolong! Jangan begitu, Teyi! Orang menjadi cantik, menjadi ayu, bukan hanya karena pakaiannya, terlebih karena sikapnya. Karena tingkah lakunya. Meskipun kamu telah melepaskan baju tangsimu dan mengenakan baju bangsawan, tetap saja kau adalah gadis penjual pisang goreng yang mengitari tangsi!” Nenek Jidan ikut tertawa.” (hlm.167).
…. Ceplik, Jemini, Tukiyem tentu akan membicarakannya sepanjang hari. Kebaya sutera seindah itu tak mungkin dimiliki oleh perempuan tangsi (hlm.167).
Berdasarkan kutipan tersebut, stereotip tentang anak tangsi yang tidak dapat berperilaku layaknya perempuan bangsawan telah menjadi mitos. Anak tangsi adalah anak kolong, sikap dan perilakunya berbeda dengan bangsawan. Perempuan tangsi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kebaya sutera. Stereotip kemiskinan telah menjadi mitos tentang masyarakat tangsi.
C. Konstruksi Mentalitas dan Semangat Nasionalisme Tokoh Teyi
Mentalitas individu menjadi sesuatu yang fundamental dalam setiap interaksi sosial. Pertanyaan tentang diri sendiri, jati diri, dapat menentukan bentuk interaksi sosialnya. Pada dasarnya setiap individu memiliki hasrat yang besar untuk membentuk identitas sosial yang positif terhadap dirinya (Lan, 2000 dalam Susetyo, 2002). Hal tersebut merupakan kerangka untuk mendapatkan pengakuan (recognition) dari pihak lain dan persamaan sosial (social equality).
Bagi setiap individu selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif yang memperbaiki citra jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk, dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial, upaya mencapai identitas sosial yang positif dapat dicapai melalui dua cara, yaitu mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. (Hogg dan Abram,1998; Sarwono,1999 dalam Susetyo,2001)
Konsep di atas dapat diaplikasikan pada tokoh Teyi dalam Gadis Tangsi. Ia berusaha untuk bangkit dari keterpurukan identitas individunya sebagai perempuan Jawa dari kalangan menengah ke bawah. Ia merasa sangat terpuruk ketika dicurigai hendak mencuri miniatur boneka mirip noni Belanda di sebuah toko milik orang Jepun, kemudian diserahkan kepada polisi. Sejak peristiwa itu, terbentuk keinginan di hatinya untuk membuktikan pada pemilik toko itu bahwa dia juga layak mereka layani dengan baik dan mampu membeli boneka miniatur itu. Teyi mengetahui dari keterangan Putri Parasi bahwa pedagang di toko itu hanya melayani dengan baik calon pembeli dari kalangan Belanda atau pribumi bangsawan yang bisa berbahasa Belanda. Kondisi tersebut telah membangkitkan semangat nasionalismenya sebagai orang Timur untuk menunjukkan pada mereka (orang Barat—Belanda) bahwa sebagai orang Timur—yang dianggap Belanda sebagai golongan kelas bawah—ia pun bisa sejajar dengan mereka. Diskriminasi yang ditunjukkan oleh pemilik toko tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu semangat Teyi untuk berusaha lebih keras, berlatih bertata krama seperi kelompok bangsawan dan belajar bahasa Belanda sampai mahir.
Teyi berhasil melakukan mobilitas sosial terhadap dirinya sendiri. Setelah ia bisa merubah image tentang dirinya, bersama Putri Parasi, ia dilayani dengan baik oleh pemilik toko tersebut. Dengan kebaya, kain, dan sanggul yang menunjukkan citra perempuan kelas menengah ke atas, ditambah lagi degan bahasa pengantar bahasa Belanda, Teyi diperlakukan dengan baik, berbeda ketika dia datang ke toko itu beberapa tahun lalu. Semangat nasionalismenya telah membuahkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam studi sosiologi, Teyi dapat dikatakan sebagai individu yang telah melakukan mobilitas sosial secara vertikal ke atas, yaitu mengangkat derajat sosialnya pada kelas sosial yang lebih tinggi (Soekanto, 2001).
Woodward (2002) mengatakan bahwa perubahan identitas tidak hanya terjadi pada sebuah negara dalam wilayah politik yang luas, tetapi juga dapat terjadi pada wilayah lokal, yaitu individu. Penyataan Woodward tersebut telah terbukti pada tokoh Teyi. Teyi telah berhasil melakukan perubahan identitas atas dirinya dengan usaha keras, belajar dan berlatih menjadi seperti perempuan bangsawan dengan bimbingan Putri Parasi. Oleh karena itu, Putri Parasi dapat dikatakan sebagai agent of change bagi Teyi. Ia membuka cakrawala Teyi tentang kehidupan kelas atas,yaitu kehidupan bangsawan yang pada masa kolonialsme Belanda mendapat perlakuan yang baik dari orang-orang Belanda. Pada masa itu, kelompok bangsawan disejajarkan dengan orang-orang Eropa (Susetyo, 2002).
Teyi sebagai orang Timur memiliki salah satu ciri orang Timur yang diutarakan Poespowardojo (1989: 108), yaitu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dengan keterbukaan menerima budaya lain. Dalam Gadis Tangsi, Teyi dapat dikatakan sebagai individu yang supel dan multikultur. Teyi sebagai ikon dari masyarakat tangsi menengah ke bawah mampu menjadi penghubung orang-orang di kelas sosialnya pada orang-orang di kelas sosial yang lebih tinggi. Bahkan Teyi dapat menghapus stereotip orang Belanda yang disegani dan ditakuti. Ia berani dan tak segan-segan mau diantarkan oleh Komandan Belanda dengan menaiki mobilnya. Ia juga berani berkomunikasi dengan orang Belanda. Ia seakan-akan berdiri sama tinggi dengan golongan bangsawan yang pada masa itu mendapatkan perlakuan istimewa dari Belanda.
Relasi kuasa yang dilihatnya sejak kecil telah membangun sebuah stereotip yang positif tentang Belanda dan bangsawan. Dalam pandangan Teyi, Belanda memiliki kedudukan yang terhormat di antara masyarakat lingkungannya dan golongan bangsawan mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang baik di kalangan Belanda. Stereotip Belanda dan bangsawan tersebut sangat bertentangan dengan stereotip kelas sosialnya. Oleh karena itulah, Teyi ingin memproyeksikan dirinya seperti bangsawan yang dapat diterima oleh Belanda.
Teyi dapat diilustrasikan seperti seorang gadis desa yang bermimpi menjadi putri dan mimpinya tersebut terwujud dengan usaha dan kerja kerasnya serta adanya peluang yang terbuka lebar. Obsesinya untuk menjadi putri bangsawan terbentuk dengan pola yang dibuat Putri Parasi. Stereotip positif tentang Keraton Jawa yang adiluhung dan perempuan bangsawan yang berkelas lebih tinggi sehingga mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Belanda serta stereotip negatif tentang perempuan tangsi membentuk keinginan Teyi untuk masuk dalam kelompok bangsawan. Ia giat belajar tentang kehidupan bangsawan Jawa dan terobsesi untuk menikah dengan laki-laki bangsawan agar derajatnya sebagai perempuan meningkat.
Untuk mencapai obsesi hidupnya, seseorang harus memiliki sejumlah strategi jitu (Antari, 2006). Strategi juga digunakan Teyi untuk mencapai obsesinya. Teyi menggunakan tiga strategi, yaitu belajar bersama Putri Parasi yang dilakukan secara tertutup setelah selesai berjualan pisang goreng agar tidak diketahui ibunya, selalu menuruti perintah ibunya agar ibunya tidak mencurigai hubungannya dengan Putri Parasi, dan menuntut cerai pada Sapardal agar dapat menjalin hubungan cinta dengan Raden Mas Kus Bandarkum, seorang laki-laki bangsawan yang diimpikannya. Berikut ini adalah kutipan yang menggambarkan strategi Teyi untuk mencapai obsesinya mendapatkan cinta laki-laki bangsawan.
“Kamu, Kang! Kumpul satu bilik begini tidak berbuat apa-apa! Mana ayam jantanmu? Aku kecewa sekali, Kang! Kecewaaaa sekali!” Teyi mengucapkan kata-kata ini dengan wajah seolah-olah sangat kecewa dengan malam pertamanya.
“Aku belum tahu perangaimu, Dik. Bagaimana kalau kita coba lagi nanti?”
“Tidak! Tidak! Semalam sudah cukup! Semalam kamu biarkan aku tidur seperti kedebok bosok, ya selamanya aku akan kamu biarkan seperti batang pisang terbujur anyep, dingin! Tidak. Batas waktu sudah habis! Cerai!” (hlm.363)
Tuntutan cerai Teyi pada Sapardal, suami semalam, dilakukannya dengan alasan Sapardal tidak memberinya keindahan cinta malam pengantin. Alasan tersebut sesungguhnya adalah sebuah strategi yang dilakukan Teyi untuk mencapai cita-citanya, meningkatkan status sosialnya dengan cara menikah dengan laki-laki bangsawan, yang sempat terhapus setelah kematian Putri Parasi dan pernikahan Kapten Sarjubehi dengan Dumilah. Kehadiran Raden Mas Kus Bandarkum dalam kehidupan Teyi telah membangkitkan semangatnya untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itulah, Teyi mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang hanya berumur sehari itu dan memilih menjalin hubungan cinta dengan Raden Mas Kus Bandarkum.
Proses pencapaian obsesi dalam kehidupan Teyi telah membentuk identitas dirinya menjadi individu yang multikultural. Teyi berusaha memahami perbedaan budaya di sekitarnya, kemudian menentukkan pilihannya dengan memposisikan diri sebagai individu yang dapat diterima di kelompok sosial manapun di tangsi tersebut. Bagi Teyi, strategi yang paling tepat untuk dapat diterima di kelompok sosial manapun pada masa itu adalah dengan memasuki golongan bangsawan, menjadi perempuan seperti perempuan bangsawan. Keputusan Teyi meninggalkan laki-laki Jawa berkedudukan sebagai prajurit dari relasi kuasa paling rendah (Sapardal) dan memilih laki-laki bangsawan yang biasa bergaul dengan orang-orang Belanda (Raden Mas Kus Bandarkum) menjadi pilihan hidupnya.
Tangsi sebagai wilayah multikultur telah membentuk Teyi menjadi sosok yang multikultural. Ia dapat meletakkan dirinya di kalangan manapun di lingkungan tangsi tersebut. Ia dapat diterima di kelompok sosialnya sendiri, yaitu kelompok masyarakat Jawa Wong Cilik, ia dapat diterima di kalangan Jawa Bangsawan karena memiliki kecerdasan dan mampu berperilaku layaknya perempuan bangsawan, dan dia juga dapat diterima di kalangan bangsa Belanda karena ia mampu berbahasa Belanda dengan baik. Teyi mampu bersikap seperti perempuan bangsawan dan bergaul dengan orang-orang Belanda tanpa meninggalkan budaya asalnya sebagai masyarakat tangsi golongan Jawa Wong Cilik. Hal itu merupakan gambaran semangat nasionalisme tokoh Teyi yang begitu besar. Ia berusaha meningkatkan derajatnya agar dapat sejajar dengan kalangan Belanda dengan tetap menjunjung tinggi budaya ketimurannya.
III. Kesimpulan
Relasi kuasa yang terkonsep dalam masyarakat dan stereotip yang hidup dan berkembang dari generasi ke generasi dapat membentuk identitas individu dalam masyarakat tersebut. Relasi kuasa dan stereotip tersebut menjadi hal yang fundamental dalam konstruksi identitas individu, seperti yang terjadi pada Teyi, tokoh utama novel Gadis Tangsi karya Suparto Brata.
Identitas Teyi terkonstruksi dari relasi kuasa yang meletakkan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat secara hierarkis, dengan urutan Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik. Selain itu, relasi kuasa yang dirasakan Teyi dalam keluarganya, terutama relasi kuasa antara ibunya (Raminem) dan Teyi serta stereotip tentang perempuan yang ditanamkan Raminem dan Putri Parasi (guru sekaligus panutannya) juga menjadi faktor pendukung pembentukan identitas Teyi.
Cita-cita dan keinginan Teyi untuk meningkatkan derajatnya dapat dicapai dengan usaha, kerja keras, strategi, serta peluang yang terbuka sangat lebar. Peluang tersebut dibentangkan oleh Putri Parasi dengan memberikan pendidikan informal kepada Teyi sehingga Teyi mampu memandang relasi kuasa dan stereotip tersebut secara positif. Teyi telah berhasil membentuk identitas dirinya menjadi gadis tangsi yang multikultural. Ia bersikap dan berperilaku seperti perempuan bangsawan dan mampu berkomunikasi langsung dengan orang-orang Belanda karena ia mahir berbahasa Belanda. Bahkan, ia juga dapat dikatakan sebagai penghubung bagi masyarakat di lingkungan tangsi. Ia berhasil menghubungkan Belanda, Jawa Bangsawan, dan Jawa Wong Cilik dalam beberapa peristiwa di tangsi tersebut.
Bagi Teyi, strategi yang paling tepat bagi dirinya untuk dapat diterima di kelompok sosial manapun pada masa itu adalah dengan belajar menjadi perempuan seperti perempuan bangsawan dan berlatih bahasa Belanda secara serius dengan bimbingan Putri Parasi. Strategi tersebut telah berhasil menempatkan Teyi pada kelompok manapun di Tangsi Lorong Belawan. Ia dapat diterima kelompok masyarakat Jawa Wong Cilik, ia dapat diterima di kalangan Jawa Bangsawan karena mampu berperilaku layaknya perempuan bangsawan, dan dia juga dapat diterima di kalangan Belanda karena mampu berbahasa Belanda dengan baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa Teyi telah berhasil menunjukkan semangat nasionalismenya sebagai perempuan Indonesia, sehingga ia bisa dihargai dan diterima di semua golongan dalam wilayah multikutur tersebut.
Daftar Acuan
Anderson, Benedict. 2001. Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang). Terjemahan Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Penerbit Insist.
Antari, Nis.2006. “Menggali Potensi Diri”. Intisari, Edisi Maret 2006.
Keesing, Elisabeth. 1999. Betapa Besar pun Sebuah Sangkar (Hidup, Suratan, dan Karya Kartini). Jakarta: Djambatan.
Pitaloka, 2004. “Kontak dalam Masyarakat Multikultur”. e.psikologi.com.
Poespowardojo, Soerjanto. 1989. Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis. Jakarta: PT Gramedia.
Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M.C. 2001. Zaman Penjajahan Baru. Yogyakarta: Insist
Said, Edward W. 2001. Orientalisme. Bandung: Penerbit Pustaka.
Soekanto, Soejono.2001. Sosiologi (Suatu Pengantar). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Susetyo, DP.Budi. 2002. “Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia”. www.unika.ac.id.
Watson, C.W. 2006. “Multiculturalism: It’s Strengths and Weaknessess”. pps.upiedu/org/sqwatson.html.
**)Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional HISKI (Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia) di Gedung Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tanggal 5-7 Agustus 2009, dengan tema: MEMBACA KEMBALI FUNGSI SOSIAL SASTRA.