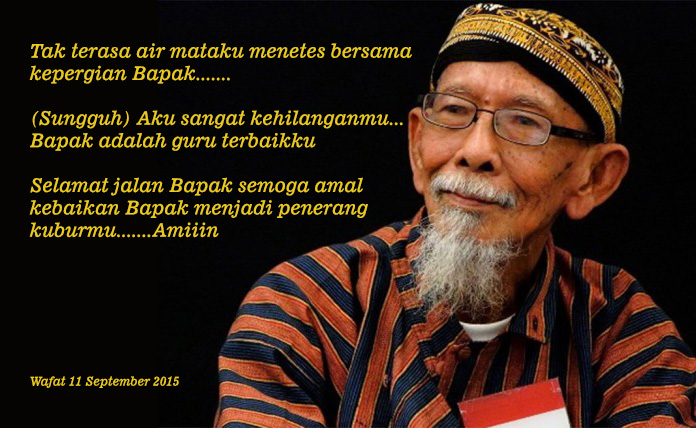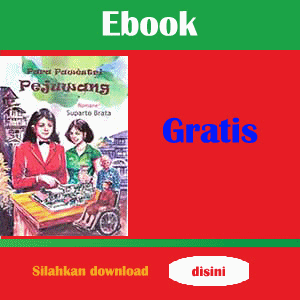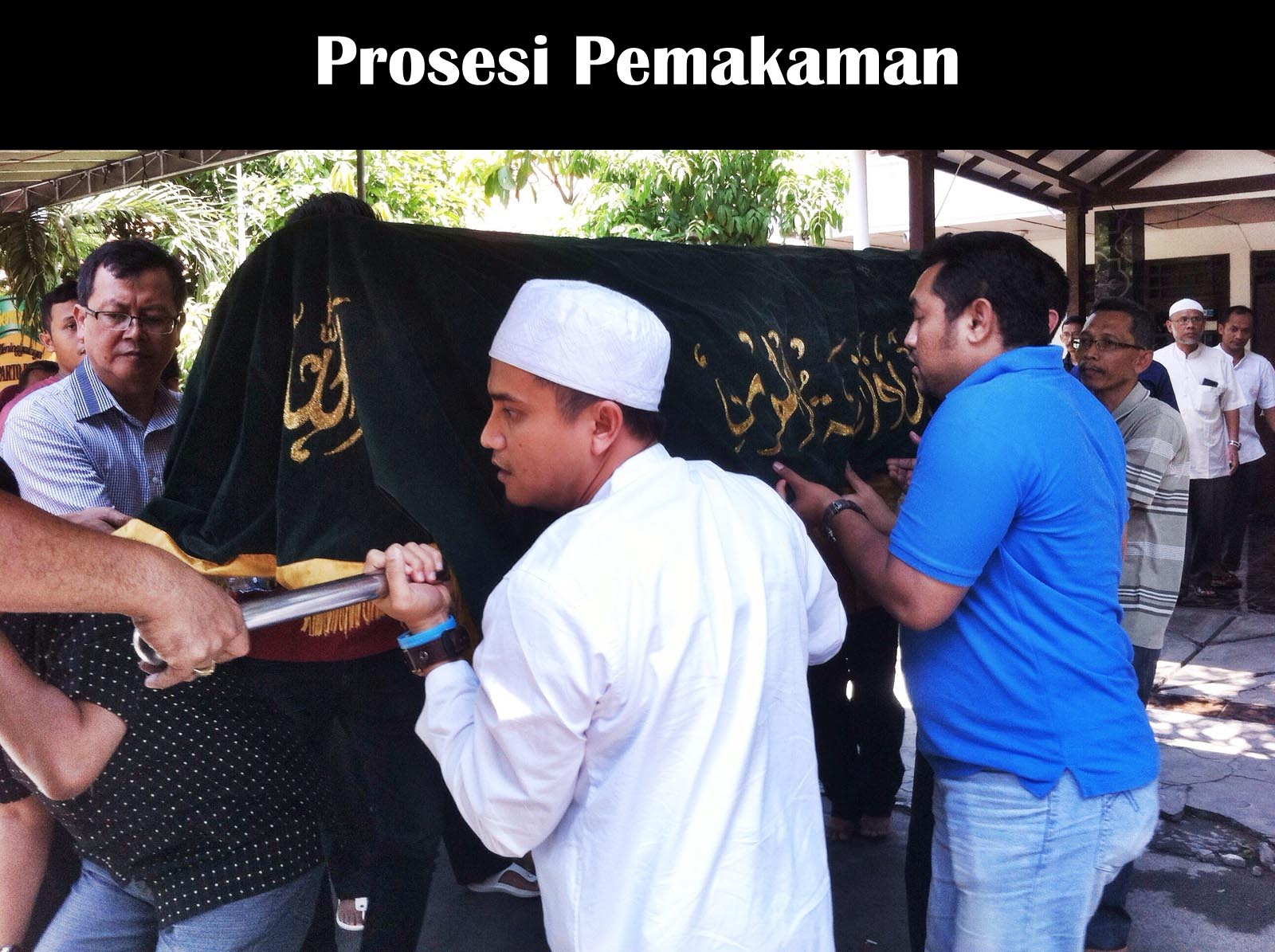JEJAK KISAH PERJALANAN MODEL JAWA
Oleh: Yulitin Sungkowati
Abstract:
The writing discusses about the trail of Jawa style traveling story in Indonesian literature, especially in novel Mencari Sarang Angin that created by Suparto Brata. The trail of Java style traveling story is seen in the identification of puppet’s character Raden Janaka, imitation theme to enrich internal experience, the background of big city such as Surabaya, Surakarta, and Yogyakarta, a symbolic tittle.
Keywords: Java style traveling story, Indonesian literature.
Identifikasi pada Tokoh Wayang Raden Janaka
Menurut Widati (1991;14), tokoh utama dalam kisah perjalanan model Jawa telah terpakem, yaitu sang tokoh adalah seorang pangeran yang menyamar menjadi orang biasa dengan semua ciri orang kecil. Penokohan seperti itu merupakan pengaruh model penceritaan wayang atau transformasi dari cerita pewayangan. Dalam Ngulandara dan Serat Riyanta ditemukan indeks konsep ksatria Raden Janaka. Konsep pahlawan seperti itu tidak ditemukan dalam kisah perjalanan model Barat karena unsur realisme dalam sastra Barat lebih menonjol. Tokoh pelaku perjalanan adalah manusia biasa. Pengembaraan tokoh dalam kisah perjalanan model Jawa biasanya didahului oleh adanya konflik. Hal itu terkait dengan falsafah Jawa, khususnya yang dianut oleh kaum priyayi yang mementingkan rasa sehingga selalu berusaha menghindari konflik terbuka. Sang tokoh mengembara atau melakukan perjalanan untuk meredakan ketegangan dalam jiwanya sebagai suatu inisiasi (Prabowo, 1995;184).
Latar belakang perjalanan tokoh seperti itu terlihat dalam novel MENCARI SARANG ANGIN. Pengembaraan Darwan ke daerah gopermen Belanda di Surabaya juga dimulai dari adanya konflik dengan Kanjeng Rama. Konflik itu dipicu oleh tulisan Darwan di koran Dagblad Ekspres berjudul “Prahara ing Surakarta” yang menempatkan R.A.Kundarti sebagai tokoh utamanya. Kerbetulan nama itu sama dengan nama salah seorang selir ayahnya, R.A.Kundarti sehingga menjadi gosip di kalangan bangsawan di Istana Prawirakusuman. Kanjeng Rama pun marah karena mengira Darwan berselingkuh dengan R.A. Kundarti. Untuk menghindari konflik tersebut, Darwan memilih pergi meninggalkan Istana Prawirakusuman. Jika tetap tinggal di Istana, ia akan terus menjadi bahan pembicaraan dan akan membuat hubungannya dengan Kanjeng Rama menjadi renggang. Oleh karena itu, Darwan memutuskan untuk mencari waktu hidup dengan jalan keluar dari tembok istana. Darwan menolak kepergiannya ke Surabaya dianggap sebagai pengaruh pendidikan Eropa. Menurut Kanjeng Rama, di Eropa, seorang anak yang telah berusia 21 tahun harus keluar dari rumah orangtuanya untuk mencari kehidupan sendiri (Brata, 2005;173). Darwan justru mengindentifikasikan kepergiannya itu dengan tokoh wayang Raden Janaka.
Mampu saja! Harus mampu! Betapapun kecilnya. Darwan kan harus prihatin. Seorang ksatria seperti Janaka, juga prihatin ketika mengembara di hutan belantara. Darwan juga seorang ksatria yang mengembara di hutan Surabaya (Brata, 2005;46).
Surabaya sebagai kota “modern” diibaratkan seperti hutan belantara untuk menunjukkan bahwa pengembaraan yang dilakukan oleh Darwan sama dengan pengembaraan Raden Janaka di hutan belantara dalam cerita pewayangan pada masa lampau. Penegasan Surabaya sebagai hutan belantara atau hutan lebat bagi Darwan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali seperti tampak pada hlm. 1, 36, 39 dan 40 untuk menunjukkan persamaannya dengan tokoh panutannya di masa lalu. Pencitraan Surabaya sebagai hutan belantara yang asing dan menakutkan dibuat sebagai upaya mendekatkan kisah perjalanan Darwan dengan pengembaraan Raden Janaka pada masa lampau ketika tanah Jawa masih berupa hutan belantara. Dengan demikian, esensi pengembaraan dengan tantangan medan yang berat dan sulit yang dialami Raden Janaka digambarkan juga harus dihadapi oleh Darwan. Dalam sebuah pengembaraan sebagai upaya penempaan jiwa agar lebih kuat dan berani, semakin tinggi tingkat kesulitan daerah pengembaraannya, semakin bernilai perjuangan sang tokoh dalam menundukan daerah tersebut dan semakin bernilai juga pengalaman batin yang didapatnya. Olerh karena itu, narator perlu memberikan penekanan pada persamaan rasa keterasingan Darwan di Kota Surabaya yang baru diinjaknya dengan rimba belantara yang menjadi medan pengembaraan Raden Janaka.
Tema Inisiasi
Gagasan pokok kisah perjalanan model Jawa adalah untuk tujuan inisiasi, tidak semata-mata melaporkan sesuatu, tetapi memberikan pendidikan pada rakyat atau pembaca (Prabowo, 1995;163). Inisiasi adalah upacara tertentu yang harus dilalui manusia dalam peralihan dari tahap kehidupan yang satu menuju tahap kehidupan berikutnya (Koentjaraningrat et al, 1982;190). Menurut Subagyo (Prabowo, 1995;163), pribadi seperti itu merupakan cita-cita seorang priyayi, yaitu menjadi seorang satria sebagaimana layaknya Raden Janaka.
Tema inisiasi juga tampak menonjol dalam MENCARI SARANG ANGIN. Darwan bukanlah orang biasa, bukan nothing. Ayahnya adalah seorang bangsawan yang mampu memberinya kemewahan. Akan tetapi, ia menolak kemewahan dan kemudahan itu, ia memilih menjadi orang biasa dengan keinginan memperoleh pengalaman yang luar biasa. Tantangan pertama yang dihadapi Darwan adalah ikatan kekerabatan dengan keluarganya, godaan kenikmatan dan kemudahan yang dijanjikan Kanjeng Rama, serta tantangan kebiasaan sebagai bangsawan yang tidak terbiasa dengan kehidupan wong cilik atau rakyat biasa. Oleh karena itu, perjalanan untuk mencapai pengalaman batin itu tidak mudah dijalani. Ia harus dapat menundukkan berbagai macam rintangan tersebut dengan kekuatan yang dimilikinya karena ia sudah bertekad hendak melepaskan kebangsawanannya dan menolak bantuan Kanjeng Rama.
Meskipun masih berada dalam satu kota, pengembaraan Darwan juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain: dari daerah Jedong yang kumuh di pinggiran Surabaya pindah ke Plemahan yang merupakan perkampungn rakyat biasa tapi terletak di dalam kota selanjutnya bergerak lagi ke Ketandan yang berada di pusat kota, sebuah wilayah hunian para priyayi dn letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Surabaya. Tempat-tempat yang disinggahi oleh Darwan dideskripsikan secara mendetail. Pengembaraan Darwan dimulai dari tempat yang paling sulit, ketika sebagai seorang bangsawan ia harus “menyamar” dan menjalani hidup sebagai rakyat jelata serta tinggal di perkampungan kumuh. Dengan tinggal di rumah Wage, yang merupakan anak Suro Kewek abdi dalemnya di Istana Prawirakusuman, Darwan dapat merasakan dan menghayati kehidupan wong cilik yang serba kekurangan dan tinggal di tempat yang tidak layak sehingga timbul empati dan rasa kasihnya pada wong cilik. Di kantor Dagblad Ekspres tempatnya bekerja, ia juga harus belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti membongkar dan mengeset huruf. Ia juga harus siap menerima perlakuan kasar sebagai layaknya rakyat jelata. Di berbagai tempat yang disinggahi dan ditinggali, Darwan harus belajar menghayati dan menjalani hidup dalam berbagai tingkatan kelas sosial itu sehingga pengalaman hidupnya semakin kaya dan jiwanya semakin matang dalam melihat kehidupan. Jiwanya tidak terkurung dalam kemegahan dan kemewahan kehidupan istana.
Pengembaraan Darwan tidak jauh berbeda dengan pengembaraan Raden Janaka, yaitu sebagai inisiasi untuk mempersiapkan diri menjadi raja. Dalam tradisi Jawa, seorang calon raja harus menjalani inisiasi untuk memperkaya pengalaman hidupnya agar jika menjadi raja, ia akan menjadi raja yang bijaksana. Artinya, pengembaraannya bukan untuk menemukan hidup yang benar-benar baru, mandiri, dan bebas dari tradisi, tetapi hanya untuk memperkaya pengalaman jiwa. Hal itu terungkap dalam narasi yang menggambarkan kepergian Darwan yang ternyata bukan tidak membawa apa-apa sebagaimana pengembaraan Robinson Crusoe. Dalam pengembaraannya, Darwan membawa bekal sekoper baju dan beberapa uang gulden. Selama berada di Surabaya, ia juga tidak pernah lepas dari pertolongan orang-orang yang masih ada kaitannya dengan istana Prawirakusuman dan Kanjeng Rama. Ketika sampai di Surabaya, ia tidak mau tinggal di hotel seperti saran ayahnya, tetapi tinggal di rumah Wage yang merupakan anak abdi dalem ayahnya.
Oleh karena itu, Darwan sesungguhnya tidak benar-benar meninggalkan Surakarta meskipun ia mengatakan tidak mau berhubungan dengan Kanjeng Rama. Hal itu berbeda dengan model pengembaraan orang-orang Barat sebagaimana tercermin dalam kisah-kisah perjalannya, seperti Robinson Crusoe. Robinson Crusoe mampu menjadi subjek bagi dirinya, tidak mengandalkan bantuan siapa pun, bahkan Tuhan, ketika ia mengembara mencari hidupnya. Robinson Crusoe menjelajahi wilayah yang benar-benar asing dan tak bernama. Ia menjadi subjek yang pertama kali “menemukan” wilayah “baru” dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, pengembaraan Darwan ke wilayah Surabaya adalah perjalanan menampaki peta yang sudah dibuat oleh Belanda atau orang-orang Barat dan dengan bekal pengetahuan serta pendidikan Belanda pula. Pengembaraan Darwan tidak jauh berbeda dengan pengembaraan dalam kisah-kisah perjalanan Jawa, seperti Ngulandara, yang hanya dimaksudkan sebagai sarana inisiasi untuk memperkaya pengalaman batin guna menyempurnakan kebangsawanannya.
Sudut Pandang Orang Ketiga
Kisah perjalanan model Jawa menggunakan sudut pandang orang ketiga sehingga lebih tampak sebagai karya fiksi daripada reportase hasil pengalaman perjalanan seorang manusia sebagaimana dalam kisah perjalanan model Barat yang menggunakan sudut pandang orang pertama “aku”. Sudut pandang orang pertama dalam kisah perjalanan Barat menunjukkan pengarang sebagai subjek yang melakukan perjalanan dan melaporkan hasilnya kepada pembaca sehingga ketepatan (bukan imajinasi) dalam menggambarkan objek-objek atau realitas yang dilihat menjadi ukuran dalam reportasenya.
Pemakian sudut pandang orang ketiga dalam kisah-kisah perjalanan Jawa terkait dengan sifat imajinatif yang menonjol dan adanya pengaruh budaya wayang yang menempatkan dalang sebagai penceritanya. Sudut pandang orang ketiga memungkinkan pengarang dapat dengan bebas menuangkan pikiran-pikiran dan obsesinya terutama yang berkaitan dengan masalah religius. Penggunaan sudut pandang orang ketiga ini menunjukkan sifat sastra Jawa modern tahun 1900-1945, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran kepada pembacanya dengan menyampaikan kisah perjalanan bagaikan pagelaran wayang yang menempatkan dalang sebagai “Tuhan” (Prabowo, 1995;178).
Pengarang berlaku sebagaimana dalang dalam pentas wayang, menguasai tokoh-tokohnya secara penuh, bahkan lebih tahu segala hal berkaitan dengan tokoh lebih dari yang diketahui oleh tokoh tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, pengarang dapat dengan leluasa berpindah dari satu tokoh ke tokoh lainnya dan dapat dengan leluasa memberikan pesan moral kepada pembacanya. Dalam novel ini, ajaran moral yang dikemukakan pun bersumber pada cerita wayang yang sudah menjadi mitologi dan filosofi bagi orang Jawa.
Buah pikiran Kanjeng Rama tentang kisah klasik perang saudara berkecamuk ketika Darwan sedang menuju ke tempat Rokhim. Rokhim dan Maladi Yusuf adalah orang-orang yang terhasut oleh pendidikan PKI, hasil pendidikan cara Ngastina. Perbedaan paham dijadikan jurang dendam kesumat, yang cara menutupnya hanya merebut kekuasaan dengan kekerasan. Mereka menyelesaikan konflik tidak dengan pendidikan mencerdaskan bangsa. Rakyat tetap bodoh dan hatinya panas dihasut oleh dendam kesumat.
Mbak Yayi bunga bangsa, juga gugur karena tindakan dungu kebodohan bangsa dewek! Kebodohan Turnadi dan Rokhim! Dan, sekarang berulang Rokhim dan Osup melakukan kebodohan. Yang ini korbannya lebih besar, tidak hanya seorang Yayi. (Brata, 2005;698-699).
Narator Kanjeng Rama menyampaikan ajaran budi pekertinya dengan mengambil contoh perebutan kekuasaan yang terjadi antara dua keluarga bersaudara. Untuk menggambarkan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok komunis, pengarang menggunakan perumpamaan perang saudara Bratayudha antara Pendawa dan Ngastina. Penyebab perang itu adalah adanya perbedaan yang dibesar-besarkan oleh orang-orang pintar, seperti Sengkuni, Durna, dan Adipati Karna sehingga menimbulkan dendam. Perilaku kaum komunis yang memandang orang-orang kaya sebagai musuh tidak jauh berbeda dengan perilaku orang-orang Ngastina yang memerangi Pendawa karena Pendawa kaya, sedangkan mereka miskin. Rakyat seharusnya dididik untuk menghargai perbedaan, bukan justru memperuncingnya hingga menimbulkan kebencian. Perbedaan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Agar tidak mudah dihasut, rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin harus dididik supaya cerdas sehingga dapat membedakan perbuatan baik dan tidak, serta menghormati perbedaan paham (Brata, 2005;694-696).
Dikutip dari: Majalah Ilmiah HALUAN SASTRA BUDAYA No.55 th. XXVII Nopember 2009; diterbitkan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.