INDONESIA REPUBLIK TANPA SASTRA
BAHAN pokoknya sama: pengajaran sastera Indonesia di sekolah lanjutan.
Budi Darma dalam kertas kerjanya mengutip ejekan Paul Theroux: Indonesia, Republik Tanpa Sastra. Sastera terpencil dari sebagian besar manusia Indonesia. Dan peserta seminar agaknya setuju dengan ini. Rasa was-was menghinggapi para pembicara dalam Seminar Pengajaran Sastera Indonesia di Sekolah Lanjutan yang berlangsung tanggal 11 � 12 September 1973 di Surabaya. Betapa celakanya nanti bangsa ini apabila keasingan akan sastera berlarut-larut.
Kebanyakan pemrasaran utama serta pembanding yang tidak kurang dari 9 orang berasal dari kaum pendidik, merasa gelisah karena terlibat, bahwa dunia tempatnya berbakti ternyata menelorkan suasana kering sastera. Mereka mengorek-orek dunia pangajaran sastera Indonesia. Apa gerangan penyebab bangsa Indonesia kalis sastera.
Rupanya kebanyakan pada sefaham, bahwa bahan sastra yang diajarkan di sekolah-sekolah terlalu kecil bila dibandingkan dengan topan kemajuan tehnik dan pembangunan dewasa ini. Buku-buku sastera tidak ada, tidak langsung dinikmati, terlalu kuno. Kebijaksanaan guru dengan membikin ikhtisar-ikhtisar ternyata menyimpangkan tujuan pengalaman sastera dari rel yang benar, mencetak murid mengerti tentang sastera tetapi tidak hidup bersama sastera. Cara mengajar memang sudah terkilir, bagaimana bisa lebih baik daripada apa yang telah berjalan sekarang? Menghafal sejarah sastera, riwayat hidup sasterawan-sasterawan pelopor, hasil karya mereka, bentuk dan jenis sastera. Bahkan ada buku wajib yang diturunkan pada instruksi atasan menghasilkan nol besar. Apa hendak dikata, kalau buku wajib Salah Asuhan tidak didapat sejilidpun pada sebuah kota kabupaten? Jalan penolong adalah analisa, bahwa Salah Asuhan karya Abdul Muis, roman bertendens, pelakunya Hanafi, Corrie. Sama dengan orang mempelajari buah mangga, kulitnya hijau, dagingnya kuning, ada peloknya, rasanya manis. Tapi menikmati buah mangga itu sendiri, menghayati buku Salah Asuhan sendiri, tak pernah. (Perumpamaan L. Martono dari Jember).
Setelah bahannya yang kekurangan, caranya mengajar yang terbatas pada pemberitahuan, dirisaukan juga tentang pengajar dan yang diajar. Pengajar yang tidak cinta sastera, yang buta sastera, terang bikin mawut. Pengajar yang tidak mengikuti perkembangan sastera mutahir, akan membesar-besarkan masa lampau seperti pada zamannya dia menerima pelajaran sastera, mungkin menganggap Angkatan 45 sebagai puncak kejayaan sastera Indonesia, akan membimbing murid ke arah pemikiran kotak-kotak.
Mereka yang menerima ajaran seperti itu semua, (baik bahan, cara, sikap pengajarnya) tidak banyak mengambil manfaatnya. Mereka dibuat mengerti akan sastera hanya untuk lulus ujian. Mendapatkan ijazah inilah yang penting, untuk bekal cari kerja atau menaikkan gaji. Setelah dapat ijazah, sastera adalah benda asing dan jauh dari dirinya.
Pengajaran sastera haruslah dihayati, apresiasi sastera harus merasuk ke jiwa pelajar, sehingga selama hidupnya sastera merupakan kebutuhan jiwa karena meningkatkan kekayaan rokhani dan dijumpai di semua aspek kehidupan. Ini tujuan pengajaran sastera di sekolah-sekolah, yang juga diarahkan oleh para pemrasaran-pemrasaran ataupun pembanding utama dalam seminar. Oleh karena itu sastera harus menarik. Bagaimana caranya ini juga dibicarakan oleh pembicara-pembicara seminar yang diselenggarakan bersama oleh Dewan Kesenian Surabaya dan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan Negeri Surabaya.
Antara lain L. Martono memberikan contoh: Membaca buku tidak menarik lagi karena adanya TV dan komik. Banyak calon mahasiswa mendaftar pada jurusan sastera Inggeris dari pada sastera Indonesia. Sebab: kepandaian berbahasa Inggeris akan lebih berguna untuk bekal hidup. Jadi menarik ada dua unsur terpenting: menimbulkan surprise dan kegunaannya. Dan ini tidak terdapat pada pengajaran sastera Indonesia.
Sebagai pembanding utamanya L. Martono, Gatut Kusumo (Surabaya) menyarankan agar pengajar berani menempuh jalan yang belum ditemukan orang. Pelajaran sastera Indonesia mungkin tidak menarik kalau mengajarkannya menggunakan sistem yang dulu-dulu juga. Adanya TV dan komik tidak bisa ditolak. Orangtua sekarang tidak dapat mendongengi anaknya dengan Timun Mas. Nah, mengapa TV dan komik tidak dijadikan sarana pengajaran sastera?
M.A.Icksan (Malang) dalam bicaranya pada hari ke dua banyak memberi pandangan baru atau jalan keluar dari lingkaran setan hambatan pengajaran sastera Indonesia di sekolah-sekolah lanjutan. Terutama guru harus berani mengadakan eksperimen. Tidak ada buku bacaan wajib, apa salahnya mengajak murid menyelami bacaan mutakhir seperti yang dimuat berserakan di suratkabar-suratkabar atau majalah-majalah? Bahan-bahan itu rieel, aktual dan menarik. Apresiasi sastera lebih mantap dan dinikmati langsung oleh murid apabila murid diajak serta menentukan sifat suatu roman atau cerita pendek yang mereka baca. Jadi jangan dibalik, diberi dulu hasil analisa lalu disuruh baca. Apa yang mereka baca, yang menarik, dan marilah itu yang dijadikan bahan pengajaran sastera. Tiap individu tentu punya pengalaman sastera yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan hidup masing-masing. Tugas pengajar adalah mengembangkan pengalaman sastera ini pada suatu tingkat, yang cocok dengan kelompok manusia, dengan rangsang, kejutan, penarikan ke arah tingkat setinggi mungkin. Inilah pengajaran apresiasi sastera. Dan bahan sastra untuk dialami bersama atau secara individu tidak terbatas pada buku wajib atau lamanya jam pengajaran. Semua benda atau lebih-lebih tulisan bisa dijadikan pengalaman sastera yang baik. Segala potongan waktu, sejam ataupun tiga jam pelajaran dalam seminggu, ataupun setengah jam sedang beromong-omong di luar bangku sekolah, bisa dijadikan pengalaman sastera yang baik. Asal dalam tuntunan guru yang baik.
Dikutip dari: SINAR HARAPAN Jakarta, Kemis 20 September 1973.
Catatan: Seminar ini sudah diselenggarakan seperempat abad yang lalu. Apakah ada perubahan pengajaran sastera di sekolah lanjutan pascaseminar? Tahun 1975 turun kurikulum baru: Dari TK hingga perguruan tinggi hanya satu bahasa, bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa asing hapus dari pelajaran di sekolah. Bahasa Inggris satu-satunya bahasa asing yang diajarkan di sekolah, sebagai ilmu pengetahuan (bukan untuk dihayati atau dikuasai, kalau bisa menguasai ya syukurlah). Pelajaran sastera Indonesia disatukan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia saja sudah sulit, menghabiskan jam pelajaran. Maka pelajaran sastera terdesak, tidak sempat lagi ada bincang-bincang pembacaan buku cerita (sastera) lagi di kelas. Dengan kata lain pelajaran sastera hapus dari sekolah lanjutan. Sastera Indonesia juga tidak diujikan dan tidak dijadikan penentu lulus tidaknya pelajar sekolah lanjutan.
Apa yang menurunkan Kurikulum 1975, bisa diterka-terka dari sejarah kurikulum sebelumnya. Mungkin sekali kegelisahan para pakar pendidikan sastera dalam seminar di DKS itu juga sebagai penggerak lahirnya kurikulum baru, yaitu bahwa pelajaran sastera tampaknya tidak urun apa-apa dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.
Kurikulum sebelumnya, masih meneruskan kurikulum zaman Belanda. Yaitu pengajaran di SMA dibagi menjadi tiga, bagian A (bahasa dan budaya), B (ilmu pasti-alam), C (untuk dipersiapkan bekerja). Selama Orde Lama kurikulum itu berlangsung, untuk bagian A yang diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa kuno dan modern, serta boleh memilih pelajaran bahasa Jerman atau Prancis. Jadi lulus SMA mereka pasti mahir bahasa-bahasa yang diajarkan itu. Untuk meneruskan ke PT, hanya ada satu, yaitu Fakultas Sastera. Kalau tidak meneruskan ke PT, lulus SMA mau bekerja apa? Tidak banyak lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA bagian A. Jadi pengangguran. Untuk SMA bagian B (ilmu pasti alam), konon kerja otaknya lebih cerdas, maka setelah lulus bisa meneruskan ke PT mana saja: Fakultas Tehnik, Hukum, Kedokteran, juga ke Sastera. Kalau tidak melanjutkan ke PT, banyak instansi yang mau mempekerjakan, karena otaknya cerdas (pendidikan IPA). Tidak menjadi penganggur. Bagian C, yang diajarkan adalah administrasi perkantoran, praktek mengetik, dan semacamnya yang berguna untuk pekerjaan. Jelas tidak untuk meneruskan ke PT. Namun bisa juga menempuh study ke PT tetapi dengan berbagai syarat yang sulit dipenuhi.
Mengamati kurikulum ini selama zaman Orde Lama, yang paling untung dan bisa memberi pengharapan hidup masa depan, adalah SMA bagian B. Mereka bisa melanjutkan ke PT dengan bebas memilih, lulus langsung bekerja pun banyak yang mau menerima. Sedang bagian A, sangat sulit mendapatkan pekerjaan, hanya menambah pengangguran saja. Melihat paradigma seperti itulah maka turun Kurikulum 1975, yaitu pelajaran ilmu pasti alam diperluas (dengan kode A1, A2 dan seterusnya), kurikulum sastera dihapus karena menimbulkan kesulitan hidup masa depannya saja. Pendeknya diusahakan lulus SMA putera bangsa harus bisa leluasa baik meneruskan ke PT dengan bebas memilih fakultasnya, atau gampang mencari pekerjaan karena otaknya sudah dipoles dengan pengetahuan IPA. Kurikulum ini sedianya dibuka dengan bagian-bagian A1, A2 seterusnya sampai A6 (entah agama atau seni untuk itu), tapi nyatanya yang diminati para pelajar hanya A1, A2. Untuk A3 saja sudah sulit menampung pelajar (yang mendaftar di A3 jarang, sehingga tidak mungkin dibuka kelas A3), apalagi A4 dan selanjutnya, Tidak ada SMA yang mau buka kelas bagian itu.
Jadi sebenarnya tujuan kurikulum 75 adalah memacu putera bangsa leluasa mencari ilmu dan bekerja dengan tenaga tehnis (IPA) dalam usaha memberantas pengangguran. Suatu terobosan potong kompas memberantas pengangguran. Tetapi, kalau para pelajar itu selama di SMA tidak punya kegemaran membaca buku, dan kegemaran membaca buku agar menarik pada awalnya dibiasakan diajarkan membaca cerita/dongeng/legenda/sastera, maka setelah lulus SMA IPA dan melanjutkan ke PT apa mereka bisa menjiwai roh ilmu yang dipelajarinya? Seperti halnya yang terjadi pada bagian A kurikulum Orde Lama, yang penting lulus mendapat ijazah; dengan ijazah bisa bekerja dan meningkatkan gajinya, tapi ilmu sastera sendiri lepas dan asing dari dirinya, maka untuk bisa lulus para pelajar sastera bukan membaca (menikmati/menjiwai) buku sastera, cukup dengan mempelajari ikhtisar sastera yang dibuat oleh guru SMA (kegelisahan pembicara di seminar DKS). Bagaimana kalau lulusanya pelajar SMA IPA selama berlakunya kurikulum 1975 cukup dengan Bimbingan Belajar selama 3 bulan? (sama dengan mempelajari ikhtisar buatan guru sastera di SMA bagian A Orde Lama). Yang penting lulus dan mendapat ijazah, dan bisa meneruskan ke PT. Lalu, tanpa berbudaya membaca buku dan menulis buku, apakah di PT mereka bisa menghayati, mengapresiasi dan merasuk menjadi jiwanya ilmu yang mereka pelajari? Jangan-jangan seperti halnya dipelajaran sastera di SMA bagian A zaman Orde Lama, lulus SMA yang paling penting adalah mendapat ijazah? Dan untuk itu ditempuh segala cara, ya bimbingan belajar, ya pelihara calo, ya nyogok guru sekolah. Sama dengan simpulan seminar di DKS tentang lulusnya pelajar dalam pengajaran sastera di SMA: lulus sekolah hanya karena pelajari ikhtisar catatan guru (tanpa membaca buku sastera), dapat ijazah untuk memperoleh kerja dan kenaikan gaji. Setelah memperoleh pekerjaan ilmu pengetahuan sastera (zaman Orde Lama) maupun IPA (kurikulum 1975) asing dari jiwanya. Kalau bisa lulus hanya karena mempelajari ikhtisar guru sastera (Orde Lama), tidak berbudaya membaca buku cerita/dongeng/legenda/sastera, apa gunanya sekolah selama 12 tahun? Begitu juga kalau bisa lulus sekolah hanya dengan bimbingan belajar selama 3 bulan, dan tidak berbudaya serta menghayati membaca buku cerita/dongeng/legenda/sastera, apa gunanya sekolah selama 12 tahun? Dan BERBUDAYA membaca buku cerita/dongeng/legenda/sastera tidak mungkin hanya dipelajari dalam 3 bulan. Untuk BERBUDAYA MEMBACA BUKU serta menghayatinya sampai ke hati sanubari setidaknya perlu bimbingan guru, putera bangsa (seperti bangsa-bangsa negeri maju lainnya) harus dibimbing diajari menggemari membaca buku setidaknya selama 12 tahun terus-menerus sejak usia dini. Di mana itu dan kapan? Bukan di bimbingan belajar.
Mungkin gejala ini pula (di SD-SMA tidak diajari menikmati membaca buku sastera), maka setelah berlakunya kurikulum 1975 (1975-2009) kelulusan hakim/dokter/sastera/tehnik tidak berjiwa sasterawi, dan mengakibatkan gonjang-ganjing di Republik ini. Banyak hakim yang tidak adil, dokter malpraktek, pejabat (sarjana) korup. Setelah mendapat pekerjaan di negeri tempatnya berbakti ilmunya kalis dipraktikkan karena memang tidak melekat di sanubari jiwa dan karakternya. Rakyatnya (yang lulusan SMA maupun yang tidak lulus) pun tidak sasterawi, tidak mandiri, berbahasa lisan sebagai kiat hidupnya, kiat hidup kodrati (melihat dan mendengar sebagai pokok ajaran hidupnya, tindakan kekerasan fisik sebagai solusinya), maka kalau dirasa ada ketidakadilan, marah dan bertindak memprotes dan merusak begitu saja. Akibat berlakunya kurikulum 1975, Indonesia benar-benar Republik tanpa sastera.
Kurikulum ini telah berlangsung seperempat abad. Jelas apa yang dikhawatirkan para pembicara pada seminar itu (bangsa celaka berlarut-larut, sastera benda asing yang jauh dari dirinya), terlaksana. �Orang dewasa� (yang melakoni ajaran kurikulum 1975) sekarang ini betul-betul menghayati dan menyemarakkan Republik Tanpa Sastera, yaitu mereka tidak beraspek kehidupan sasterawi. Bisa dilihat dari gejolak perbuatannya dan karakternya kini.
Yang mengherankan selama ini tetap ada Fakultas Sastera, dan mahasiswanya yang mendaftar tidak pernah minim. Kalau mereka tidak mengenal, menghayati, dan cinta sastera, apa tujuan mereka masuk ke Fakultas Sastera? Dalam seminar DKS disebutkan, untuk lulus mendapatkan ijazah, mendapatkan pekerjaan, dan menaikkan gaji. Setelah itu sastera merupakan benda asing yang menjauh dari diri mereka. Sastera bukan merupakan kebutuhan jiwa untuk meningkatkan kekayaan rokhani (amanat seminar di DKS).
Kalau begitu mengapa Fakultas Sastera dibuka terus? Hanya meniru negeri lain, karena di negeri-negeri mana saja yang maju dan beradab pasti mendirikan Fakultas Sastera?
Dalam kurun 25 tahun ini (setelah sastera tidak diajarkan lagi di sekolah) tentu Fakultas Sastera telah meluluskan para sarjana sastera. Bagaimana kegiatan hidup mereka? Apa seperti yang diseminarkan dan digelisahkan oleh para kaum pendidik di DKS 25 tahun lalu? Yakni dunia tempatnya berbakti ternyata benda asing yang tidak dibutuhkan untuk pembangunan bangsa, baik karakter maupun kebendaan ri�l?
Konggres Sarjana Sastera Indonesia telah diselenggarakan berkali-kali. Tahun 2010 akan diselenggarakan di Surabaya. Tapi hasil-hasil konggres tampaknya belum bisa memuaskan dan menjawab kegelisahan kaum pendidik dalam seminar di DKS 25 tahun yang lalu itu. Sastera tetap tidak merupakan kebutuhan jiwa yang meningkatkan kekayaan rokhani dan tetap tidak dijumpai dalam segala aspek kehidupan.
Saran saya: Solusi utama adalah, Ajarkanlah (kembali) membaca buku dan menulis buku sejak masuk sekolah klas I SD hingga klas 12 SMA, tiap hari tanpa jeda, sehingga mereka punya budaya membaca buku dan menulis buku. Pelajaran membaca buku dan menulis buku yang paling dini adalah membaca cerita/dongeng/legenda. Di situ pelajaran membaca (sastera) jadi menarik (amanat seminar), tidak membosankan, dan akhirnya murid punya kebiasaan dan gemar (punya budaya) membaca BUKU dan CERITA. Lebih meningkat dari cerita adalah sastera. Sejak bocah membaca BUKU CERITA, setelah dewasa gemar membaca BUKU SASTERA, berjiwa sasterawi, dan meraih ilmu kehidupan jenis apapun (sastera, politik, ekonomi, tehnik) dengan MEMBACA BUKU ilmiahnya tidak canggung, bisa diapresiasi dengan baik sehingga merasuk ke dalam hati nuraninya, karena sudah punya BUDAYA MEMBACA BUKU, dan segala ilmu yang diraihnya akan dijiwai sampai sanubarinya, jadi kiat hidupnya, tidak bakal asing lagi dari dirinya. Dengan kata lain, berbudaya membaca buku dan menulis buku BISA MENGUBAH TAKDIR menjadi hidup lebih berkeadilan sosial dan sejahtera daripada nasib kodrati. Tetapi kalau sejak bocah tidak diajari membaca buku, meraih kenikmatan hidupnya hanya dengan menonton dan mendengar (menonton TV, kodrati, seperti orang zaman kuno, primitif), setelah dewasa tidak gemar membaca buku, meraih kenikmatan hidupnya dengan menonton dan mendengar, primitif, dan sampai tua pun meraih kenikmatan hidupnya sebagai orang primitif. TIDAK BERUBAH DARI TAKDIRNYA YANG KODRATI. Sejak bocah diajari membaca buku, lulus SMA (remaja) punya budaya membaca buku, setelah dewasa menuntut ilmu untuk hidup tidak canggung karena telah berbudaya membaca buku, membaca buku dihayati hingga merasuk ke sanubarinya dan menjadi kiat hidupnya selamanya, dan itu bisa mengubah takdirnya menjalani hidup yang lebih baik daripada kodratnya. Hidup zaman tehnologi modern tidak bisa lagi kiat hidupnya hanya dari menonton dan mendengarkan ajaran/kuliah guru/dosen, seperti yang dilakukan orang primitif zaman kuno mendengarkan dongeng nenek. Pada zaman ini (modern) segala ilmu hidup telah direkam dalam buku, Segala ilmu hidup bisa dipelajari dengan cara MEMBACA BUKU. Berbudaya (kebiasaan) membaca BUKU sastera berarti menghayati akan sastera, berbudaya membaca BUKU tehnik akan menghayati ilmu tehnik. Yang paling penting sudah punya budaya atau kebiasaan MEMBACA BUKU. Awal mula mendidik membaca buku agar menarik adalah membaca buku cerita (sastera). Lepas sekolah 12 tahun sudah punya kebudayaan membaca buku terutama sastera. Mau melanjutkan ke Fakultas Sastera, Kedokteran, Hukum, Tehnik, mereka tidak masalah karena sudah berbudaya membaca buku dan menulis buku. Dan apa yang dipelajari di fakultasnya pasti dengan kejiwaan menghayati ilmunya. Bukan hanya untuk mencari kerja dan kenaikan gaji belaka (tapi ilmunya asing dari dirinya) seperti yang disindirkan dalam seminar di DKS 25 tahun yang lalu. Misalnya dari Fakultas Hukum, setelah bekerja menjadi hakim, di tempatnya berbakti ilmunya jadi asing dari dirinya, lalu keputusan hakim tidak dihayati dari hati sanubari, melenceng dari roh ilmu yang dipelajarinya.
Di negeri maju, membaca buku (dan menulis buku) serta menghayati sastera dapat dijumpai di segala aspek kehidupan. Orang membaca buku terlihat di mana-mana, di stasion, di taman, waktu antre. MEMBACA BUKU, bukan membaca surat cinta, reklame, surat kabar. Seorang buruh pabrik atau seorang ibu rumah tangga di Negeri Belanda, pasti tahu dan menghayati (karyanya) siapa itu Shakespear siapa itu Dostoevski atau Anne Frank. Bocah klas 11 sekolah dasar di Amerika Serikat tentu sudah tahu dan menghayati (pernah membaca bukunya dengan tekun) Adventures of Huckleberry Finn atau Portrait of Jennie, bahkan mungkin For Whom the Bell Tolls. Seorang buruh pabrik di Indonesia tidak pernah tahu (baca buku) siapa itu NH Dini, Ahmad Tohari, Ayu Utami. Tapi kalau gajinya kurang, dengan semangat mau diajak demonstrasi berteriak-teriak (karena kiat hidupnya hanya berbahasa lisan) menyalahkan pemerintah. Ibu-ibu rumah tangga Indonesia lebih tahu KD dicerai Anang, Tamara mau kawin lagi dengan jejaka dari Kanada yang belum jadi WNI, Yuni Shara pacaran jadian dengan Rafi Akhmad, semua dipelajari dari yang ditonton di TV dan kalau kurang jelas ditelusuri di media cetak. Lebih penting menonton mengapresiasi begitu daripada tekun membaca buku karyanya Mira W, V.Lestari, Marga T atau Sandra Brown. Pelajar lulus SMA di Indonesia menurut penelitian Taufik Ismail (1996) rata-rata membaca 0 buku. Maka buku murah lewat e-book pun tidak terbeli dan tidak terbaca karena di sekolah tidak ada pelajaran gemar membaca buku. Apalagi buku ajar e-book bukan buku ajar baca cerita/dongeng/sastera, (tapi buku ajar matematika, buku yang tidak menyenangkan untuk dibaca oleh anak yang tidak diajari cara menikmati membaca buku). Tidak terganyang oleh anak orang kaya, apalagi orang miskin. Segala pelajaran di sekolah selama 12 tahun hanya dengan cara hadir di sekolah dan mendengarkan guru bercerita (menonton dan mendengar, sama halnya orang primitif yang melakukan segala usaha kenikmatan hidupnya hanya dengan cara melihat dan mendengar). Jadi lulus sekolah 12 tahun ya kiat cara meraih kenikmatan hidupnya seperti orang primitif, hanya dengan cara kodrati melihat dan mendengarkan. Melihat dan mendengar itu kodrat, tidak usah diajarkan pun anak bisa melakukan. Tapi juga hanya kenikmatan sementara dan pribadi, sulit direkam lama di sanubari, tidak bisa ditularkan kepada orang lain yang tidak bersama menyaksikan (melihat dan mendengar bersama). Maka ilmu yang diajarkan di sekolah hanya melalui melihat dan mendengar, sulit sekali direkam berlama-lama untuk digunakan meneruskan pelajaran di kehidupan selanjutnya, termasuk untuk melanjutkan meraih ilmu di perguruan tinggi.
Contoh soal, tahun 2003 orang heboh menonton dan mendengar (lewat TV) Goyang Inul. Kenikmatan menonton Inul itu tidak dapat ditularkan kepada orang lain yang tidak menonton sendiri pada peristiwanya. Kenikmatan menonton Inul (belum lagi 10 tahun yang lalu) tidak bisa ditularkan kepada generasi berikutnya. Andaikata Goyang Inul itu suatu ilmu hidup (filsafat), bagaimana cara menularkan kepada generasi berikutnya? Tidak bisa karena ilmu-hidupnya hanya digelar dalam dimensi bisa dilihat dan didengar. Sama dengan pidato pembelaan Socrates atas hukuman mati dirinya harus minum racun di pengadilan Athena. Suatu misi kemanusiaan yang sangat bagus, sangat mencekam ketika dilihat dan diperdengarkan. Beda dengan peristiwa Inul, pidato pembelaan Socrates yang bagus ditonton dan didengar tadi sampai kini tetap abadi bisa diunduh ilmu filsafat misi kemanusiaannya itu, sehingga menjadi pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa selama hampir 2500 tahun ini. Sebabnya? Karena �tontonan pembelaan Socrates� itu ditulis oleh muridnya, Plato (427-347 S.M.), dalam bukunya The Apology of Socrates. Jadi, ilmu hidup yang direkam hanya dari melihat dan mendengar (anak di sekolah: hadir dan mendengarkan cerita guru) tidak bisa dihayati abadi untuk kiat hidupnya. Agar bisa direkam, ditularkan, dikembangkan, dihayati jadi kiat hidupnya harus diunduh dengan cara membaca buku dan menulis buku. Tapi membaca buku (dan menulis buku) itu bukan kodrat, harus diajarkan, harus dilatih terus-menerus (setidaknya selama 12 tahun awal sekolah) sehingga berbudaya. Bukan hanya dengan melihat dan mendengar (kodrati, primitif), tetapi harus disertai kegemaran membaca buku dan menulis buku. Sesudah mahir dan gemar membaca buku dan menulis buku putera bangsa baru bisa menunaikan hidupnya secara modern. Yaitu meraih ilmu hidupnya dengan kegemaran membaca buku ilmiahnya, dan mengubah takdir nasibnya dari yang kodrati menjadi modern dalam mengarungi hidup zaman kemajuan tehnologi global masa kini dan masa yang akan datang.
Berbudaya membaca buku sastera sama dengan menghayati kehidupan sasterawi. Penghayatan kehidupan sasterawi merupakan kebutuhan jiwa karena meningkatkan kekayaan rohani dan dijumpai di semua aspek kehidupan (amanat seminar). Membaca buku sastera merupakan dulce et utile (menyenangkan dan berguna). Membaca buku sastera, berarti juga meningkatkan kekayaan rohani, menguatkan iman tanpa kekerasan dan tidak berpihak (selain berpihak pada perikemanusiaan), mandiri (menyelesaikan masalah tanpa ketergantungan oleh dan pada pihak lain, baik masalah pribadi maupun masalah bersama), banyak inisiatif untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan fisik. Jika membaca buku sastera meningkatkan kakayaan rohani, berarti membaca buku sastera menjadikan orang tidak miskin dan tidak bodoh. Kalau 100% orang dewasa Republik ini membaca buku sastera, maka pemerintah tidak usah lagi kepikiran memberantas kemiskinan dan kebodohan. Mereka yang gemar membaca buku sastera akan mengatasi masalahnya (kesulitan hidup) dengan cara mandiri, tanpa konflik atau kekerasan (karena banyak insiatif, sasterawi, kaya rohani), dan adil (tidak berpihak selain berpihak pada perikemanusiaan). Caranya? Ajarilah putera bangsa membaca buku dan menulis buku sejak masuk sekolah dini, agar setelah remaja sudah punya budaya membaca buku dan menulis buku. Setidknya buku (cerita, dongeng, legenda) sastera. Maka BUKU SASTERA WAJIB DIBACA oleh seluruh putera bangsa (warga negara), dan di Fakultas Sastera dihayati ilmu inti murninya untuk memperdalam dan memperhalus karakter manusia, utamanya manusia Indonesia. Tidak nanti lalu asing dari dirinya, setelah punya pekerjaan (profesi) yang menghidupinya. Gelorakanlah semboyan dan penghayatan: Indonesia bukan Republik Tanpa Sastera.
Pada tahun 1948-1949 ketika Belanda dengan kekuatan militer ingin menghancurkan Republik Indonesia, salah satu kecamannya adalah: Bangsa Indonesia apa patut merdeka, wong rakyatnya buta huruf, kiat hidupnya hanya dengani melihat dan mendengar, hanya berbahasa lisan seperti orang primif!
Apa patut merdeka, maksudnya apa sudah waktunya merdeka, apa sudah siap?
Pada tahun 2008-2009 bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum langsung oleh rakyat. Belum 100 hari presiden yang terpilih secara langsung oleh lebih 50% dari rakyat, didemonstrasi agar turun dari jabatannya. Kecaman militer Belanda tahun 1948-1949 perlu diulang: Apa patut memilih presiden secara demokratis langsung diselenggarakan, wong rakyat Indonesia 90% kiat hidupnya hanya berbahasa lisan?
Ketika Juventus melawan Bayer Munchen di Stadion Olimpico, Turin, untuk memperebutkan 16 besar Liga Champion 2009-2010, Juventus di atas angin. Kecuali bermain di Italia negerinya Juventus, Juventus hanya memerlukan seri sudah cukup untuk masuk ke laga 16 besar Liga Champion. Pada menit ke-19 David Trezeguet berhasil membuahkan gol untuk Juventus. Kian nyatalah asa kemenangan di kubu Juventus. Tepuk gemuruh kegembiraan terjadi di penggemar Juventus. Tapi para penggemar Bayer Munchen yang �ketiwasan� , tidak lalu beringas mengumpat dan menghujat kesebelasan favoritnya, seperti halnya Kabinet Indonesia hasil pemilihan umum yang dipilih lebih 50% rakyat Indonesia belum 100 hari bekerja dijegal harus turun jabatan. Permainan dilanjutkan sebagaimana aturannya. Ternyata akhirnya Juventus kalah 1-4 oleh Bayer Muchen. Bayer Munchen yang lolos menuju laga 16 besar Liga Champion 2009-2010. Mengapa penggemar Bayer Munchen tidak lalu menghujat anarkitis Bayer Munchen ketika kesebelasan pilihannya itu sangat rawan menyandang kekalahan? Karena mereka (orang Eropa) 100% pasti berbudaya membaca buku dan menulis buku, termasuk sejak SD membaca buku cerita/sastera, dan oleh karenanya sangat terpengaruh pemikiran filsafat Socrates ~ misi kemanusiaan untuk menata kehidupan manusia: kebenaran, etika, kebaikan dan kejahatan, menuju masa depan kehidupan manusia yang ideal. Sejak Plato, murid Socrates menulis pidato pembelaan Socrates The Apology of Socrates, dan menulis buku sawala lisan Socrates lainnya seperti Crito, Phaedo, Dialogues, lalu mendirikan sekolah filsafat yang dinamai Academus, di mana sejarah dan perbaikan hidup manusia diperbincangkan dengan cara-cara menulis buku dan membaca buku, maka sebenarnya sejak itulah sekolah akademi didirikan di seluruh jagad, membaca buku dan menulis buku menjadi dasar kurikulum utama sekolah atau akademi, membaca buku dan menulis buku menjadi kiat hidup modern. Hanya dengan kegiatan membaca buku dan menulis buku (hidup secara bersekolah dan akademis) maka kehidupan seorang manusia atau sekelompok bangsa bisa menjalani hidup modern, mengubah takdirnya menjadi hidup yang lebih baik. Membaca buku dan menulis buku menjadi budaya atau kegemaran seseorang, kalau awalnya dia diajari dengan suka hati dan menarik karena membaca buku cerita, lalu kian lama membaca buku sastera, menekuni, menghayati, bertabiat dan bertingkah sasterawi. Kehidupan sastrawi merupakan kebutuhan jiwa, karena meningkatkan kekayaan rohani dan dijumpai di semua aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan para penggemar sepakbola Bayer Munchen. Sepakbola Juventus vs Bayer Munchen berjalan langsung menurut aturan, indah ditonton, dan tidak timbul gonjang-ganjing anarkitis seperti kepemimpinan bangsa Indonesia yang bertugas belum 100 hari sudah dibakar gambarnya. Tidak terjadi pembakaran gambar pemain Bayer Munchen seorang pun di Stadion Olimpico, ketika pertandingan baru berjalan belum 20 menit, kekalahan Bayer Munchen telah terbayang-bayang.
Tan Malaka adalah orang pertama yang mewacanakan bangsa Indonesia bercita-cita membangun negara merdeka dengan sifat Republik (menulis buku Naar de Republiek Indonesia 1925, sebelum pemimpin yang lain memikirkannya, bahkan istilah �Indonesia tumpah darahku� pun belum masuk batin pemimpin bangsa. Konon WR Soepratman tahun 1928 memasukkan istilah itu ke lagu Indonesia Raya mengutip dari tulisan Tan Malaka). Selama 51 tahun hidupnya Tan Malaka menjelajahi 11 negara, seperti Belanda, Inggeris, Rusia, Thailand, RRC dan lain-lain, dalam keadaan sakit-sakitan dan dalam pengawasan ketat agen-agen Interpol. Sepak terjang hidupnya seperti itu hanya untuk satu tujuan, Indonesia Merdeka. Ketika bangsa Indonesia telah mulai mencanangkan kemerdekaannya (masih dalam pergolakan melawan penjajah Belanda), Tan Malaka bergerilya ke Banten, Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Jogjakarta, dan akhirnya tewas �dibunuh� (oleh bangsanya sendiri) di Kediri pada 21 Februari 1949. Tan Malaka merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang militan, cerdas, kreatif, ulet dan cekatan dalam menggagas dan mengoraganisasi massa rakyat. Tidak hanya dengan bahasa lisan, tetapi lebih-lebih terlihat kecerdasannya dalam buku-buku tulisannya. Buku-buku revolusi gagasannya yang ditulisnya adalah Parlemen atau Soviet (1920), Si Semarang dan Onderwijs (1921), Naar de Republiek Indonesia (1925), Massa Actie (1926), Manifesto Bangkok (1927), Asia Bergabung (1928), Madilog (1943), Dari Penjara ke Penjara (1944), Muslihat (1945), Thesis (1946), Islam dalam Tinjauan Madilog (1948), Pandangan Hidup (1948), Kuhandel di Kaliurang (1948), Gerpolek (1948). Semua fakta perjalanan hidup Tan Malaka telah diungkap oleh sejarawan Belanda Harry Albert Poeze dalam buku setebal 2200 halaman. Judulnya VURGUISD EN VERGETEN, Tan Malaka, de Linkse Beweging en de Indonesische Revolutie (Dihujat dan dilupakan, Tan Malaka dalam pergerakan kebangsaan kiri dan revolusi Indonesia)
Sangat memalukan. Sepak terjang pelopor cinta tanah air Indonesia dan pejuang perintis kemerdekaan Indonesia (yang akhirnya membuat bangsa Indonesia mengalami/menikmati kemerdekaannya saat ini) tidak dapat kita pelajari gagasannya tentang perjuangannya mendirikan negara Republik Indonesia yang Merdeka. Justru yang bisa mempelajari dan memanfaatkan ilmunya bangsa Belanda, karena semua sepak terjang gagasan dan perilakunya ditulis runtut oleh orang Belanda, dalam bahasa Belanda tertulis. Bahwa Harry A. Poeze bisa tekun menulis runtut buku setebal 2200 halaman, bukanlah istimewa, karena sejak dahulu 100% orang Belanda dewasa pasti berbudaya membaca buku dan menulis buku.
Tan Malaka. Seorang pemikir dan perintis cinta tanahair, bisa dipelajari dan dihormati roh pemikirannya oleh orang Belanda untuk dijadikan acuan perjuangan ketatanegaraan yang akan datang, tidak mendapat tempat di hati para penghuni Republik Indonesia Merdeka yang dirintis dan dipeloporinya, karena tidak diketahui riwayat perjuangannya, dan telah tewas dibunuh tahun 1949. Di-verguisd dan di-vergeten. Jangankan perintis cinta tanahair yang telah tewas 1949. Pemimpin bangsa yang dipilih secara demokratis langsung oleh lebih 50% rakyat Indonesia tahun 2009 saja, belum bekerja 100 hari sudah di-verguisd disuruh meletakkan jabatan. Kira-kira apa sebabnya? Coba renungkanlah alasan militer Belanda 1948-1949 tidak mau memerdekakan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia hanya berbahasa lisan.
Harry A. Poeze menulis dengan tekun 2200 halaman riwayat perjuangan Tan Malaka bukan saja sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai penghormatan profesinya sebagai sejarawan yang mengutamakan budayanya membaca buku dan menulis buku telah menjadi roh jiwanya. Bangsa Belanda sejak masuk sekolah dasar digembleng membaca buku dan menulis buku. Bukan itu saja, tetapi orang Belanda dewasa pasti menguasai beberapa bahasa asing lisan dan tulisan. Karena sejak masuk sekolah dasar (bahkan pergaulan di rumah sebelum masuk sekolah pun) diajarkan bahasa-bahasa asing itu. Konon kepekaan anak menerima berbagai bahasa-bahasa aneka (lebih dari 8 bahasa yang berbeda) lebih mampu daripada orang dewasa, maka pengajaran banyak bahasa pada anak lebih cepat terserap terhayati daripada setelah berumur. Dan itu diterapkan dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah. Sejak masuk sekolah dasar diajari berbagai bahasa nasional bangsa yang berbeda. Ingatlah juga Bagian A SMA zaman Orde Lama, yang kurikulumnya meneruskan zaman Belanda. Semboyan mereka (Belanda) taal is macht. Language is power. Menguasai bahasa (berbagai bahasa) itu suatu kesaktian. Dan itu terbukti sejak zaman penjajahan Belanda dulu hingga sekarang. Daerah Aceh dulu paling susah menjadi jajahan bangsa Belanda, karena penduduk aselinya sangat kuat beragama Islam. Tidak percaya dengan wajah-wajah Eropa yang ingin menguasai daerahnya, karena itu selalu mengadakan perlawanan. Namun akhirnya terjajah juga menjadi Hindia Belanda, karena jasa orang Belanda bernama Snouck Hurgeronje, yang fasih bicara Arab dan ahli Islamology (tentu keahliannya karena membaca buku sastera Arab). Menguasai bahasa Arab menjadi kesaktiannya. Noordin M. Top berhasil bertualang melakukan teror selama 9 tahun di Jawa karena dia orang Malaysia yang pandai berbahasa Jawa (terdidik sejak kecil berbahasa Jawa di Malaysia). Menguasai bahasa Jawa adalah kesaktian.
Bandingkanlah dengan kurikulum 1975 Indonesia: sejak TK sampai PT hanya dididik berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa lain, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Batak, dilarang masuk sekolah. Sehingga setelah dewasa (lulus SMA) yang dikuasai juga hanya satu bahasa, bahasa Indonesia. Tapi dalam praktiknya, berbahasa Indonesia pun tidak cerdas dan cermat, karena kiat hidupnya hanya dari melihat dan mendengar, sedang yang ditonton (TV) bahasa Indonesianya dilumuri kata-kata dikibulin, ditemenin, mbokap, gue, yang tidak ada di pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebaikan dan kebenaran selalu gampang diputar-balikkan oleh mereka yang kiat hidupnya hanya berbahasa lisan. Karena lidah memang tak bertulang. Tetapi kebenaran yang tertulis, akan murni abadi meski melalui 2500 tahun berlangsung.
Kita kalah dari bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, termasuk menyelenggarakan dan memajukan bangsa dan negara, karena selama ini (dalam abad tehnologi modern) bangsa Indonesia kiat hidupnya hanya dengan bahasa lisan, kiat hidup bangsa-bangsa purba. Sifatnya menikmati saja (apa yang dilihat dan didengar), tidak kreatif. Maka segala kemajuan zaman, terutama kemajuan tehnologi, bangsa Indonesia hanya menjadi penikmat, konsumtif. Selama Indonesia Merdeka sampai dewasa ini Indonesia memang Republik Tanpa Sastera. Kalah di segala aspek kehidupan antarbangsa-bangsa di dunia. Menjadi bangsa yang penikmat kemajuan tehnologi, terutama tehnologi yang memudahkan melihat dan mendengar, seperti TV, radio, telepon, HP, potret, playstation, komik, sinetron. Menjadi penikmat alat-alat tehnologi modern itu berarti konsumtif, terjajah, malas bekerja, terbius oleh kemajuan tehnologi lihat dan dengar. Menjadi bangsa konsumtif, pemalas, dan terjajah. Itulah Indonesia, Republik Tanpa Sastera.
The moral of the story: Sejak Plato mendirikan Academus 2500 tahun yang lalu, usaha manusia untuk menikmati hidupnya hanya ada dua pilihan cara: KODRATI atau SASTERAWI. Hidup secara kodrati adalah hidup sebagaimana kodratnya, yaitu hidup dengan hanya segala kekuatan indrawinya (terutama kepekaan serapan melihat dan mendengarnya), menerima nasib hidupnya sebagaimana takdirnya. Hidup secara sasterawi adalah selain mengandalkan kekuatan indrawinya (melihat dan mendengar) juga disertai budaya membaca buku dan menulis buku (sastera), yang berarti ada usaha untuk mengubah takdir nasib hidupnya menjadi yang lebih baik.

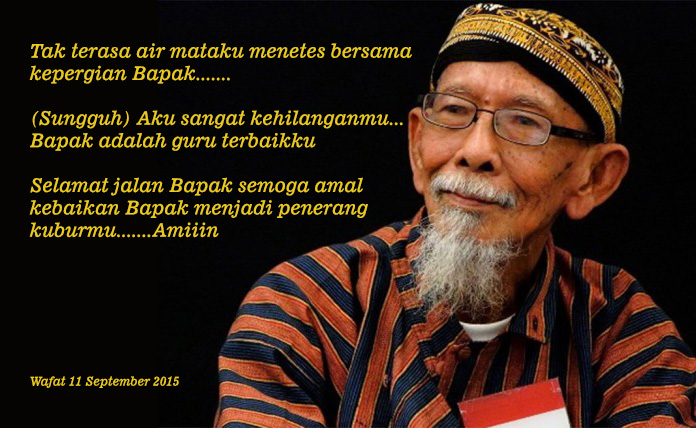



































Indonesia bukan Republik Tanpa Sastra ? Menapa kinten-kinten boten kados “pambengok ing satengahing segara wedhi?”. Kula kinten kathah para guru sastra (bahasa) ingkang nggadhahi pamanggih bilih langkung sae sinau ngadhepi UNAS tinimbang maos buku sastra (sanajanta punika kedah dipun wontenaken panaliten).
solusi akhir yang menurut saya sesuai ialah dengan bergelut dalam dunia birokrat. Sebab kebijakan dibuat oleh para birokrat. Orang yang mau peduli dengan urusan baca tulis, harus mau masuk ke dalam sistem pemerintah yang mengurusi pendidikan. Sebab, pendidikan inilah yang sangat tepat untuk membidik sasaran, yakni menciptakan masyrakat baca-tulis. Dengan adanya orang-orang yang berkomitmen untuk merombak kurikulum dan menerapkan pengajaran sastra dan yang lainnya lebih proporsional, maka kemungkinan terciptanya masyrakat yang berbudaya sebab baca buku, bisa terwujdukan. Persoalannya, kendala akan hal ini ialah malah makin banyak yang mengalami terkikisan komitmen untuk merubah sistem ketika berada di dunia birokrat. Berbagai alasan kerap didengungkan. Nah, langkah awal, tampaknya, jadilah teladan pemabaca dan penulis yang baik, yakni yang selalu aktif berkarya. Lalu tunjukkan perilaku yang berbudaya, yang santun dan beradab. Dengan demikian, akan terlihat adanya korelasi yang sangat kuat tentang pentingnya baca-tulis bagi kehidupan.
Gambaran pas untuk bangsa kita saat ini. Sekarang Sangkuni, Durna, dll telah menjelma dan mulai mengobrak-abrik kehidupan bernegara. Lihatlah bagaimana mereka sedang berusaha menyemangati Yudistira agar bersedia mempertaruhkan negaranya di atas meja judi dadu. Terlepas bhw sastra jawa tak bisa lepas dr warna wayang, sangat dimungkinkan karena penulis sastra jawa sangat nglothok dlm hal tersebut. Yang sangat menakjubkan adalah: bagaimana ‘kondisi negara pewayangan’ menitis ke negeri ini. Bagaimana para birokrat negeri antah berantah tersebut menjelma nyata di negara ini. Saya jd takut untuk mengingat akhir dari mahabarata. Jangan-jangan endingnya akan benar-benar terjadi di negeri ini. Ohhh….