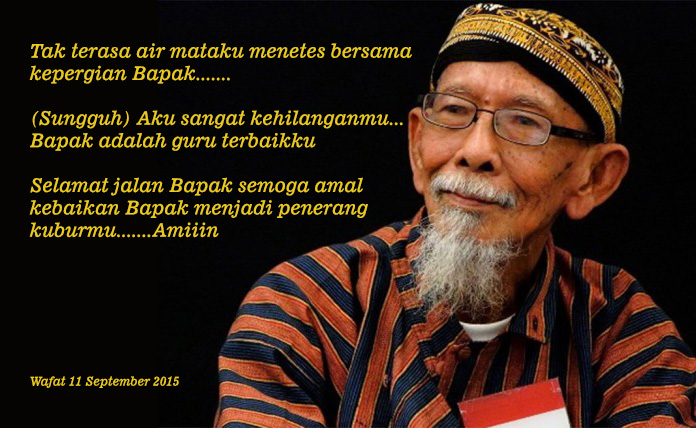Bedah buku Mozaik Ingatan
cerita Suparto Brata
Saya dapat telepon dari Bu Evie, Perpustakaan Rungkut Surabaya: “Pak, mau hadir pada hari Minggu 26 Juni di Perpustakaan? Ada bedah buku”. Ya. Kalau siang saya mau hadir. “Masih ada waktu. Nanti undangannya kami kirimkan”. Tapi, kok aku betul yang diundang? “Ya, kalau Pak Parto yang bicara rasanya enak. Seperti waktu bedah buku The Souls Moonlight Sonata, karangan Wina Bojonegoro dulu itu”.
Memang pada hari Minggu 27 Maret 2011 yang lalu saya hadir di Perpustakaan Rungkut waktu secara mendadak di SMS Mbak Wina, bahwa dia hari itu jam 10 pagi bedah buku di Perpustakaan Rungkut. Harap saya hadir. Waktu itu jam 9 pagi. Jadi saya tergesa pergi ke Perpustakaan Rungkut. Tamu sudah ramai. Ada pertunjukan musik klasik juga dari sekolah musik di Rungkut. Mbak Wina kalau menyelenggarakan bedah bukunya memang mewah. Namun Mbak Wina dan Mas Bonari sendiri belum datang. Konon malam harinya bedah bukunya di Bojonegoro. Kini sedang meluncur ke Perpustakaan Rungkut. Sampai di Gresik jalan macet karena banjir. Akhirnya untuk mengisi kekosongan saya didaulat untuk berbicara di depan, bersama Mbak Diana Salsa. Saya ngomong bukan tentang buku THE SOULS MOONLIGHT SONATA, melainkan perkenalan saya dengan Mbak Wina Bojonegoro yang cantik dan cerdas itu. Nun di Kanigoro Blitar empat-lima tahun yang lalu.
*
Senin 20 Juni Bu Evie datang ke rumah mengantar surat undangan resmi dari ‘Arm’s management’ bahwa saya diharap membedah buku puisinya Dr. Armanto Sidohutomo, SpM. KORNEA HATI, hari Minggu 26 Juni 2011, jam 10.00 – 12.00 WIB. Saya diberi bukunya. Lo, saya terkejut, yang dibedah kok buku antologi puisi. Padahal saya kurang faham sama yang namanya puisi.
Minggu 26 Juni 2011, sebelum berangkat ke Perpustakaan Rungkut, saya baca berita sastera di Jawa Pos. Ada artikel: SANGGAHAN KEMATIAN PROSA SURABAYA, tulisan Risang Anom Pujayanto. Ia membahas buku MOZAIK INGATAN antologi 14 cerita pendek yang ditulis oleh Agus Budiawan dkk. Selesai baca koran, baru pergi ke Perpustakaan Rungkut, jalan kaki saja, kira-kira 2 km dari rumah saya.
Acara bedah buku antologi puisinya Dr.Armanto berlangsung gayeng. Lebih cocok dinamakan launcing daripada bedah buku, sebab (untunglah) Dr. Armanto begitu jelas mengemukakan riwayat ketertarikannya menulis puisi meskipun profesinya sebagai dokter mata sukses. “Sekolah sing perlu aé//Golek ilmu sing iso nulung masyarakat” begitu salah satu bait puisinya dr. Armanto Sidohutomo, SpM yang saya amati. Baik sekali. Yang saya tangkap, kedudukan atau jabatan sebagai dokter tidak harus dibangga-banggakan sebagai orang sukses, mapan dan kaya, melainkan akan lebih memuaskan kalau ilmu kedokterannya itu bisa berguna untuk menolong sesama manusia. Dan dalam launcing bukunya Dokter Armanto banyak berkisah bagaimana menolong orang dari kebutaan menjadi bisa melihat lagi itu sebagai gairah hidupnya, meskipun yang ditolong itu tukang becak yang tidak akan kuat menanggung beaya pengobatannya. Kegairahan itu diekpresikan oleh Pak Dokter menjadi bait-bait puisi. Dan itu merupakan kepuasan batin sendiri dalam kehidupan Pak Dokter.
*
Siang hari launcing buku Kornea Hati selesai, sore harinya habis magerip ada tamu dari kelompok sastra Cak Die Rezim, Finsa Saputra dan Itok K, memberi buku Antologi 14 Cerita Pendek MOZAIK INGATAN serta mengundang saya untuk hadir esok harinya (Senin 27 Juni) di Fak.Ilmu Budaya Unair, Ruang Sidang Lt II jam 0900-1200. Acaranya mendadak, jadi undangannya lisan begitu. Kok saya diundang? Ya, menurut Finsa, itu merupakan balas budi karena saya sudah memberi endorsement di sampul luar belakang pada buku itu. Lo, aku tidak ingat memberi endorsement itu. Belakangan ini semua permintaan yang melibatkan saya harus menulis, saya hindari. Sebab sejak bulan Maret kemarin komputer saya rewel. Saya ingat saya menolak keinginan Mas Sunaryono Basuki Ks untuk memberi ulasan pada bukunya. Begitu juga saya tidak menyanggupi menuliskan kata pengantar untuk buku tulisan Mas Koes Indarto ITI KATHA AJII-SAKHAA (buku kisah Ajii-Sakhaa, guru sastera di wilayah Nusajawa bahasa Jawa Kuna). Ya karena komputer rusak, saya jadi kesulitan mengetiki gagasan-gagasan saya. Hari-hari itu hingga hari ini pengetikan saya di komputer agak tersendat.
Namun saya memang rajin menghadiri bedah buku, selagi ada undangan, meskipun hanya hadir sebagai penonton dan pendengar belaka. Betapapun itu mempertemukan saya dengan masyarakat sastra. Saya perlu dan butuh. Kalau siang hari, saya bisa datang. Kalau malam hari, maaf, mata saya sulit untuk memandang malam.
Sebenarnya saya masih trauma kemarin disuruh bedah buku antologi puisinya Dokter Armanto, karena puisi saya tidak kuasai. Karena itu saya tanya, undangan bedah buku MOZAIK INGATAN ini saya datang sebagai apa? “Sebagai tamu,” tegas Itok. Dan kalau perlu kendaraan besok akan dijemput. Acaranya mulai jam 0900. Baiklah, saya bilang saya siap dijemput jam 0800. Kalau sebagai tamu, menonton dan mendengarkan pertemuan sastra, saya memang suka dan butuh. Apalagi dijemput. Saya pasti siap.
Karena habis magerip, saya tidak sempat membaca buku MOZAIK INGATAN. Mata saya kurang jelas untuk membaca buku dengan sinar lampu. Karena itu sinar matahari saya butuhkan untuk membacai buku-buku.
Keesokan harinya, jam 0800 saya sudah siap dijemput. Menunggu jemputan, saya bukai buku MOZAIK INGATAN. Melihat wajah buku, saya ingat artikel sastra di Jawa Pos Minggu yang saya baca sebelum berangkat ke Perpustakaan Rungkut kemarin. Betul. Itulah bukunya. Maka saya baca lagi artikel SANGGAHAN KEMATIAN PROSA SURABAYA. Saya setuju, prosa Surabaya tidak mati, kok. Ini harus saya buktikan nanti di bedah buku di Unair. Aku ambili buku-buku prosa tulisan orang Surabaya di almariku, saya bawa ke Unair sebagai bukti bahwa prosa Surabaya tidak mati.
Buku MOZAIK INGATAN saya bukai. Tidak sempat baca cerita pendeknya yang dimuat, saya coba bacai sekilas hal-hal yang bukan cerita pendek. Di halaman awal ada catatan semacam kata pengantar, antara lain dengan judul: “Ingatan Perlawanan yang Belum Usai” tidak tercatat nama penulisnya, di akhir halaman ada tulisan semacam kritik tentang tulisan 14 cerita pendek di buku itu, dengan judul: “Narasi Fotografi Distopia” tulisan Bramanto. Saya sempat membaca dua “Kata Pengantar” itu.
Membaca “Kata Pengantar” yang berjudul Ingatan Perlawanan yang Belum Usai, ingatan saya melayang mengomentari. Saya kutip beberapa bait yang tersurat: Tujuh penulis dalam buku antologi CDR ke-2 ini (termasuk CDR sebagai komunitas, semoga) tidak ingin menjadi “Timur”, yang terancam bisu selamanya sebelum orang-orang brilian seperti Said, Spivak, dan Homi Bhaba, hadir. Tujuh penulis tersebut tidak sudi menjadi Timur yang mengalami ambivalensi. Di satu sisi membenci ketertindasannya, di sisi yang lain justru mengagumi keperkasaan Barat. Bahkan dalam konteks tulisan ini (diakui atau tidak, tulisan ini memang sangat kontekstual) mereka lebih tepat disebut mengalami desublimasi represif. Ambevalensi masih mengindikasikan kesadaran akan “ketertindasan”, sedangkan mereka yang mengidap virus desublimasi represif justru tidak menyadari “ketertindasan”-nya, dan dengan konyol malah merayakannya. Selama mereka bisa tampil, maka tak ada masalah dengan “ketertindasan”.
Saya kutip tulisan itu, karena banyak ahli sastra mengatakan bahwa tokoh-tokoh cerita buku saya adalah bukti jelas apa yang dikatakan oleh Homi Bhaba, tokoh “Timur” yang mengalami ambivalensi. Membenci ketertindasan, tetapi sekali gus konyol mengagumi keperkasaan “Barat”.
Lina Puryanti (dosen sastra Inggris Unair) membadah buku saya “Mencari Sarang Angin” menulis begini:
The postcolonial discourse in the novel Mencari Sarang Angin by Suparto Brata shows an ambivalence identity of the characters. In one side this novel welcomes the modernity offered by the colonizer ideology while, at the same, it also tries to build a local identity related with the matter of self-authenticity. Bhabha said this situation and the condition as the “location of culture” which shows in-between position of the subject. In this case, mimicry or imitation experienced by the postcolonial subject has put them as the mediator group between the colonizer’s interests in distributing its power towards the colonialized community. In spite of giving a heroic political resistance against the colonizer, the discourse of postcolonial tends to pay attention on the heritage of the realm of colonial in postcolonial period which is signified by the ambivalence and unstable meaning.
Ujar Bu Lina Puryanti: “Bhabha mengatakan warga terjajah (bangsa “Timur”) dididik oleh orang Barat (kulit putih) untuk menjadi almost the same, but not quite, atau dengan ungkapan rasialis yang tepat, almost the same, but not white. Manusia bukan “Barat” dapat diajar “meniru”, tapi bagi penjajah, “peniruan” itu akan terhambat oleh sifat-sifat “kodrati” yang selalu membedakan Barat dan bukan Barat (“Timur”)”.
Itu yang kutanggapi dalam pikiranku ketika saya membaca sekilas tulisan: Ingatan Tentang Perlawanan yang Belum Usai, pada halaman V buku MOZAIK INGATAN ketika masih di rumah menunggu jemputan. Sampai kapan pun “Timur” yang semacam itu tidak akan pernah bisa mandiri, yang tertulis pada halaman itu berikutnya, juga menggagapi pikiranku.
Yulitin Sungkowati (Balai Bahasa Surabaya) menganalisis buku-buku novel saya yang mengandung lintas sejarah Indonesia (yang dianalisis sebanyak 11 judul buku), menulis begini:
Dalam beberapa hal, novel-novel Suparto Brata merefleksikan kolonialisme Belanda yang berbeda dengan catatan dua sejarawan (Kuntowijoyo, 1987;127, dan Ricklefs, 2005;374) tersebut, sebagaimana terungkap dalam novel Gadis Tangsi dan Mencari Sarang Angin. Kedua novel itu tidak secara jelas memosisikan Belanda sebagai musuh, tetapi justru sebagai sumber wacana untuk meningkatkan peradaban bangsa Jawa (baca Indonesia), dengan menggambarkan transformasi seorang rakyat biasa berperadaban rendah menjadi priyayi berperadaban tinggi melalui proses pendidikan membaca dan menulis dengan “kiblat” pada kemajuan peradaban bangsa Belanda (garis bawah dari saya, Sbrata). Melalui pendidikan membaca dan menulis, Rokhayah (pada novel Mencari Sarang Angin) berhasil meningkatkan martabatnya dari gadis kampung yang bodoh dan liar menjadi priyayi terhormat. Perubahan hidup Rokhayah itu dioposisikan dengan nasib Turnadi dan Rokhim yang menjadi pengkhianat bangsa hingga hidupnya berakhir tragis. Materi sejarah dalam novel ini dimanfaatkan sebagai penyampai gagasan pentingnya peran pendidikan dalam upaya membangun hidup merdeka dan bermartabat.
Dalam novel Gadis Tangsi Suparto Brata menggambarkan kehidupan pribumi, baik dari kelas wong cilik (keluarga Wongsodirjo dan penghuni tangsi lainnya) maupun bangsawan (Kapten Sarjubehi) yang bekerja sebagai tentara Kompeni Belanda di tangsi militer Lorong Belawan, Medan. Akan tetapi, fokus novel ini tidak pada aktivitas tentara KNIL, melainkan pada perjuangan Teyi dan Raminem, anak dan istri Wongsodirjo serta para istri dan anak serdadu KNIL lainnya yang berasal dari Jawa. Dalam lingkungan yang liar dan serbakekurangan itulah, diperlihatkan bagaimana semangat Teyi mengubah hidupnya menjadi manusia berperadaban tinggi. Di bawah bimbingan Putri Parasi, Teyi mendapat pendidikan membaca, menulis, bahasa Jawa halus dan bahasa Belanda, serta sopan santun (garis bawah dari saya, Sbrata). Bekal pendidikan inilah yang mengendalikan hidup Teyi sehingga tidak terseret dalam kehidupan liar tangsi. Semangat dan cita-cita Teyi untuk membangun hidup yang bermartabat itu digambarkan tidak mendapat halangan dari Belanda atau Jepang, tetapi justru oleh Manguntaruh dan Dasiyun yang masih tergolong saudaranya. Dalam novel ini pun, oposisi menyangkut nasib orang-orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan sangat jelas dengan menempatkan keberhasilan hidup orang-orang yang mau belajar dan kegagalan hidup orang-orang yang hidup dalam kebodohan.
Dari 11 novel yang telah dibicarakan tadi dapat ditarik suatu benang merah bagaimana “sejarah bangsa” ditafsirkan oleh Suparto Brata, yaitu perjuangan hidup berbagai elemen bangsa: laki-laki-perempuan, wong cilik-bangsawan, tentara, jurnalis, sopir, orang dewasa, dan anak-anak yang tidak hanya harus berhadapan dengan musuh asing (baca penjajah), tetapi juga rongrongan dari saudara sebangsa. “Sejarah bangsa” juga ditafsirkan sebagai sejarah kebodohan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau belajar dari masa lalu dan membaca sejarah bangsanya. Secara implisit hal itu menyiratkan pemikiran pengarang (Suparto Brata) bahwa musuh terbesar bangsa Indonesia dari dulu hingga kini sesungguhnya bukan Belanda, Jepang, Inggris atau Sekutu, atau bangsa lainnya, tetapi kebodohan. Kebodohan telah menjerumuskan bangsa Indonesia menjadi bangsa nista yang hidup dalam penjajahan bangsa lain selama berabad-abad pada masa lalu. Kebodohan juga yang membuat bangsa Indonesia di era kemerdekaan kini tetap terpuruk dan tertinggal jauh dari bangsa-bangsa “modern”. Oleh karena itu, perjuangan melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain itu memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah perjuangan memerdekakan diri dari kebodohan, dan kebutaan baca tulis, dan kebutaan sejarah (garis bawah dan tebal dari saya, Sbrata). Secara politik, bangsa Indonesia memang sudah mencapai kemerdekaannya, tetapi secara kultural masih hidup dalam alam kebodohan sehingga bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras lagi untuk membebaskan diri dari belenggu kebodohan.
Sebagaimana Nevins (Sugihastuti, 2007;161) yang mengatakan bahwa sejarah dapat menjadi cermin untuk melihat masa sekarang dan menjadi pedoman untuk menata masa depan, Suparto Brata pun tampaknya mencoba mengatakan bahwa masa lalu itu penting sebagai cermin untuk melangkah ke depan agar apa yang buruk di masa lalu tidak terulang lagi. Melalui novel-novelnya, ia berupaya membantu mengenalkan dan mengakrabkan masyarakat pada masa lalu bangsanya dengan harapan dapat menanamkan akar yang kuat sebagai landasan untuk merumuskan dan menata masa depan yang lebih baik. Karya prosa Suparto Brata ini barangkali dapat dijadikan sebagai semacam wacana alternatif tentang sejarah bangsa.
(Dikutip dari: LiNGUA, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, Volume 4, Nomor 1, Juni 2009, Unit Penerbitan Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim UIN, Malang).
Zainuddin Hakim dan Ratun Untoro (Peneliti Madya dan Tenaga Teknis Balai Bahasa Sulawesi Utara), meneliti buku novel GADIS TANGSI karya Raden Mas Suparto Brata, berkesimpulan sebagai berikut:
Pandangan umum novel ini adalah cerita tentang keunikan dan keunggulan budaya kawula. Hal itu diceritakan oleh pengarang yang juga seorang bangsawan kraton. Namun, kebaikan sikap, perilaku, dan adat istiadat bangsawan kraton tersebut berada di balik bayang-bayang sikap, watak dan perilaku kaum penjajah Belanda. Disadari atau tidak, pengarang yang juga seorang bangsawan secara tidak langsung telah turut menjajah sikap, watak dan perilaku kawula (garis bawah dari saya, Sbrata).
(Dikutip dari: Jurnal SAWERIGADING, Bahasa, Sastra, dan Pengajaran. Volume 15, Nomor 1, April 2009).
Meskipun sebenarnya sebuah karya sastra kalau sudah diumumkan penilaiannya terserah kepada tanggapan pembacanya, tidak lagi si pengarang perlu mengomentari, namun tentunya masih boleh si pengarang karya sastra balik menanggapi hasil penelitian pembacanya. Karena pembaca karya sastra juga terdiri dari banyak pembaca dengan tingkat sosial, arah sentimen atau kepentingan yang berbeda-beda, mungkin saja pembaca yang bocah lain tanggapannya dengan pembaca yang sarjana, nilai tanggapannya pun bisa berbalikan satu dengan yang lain. Dan juga karya penelitian kalau sudah diumumkan juga bebas, para pembacanya yang berhak menilai karya penelitian tadi.
Menanggapi karya penelitian Zainuddin Hakim dan Ratun Untoro tersebut saya (Suparto Brata) menulis tanggapan di sini, begini:
Dari simpulan peneliti mengungkapkan: “Disadari atau tidak, pengarang yang juga seorang bangsawan secara tidak langsung telah turut menjajah sikap, watak dan perilaku kawula”. Disadari atau tidak, atau tidak teliti, peneliti tidak melihat bahwa yang menjajah sikap, watak, perilaku, kebodohan, ketidakberadapan kawula, adalah mereka tidak membaca buku dan hanya berbahasa tunggal. Teyi (tokoh kawula dalam novel) menjadi pandai, kuasa, mandiri, bukan hanya meniru kebudayaan bangsawan atau Belanda, melainkan (yang paling ditekankan oleh pengarang dengan sangat jelas diceritakan dalam buku Gadis Tangsi) Teyi belajar membudayakan membaca buku dan belajar bahasa asing (Belanda), dan dari situlah Teyi bisa hidup mengikuti zaman modern yang berlaku. Pembudayaan Teyi membaca buku telah mengatasi budaya bangsawan Jawa (priyayi) pada umumnya atau sama dengan budaya bangsa Belanda yang kolonialist. Bacalah lagi penelitian itu dengan mengubah istilah kawula (= orang yang tidak membaca buku), dan kraton/raja/priyayi/bangsawan/Belanda (= orang yang berbudaya membaca buku). Maka akan terlihat nyata mengapa mentalitas kawula zaman kolonial itu tetap masih ada sampai pada zaman teknology Global, ketika bangsawan/raja sudah tidak ada lagi. Mentalitas kawula tetap ada karena putra bangsa tidak punya budaya membaca buku. Putra bangsa berbudaya membaca buku (untuk menghapus kebodohan dan mengentas kemiskinan = mentalitas kawula), itulah yang diperjuangkan pengarang Suparto Brata (seorang bangsawan yang terlunta-lunta, tidak pernah menikmati kekayaan bangsawan, kebudayaan bangsawan, maupun kekuasaan bangsawan, ~ tetapi untunglah berbudaya membaca buku dan menulis buku) hingga saat ini. Tanpa berbudaya membaca buku (dan syukur menulis buku) bangsa Indonesia pada zaman kolonial sampai abad 21 ini akan tetap menjadi KAWULA (= bodoh, berperadaban kasar, miskin, primitip, did not have power authority, selfdown, rude, uneducated) dalam kehidupan modern.
Lihat saja, Indonesia sudah Merdeka 65 tahun, bangsa Indonesia belum merdeka dari kebodohan, selfdown, rude, uneducated, saling menyalahkan orang lain meskipun itu teman perjuangannya sendiri. Saya mengistilahi suasana hoping ciyak hoping (bahasa Mandarin yang artinya “teman makan teman sendiri”) zaman sekarang ini sebagai nekrofilia.
Mengamati tiga tulisan analisis buku novel saya di atas, maka kiranya menjadi lebih jelaslah apa masalahnya yang ditulis pada Ingatan Tentang Perlawanan yang Belum Usai. Tujuh penulis cerita pendek dalam MOZAIK INGATAN ini tidak sudi menjadi Timur yang mengalami ambivalensi. Ambivalensi masih mengindikasikan kesadaran akan “ketertindasan”. Sampai kapan pun “Timur” yang semacam itu (mengalami ambivalensi?) tidak akan pernah bisa mandiri. Eksistensi mereka hanya menunggu belas kasihan Barat. Seperti kredo Marx: Mereka tak bisa tampil sendiri. Yang menjijikkan, ada kecenderungan mereka ingin dianggap sebagai Barat pula, sehingga prestise dan harkat mereka akan terangkat. Sebab bagaimanapun Barat adalah cerita tentang kejayaan dan kekuasaan tiada batas. Akhirnya, sikap dan tingkahlaku Timur yang terobsesi pada Barat ini menjadi jumawa dan angkuh, bahkan melebihi Barat yang sesungguhnya (MOZAIK INGATAN halaman V).
Setelah mengamati tiga tulisan analisis buku novel saya masalahnya menjadi jelas, karena tentang “peniruan terhadap Barat yang berkiblat ambivalensi”, “Barat yang intelek”, “Barat adalah kekuatan dahsyat yang menindas”, “Barat adalah bapak yang otoritatif, Timur adalah anak yang tersesat jika tanpa arahan dan asuhan Barat”, sumber masalahnya hanyalah satu. Yaitu: Barat yang kuasa, Barat yang menindas, Barat yang membimbing, karena mereka menjalani hidupnya dengan kiat MEMBACA BUKU DAN MENULIS BUKU. Sejak Plato (427-347 S.M) mendirikan Akademus dan menulis buku The Apology of Socrates, yang mengisahkan pembelaan Socrates ketika dijatuhi hukuman mati minum racun, maka ilmu filsafat misi kemanusiaan Socrates untuk menata kehidupan manusia masa depan yang ideal (kebenaran, etika, kebaikan dan kejahatan) menjadi pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa selama hampir 2500 ini. Sejak itu hidup modern dikembangkan, yaitu untuk meraih kepuasan hidupnya yang lebih mapan manusia harus berkiat membaca buku dan menulis buku. Membaca buku dan menulis buku menjadi sanggaran (pathok atau tuak) hidup modern. Sedangkan mereka yang tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku, memuaskan hidupnya hanya dengan kekuatan indrawinya saja, mereka disebut hidup kodrati, hidup seperti orang-orang zaman dulu kala alias hidup primitif.
Ingatan Tentang Perlawanan yang Belum Usai menandaskan bahwa para pengarang (sasterawan) menentang kecenderungan mereka ingin dianggap sebagai Barat. Mereka menilai sikap dan perilaku Timur yang terobsesi pada Barat menjadi jumawa dan angkuh, bahkan melebihi Barat yang sesungguhnya. Bagaimana mereka (7 penulis cerita pendek MOZAIK INGATAN) menghindar dari pengaruh Barat, karena mereka justru menapaki hidup di bidang sastra atau penulisan buku. Sedang sastra atau “membaca buku dan menulis buku” sudah menjadi kiat hidup mereka (orang Eropa = Barat). Tiap orang dewasa di Eropa, setelah melalui sekolah awal 12 tahun, pasti berbudaya membaca buku dan menulis buku, dan itu menjadi kiat hidup mereka untuk meraih kepuasan hidupnya. Meskipun tidak semua jadi sasterawan, di segala bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, mereka hidup tidak hanya mengandalkan ketajaman insting kodrati-indrawi saja, melainkan juga didukung kekuatan sastrawi (membaca buku dan menulis). Sedang bangsa Indonesia, setelah melewati 12 tahun sekolah pemula, tidak punya budaya membaca buku (DR.Taufik Ismail 1996: anak Indonesia lulus sekolah SMA membaca buku 0 judul). Sistem pendidikan nasional Indonesia: putra bangsa yang penting lulus UNAS. Hidup sasterawi, membaca buku dan menulis buku, tidak perlu. Padahal di Barat, sejak zaman Plato sampai sekarang, orang hidup modern itu harus sasterawi, oleh karena itu sepanjang 12 tahun awal sekolah yang paling penting putera bangsa Eropa harus berbudaya membaca buku dan menulis buku. Dan para pengarang Indonesia, termasuk 7 pengarang cerita pendek di buku MOZAIK INGATAN, betapapun dengan menulis cerita, mereka hidup sasterawi, mereka hidup memasuki ranah “kekuasaan” Barat, karena membaca buku dan menulis buku adalah kebudayaan Barat sejak zaman 400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kurikulum pendidikan nasional Indonesia pada abad 21 ini, lulus SMA tetap tidak sasterawi. Jadi (boleh dikata) hanya para pengarang Indonesialah yang memasuki ranah kehidupan Barat, yaitu sasterawi. Dan itu boleh dikata terpengaruh virus ambivalensi. Sebab potensi bangsa Indonesia yang lain (politik, ekonomi, sosial) mereka tetap berusaha menolak kekuatan Barat, menganggap Barat sebagai penindas, mereka menolak penindasan Barat dengan cara lulus pembelajaran sekolah 12 tahun tidak berbudaya membaca buku dan menulis buku. Betul-betul murni tidak terkena virus ambevalensi.
Sangat mungkin 7 pengarang cerita pendek penulis MOZAIK INGATAN itu bakal kreatif mandiri, bisa tampil sendiri, tidak menunggu belas kasihan Barat sudah bisa melebihi karya orang Barat. Sangat mungkin, karena para sasterawan itu sudah memasuki ranah kehidupan modern, kehidupan Barat yang sudah tercipta sejak hampir 2500 yang lalu. Mereka itu bisa seperti tokoh Teyi pada novel saya Gadis Tangsi, seperti tokoh Rokhayah pada novel saya Mencari Sarang Angin, yaitu kecenderungannya terobsesi “meniru” Barat, dalam hal ini khususnya membaca buku dan menulis-nulis. Meskipun tertakdir sebagai orang sudra (kawula atau kampung) Teyi maupun Rokhayah mau belajar membaca buku dan belajar tidak hanya satu bahasa (kurikulum pendidikan nasional Indonesia 1975: dari TK sampai PT hanya dididikkan satu bahasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ada pendidikan bahasa daerah atau etnis lain). Sehingga taraf hidup, kecerdasan, moral, etika, kewibawaan Teyi maupun Rokhayah serasi dan harmoni, bahkan melebihi bijak dengan suami mereka yang mengalami ambivalensi, berpendidikan dan berpikir seperti bangsa Belanda, tetapi tetap seperti kodratnya, bangsawan Surakarta Hadiningrat. Mereka adalah Raden Mas Kus Bandarkum (suami Teyi) dan Darwan (suami Rokhayah) yang almost the same but not white. Bahkan pada novel trilogi saya Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem, Mahligai Di Ufuk Timur, potensi Teyi sudah melampaui suaminya Raden Mas Kus Bandarkum yang bangsawan Surakarta Hadiningrat dan berpendidikan Barat. Setelah menjadi isteri Kus Bandarkum Teyi tetap sopan-santun, tapi juga menuntun kehidupan rumahtangganya menguak integritas sesuai zamannya (pascakolonialisme). Teyi yang berpendidikan mimikri “meniru” Barat, yang almost the same but not quite, pada akhir cerita saya gambarkan tetap humble, tapi integrity, leadership, profesional, innovative, dan care.
Tujuh pengarang MOZAIK INGATAN sangat mungkin bakal kreatif mandiri, karena mereka bergiat hidup dalam membaca buku dan menulis buku. Membaca buku dan menulis buku menjadi kiat hidupnya, seperti halnya semua orang dewasa Barat. Tetapi kehidupan politik, sosial, ekonomi, demokrasi, etika, dan tata kehidupan yang lain, bangsa Indonesia sampai kapan pun tidak pernah bisa mandiri. Eksitensi mereka hanya menunggu belas kasihan (dijajah) Barat. Yaitu kalau mereka seperti apa yang ditemukan oleh DR.Taufik Ismail, lulus SMA membaca 0 buku. Karena bukan sasterawan dan tidak membaca buku dan menulis buku setelah dewasa, berprofesi ataupun bekerja apa pun yang kiatnya bukan membaca buku (dan menulis buku), mereka itu (bangsa Indonesia) seperti tokoh Manguntaruh dan Dasiyun pada novel saya Gadis Tangsi, atau Turnadi dan Rokhim pada novel saya Mencari Sarang Angin. Tokoh-tokoh itu, karena tidak punya budaya membaca buku, berperadaban kasar, primitip, selfdown, rude, did not have power authority, penghambat kemajuan bangsa pada zamannya, bahkan menjadi pengkhianat bangsa. Hoping ciyak hoping, saling menjegal potensi kreatif membangun bangsa, alias nekrofilia.
*
Saya sampai di depan Fakultas Ilmu Budaya jam 0930. Seperti biasa banyak mahasiswa di situ. Dan tidak menghiraukan saya, jadi tidak ada yang mengenal saya. Saya pun terus menuju lantai 2, ke ruang sidang. Sudah beberapa kali saya ke ruang itu, baik hadir sebagai pendengar maupun pembicara. Di depan ruang itu ada meja-kursi untuk panitia penyambutan, beberapa orang menyambut kedatanganku, dan seorang mahasiswa bahkan lalu mempersilakan saya memasuki ruangan, dia tergopoh memberi tahu temannya yang sedang sibuk mengatur pertemuan itu. Separuh ruang telah diisi oleh peserta. Saya dipersilakan duduk di depan. Terus terang, tidak ada seorang pun yang saya kenal. Itulah kelemahan saya. Mata kurang awas, dan kurang merekam wajah yang pernah saya kenali, kalau wajah itu bertemu saya sekali dua kali, lalu lama menghilang. Saya bilang kepada para penyambut saya, bahwa saya ini tamu yang memenuhi undangan biasa, tidak diistimewakan. Mereka masih melanjutkan menata persidangan beberapa waktu lamanya. Lalu, ketika sidang dimulai panitia menuntut supaya saya duduk di mimbar bersama 3 orang lainnya sebagai pembicara. Saya tidak kenal siapapun.
Sidang dimulai, seorang yang ditunjuk dadakan sebagai moderator dan kurang siap memperkenalkan kami berempat yang duduk di mimbar, yaitu mahasiswa yang bernama Risang Anom Pujayanto (jadi ini yang menulis resensi di Jawa Pos kemarin), lalu Bramanto (o, ini yang menulis kritik “Narasi Fotografi Distopia” di buku MOZAIK INGATAN), saya, dan seorang lain yang juga asing seperti saya, yaitu mewakili penerbit dari Jogja “leutikaPrio” yang menerbitkan buku MOZAIK INGATAN.
Sebelum para pembicara diminta menyampaikan pendapatnya kehadirannya di situ lebih dulu oleh moderator ada seorang peserta yang disuruh membaca salah satu cerita pendek yang dimuat di buku MOZAIK INGATAN. Seperti biasanya, saya tidak konsen pada pegelaran sastera (pembacaan sastra maupun deklamasi di panggung) karena betapa pun sastera itu lebih nikmat “dibaca” daripada dilihat dan didengar.
Giliranku bicara, saya mengatakan sebenarnya kemarin diundang ke situ sebagai tamu. Saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk berbicara. Tapi saya memang sempat tersanjung ketika membaca Sanggahan Kematian Prosa Surabaya yang meresensi buku MOZAIK INGATAN di Jawa Pos kemarin, nama saya (Suparto Brata) dicantumkan sebagai sastrawan sederet dengan Shoim Anwar dan Budi Darma. Terus terang, selama ini pada buku-buku Sastra Indonesia yang menjadi pedoman angkatan yang ditulis para ahli sastra seperti HB Jasin, Jacob Sumardjo, maupun Korri Layun Rampan, nama saya tidak pernah disebut. Ya agak kecewa, tapi juga tahu dirilah, karena apa yang saya tulis selama ini merupakan sastra hiburan, bukan serius. Saya lebih suka baca bukunya V.Lestari, Mira W. Marga T., S.Mara Gd, daripada bukunya Ayu Utami, NH Dini, Djenar Maesa Ayu. Lo, kok tiba-tiba kemarin nama saya dicantumkan sederet dengan Shoim Anwar dan Budi Darma (sasterawan serius). Ya tersanjung. Tapi juga terasa narsis. Yang menyebut kok Kanca Dhèwèk.
Yang kedua, saya puji tampilan buku MOZAIK INGATAN ini karena dimuat juga analisis kritik tentang ke 14 cerita pendek yang dikarang oleh 7 pengarang. Saya rasa itu baik sekali, dan juga saya lakukan pada penerbitan buku-buku saya sastra Jawa. Sastra tanpa kritik (penilaian dari pembaca) akan stagnan. Artinya cerita sastra tadi tidak dibaca (oleh orang umum), atau tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap pembaca.
Yang ketiga, saya ikut menyanggah bahwa sementara para penyair Ibu Kota Jawa Timur ini masih memberi andil menata sejarah sastra Indonesia, habitat prosa justru mengesankan suasana adem ayem, diam, lembam, vakum, beku, mandul, atau lebih parah lagi sedang dalam berada dalam kondisi mati suri (pinjam ungkapan Risang Anom Pujayanto di Jawa Pos). Sebagai buktinya bahwa para pengarang prosa Surabaya tidak diam, saya ambil buku-buku pengarang Surabaya yang tadi saya ambili dari lemari buku saya dan yang saya bawa ke situ: Perempuan Kembang Jepun (Lan Fang, Gramedia Pustaka Utama 2006), Ciuman Di Bawah Hujan (Lan Fang, Gramedia Pustaka Utama 2010), Serimpi (Rohana Handaningrum, Jaringpena 2009), Pemuja Oksigen (Brahmanto Anindito, Jaringpena 2010. Mula-mula Brahmanto Anindito ini saya kira Bramantio yang menulis kritik pada buku Mozaik Ingatan yang sedang kami bedah. Ternyata bukan. Bramantio adalah dosen sastera Indonesia Unair, yang waktu itu duduk di sebelah kiriku pada diskusi bedah buku ini), Existere (Sinta Yudisia, Lingkar Pena Kreativa, 2010), Nona M (M.Djupri, Rumah Kata-kata 2010), The Souls Moonlight Sonata (Wina Bojonegoro, Genta Pustaka, 2011). Itu yang bisa saya bawa waktu itu, dan terbit tahun-tahun akhir ini. Belum penerbitan tahun-tahun yang lalu, termasuk karangan saya (Suparto Brata) seperti:Kremil (Pustaka Pelajar 2002), Mencari Sarang Angin (Grasindo, 2005), Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem, Mahligai Di Ufuk Timur (Grasindo, 2004,2005, 2006), Sebiji Pisang Dalam Perut Jenazah (M.Shoim Anwar, Tiga Serangkai 2004), Sensasi Selebriti (Sirikit Syah, Pustaka Pelajar 2007), Aku Terjebak Di Taipei City (Dede. C, Ombak 2006), Kera Di Kepala (Soeprijadi Tomodihardjo, Gramedia Pustaka Utama, 2006). Dari serangkai penerbitan buku prosa pengarang Surabaya, pada tahun-tahun berapa pengarang prosa Surabaya dikatakan vakum, adem ayem, diam? Yang saya sebut tadi hanya buku-buku prosa yang berhasil saya raih dan beli. Betapa pula yang saya tidak tahu dan tidak teraih olehku.
Saya memang pemburu buku untuk saya miliki dan saya nikmati membacanya di rumah sementara matahari bersinar (siang hari). Selain buku-buku karangan yang saya kagumi, juga buku apa saja yang berhubungan dengan Surabaya, entah itu pengarangnya maupun ceritanya tentang Surabaya. Misalnya buku Aku Terjebak Di Taipei City. Dede.C memang betul-betul ada di Taipei, tapi dulu dia sekolah di UPN “Veteran” Jawa Timur (Surabaya). Dan buku Kera Di Kepala, Soeprijadi Tomodihardjo, meskipun dia sekarang menetap di Kőln (Jerman), tetapi dulu orang Surabaya rumahnya di Putroagung Surabaya.
Meskipun bukan buku prosa sastra, kalau itu ada hubungannya dengan Surabaya, dan dapat saya capai (dengan kekuatan keuangan saya maupun keakraban saya) tentu saya coba memburunya. Misalnya (1) MEMOAR HARIO KECIK (731 halaman Yayasan Obor Indonesia Jakarta 1995), Soeharjo Ketjik. Soeharjo Ketjik adalah seorang pemicu perebutan senjata Jepang di Surabaya, dari pembentukan Pasukan Khusus 23 September 1945 di Julianalaan/M.Duryat bersama Abdul Wahab (Ketua BKR Karesidenan Surabaya), yang selanjutnya terjadi perebutan kekuasaan di Gedung Kenpeitai Surabaya 2 Oktober 1945 yang sekarang jadi Tugu Pahlawan Surabaya. Soeharjo Ketjik adalah pemicu perjuangan 10 November 1945 di Surabaya yang sampai sekarang (2011) masih aktif menulis buku-buku pengalaman hidupnya maupun profesinya sebagai ahli strategis ketentaraan (1959-1964 jadi Pangdam Mulawarman Kalimantan Timur, 1965 dikirim sekolah ketentaraan di Moskow). (2) Buku YOGYAKARTA 19 Desember 1948, karangan Himawan Soetanto, (424 halaman, terbitan Gramedia Pustaka Utama 2006), saya koleksi (dan saya baca). Letjen (purn) Himawan Soetanto M.Hum. adalah putera HR.Mohammad Mangundiprojo yang namanya sudah jadi nama jalan di Surabaya. Waktu revolusi Agustus 1945, Himawan Soetanto sudah jadi pelajar SMP Praban, tentunya juga ikut-ikutan perang. (3) IBNU SUTOWO Saatnya Saya Bercerita! (536 halaman National Press Club of Indonesia, Jakarta 2008). Ibnu Sutowo adalah dokter lulusan NIAS Surabaya 1940 ketika zaman Indonesia berjuang untuk merdeka menjadi tentara di Plaju Sumatera Selatan (1945), dan menyelamatkan tambang-tambang minyak di Indonesia dari kekuasaan orang asing (1958-1965).
Begitulah kerakusan saya mengenai penerbitan buku-buku yang pengarangnya maupun ceritanya tentang Surabaya. Sampai ada buku the sensational world best-seller, over 10.000.000 copies sold yang pernah jadi best seller majalah Time beberapa minggu, The Happy Hooker, karangan Xaviera Hollander, saya dengar bahwa Xaviera Hollander kelahiran Surabaya, saya memburunya hingga dapat.
Selain disuruh menulis mengenai peristiwa 10 November 1945 di Surabaya bersama Prof.DR.Aminuddin Kasdi dan Drs.Sudjijo oleh panitia yang diketuai oleh Pak Blegoh Sumarto 1986, saya juga berhasil mendapatkan buku-buku tentang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tulisan orang Belanda MACABER SOERABAJA 1945 Richard L.Klaesen, 2004; REVOLUTIE IN SOERABAJA, W.Meelhuijsen 2000. Baik Richard L.Klaesen maupun W.Meelhuijsen berada di Surabaya 17 Agustus 1945-31 Desember 1945, mereka mengalami pahit-getirnya orang Belanda hidup di Surabaya pada zaman peristiwa 10 November 1945.
Jadi sebenarnya tidak ada kevakuman Surabaya dalam buku.
*
Diskusi bedah buku MOZAIK INGATAN berlanjut pada sesi tanya-jawab. Berlangsung dua tahap mengusung 10 penanya/penanggap. Ada beberapa yang saya jawab, antara lain seorang penanya tidak percaya kalau saya datang ke diskusi bedah buku itu hanya sebagai tamu. Hal itu, katanya, terlihat bahwa saya sangat ‘bersiap’ sebagai pembicara di mimbar daripada pembicara lainnya. Misalnya kesiapan saya dengan menunjukkan buku-buku karangan orang Surabaya yang saya miliki.
Saya jawab: Betul-betul saya kurang siap. Undangan begitu tiba-tiba, saya tidak sempat baca bukunya menyeluruh. Tidak sempat baca satu pun dari cerita pendek yang jadi pokok buku itu, melainkan hanya kata pengantar dan sekilas tulisan kritiknya. Itu sama dengan peristiwa sehari sebelumnya (hari Minggu 26 Juni 2011 di Perpustakaan Kota Surabaya Rungkut). Yaitu saya harus membedah buku antologi puisinya Dokter Armanto Sidohutomo KORNEA HATI di Perpustakaan Rungkut Surabaya kemarin itu. Saya kurang sekali membaca puisi, lalu kemarin disuruh membedah puisi. Tapi kemarin itu saya juga masih merasa beruntung. Beruntung oleh Pak Dokter disuruh membedah buku antologi puisi. Andaikata oleh Pak Dokter disuruh membedah silikon payudaranya Malinda Dee….. tahu barangnya saja saya sudah terbelalak.
Tetapi sungguh, kehadiran saya Senin 27 Juni 2011 di Ruang Sidang Lantai 2 Fakultas Ilmu Budaya Unair dan duduk di mimbar sebagai pembicara itu saya menjawab pertanyaan serbaspontan belaka. Kalau pun lancar, mungkin karena pengalaman tentang perbukuan sudah terlalu banyak, sehingga apa saja yang ditanyakan di situ saya punya pengalaman sebagai jawabannya. Misalnya ada penanya yang ditujukan kepada Pak Bramantio bahwa tulisan kritiknya memotret hampir semua cerpen yang dimuat MOZAIK INGATAN bernada dunia yang muram, sebuah distopia. Antara lain ketergesaan pengarang menyelesaikan cerpennya sehingga seliar apapun pada awalnya berakhir pada lubang hitam yang sama di akhir cerita untuk kemudian runtuh ke kekelaman. Kritik yang pesimistis. Diucapkan oleh penanya Pak Bramantio seperti tidak menunjukkan ada harapan para pengarang akan berkembang. Akan menemui kegagalan.
Meskipun pertanyaan tadi bukan ditujukan kepada saya, tapi saya juga menyahuti saja. Menurut pengalaman saya, suatu kritik yang pesimistis, bisa saja itu bahkan menjadi cambuk bagi yang dikritik (sang pengarang) untuk lebih semangat berjuang mencapai kedudukan yang dicita-citakan. Seperti yang saya alami sendiri menjadi seorang pengarang, sebegitu lama berkecimpung dalam sastra sejak tahun 1952, nama saya tidak dianggap sebagai sastrawan Indonesia oleh para ahli sastra seperti HB.Yasin, Jacob Sumarjo, Korrie Layun Rampan. Tapi toh akhirnya pada tahun 2007 saya mendapat Hadiah Sastra Indonesia tahunan bersama 2 orang sasterawan Indonesia lainnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, dan saya direkomondasikan mendapat hadiah The S.E.A Write Award 2007 (hadiah tahunan ke-29 Sastra Asia Tenggara) di Thailand. Ya, meskipun bersastra-sastra begitu lamanya tidak dianggap (seperti dikritik pesimistis), saya tetap saja tidak mau berhenti untuk bersastra-sastra.
Dan setelah mendapatkan Hadiah-hadiah seperti itu (bangga mendapat hadiah), saya tetap tidak berhenti mengarang sastra seperti penulisan sastra yang saya senangi (tidak mengubah dari menulis sastra kontekstual ke sastra absurd, misalnya). Saya ingat anjuran Mary Higgins Clark, wanita penulis cerita detektif Amerika yang dijuluki Agatha Christie era 80-an: “Kalau kamu kepingin hidup bahagia setahun, menangkanlah kuis, atau lomba (mendapat hadiah), kalau kamu kepingin hidup bahagia selama hidup tekunilah pekerjaanmu selamanya”. Nah, saya kepingin bahagia selama hidup. Jadi, setelah dipilih mendapat hadiah sastra tahunan Asia Tenggara di Thailand, ya saya terus saja menulis dan mengarang cerita, karena mengarang adalah pekerjaan saya yang merupakan amanah Allah kepada saya yang harus saya ibadahkan, dan Alhamdulillah kepengarangan saya menjadi barkah.
Begitu pula setelah mendapat Hadiah Sastra Rancagé buku bahasa Jawa tahun 2001, saya tidak berhenti menulis sastra Jawa hingga mendapat Hadiah Sastra Rancagé lagi tahun 2005. Mendapat hadiah-hadiah seperti itu memang bukan tujuan terakhir dari kegiatanku menulis sastra. Oleh karenanya sampai sekarang pun saya tetap menulis dan menerbitkan buku bahasa Jawa, sekalipun buku bahasa Jawa sulit dipasarkan. Sukses finansial dalam menulis dan menerbitkan buku bahasa Jawa belum tentu memuaskan, terkadang bahkan merugi (bukunya tidak laku), tetapi saya selalu berusaha bahwa buku yang saya terbitkan tadi berguna bagi pembacanya. Kemudian saya ketahui bahwa kegiatan saya seperti itu telah dirumuskan dan dinasihatkan oleh Albert Einstein: “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”.
Sudah banyak contoh, bahwa penderitaan seseorang atau kelompok orang (karena dianggap atau dinilai rendah, seperti dikritik tak punya masa depan yang gemilang) justru merupakan cambuk untuk bersemangat mencapai cita-cita. Banyak orang yang semula menderita memperjuangkan cita-citanya, akhirnya tercapai, dan itu merupakan kemenangan yang lebih mengharukan daripada seseorang yang sejak semula punya fasilitas segalanya lalu langsung bisa mencapai cita-citanya (tidak mengalami penderitaan). Dalam kehidupan masyarakat saja sudah sangat umum, bahwa orang yang miskin berjuang untuk menjadi kaya tanpa kekhawatiran dengan kemiskinannya; sedang orang kaya berjuang mempertahankan kekayaannya dengan kekhawatiran (jiwanya rentan) akan menjadi miskin. Karena khawatir menjadi miskin maka orang kaya mempertahankan kekayaannya dengan segala cara ditempuh, mungkin tidak jujur, tidak adil, termasuk berbuat kriminal, korupsi dan menyelewengkan etika.
Perihal penulisan (cerpen) yang tergesa yang awalnya begitu liar tetapi menyelesaikan cerpennya ke lubang hitam kekelaman, pada galibnya pasti dialami oleh semua pengarang. Ketergesaan dilakukan mungkin karena keterbatasan tempat dan/atau waktu. Saat proses mengarang, tentu ada cita-cita karangannya akan dikirim dan diterbitkan oleh apa, siapa, di mana. Kalau dikirimkan ke majalah maupun suratkabar, pasti panjang-pendeknya karangan terbatas, sehingga pengarang mengalami ketergesaan menyelesaikan cerpennya karena keterbatasan tempat terbit. Kalau dikarang untuk mengikuti lomba, ketergesaan dialami karena keterbatasan waktu. Dua keterbatasan tempat terbit dan waktu tadi adalah merupakan niatan mengapa seorang pengarang menulis sastra. Yaitu untuk mendapatkan pengakuan (nama) sebagai pengarang, dan mendapat imbalan karyanya. Pastilah begitu angan-angan 7 penulis cerita pendek MOZAIK INGATAN, mengingat 12 cerita pendek di situ dikutip dari pemuatan di majalah, dan 2 cerita pendek sebagai pemenang lomba.
Lain halnya kalau menulis untuk sarana curhat. Entah diary atau surat cinta. Bisa tidak tergesa karena panjang tulisan tak terbatas, dan waktunya pun leluasa semau si penulis. Meski menulis tidak bertujuan meraih sukses dinobatkan jadi sasterawan maupun menjadi kaya (sukses finansial), banyak juga yang justru menjadi masyur dan kaya akibat tulisannya. Justru karena tulisannya kemudian termasyur sebagai penulisan sastra. Antara lain The Diary of Young Girl, yang ditulis oleh Anne Frank dari 12 Juni 1942 – 1 Agustus 1944. Panjang pendeknya tulisan tidak dibatasi oleh tempat maupun waktu, ketergesaan menulis karena ancaman hidupnya. Kemasyuran atau pun kejuaraan bukan lagi tujuan. Tapi bagaimana pun tetap ada tujuan mengapa seseorang menulis sastera. Anne Frank menulis sebagai curhat, kebetulan tulisan curhatnya jadi karya sastra yang berhasil. Tujuh penulis cerpen MOZAIK INGATAN menulis cerpen pastilah bukan dengan cara “kebetulan” begitu namanya dan karyanya menjadi termasyur. Melainkan menulis cerpen dengan cita-cita cerpennya menjadi karya sastra yang bermutu betulan.
Para penulis MOZAIK INGATAN menerbitkan cerpennya menjadi buku, kian menunjukkan niatnya mengapa mereka menulis cerpen. Tidak melulu mengandalkan ketermasyuran atau pendapatan, namun lebih pada pengakuan eksitensinya dan kelestarian karyanya. Penerbitan buku adalah bagai fosil karya penulisan orang. Apalagi penerbitan buku ada pencatatan ISBN dan KDT. Berarti penerbitan buku tadi terjamin peredarannya di dunia.
Sebagai penulis sastra Jawa, saya pun mengalami begitu. Untuk diakui sebagai penulis sastra Jawa, maupun penggemar sastra Jawa sarananya hanyalah pada majalah bahasa Jawa. Penerbitan buku, sejak tahun 1973 ketika buku-buku sastra Jawa dilarang beredar oleh Kepolisian Surakarta, tidak berani terbit. Meskipun pelarangan tadi maksudnya memberantas penerbitan buku sastra Jawa yang mengandung unsur pornografi, antem kromo saja, termasuk buku-buku saya yang isinya maupun formatnya beda dengan buku-buku sastra Jawa porno, dan penerbitan buku saya ada izin dari DPKN (polisi), ya kena sikat juga. Penjual buku sastra Jawa tidak berani menjual. Dan sejak itu, sangat sulit untuk meyakinkan publik bahwa buku bahasa Jawa yang terbit tidak dilarang polisi, dan isinya bermutu, tidak porno. Ketika muncul penghargaan buku sastra Jawa oleh Yayasan “Rancagé” pimpinan Ayip Rosidi tahun 1994, maka mulai ada pergerakan para pengarang sastra Jawa menerbitkan buku. Mereka menerbitkan karyanya menjadi buku dengan cita-cita mendapat hadiah sastra Rancagé. Ayip Rosidi sendiri tiap tahun memberi hadiah sastra Rancagé untuk penerbitan buku sastra Sunda, sastra Jawa, sastra Bali dan sastra Lampung tentulah dengan cita-cita adiluhur agar penerbitan sastra etnis itu juga menjadi bacaan buku yang bermutu dan digemari pembaca banyak orang.
Berkarya sastra bahasa Jawa kian mengerdil ketika ajang penulisan dan pembacaan karya sastra bahasa Jawa kian susut kian susut. Tiras majalah bahasa Jawa juga kian susut dan jumlah penerbitan majalah pun kian sedikit jumlahnya. Sedang sumbangan karangan tetep membeludak. Hampir tiap hari redaksi majalah bahasa Jawa menerima kiriman cerpen (seminggu 7 hari 7 cerpen), namun sebagai majalah mingguan yang bisa dimuat hanya satu cerpen. Lalu yang 6 cerpen diapakan?
Bagaimana pun penerbitan sastera di majalah maupun suratkabar itu perlu. Perlu untuk ajang pelatihan menulis sastera dan menggemari sastera. Lebih-lebih bagi para pengarang sastera Jawa. Tanpa terbitnya majalah bahasa Jawa, sangat sulit para penggemar sastera Jawa mencari bacaan sastera Jawa; dan sangat sulit para pengarang sastera Jawa menyebarkan karya sasteranya. Untuk kehidupan sastera Jawa, majalah mingguan seperti Panjebar Semangat, Jaya Baya, Djaka Lodhang, tetap harus ada. Sedang untuk kepengarangan sastra Indonesia, koran dan majalah masih sangat dibutuhkan untuk merintis kegiatan penulisan sastera. Tapi tujuan akhir penulisan sastera, baik sastera Jawa maupun sastera Indonesia, haruslah tetap pada penerbitan buku.
Dan itu pulalah yang saya anggap benar langkah para penulis cerpen buku MOZAIK INGATAN. Cerpen-cerpennya diterbitkan jadi buku. Sebab sastera itu (wujudnya) buku.
Kesulitanku menulis sastra Jawa kian bertambah ketika pada tahun 2000 ada anjuran dari seorang penulis muda sastra Jawa agar para penulis sastra Jawa yang tua-tua jangan lagi menulis di majalah. Karena majalah adalah ajangnya para kaum muda untuk berkarya. Saya harus sadar diri. Dan mengalihkan berkarya dengan menerbitkan buku. Memang sejak dulu saya mengenal sastra itu dari membaca buku, jadi seharusnya menyebarkan sastera itu juga dengan menerbitkan buku. Dan dalam pengalaman saya menggeluti sastra Jawa, sudah sejak awal saya berusaha menyebarkan karya sastera saya jadi buku. Lebih-lebih sastra Jawa, karena sejak pembereidelan oleh Polisi Surakarta tahun 1973 itu tidak ada penerbit buku profesional yang mau menerbitkan buku sastra Jawa, maka karya sastera saya saya usahakan sendiri terbit jadi buku.
Dengan adanya hadiah Rancagé untuk penerbitan buku sastra Jawa, maka kian ramailah penerbitan buku sastera Jawa. Banyak pengarang sastera Jawa berusaha menerbitkan karyanya menjadi buku. Namun karena buku sastra Jawa sulit dijual, tujuan para pengarang sastra Jawa bukan mencari keuntungan finansial dari penjualan bukunya, melainkan merebut hadiah Rancagé. Ini kalau dilihat dari kegairahan pengarang sastera Jawa menerbitkan karyanya jadi buku setelah ada hadiah Rancagé untuk penerbitan buku sastra Jawa. Dan juga hadiah Rancagé menjadi tujuan penerbitan buku para banyak pengarang sastra Jawa. Banyak di antara mereka, setelah mendapat hadiah Rancagé tidak lagi mengarang sastera Jawa. Seakan-akan sudah puas dengan dirinya diakui sebagai pemenang hadiah sastra Rancagé.
Meskipun akhir-akhir ini banyak buku sastra Jawa diterbitkan, saya juga tetap menerbitkan buku-buku karangan saya. Mungkin sekali tujuan mereka menerbitkan karyanya jadi buku yang utama bukunya laku dan modal kembali, dan syukur mendapat hadiah Rancagé. Sedang tujuan saya menerbitkan buku sastera Jawa tetap seperti sebelum hadiah Rancagé ada, bahkan sebelum penerbitan buku sastra Jawa porno dilarang oleh Polisi Surakarta 1973. Tujuan saya terus menerbitkan buku (sastera Jawa) adalah anggapan bahwa karya sastra itu berwujud buku. Saya mengenal cerita-cerita karya sastera karena gemar membaca buku. Masih di sekolah dasar (SD) kelas IV, V, VI saya dengan generasiku telah membacai buku-buku sastera dunia seperti Don Kisot (Miguel Cervantes – Sepanyol), Angin Barat Angin Timur (Pearl Buck – Amerika), Rumah Mati Di Siberia (Feodor Dostoevski – Rusia), Tiga Orang Panglima Perang (Alexadre Dumas – Prancis), Kim Anak Rimba (Rudyard Kipling – Inggris), dan banyak lagi lainnya. Buku-buku semacam itu sudah kami baca dan kami gemari ceritanya karena buku-bukunya tersedia di perpustakaan sekolah. Saya mengenal sastera dari membaca buku, maka kemudian ingin mengarang cerita seperti buku yang saya baca, dan cerita karangan saya tadi seharusnya ya terbit berupa buku.
Berbagai motif pengarang menerbitkan buku. Saya tetap ingin menerbitkan cerita-cerita karangan saya bahasa Jawa jadi buku (meskipun semula sulit mencari penerbit karena buku sastra Jawa sulit mendapatkan pembaca/pembeli) dengan sasaran pembaca/pembeli buku saya adalah: orang kaya, orang kuasa, orang pintar, orang muda. Buku saya harus digemari dibaca oleh orang-orang seperti itu. Itu merupakan perjuangan saya untuk membangkitkan kesadaran bahwa buku sastera Jawa itu tidak seperti pencitraan pembaca majalah bahasa Jawa sekarang. Pembacanya hanya orang tua, ceritanya tidak mengikuti zaman, bahasa Jawa sudah tidak laku untuk orang muda. Saya ingin hapus pencitraan itu. Kalau toh buku saya tidak terbaca/terbeli/menarik empat sasaran pembacanya, janganlah salahkan mereka. Barangkali kesalahannya terdapat pada buku penerbitan kita. Mungkin sampulnya tidak menarik, atau bukunya terlalu tipis, atau harganya terlalu mahal, atau uraian di halaman luar belakang buku kurang memikat.
Saya yakin, para pengarang antologi cerpen MOZAIK INGATAN juga dihinggapi perasaan seperti yang saya alami sepanjang usaha saya mempublikasikan karya sastra saya, sehingga akhirnya mereka memutuskan karya sastranya diterbitkan jadi buku. Karya sastra itu wujudnya buku. Kalau dimuat di koran atau majalah, karya sastra itu umurnya pendek. Setelah koran atau majalah yang lebih baru terbit, koran atau majalah yang lama yang memuat karya sastra saya, sudah habis riwayatnya. Sudah tidak terbaca lagi oleh umum. Sedang kalau diterbitkan jadi buku, buku tadi bisa disimpan lebih lama, dan dibaca lagi kapan saja. Verba volant, scripta manent (kata-kata lisan terbang hilang, sementara tulisan menetap permanen). Namun kalau tulisan di majalah ataupun koran, korannya sudah lewat dan terbuang tidak tentu rimbanya, maka karya tulis tadi juga sama dengan kata-kata, terbang hilang. Hanya tulisan di bukulah yang tetap permanen, dan dibaca lagi kapan saja.
*
Zawawi Imron, pernah bertahun-tahun tiap minggu menulis esei di Jawa Pos. Berbagai macam pengalaman sastera ditulis dalam esei sastra mingguannya. Termasuk puluhan tahun yang lalu pertemuannya dengan saya, bisa diungkap kembali oleh beliau lewat eseinya di Jawa Pos. Baru saya baca ketika beliau memberitahu bahwa pertemuan itu dimuat di Jawa Pos yang terbit waktu itu. Waktu ketemu beliau waktu lain, saya mengatakan, alangkah baiknya kalau esei sastranya tadi diterbitkan jadi buku. Kalau hanya ditulis di koran atau majalah biasanya tidak berumur panjang.
Dan sekarang, setelah Zawawi Imron tidak lagi tulisannya muncul di Jawa Pos secara rutin, lenyap sudah cerita esei sastranya yang bertahun-tahun ditulisnya.
Suatu bukti lagi bahwa buku merupakan fosil karya kehidupan manusia. Maka saya sangat setuju dengan usaha para penulis cerpen (prosa) Surabaya bersama menerbitkan buku MOZAIK INGATAN. Mereka menerbitkan buku dengan urunan membeayai bukunya itu. Bahwa akan memberikan untung finansialkah mereka dengan penerbitan buku tadi, tampaknya belum berharap sampai ke sana.
*
Salah seorang penanggap bedah buku adalah Ibu Hadi, dosen sastera Indonesia Unair. Salah satu yang disoal adalah keuntungan finansial dengan penerbitan buku-buku. Bu Hadi menceritakan kenal benar dengan NH. Dhini. Beberapa prosanya diterbitkan oleh penerbit besar ternama, dan bukunya dipajang di toko buku Gramedia. Namun hasil honorarium atau royalty dari penerbitan bukunya tidak bisa digunakan untuk hidup dengan baik-baik.
Tentang honorarium dan royalty dari penerbit terkenal pun saya punya cerita. Memang benar bahwa bagi pengarang, menulis di majalah atau suratkabar lebih langsung dirasakan keuntungan finansialnya, karena setelah karangannya dimuat segera pengarang dapat honorarium. Itu sudah sangat saya rasakan sepanjang kehidupan kepengarangan saya, baik karya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Dan saya tahu juga ketika honorarium tulisan yang diterima pengarang dari koran bahasa Indonesia Rp 100.000,00 (seratus ribu), dari majalah bahasa Jawa hanya Rp 25.000,00 (duapuluhlima ribu). Meskipun berkeluhkesah tentang kecilnya honorarium pada penulisan di majalah bahasa Jawa, para pengarang sastera Jawa tidak patah semangat mengirimkan ceritanya ke majalah bahasa Jawa.
Pada tahun-tahun 1960-an, saya apabila mendapat honorarium dari majalah terbitan luar Surabaya, uang dikirim lewat poswisel, pasti diberi catatan dipotong pajak 10%, tertulis pada strok berita. Akhir-akhir ini saya tidak pernah menulis di suratkabar maupun majalah luar kota Surabaya, tidak memperhatikan cara-cara mendapat honoraium. Dan bentuk poswisel sekarang juga lain dari zaman dulu. Dulu berupa sebuah kartu, yang menulisi kartu tadi si pengirim, sehingga ketika menerima poswisel si penerima bisa melihat seluruh tulisan yang ditulis oleh pengirim pada kartu poswisel tadi. Poswisel sekarang oleh pengirim ditulis pada selembar formulir (bukan kartu), dan oleh pegawai kantor pos isi formulir tadi diketik elektronik ke kantor pos tujuan. Saya sering menerima dan mengirim poswisel zaman yang beritanya diketik oleh pegawai kantor pos. Pegawai kantor pos seringkali lupa mengetik berita yang ditulis pada formulir, karena letaknya di bawah. Seringkali saya menerima kiriman uang pemesanan buku, judul bukunya tidak tertulis pada ruang berita sehingga membuat saya bingung buku apa yang dipesan itu. Dan setahu saya, kalaupun honorarium dari suratkabar atau majalah, saya tidak lihat lagi jumlah honorarium itu sudah dipotong pajak atau belum. Penerima honorarium kurang perduli hal itu, karena yang harus memotong dan menyetorkan potongan itu ke kantor pajak memang pemberi honorarium (majalah).
Mengenai royalty dari penerbitan buku, ada pengalaman saya yang berkenaan dengan pajak. Pada pertengahan tahun 2008, saya mendapat surat dari dua penerbit buku saya di Jakarta, keduanya memberitahu bahwa untuk tahun depan (2009), seorang pengarang diwajibkan punya NPWP (nomer pokok wajib pajak). Kalau punya NPWP royalty dipotong 10%, Kalau tidak punya NPWP royaltynya akan dipotong (pph) 20%. Oleh karena itu saya disuruh mengurus NPWP ke kantor pajak, setelah dapat agar memberitahu nomer NPWP-nya ke penerbit. Saya pun mengurus NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Rungkut Surabaya. Selain pensiun PNS, saya katakan saya dapat penghasilan dari mengarang buku dan kadang menjadi pembicara pada hal-hal yang berkenaan dengan seni, khususnya sastera. Mengurusi NPWP sama sekali tidak dipungut biaya. Setelah mendapat NPWP saya hanya harus lapor penghasilan tiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak). Karena tidak tiap bulan saya mendapatkan royalty, maka pada SSP penghasilan ditulis NIHIL. Dan nanti kalau dapat royalty, biasanya penerbit mencantumkan juga potongan pajaknya, serta mengirimkan bukti (resi) bahwa potongan pajak tadi sudah disetorkan ke kantor pajak. Maka pada SSP ditulis jumlah potongan pajak disertai nomor penyetoran pajaknya menurut resi yang dikirimkan pemberi royalty. Dengan penghasilan tiap bulan nihil, maka tiap tanggal muda saya harus mengirim SSP ke Kantor Pelayanan Pajak. Saya harus naik bemo pulang-pergi.
Sudah dapat NPWP, segera ke dua penerbit saya di Jakarta saya beritahu. Royalty biasanya dikirim 2 kali dalam setahun, yaitu Juli dan Desember. Sampai habis tahun 2008, saya tidak pernah lagi dapat royalty dari penerbit buku saya di Jakarta tadi. Oleh Kantor Pajak selain tetap membuat SSP, saya diharuskan membuat laporan tahunan penghasilan selama 2008. Untuk mengisi laporan tahunan 2008 itu saya bisa konsultasi dengan pegawai kantor pajak di lantai 3. Segera saya lakukan dengan mengisi formulir 1770 (I-IV) disetorkan ke kantor pajak.
Selanjutnya selama 2009, saya sama sekali tidak mendapatkan royalty dari penerbit buku saya. Jadi tiap bulan saya mengirim SSP (karena pendapatan nol maka setoran pajaknya NIHIL ditulis pada formulir SSP) ke kantor pajak. Akhir tahun 2009 saya mendapat surat teguran dari kantor pajak, bahwa laporan tahunan saya 2008 tidak akurat. Maka saya harus bayar Rp 100.000,00 segera. Saya pun datang ke Kantor Pajak untuk mengurusi pembayarannya. Konsultasi lagi dengan pegawai kantor pajak di lantai 3. Hasil konsultasi, saya harus membayar Rp 100.000,00, tapi tidak di kantor pajak, melainkan di kantor bank atau di kantor pos. Untuk tahun 2010 selanjutnya agar tidak terjadi teguran begitu lagi, saya dianjurkan membayar uang setoran pajak dari 15% perkiraan penghasilan saya tiap bulan dari royalty maupun penghasilan lain dari pengelolaan seni. Pada formulir SSP tidak lagi NIHIL, melainkan ada angka uangnya. Berapa? Terserah saya.Saya sanggup Rp 25.000,00 tiap bulan. Tidak. Disuruh Rp 40.000,00. Ya, saya setuju. Dan membayarnya (Rp 40.000,00) tidak di kantor pajak, melainkan di kantor pos atau bank. Selama tahun 2010 saya membuat SSP dengan setoran Rp 40.000,00 (tidak ditulis NIHIL lagi, tapi Rp 40.000,00) setoran SSP maupun uangnya ke Kantor Pos Rungkut, dekat rumah saya, jalan kaki tidak lelah. Untuk laporan tahunan 2010 saya harus menyertakan segala pendapatan saya dari penerbit (yang sama sekali tidak terima royalty), dan rekap penghasilan pensiun saya (saya minta ke Kantor PT Taspen). Untuk melaporkannya saya perlu konsultasi ke kantor pelayanan pajak, dan bagaimana caranya mengisi formulir 1770 (selain mengisi kotak-kotak pada formulir harus disertai lampiran-lampiran akurat dari instansi lain, misalnya rekap penghasilan pensiun dari PT Taspen, dan banyak lagi). Ternyata penghasilan saya hanya dari pensiun saja. Saya tunjukkan pula slip penerimaan uang hasil rapat seni sastra yang saya dapat tahun 2010 (saya ikut dipilih jadi panitia penyelenggaraan Kongres Bahasa Jawa V Provinsi Jawa Timur, tiap rapat dapat uang sidang), dan pada penerimaan uang sidang ada slipnya bahwa uang yang saya terima sudah dipotong PPh 21.
Dengan kenyataan laporan tahunan 2010 tadi (mengisi formulir 1770 disertai lampiran-lampirannya), pegawai pajak mengatakan untuk tahun 2011 saya tidak perlu setor pajak Rp 40.000,00 tiap bulan lagi. Jadi kembali laporan SSP tiap bulan ke kantor pajak dengan penghasilan NIHIL. Dan setoran pajak tiap bulan Rp 40.000,00 tahun 2010, bisa saya ambil kembali. Tentu saja dengan mengurusi administrasi yang rumit. Saya enggan mengurus (tidak saya ambil kembali).
Cerita pengalaman NPWP itu sebetulnya hanya untuk menyokong cerita Bu Hadi, bahwa penghasilan pengarang yang terkenal seperti NH Dhini yang bukunya diterbitkan oleh penerbit yang bonafit pun, tidak menjamin pendapat keuntungan finansial yang berlebihan. Meskipun saya tahu juga ada (tidak sedikit) yang sukses finansial karena mengarang prosa. Semua itu tentu saja juga menjadi cita-cita 7 pengarang cerpen buku MOZAIK INGATAN, karena itu mereka memerlukan bersatu menerbitkan buku. Menerbitkan buku begitu paling saya dukung untuk penulisan apa saja: prosa, sastra, sejarah, ilmu pengetahuan dan segala hal. Penerbitan buku setidaknya mengurangi masyarakat Indonesia terkungkung oleh tradisi kelisanan, dan mengubah menjadi masyarakat yang berkeaksaraan (Ayu Sutarto, Mulut Bersambut, 2009). Verba volant, scripta manent (kata-kata lisan terbang hilang, sementara tulisan menetap permanen).
*
Akhir diskusi ditutup dengan pemberian kenangan untuk para penanggap. Meskipun jumlah hadirin berkurang, ternyata para penanggap yang berjumlah 10 orang masih tetap berada di tempat, ketika para penanggap pada diberi doorprize. Pertanda bahwa mereka memang tertarik dan bersemangat menghadiri bedah buku ini. Dan ternyata mereka ada yang dari kelompok penggemar buku lain di luar kelompok Cak Die Rezim (kelompok penulis/penerbit buku MOZAIK INGATAN). Banyak yang minta berfoto bersama (juga dengan saya), dan juga minta tandatangan buku MOZAIK INGATAN yang baru dibelinya.
Sayang sampai tulisan ini saya tayangkan di sini, tidak ada yang mengirimkan foto hasil cepretan saat itu kepada saya, sehingga pada tulisan ini tidak ada gambaran kejadian tersebut.
Surabaya, 29 Juli 2011.