MENTALITAS KAWULA PADA MASA KOLONIAL DALAM GADIS TANGSI KARYA RADEN MAS SUPARTO BRATA
Zainuddin Hakim dan Ratun Untoro
(Peneliti Madya dan Tenaga Teknis Balai Bahasa Sulawesi Utara)
Abstract
The Lord and priyayi (read: kraton) perceived kawula as a wong cilik who did not have power authority, so they were selfdown, rude, and uneducated. The views of kraton about the kawula were very influnced on attitude and behavirious of kawula. The facts, it was approved on novels by nobilities (priyayi). Gadis Tangsi written by the novilities from Surakarta’s Kraton contented views and purposes of kawula that followed priyayi as one of effort to increase degree and dignity even civilitation. Yet, mental, purposes, and views of the kawula were constructed by writers as a priyayi.
Key words: servant, belonging to upper classes, mentality.
1. Pendahuluan
Secara implisit tulisan ini berbicara tentang hubungan antara kawula dengan kraton (bangsawan) pada masa kolonial. Kata kawula pada makalah ini berpasangan dengan penguasa (raja) dalam hubungan patron-klien. Apa yang dilakukan raja adalah dalam rangka menunjukkan kekuasaan dan perbedaannya dengan kawula seperti yang terlihat pada upacara-upacara adat yang dibuat serba mewah (upacara kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain). Raja dan priyayi (kraton) melihat kawula sebagai wong cilik yang tidak mempunyai simbol kekuasaan, dan karena itu mereka dianggap rendah, kasar, dan tidak terpelajar (Kuntowijoyo, 2004;9). Cara pandang kraton terhadap kawula tersebut sangat berpengaruh pada sikap dan tingkah laku kawula itu sendiri. Sebaliknya, Kawula memandang priyayi sebagai kelompok yang berstatus sosial tinggi yang tergambar melalui sikap dan tingkah laku tertentu, seperti cara berbicara dan cara menyembah. Cara ini menegaskan bagaimana kawula memandang dirinya sendiri. Di bawah sadar, kawula memperlakukan dirinya sebagai orang rendahan, kasar, bodoh, dan semacamnya. Namun, muncul kesadaran dan impian di kalangan mereka untuk menjadi pandai, kaya, dan jika perlu dapat berkuasa seperti halnya para priyayi. Kawula melihat bahwa apa yang diperbuat dan dimiliki oleh bangsawan kraton adalah baik, benar, dan patut dijadikan norma hidup yang pantas diidam-idamkan. Etiket hidup yang baik adalah yang sesuai dengan etiket hidup kraton.
Kuntowijoyo pernah melakukan penelitian mengenai hubungan antara raja, priyayi, dan kawula. Salah satu analisisnya mengenai mentalitas kawula. Mentalitas sendiri adalah hal-hal yang antara lain berhubungan dengan perasaan, impian, ilusi, citra kolektif, endapan ajaran-ajaran lama di kalangan rakyat, pandangan, sikap, dan perilaku (Kuntowijoyo,2004;xxiii). Mentalitas kawula berarti membicarakan bawah sadar mereka, menggambarkan perilaku otomatis masyarakat sebagai manifestasi dari bawah sadar itu.
Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana mental kawula dalam hubungannya dengan kraton seperti terlukis pada novel Gadis Tangsi karya Raden Mas Suparto Brata (atau lebih tepatnya bagaimana priyayi Suparto Brata menggambarkan mentel kawula). Apakah kawula mendukung, mengkritik, atau meniru penguasa.
Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Sumber datanya terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diangkat dari novel Gadis Tangsi karya Suparto Brata yang terbit di Jakarta tahun 2004 oleh Penerbit Buku Kompas. Sementara itu, data sekunder berupa kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan.
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi berbagai leterature yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dibarengi dengan teknik penjaringan data, misalnya teknik inventarisasi, baca-simak, dan pencatatan. Data yang diperoleh melalui penelitian diolah serta diuraikan dengan menggunakan pola penggambaran deskriptif.
2. Pembahasan.
2.1 Kolonial Kraton dan Pemerintah
Priyayi dan kawula memandang raja sebagai pemilik sah kerajaan melalui kepercayaan adanya wahyu sehingga raja mempunyai otoritas kuat dan dipercaya penuh oleh rakyat. Raja mempunyai wewenang pada rakyat berdasar hubungan kawula-Gusti (Kuntowijoyo, 2004;22). Oleh karena itu, penjajah memerlukan otoritas kraton untuk berhubungan dengan rakyat. Kraton menjadi mediator hubungan antara pemerintah kolonial dengan rakyat. Pada hal-hal tertentu Pemerintah Kolonial sama sekali tidak mampu menghalangi hubungan emosional antara kawula dengan raja. Ada dua hal menurut Residen Schneider yang membuat posisi residen di depan elite pribumi dan rakyat itu sulit, yaitu: tradisi dan ideologi panatagama (lihat: Kuntowijoyo, 2004;30-40). Hubungan emosional ini menyebabkan pemerintah kolonial merasa perlu menguasai kraton. Buku Kuntowijoyo (2004) memuat data tentang bagaimana pemerintah kolonial menguasai dan mengkonstruksi kraton (Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwana X). Belanda membawahi Kasunanan, meskipun Kasunanan tetap berkuasa atas perkara sipil dan sampai batas tertentu juga hukum (hal. 16). Selain itu, pemerintah kolonial juga turut mencampuri urusan rumah tangga kraton. Lemahnya kekuasaan Sunan juga terlihat pada sikap Sunan yang tak pernah (tak mampu?) menerapkan etiket Jawa yang kaku untuk orang Eropa meski di dalam lingkungan keraton (hal. 4). Sementara simbol-simbol menegaskan kedudukan Sunan sebagai raja, yaitu sebagai pusat dunia di mana makrokosmos dan mikrokosmos bertemu, tetapi secara faktual dan kontekstual dia berada di bawah Pemerintah Hindia-Belanda (hal. 44).
Kekuasaan Pemerintah kolonial tidak hanya sebatas pada masalah administrasi, tetapi juga menyangkut sikap dan tingkah laku raja dan priyayi. Pada abad kedua puluh terdapat kamus Subasita karya Padmasusastra yang berisi mengenai perilaku-perilaku santun yang pantas dilakukan seorang priyayi Jawa. Dalam pengantar buku itu, penulisnya mengatakan bahwa etiket Jawa yang berlaku waktu itu harus disesuaikan dengan budaya dominan panguasa, Belanda! (hal.52). Simbol orang yang berbudaya adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan etiket Barat antara lain ditunjukkan oleh Padmasusastra yang progresif. Pada waktu itu orang Jawa (serta Cina) mulai memotong rambut panjang mereka seperti orang Belanda (hal.52).
Data tersebut di atas menegaskan bahwa kekuasaan raja berikut tingkah laku, etiket dan kepribadian priyayi dan bangsawan kraton adalah semu. Mereka sebenarnya tidak mempunyai jati diri. Kekuasaan, gaya, dan sikap serta tingkah laku bangsawan kraton adalah kekuasaan, gaya, dan sikap serta tingkah laku Belanda. Apa yang dititahkan raja adalah apa yang dikatakan Belanda. Dengan demikian apa yang dipuja-puja kawula, apa yang diimpikan kawula adalah kekuasaan dan etiket hidup Belanda. Kawula yang merasa bodoh, rendah, dan kasar adalah hasil konstruksi dan wacana Belanda melalui kraton.
Panjabaran mengenai hubungan kawula ~ kraton dan kraton ~ Pemerintah Kolonial tersebut digunakan untuk melihat mentalitas kawula dalam novel Gadis Tangsi karya Suparto Brata. Bagaimana ia melihat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan para priyayi pribumi dan dengan Pemerintah Kolonial Belanda.
2.2 Tentang Pengarang
Suparto Brata masih mempunyai darah biru, keturunan kraton Solo bergelar Raden Mas. Anak pasangan Raden Ayu Jembawati Bratatenaya dan Raden Mas Suratman. Sejak kecil ibunya ikut buliknya, Gusti Bandara Raden Ayu Jayadiningrat di salah satu kraton pangeran kampung Gajahan, Solo. Seperti halnya putra pangeran lainnya, ibunya biasa bermain di dalam kraton dan menjalani kehidupan tatacara kraton. Suparto Brata sangat dekat dengan ibunya lebih-lebih ketika orangtuanya berpisah. Kehidupan ala kraton turut berkembang dalam jiwa Suparto Brata karena ibunya sering mengajaknya menemui saudara-saudaranya di Kraton Sala.
Keadaan ekonomi yang kekurangan membuat ibunya hidup berpindah-pindah, bahkan pernah menjadi pembantu rumah tangga di rumah Bupati Sragen. Hidup yang tidak menetap itu membuat Suparto Brata kecil sering bermain dengan anak-anak desa.
Dengan djemikian, sejak kecil Suparto Brata hidup dalam dua budaya yaitu budaya kraton (priyayi) ketika di rumah dan budaya kawula ketika bermain. Namun, karena ibunya masih teguh memegang adat budaya kraton, Suparto Brata lebih cenderung mengikuti budaya kraton (priyayi). Kebangsawanannya tetap mengalir dalam diri dan kepribadiannya, (selanjutnya lihat: “Srawungku Karo Sastra Jawa”, 2002).
Melihat latar belakang pengarang, seorang priyayi yang tahu persis tatacara kehidupan kraton sekaligus mengenal betul kehidupan kawula, penelitian ini akan melihat pengarang pada posisi itu.
Dalam novel Gadis Tangsi, Suparto Brata bercerita dari sudut pandang tokoh Teyi (kawula) dan Putri Parasi (priyayi). Kedua tokoh itu dicipta tidak lepas dari pengaruh budaya kraton yang mengalir dalam tubuh pengarang. Kutipan berikut menunjukkan keberpihakan pengarang terhadap sistem pemerintahan kraton melalui tokoh Teyi.
Masyarakat yang berperadaban tinggi itu ibarat butir-butir nasi yang berbentuk tumpeng atau kerucut, dengan raja berada di puncak. Tingkat kehidupan rakyat sesuai dengan harkat dan martabatnya, ketrampilannya, kepandaiannya, atau etos kerjanya ~ semakin ke bawah semakin banyak, tapi tetap membentuk tumpeng. Sedangkan masyarakat yang tidak punya raja, seperti kehidupan tangsi misalnya, digambarkan Teyi seperti butir-butir nasi basi yang berserakan di tanah, dikais-kais induk ayam untuk jadi makanan unggas itu dengan anak-anaknya. (GT, 2004;231).
2.3 Analisis Postkolonial
Analisis postkolonial ini meliputi aspek struktur naratif, aspek sikap dan perilaku kawula, aspek tata ruang, aspek tubuh atau rasial, dan lain-lain. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk melihat mentalitas kawula pada masa kolonial.
2.3.1 Struktur Naratif
Novel ini dituturkan dengan sudut pandang orang ketiga, pengarang atau penulis ada pada posisi mahatahu. Namun demikian, pengarang lebih mengutamakan perasaan Teyi (dan Putri Parasi khususnya bab II) sehingga seolah-olah pengarang berada pada pihak kedua tokoh tadi. Dengen demikian pengarang membatasi diri pada pengetahuan kedua tokoh itu. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka perhatian akan difokuskan pada perasaan kawula yang diwakili Teyi sekaligus gambaran tentang mental kawula pada umumnya. Keberpihakan pengarang kepada perasaan Teyi dapat dilihat pada kutipan-kutipan berikut.
“Teyiii! Anak perempuan jangan lari-lari begitu!” Raminem juga menegur. Perintah lagi! Sebel! Ih, simboknya ikut-ikutan Sudarmin! Kali ini Teyi tidak menghiraukan larangan itu. Ia berlari sambil membawa setandan pisang. (GT, 2004;19)
Keberpihakan pengarang pada perasaan Teyi juga terlihat saat pengarang ingin secara obyektif mengemukakan alasan dan pikiran Raminem yang baik. Pada baris berikutnya cerita dari sudut pandang Raminem tersebut dibantah oleh pikiran Teyi.
Raminem ganti berdagang pisang goreng karena, katanya, berjualan nasi bungkus sangat rebyek, rumit, banyak hal harus dikerjakan, tapi keuntungannya tidak seberapa. Apalagi nasi bungkus tidak tahan lama. Bila waktu sarapan orang tangsi sudah lewat, biasanya mereka tidak berselera lagi beli nasi.
Bohong! Ganti berjualan pisang goreng karena Teyi bisa membantu segalanya! Simboknya tidak mengizinkan dirinya mengasuh Tumpi sambil bermain-main dengan teman-temannya (GT, 2004;5).
Dengan cara demikian, pengarang menempatkan diri pada posisi Teyi. Namun, keberpihakan pengarang pada Teyi tidak menguatkan bahwa novel ini diceritakan dengan sudut pandang orang pertama taksertaan. Bab II novel ini bercerita tentang latar belakang kehidupan Putri Parasi tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan Teyi. Lagi pula ada bagian-bagian tertentu yang memuat perasaan Putri Parasi yang tidak diketahui Teyi.
Meskipun kecewa, Putri Parasi masih menaruh harapan besar bisa mendidik Teyi. Biarlah Teyi datang ke rumah loji sesuka hatinya dan sesempatnya seperti biasanya (GT, 2004;132).
Pembaca dapat merasakan bahwa pengarang lebih cenderung mengungkapkan pikiran dan perasaan Teyi. Cerita yang dituturkan dengan lebih mengutamakan sudut pandang Teyi ini dapat digunakan untuk melihat mentalis kawula dan hubungannya dengan priyayi kraton (dalam novel ini sekaligus dengan penjajah, Belanda). Bagaimana Teyi melihat diri dan sesamanya serta bagaimana Teyi melihat priyayi kraton dapat dilihat pada sikap dan perilakunya. Namun, harus pula diingat bahwa tokoh-tokoh dalam cerita baik kawula maupun priyayi adalah tokoh ciptaan pengarang yang masih berdarah kraton. Apa yang dirasakan Teyi dan Putri Parasi adalah perasaan hasil konstruksi priyayi kraton.
2.3.2 Sikap dan Perilaku Kawula
Pengarang seolah-olah menegaskan pandangan raja dan priyayi bahwa kawula adalah rendah, kasar, dan tidak terpelajar. Sebagai kawula, Teyi identik dengan umpatan kata-kata kasar, baik tatkala marah, kaget, maupun heran, misalnya: Trukbyangan (sebutan kasar alat kelamin wanita); Trukbyangane silit (sebutan kasar alat kelamin wanita dan dubur disebut sekaligus); Bajingan; Entutmu berut (kentut yang sangat bau); Ediiiaan, Trondolo kecut (nama hewan).
Dalam pengertian luas, umpatan dan makian Teyi tersebut menunjukkan bagaimana kehidupan di masyarakat bawah (kawula). Baik teman-teman sebaya maupun orang-orang tua sering mengucapkan kata-kata itu termasuk ibunya. Demikian halnya dengan teman-teman seusia Teyi. Meski demikian, sebenarnya Ibu Teyi, Raminem, melarang Teyi mengumpat.
“Heh, Teyiiii! Jaga mulutmu! Gadis jangan suka mengumpat! Mengumpat itu kotor! Jiwamu kotor! Jangan sekali-kali mengumpat dengan kata-kata kotor begitu. Berapa kali aku harus memperingatkan ucapanmu yang kotor itu, Teyii? (GT, 2004;86).
Kawula diidentikkan dengan hal-hal yang jorok dan tidak mengenakkan seperti kutipan berikut.
“Adduuuh, abab-mu (nafasmu) bau pete-jengkol!” seru Teyi sambil tertawa (GT, 2004;149).
Ya, simbok, ataupun bapaknya, biasa kencing di kaleng mentega itu sambil jongkok agar keluarnya terarah. Teyi kerap mendengar di malam hari bunyi air kencing masuk ke kaleng, srooong! Srooong, kalau kaleng mulai terisi, bunyinya berubah, srriiing! Srriing! Bila hampir penuh, bunyinya jadi lain lagi, sreeeng! Sreeeng! (GT,2004;3)
Perilaku rendah kawula juga digambarkan dengan kata-kata porno, pelacuran ataupun perselingkuhan. Sikap dan perilaku kawula tersebut oleh pengarang dibandingkan langsung dengan tata perilaku kehidupan kraton. Dalam cerita ini, tata perilaku kehidupan kraton semakin sempurna jika ditambah dengan ilmu pengetahuan dari Eropa. Hal itu digambarkan pengarang melalui sikap, perilaku, dan pikiran Putri Parasi.
Si cerdas Putri Parasi menolak mentah-mentah anjuran menikah itu. Alasannya, usianya belum lagi delapan belas tahun. Belajar dari nonik-nonik Belanda, ia berpendirian bahwa perempuan baru siap menikah setelah berusia dua puluh dua tahun. Menurut rerasan para nonik, perempuan yang melahirkan sebelum berusia dua puluh dua bisa membuat bayinya tidak sehat. Orang Jawa banyak yang dilahirkan oleh ibu-ibu muda sehingga kualitas manusianya tidak bagus. Berdasarkan menyelidikan Putri Parasi sendiri ternyata neneknya melahirkan ibundanya juga pada usia yang sangat muda. Sebagai putri bangsawan yang berpendidikan Belanda, Putri Parasi menyingkirkan dulu pengobatan dirinya dengan jalan menikah (GT, 2004;96).
Melalui perasaan Teyi, pengarang membandingkan langsung sikap dan perilaku kawula dengan priyayi kraton (yang hanya diwakili seorang abdi) yang jelas menunjukkan perbedaan mencolok.
Teyi terpesona mendengarkan cara bicara dan soal yang dibicarakan oleh Ninek Jidan. Bahasa Jawa, tetapi lain, lain lagu dan iramanya. Dan yang dibicarakan soal makanan, majikan asuhan, adat yang berbeda, putri bangsawan. Ah, seperti dongeng saja. Pakaian orang tua itu mengingatkan Teyi pada Mbokdhe Camik. Cuma sikapnya sangat beda. Mbokdhe Camik cekatan dan sombong, suaranya lantang, Ninek Jidan gerakannya lamban, ramah-tamah, suaranya lembut. Dengan suaranya yang lembut Ninek Jidan menuturkan kisahnya yang meluncur bak air terjun. (GT, 2004;112).
Teyi kerasan bergaul dekat dengan Putri Parasi dan Ninek Jidan karena ia seakan hidup di dunia lain, dunia impian yang jauh lebih baik daripada kehidupan di tangsi. Banyak hal baru yang didengar, dipelajari, dan dinikmati oleh Teyi (GT, 2004;123).
Novel ini mengemukakan kebaikan atau keunggulan adat istiadat dan tata perilaku bangsawan kraton baik diceritakan langsung maupun melalui tokoh-tokohnya. Pengarang yang masih keturunan kraton membuat oposisi sikap dan perilaku antara priyayi kraton dan kawula. Perilaku rendah, kasar, dan tak terpelajar kawula disandingkan dengan perilaku mahabaik para priyayi kraton yang telah ‘disempurnakan’ dengan etiket penjajah.
Oleh sebab itu, sikap dan perilaku kawula tersebut harus ‘dibenahi’ dan ‘dibenarkan’ menurut etiket kraton. Pembenahan perilaku kawula itu ditunjukkan dengan usaha keras Putri Parasi dalam mendidik Teyi agar bisa memakai etiket kraton. Namun, kerja keras Putri Parasi membenahi sikap dan perilaku Teyi tidak semudah yang dibayangkan. Kebaya pemberian Putri Parasi yang dikenakan Teyi tidak kuasa mengangkat derajat Teyi.
“Dasar anak tangsi! Anak kolong! Jangan begitu, Teyi! Orang menjadi cantik, menjadi ayu, bukan hanya karena pakaiannya, tetapi terlebih karena sikapnya. Karena tingkah lakunya. Meskipun kamu telah melepaskan baju tangsimu dan mengenakan baju bangsawan, tetap saja kau adalah gadis penjual pisang goreng yang mengitari tangsi!” Ninek Jidan ikut tertawa (GT, 2004;167).
Pada akhir cerita, derajat Teyi hanya bisa diangkat oleh bangsawan yang menikahinya. Kecerdasan, kecantikan, dan pendidikan ala kraton yang diterima Teyi si gadis tangsi tidak mampu mengangkat martabatnya. Dia tetap membutuhkan wahyu, benih dari pria bangsawan untuk mengangkat derajat dan martabatnya. Pernikahan dengan priyayi-lah yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya, jinunjung saking ngandhap, sinengkakaken ing ngaluhur. Itulah sebenarnya pengertian tentang tujuan hidup perempuan Jawa (hal. 319).
Pandangan kraton yang menganggap bahwa kawula adalah rendah, kasar, dan tak terpelajar sedangkan kraton adalah baik dan sempurna tidak hanya tertanam pada jiwa bangsawan kraton, tetapi juga pada kawula itu sendiri. Pandangan yang telah tertanam pada diri kawula tersebut mengakibatkan mereka ingin bisa hidup seperti bangsawan entah kekayaannya, kekuasaannya ataupun kehormatannya. Hidup layaknya seorang bangsawan adalah sebuah cita-cita bahkan mereka rela menjadi gundik atau munci.
“Goblok, kamu! Goblok kalau tidak mau! Ndara Tuan Kapten itu pangkatnya sama dengan orang Belanda. Derajatmu bisa naik tingkat jadi Ndara Nyonya. Itu kalau dimunci oleh orang Belanda. Kalau orang Jawa, ya… ya… Ndara Nganten. Terlalu rendah? Tidak apa. Yang penting, kalau kamu kenal laki-laki, maksudmu tubuhmu sering digerayangi oleh laki-laki, bisa cepat dewasa, buah dadamu cepat membesar…..! (GT, 2004;136).
Teman-teman Teyi banyak yang ingin dimunci oleh priyayi. Bagi mereka, dimunci bangsawan adalah mendapat wahyu untuk mengangkat derajat diri dan keturunannya. Hal tersebut juga terjadi di dalam kraton. Para abdi kraton banyak yang menginginkan wahyu keturunan bangsawan.
….para ndaramas, meskipun belum sunat, diajak berduaan oleh seorang abdi gadis perwara dan digerayangi dengan harapan mendapatkan wahyu, syukur-syukur bisa dijadikan selir karena hamil!” (GT, 2004;99).
Cerita tersebut tidak ditujukan untuk menunjukkan tindakan tercela/keburukan yang terjadi di lingkungan kraton melainkan semata-mata untuk menunjukkan tingginya derajat kebangsawanan kraton serta rendahnya kawula.
Selain dengan cara menikah dengan priyayi, kawula juga ingin seperti bangsawan atau setidaknya dapat bergaul dengannya. Tegur sapa seorang priyayi kepada kawula merupakan suatu kebanggaan. Dengan demikian, merupakan suatu keganjilan jika ada kawula yang secara terang-terangan melawan priyayi. Raminem, ibu Teyi, adalah satu-satunya tokoh yang digambarkan pengarang sebagai orang yang tidak tahu diri, tidak tahu sopan-santun karena berani menolak permintaan priyayi. Penolakan Raminem merupakan suatu keganjilan. Perbuatan Raminem itu dditolak oleh suaminya. Perdebatan dengan suaminya itu menunjukkan bahwa perbuatan Raminem itu tidak sopan dan tidak pantas dilakukan kawula terhadap priyayi.
“Kamu ini memang keterlaluan kok, Nem. Bicara sama Ndara Tuan Kapten seperti orang mengusir burung di sawah saja!” ujar Wongsodirjo sengit. (GT, 2009;127).
Akan halnya dengan sikap Ndara Tuan Kapten yang tidak marah bukan bertujuan untuk menunjukkan kekalahan seorang priyayi terhadap kawula, tetapi sebaliknya ingin menunjukkan bahwa sikap bangsawan adalah lemah lembut, tenang, dan besar hati. Itulah yang hendak ditekankan oleh pengarang yang juga seorang bangsawan.
Raminem adalah perempuan berhati keras. Cita-cita utamanya adalah menjadi kaya dengan cara bekerja keras tanpa harus bergantung kepada orang lain. Ia pun berani menolak Ndara Tuan Kapten. Kelakuan Raminem itu dicela oleh banyak orang termasuk suaminya sendiri.
Dalam novel ini Raminem adalah tokoh yang termarjinalisasi. Ia miskin, keras kepala, bodoh, tidak sopan, dan tidak tahu diri. Penolakannya terhadap Ndara Tuan Kapten Jawa dianggap suatu tindakan yang tidak tahu diuntung. Raminem yang termarjinalisasi tersebut dalam batas-batas tertentu bisa dijelaskan dengan pengetahuan negatifnya Gayatri Spivak (1985). Ada yang benar dengan sikap yang diambil Raminem. Ia adalah contoh orang yang tidak mau dikuasai, pekerja keras, tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, tidak mau nempil kamukten. Menurutnya, segala cita-cita hanya bisa diperoleh dengan usaha kerasnya sendiri.
Akan halnya hubungan kawula dengan orang-orang Belanda, dalam novel ini tersirat bahwa kedudukan Belanda di mata kawula lebih tinggi daripada bangsawan pribumi. Hal ini terkait dengan posisi politik yang menempatkan Belanda di atas kraton.
“Goblok, kamu! Goblok kalau tidak mau! Ndara Tuan Kapten itu pangkatnya sama dengtan orang Belanda. Derajatmu bisa naik tingkat jadi Ndara Nyonya. Itu kalau dimunci oleh orang Belanda. Kalau orang Jawa, ya… ya… Ndara Nganten. Terlalu rendah? Tidak apa….” (GT,2004;136).
Dapat bergaul dengan priyayi pribumi memang membanggakan, tetapi akan lebih bangga jika mampu berhubungan dengan orang-orang Belanda atau bahkan bersikap seperti orang Belanda.
Teyi dahulu selalu menghindari Kapten Sajubehi, tapi sekarang tidak lagi. Ia sudah terbiasa bergaul dengan Meneer Sarjubehi. Rasa malu, takut, atau rendah diri bila berbicara dengan Sarjubehi telah hilang. Dengan berbahasa Belanda Teyi`bisa bicara sambil menatap matanya, sama-sama berdiri dan tidak perlu membungkuk-bungkuk. Cara menghormat gaya Jawa tidak perlu dipakai ketika berbicara dalam bahasa Belanda, sekalipun Teyi tetap berbusana bak Putri Solo di rumah loji (GT, 2004;230).
2.3.3 Struktur Ruang
Cerita dalam novel ini terjadi pada ruang tempat tertentu. Ruang tempat terjadinya cerita ini adalah Surakarta dan Medan. Dalam lingkup yang lebih sempit, ruang tempat kejadiannya antara lain adalah tangsi militer Lorong Belawan, Kampung Landa, rumah loji, Kota Medan, toko, dan jalan-jalan.
Jarak antara Surakarta dan Medan secara geografis jauh bahkan berbeda pulau, yaitu Jawa dan Sumatera. Secara sosiologis kedua tempat itu mempunyai jarak budaya yang jauh pula yaitu Jawa dan Melayu. Namun, novel ini bercerita tentang penerapan kebudayaan Jawa (baca: kraton) di Medan meski hanya berlaku bagi orang Jawa yang berada di Medan. Hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan kraton bagi orang Jawa tidak memandang tempat. Budaya kraton berlaku bagi semua orang Jawa di manapun mereka berada. Ninek Jidan, pembantu Putri Parasi yang ikut ke Medan, merasa bahagia ketika bertemu dengan Teyi. Bahasa Jawa yang dipergunakan Teyi membuat Ninek Jidan merasa bertemu dengan ‘orang’. Nenek itu tidak jadi marah.
“Hee! Kamu bisa bahasa Jawa, ya? Kamu bukan gerombolan anak-anak pencuri mangga yang kemarin dulu?” (GT,2004;111).
Pertanyaan Ninek Jidan kepada Teyi tentang gerombolan anak-anak pencuri mangga mengandung ungkapan psikologis bahwa ia anak Jawa yang tentu tidak suka mencuri. Padahal kenyataannya Teyi adalah teman anak-anak pencuri mangga itu. Anggapan itu menyiratkan bahwa orang Jawa tidak mungkin jahat. Pikiran itu juga ada pada benak Teyi.
Nenek itu orang Jawa! Mengenakan kain dan kebaya! Tidak pakai rok. Bukan orang Belanda! Teyi tercengang, tapi sekaligus bersorak kegirangan dalam hati. Ia yakin bisa mendapatkan buah mangga muda dengan cara damai (GT,2004;111).
Pertemuan Ninek Jidan dan Teyi merupakan langkah awal bertemunya Putri Parasi dan Teyi. Perbedaan status sosial keduanya telah dinegosiasi oleh Ninek Jidan yang mampu mempertemukan kawula dan priyayi. Cerita berlanjut pada usaha Putri Parasi mengajarkan budaya kraton pada Teyi. Hal ini menegaskan bahwa budaya kraton tetap berlaku di tempat lain.
Untuk belajar budaya kraton Teyi harus bolak-balik antara rumah loji dan tangsi. Antara tangsi dan rumah loji yang terletak di Kampung Landa terdapat sekat berupa pagar kawat berduri. Pagar itu tidak semata-mata sebagai pembatas antara tangsi dan Kampung Landa melainkan mempunyai dimensi sosiologis. Kampung Landa adalah milik priyayi, milik orang beradab dan beretiket. Sedangkan tangsi adalah milik kawula yang rendah, kasar, dan bodoh. Tidak sembarang orang bisa menginjakkan kaki di halaman rumah loji.
Anak-anak pribumi paling-paling hanya bisa turut berteduh di bawah pohon mangga milik salah satu penghuni rumah loji yang kebetulan dahannya berada di luar pagar. Hal ini dapat diartikan betapa hebat kekuasaan priyayi terhadap kawula sehingga ranting pohon yang keluar dari pagar pun dapat dipergunakan kawula untuk berlindung. Tangsi adalah kebodohan dan kekasaran tempat orang-orang rendah. Teyi yang setiap hari menerobos kawat berduri untuk dapat bertemu dengan priyayi adalah penggambaran bagaimana susahnya seorang kawula yang akan bertemu priyayi atau bahkan ingin jadi priyayi. Teyi melakukan penerobosan dari ketidakberadaban menuju ke keberadaban. Untuk menjadi seorang priyayi, yang beradab, seseorang harus menempuh berbagai macam tahapan antara lain mempelajari adat istiadat, tata krama, dan punya bekal kepandaian. Hal itulah yang sedang digemblengkan Putri Parasi kepada Teyi. Modal kekayaan saja tidak akan sanggup mengangkat derajat kepriyayian seseorang. Pada suatu waktu Teyi pernah minggat ke kota Medan. Ia masuk ke sebuah toko mainan milik saudagar Jepun. Meskipun ia mempunyai uang cukup untuk membeli sebuah boneka Belanda, tetapi ia diusir oleh penjaga toko karena pakaian dan perilakunya tidak mriyayeni (hal.63). Namun, ketika Teyi kembali ke toko itu bersama Putri Parasi dan mengenakan pakaian priyayi, ia mendapat pelayanan yang baik sekali oleh pemilik toko. Toko milik orang Jepun itu adalah tempat orang beradab. Keadaan seperti inilah yang mendorong kawula ingin seperti priyayi, ingin beradab. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa kawula sendiri merasa dirinya tidak beradab.
Antara tangsi – Kampung Landa, tangsi – toko di Medan tidak hanya mempunyai jarak geografis, tetapi juga mengandung dimensi jarak sosiologis yang jauh. Jarak sosial itu dapat pula dilihat dari perabot rumah yang dimiliki priyayi dan kawula. Karena perbedaan itu, saat masuk rumah loji, Teyi merasa senang dan tentram atau lebih tepatnya takluk tak berdaya oleh kemegahan rumah loji. Takluknya seorang kawula oleh kemewahan rumah priyayi ini seperti takluknya harimau kumbang yang tertangkap.
Harimau kumbang terkenal buas, tetapi yang dilihat oleh Putri Parasi saat itu adalah harimau yang tidak berdaya, seperti Teyi sekarang ini. Buas dan liar, namun diam tak berdaya. Hanya saja ketidakberdayaan Teyi bukanlah oleh keperkasaan manusia, melainkan oleh pesona keindahan dan kebersihan rumah loji itu (GT,2004;119).
Gambaran itu sekaligus mengartikan bahwa meskipun aturan bangsawan Jawa tidak berlaku ketat, tapi seorang kawula tetap takluk pada hal lain seperti kekayaan yang dimiliki oleh priyayi.
2.3.4 Ras dan Tubuh
Ras merupakan salah satu persoalan yang sering diungkap dalam novel ini. Dalam setiap penyebutan atau identifikasi tokoh, ciri-ciri tubuh selalu diungkap. Jika diteliti lebih lanjut persoalan ras bisa menjadi dasar penentuan sikap. Teyi sering mengungkapkan kekaguman atau ketidaksukaannya terhadap bentuk tubuh seseorang. Secara umum bentuk tubuh dan warna kulit Belanda lebih disukai atau setidaknya mereka membandingkan kebagusan tubuh dengan tubuh Belanda. Seperti kutipan berikut.
Tidak bisa Teyi mengajak Suwarti pagi ini bermain-main. Lagi pula Teyi kurang suka bermain dengan Suwarti. Wajahnya jelek. Hidungnya penyek, dahinya nonong seperti angsa jantan. Entahlah mengapa Teyi enggan bermain dengan Suwarti. Teman-temannya yang lain juga demikian (GT,2004;6).
“O, iya! Ini tadi komandan baru, ya? Makanya aku kok seperti belum pernah lihat Ndara Tuan Kapten Jawa seperti itu. Kelihatannya gagah, ya! Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih seperti peranakan Belanda….” (GT,2004;35)
Perhatian pada tubuh ini tidak hanya pada orang, tetapi juga terhadap boneka. Boneka yang indah adalah yang mirip noni Belanda. Teyi, sebagai pribumi sangat tertarik dengan boneka Belanda, bukan sekedar karena ingin sebuah mainan boneka, tetapi lebih cenderung karena itu boneka Belanda.
Novel ini mengajak pembaca untuk memilih bentuk tubuh seperti Belanda atau setidaknya seperti priyayi yang mempunyai kebagusan seperti tubuh Belanda.
Melihat laki-laki itu berpakaian cara Belanda, meengenakan sepatu hitam mengkilap, Gusti Parasi menilai bahwa penolongnya tentulah bukan laki-laki awam, bukan orang kebanyakan (GT,2004;103).
Bentuk tubuh juga digunakan untuk menggambarkan kehebatan tokoh, bahkan untuk kuda. Kuda hebat yang digunakan untuk menarik kereta kraton adalah kuda yang didatangkan dari Australia bukan kuda lokal. Persoalan tubuh yang rasial ini tidak hanya berhenti pada sosok fisik seseorang melainkan merembet pada persoalan sosial dan kultural. Seperti kutipan berikut.
Nah, terompet pertama sudah berbunyi. Waktu bangun telah tiba. Itu bunyi terompet tiupan Landa Dawa. Begitu nyaring, iramanya teratur, halus, dan panjang. Landa Dawa memang jago meniup terompet. Berbeda dengan tiupan Sudarmin, misalnya, yang bunyinya terasa tersengal-sengal, patah-patah, dan seringkali hilang tiba-tiba…. Teyi lega dengan terdengarnya terompet itu. (GT, 2004;1).
Bentuk tubuh memang menjadi persoalan. Oleh karenanya (oleh pengarang), tokoh kawula yang hendak dijadikan priyayi diperhatikan betul bentuk tubuhnya. Tokoh Teyi dan Dumilah yang dijagokan akan menjadi sosok priyayi sejak awal diceritakan mempunyai tubuh yang memenuhi syarat. Dengan demikian bentuk tubuh turut mempengaruhi syarat-syarat kepriyayian. Namun, adakalanya kepriyayian yang telah disandang Teyi tidak sama persis dengan priyayi tulen. Tiruan Teyi (kawula) tidak pernah sempurna.
“Dasar gadis tangsi, gadis berbudaya anak kolong! Sudah digembleng selama tiga tahun oleh putri keraton masih saja kembali ke budaya asalmu kalau sedang bergairah,” sindir Ninek Jidan kepada Teyi suatu kali, seperti ketika Teyi mula-mula mengenakan kain dan kebaya ala putri keraton. (GT, 2004;373).
3. Simpulan
Pandangan umum novel ini adalah cerita tentang keunikan dan keunggulan budaya kraton berikut bentuk fisik tokoh-tokoh bangsawan kraton dibanding dengan budaya kawula. Hal itu diceritakan oleh pengarang yang juga seorang bangsawan kraton. Namun, kebaikan sikap, perilaku, dan adat istiadat bangsawan kraton tersebut berada di balik bayang-bayang sikap, watak dan perilaku kaum penjajah Belanda. Disadari atau tidak, pengarang yang juga seorang bangsawan secara tidak langsung telah turut menjajah sikap, watak dan perilaku kawula.
DAFTAR PUSTAKA
Brata, Suparto, 2002, “Srawungku Karo Sastra Jawa”. Kumpulan Makalah, belum diterbitkan.
Brata, Suparto, 2004. Gadis Tangsi, Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
Esten, Mursal, 1992. Tradisi dan Modernitas dalam sandiwara. (Disertasi). Jakarta; Internusa.
Junus, Umar, 1985, Resepsi Sastra, Sebuah Pengantar, Jakarta, PT.Gramedia.
Kuntowijoyo, 2004. Raja, Priyayi, dan Kawula; Surakarta, 1900-1915. Yogyakarta; Ombak.
Luxemburg, Jan van. 1987. Tentang Sastra (Terjemahan Achadiati Ikram), Jakarta; Intermasa.
Soemardjan, Selo. Dkk. 1984. Budaya Sastra, Jakarta; Penerbit CV Rajawali.
Sudjiman, Panuti, 1988. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta; Pustaka Jaya.
Dikutip dari; Jurnal SAWERIGADING, Bahasa, Sastra, dan Pengajaran.
Volume 15, Nomor 1, April 2009.
***
Komentar pengarang Gadis Tangsi (Suparto Brata):
Dari simpulan peneliti mengungkapkan: “Disadari atau tidak, pengarang yang juga seorang bangsawan secara tidak langsung telah turut menjajah sikap, watak dan perilaku kawula”. Disadari atau tidak, atau tidak teliti, peneliti tidak melihat bahwa yang menjajah sikap, watak, perilaku, kebodohan, ketidakberadapan kawula, adalah mereka tidak membaca buku dan hanya berbahasa tunggal. Teyi menjadi pandai, kuasa, mandiri, bukan hanya meniru kebudayaan bangsawan atau Belanda, melainkan (yang paling ditekankan oleh pengarang) Teyi belajar membudayakan membaca buku dan belajar bahasa asing (Belanda), dan dari situlah Teyi bisa hidup mengikuti zaman modern yang berlaku. Pembudayaan Teyi membaca buku telah mengatasi budaya bangsawan Jawa (priyayi) pada umumnya atau sama dengan budaya bangsa Belanda yang kolonialist. Itulah yang diperjuangkan pengarang (seorang bangsawan yang terlunta-lunta, ~ tidak pernah menikmati kekayaan bangsawan, kebudayaan bangsawan, maupun kekuasaan bangsawan, ~ tetapi untunglah berbudaya membaca buku dan menulis buku) hingga saat ini. Tanpa berbudaya membaca buku (dan syukur menulis buku) bangsa Indonesia pada zaman kolonial sampai abad 21 ini akan tetap menjadi KAWULA (bodoh, berperadaban kasar, miskin, primitip, did not have power authority, selfdown, rude, uneducated) dalam kehidupan zaman modern. Ditulisnya novel-novel seperti Gadis Tangsi oleh pengarang, selain untuk memperkaya pengetahuan tentang sejarah/sosial/budaya bangsa (terjajah) mengikuti zamannya (saya tulis sedekat mungkin dengan situasi sosial-budaya zaman terjadinya cerita menurut yang saya dengar dan baca), juga disertakan bagaimana sebaiknya bangsa Indonesia bangkit untuk tidak terus menjadi bangsa yang terjajah/kawula sepanjang zaman. Tidak teruuus berperan jadi KAWULA sejak zaman kolonial Belanda hingga zaman Reformasi, dan Global. Contohlah perjuangan Teyi “Gadis Tangsi” yang dihimpit kebodohan, kasar, tidak beradab, sebagai pihak kawula, tapi bisa melepaskan diri dari konstruksi kolonial yang merendahkan kawula. Teyi berhasil hidup mandiri, kaya ide dan berkuasa mendahului zamannya (kolonial). Hanya membaca (meneliti) buku Gadis Tangsi saja, cerita perjuangan Teyi belum berakhir. Jadi tidak benar dikatakan “akhir cerita derajat Teyi hanya bisa diangkat oleh bangsawan yang menikahinya” diteliti hanya pada buku Gadis Tangsi saja. Tengah cerita Teyi lebih menguasai kesulitan-kesulitan hidupnya karena kecerdasannya (tanpa mengandalkan budaya kratonnya). Akhir cerita, Teyi lebih berkuasa dari pada budaya kraton (priyayi) pada umumnya. Akhir cerita, Teyi dinikahi oleh bangsawan Surakarta Hadiningrat tidak sebagai kawula, melainkan sebagai seorang Ratu dari sebuah Kerajaan, Kerajaan Raminem. Apa kiatnya? Punya budaya membaca buku.

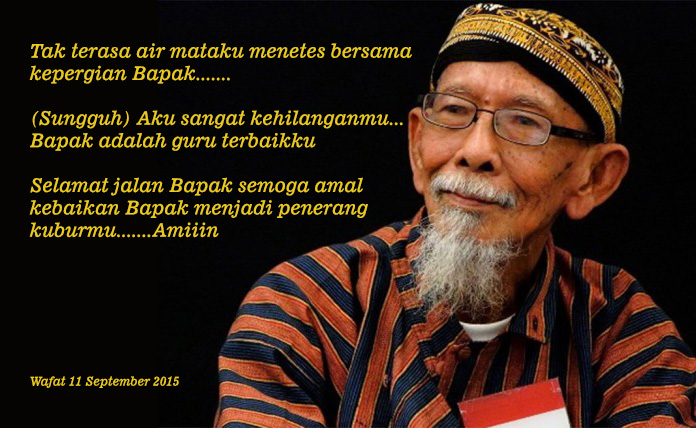































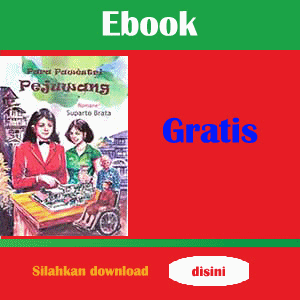
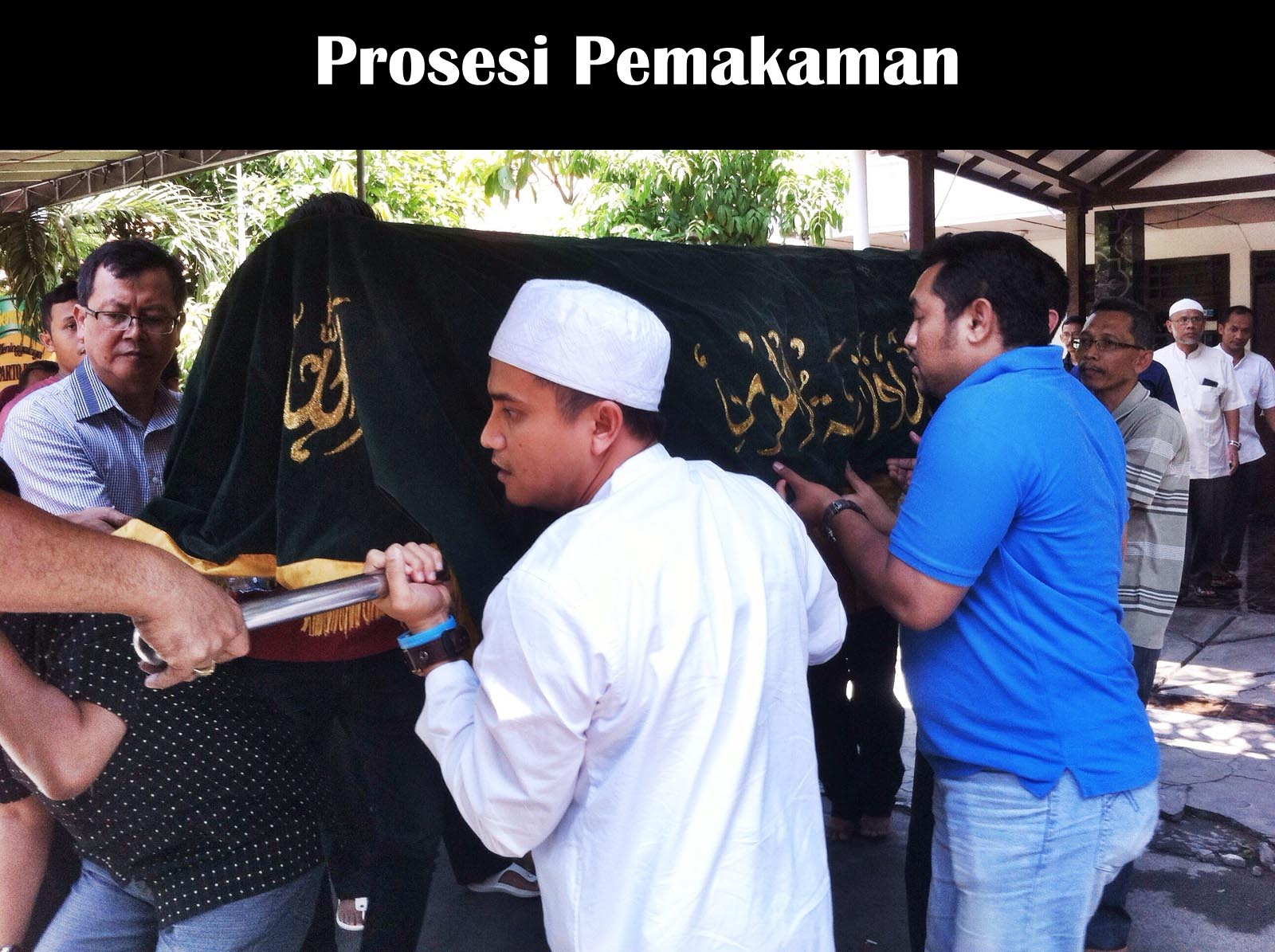


Yth. Bpk. Suparto Brata
di tempat
Dengan hormat,
Saya, Amin Sriyono, guru Bahasa Indonesia SMP/SMA Ciputra.
Dengan ini saya memberitahukan bahwa trilogi karya Bapak (Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem dan Mahligai di Ufuk Timur ) telah menjadi bacaan wajib di sekolah kami.
Kami mengagumi karya tersebut terutama unsur-unsur nasionalisme dan emansipasi wanitanya. Pada akhir bulan Oktober, kami merencanakan mengadakan Bulan Bahasa, salah satu acaranya adalah berdialog/berdiskusi dengan Bapak. Di samping untuk meningkatkan kemampuan apresiasi siswa, kami juga ingin belajar tentang nasionalisme.
Untuk itu jika Bapak tidak berkeberatan, saya ingin bertemu dan berbincang-bincang di rumah Bapak, merencanakan hal itu. Saya ada waktu pada hari Sabtu atau Minggu.
Namun demikian, supaya mudah koordinasi saya mohon informasi no HP atau no telepon rumah Bapak. Saya berharap Bapak tidak berkeberatan, bak gayung bersambut.
Demikian atas segala kebaikan dan pengertian Bapak, saya sampaikan terima kasih
Surabaya, 23 Juli 2009
Hormat saya,
Amin Sriyono
SMP/SMA Ciputra
Kawasan Puri Widya Kencana Surabaya