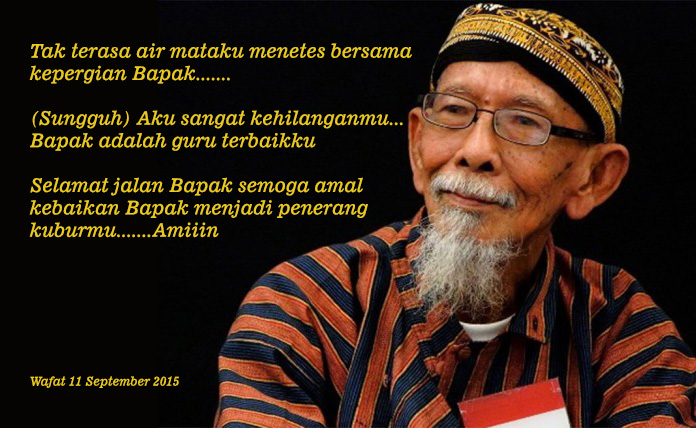LASKAR PELANGI DAN IHWAL FILM NASIONAL
Oleh Fahrudin Nasrulloh
Penggiat Majavanjava Cinema Club
Dan Komunitas Lembah Pring Jombang
Memperingati 10 November 1945 adalah mengenang pekik hidup-mati, geriung tank yang merangsek, dan simbahan getih di Jembatan Merah Surabaya. Ini lelayap bayangan saya kiranya, sebelum saya menyimak memoar Bung Tomo dalam bukunya 10 Nopember (Penerbit Balapan Jakarta, 1951). Tersebab itu, saya memburu berbulan-bulan film garapan Imam Tantowi yang berjudul Soerabaia 45: Hidup atau Mati! Susah memang, tapi akhirnya ketemu juga di rentalan film di depan GOR Jombang.
Film itu tidak bejibun aktor terkenal. Hanya beberapa, seperti Anneke Putri, S.Bono, Ade Irawan, dan Rudy Wowor. Selebihnya aktor-aktor anyar orbitan Imam Tantowi. Meski begitu, mantap aktingnya. Di film itu, Leo Kristi memerankan sebagai Bung Tomo yang berapi-api mengobarkan perlawanan arek-arek Suroboyo. Dukungan Gubernur Imam Soelarso pada era 90-an, sungguh sangat menentukan. Imam Tantowi juga menggarap skenarionya bersama Gatut Kusuma.
Film itu dibuka dengan kidungan ludruk yang ritmis: Gunung guntur segara kocak / ana lindu gede munclak / aja mundur cak pucuke tumbak / asal awakmu gelem bersatu.
Seketika saya teringat pada sajak karya Trinil berjudul “Getih Nang Treteg”: ‘Lo, gak iya tah? Treteg abang iku / Sing biyen kudanan getih / Nyekseni jaman / Nduk kono arek-arek / To-tohan nyawa.
Ternyata lanskap film itu tak kalah jika dibandingkan dengan film-film perang Hollywood. Cita rasa garapan Tantowi terbilang nyaris mencerminkan kecamuk psikologis arek-arek Suroboyo kala itu. Semisal, dialog sejumlah pejuang saat terpukul mundur oleh tank-tank Inggris: “Mundur, onok tank, onok tank!!” Pejuang lain malah bikin gojekan. “La po mondur, wong mek gudir ae wedi!!”
Ya, pejuang pertama merasa bedilnya tak mempan menghalau tank dan terdesak, sedangkan pejuang kedua hanya menganggap tank-tank itu tak lebih cuma gudir (kue agar-agar). Akhirnya pejuang ini nekad menghamburkan diri ke tengah lingkaran roda besi tank dengan bom molotov yang tergenggam di tangannya sambil memekik, “Allahu Akbar. Allahu Akbar!!”
Bung Tomo dalam buku yang ia tulis di Malang pada November 1951 tersebut coba melukiskan betapa gentingnya situasi arek-arek Suroboyo melawan arogansi tentara Sekutu. Kenang Bung Tomo: Karena Inggeris kemudian memastikan, bahwa penumpang mobil jang hangus-terbakar tersebut adalah Djenderal Brigadir Mallaby jang dibinasakan oleh rakjat Indonesia! Peristiwa itu lalu dinamakan “a new turn to the situation in Java”. Maka komandan angkatan perang Inggris di Indonesia, Djenderal Christison sendiri menamakan peristiwa tersebut sebagai foul murder, pembunuhan jang kejam. Ia berseru, bring the whole of sea, land and air forces and all the weapon of modern war against the Indonesians who committed these act.
Bung Tomo menyebut bahwa: Pertempuran jang dimulai tanggal 10 Nopember 1945 didahului dengan suatu ‘ultimatum’, suatu pernjataan terang2an jang merupakan tantangan terhadap rakjat Republik Indonesia. Untuk pertama kalinja dalam sejarahnja, Republik Indonesia menerima tantangan kekuasaan asing jang hendak melanggar kedaulatannja, dan untuk pertama kali pula Republik Indonesia melawan!
Laskar Pelangi.
Beranjak dari film tersebut, sutradara-sutradara di Indonesia kini masih belum tergerak untuk menggarap film-film perjuangan semacam. Memang belakangan kita layak berdecak kagum pada sineas-sineas muda seperti Riri Reza yang sukses mengangkat novel inspiratif Laskar Pelangi karya Andrea Hirata menjadi film fenomenal dengan judul yang sama. Sejumlah media cetak dan TV mengekspos besar-besaran pemutaran film bertema pendidikan itu. Dari sini, peleburan antara idealisme, modernisme, dan logika pasar telah menentukan sejauh mana arus budaya global secara tersamar membentuk atau memurukkan kepribadian bangsa. Mungkin spirit nasionalisme tidak sepenuhnya mengungkit yang lama dan adiluhung sebagaimana yang digarap oleh Imam Tantowi di atas. Nasionalisme dan pemaknaan heroisme, dalam konteks yang lebih luas, juga dapat kita temukan dalam tokoh-tokoh di Laskar Pelangi. Namun tema nasionalisme dalam film kita yang mengangkat tragedi perang dan para tokoh perjuangan tidak (dan belum) dilakukan oleh kalangan sineas sekarang.
Dalam ranah diskursif, sebuah novel dan film merupakan katalisator penting untuk menakar sejauh mana perkembangan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa, selalu sebagai budaya tanding (atau propaganda?). Banyak novel di sejumlah negara maju di Eropa yang diangkat ke dalam film. Contohnya War and Peace-nya Leo Tolstoy. Dengan judul yang sama, novel itu diangkat ke dalam sebuah film dalam beberapa kurun lampau. Sebelumnya, War and Peace, bahkan menjadi bacaan wajib di sekolah umum Rusia, karena mengangkat peristiwa momentum ihwal pergolakan politik di Rusia di awal abad 20-an.
Di tanah air, sejak masa kejayaan Usmar Ismail hingga sekian tahun kemudian, hanya beberapa gelintir film perjuangan yang digarap. Misalnya, November 1928 (Teguh Karya) atau Cut Nyak Dien (Eros Djarot). Selain itu, ada sederet film yang berdasarkan skenario keroyokan atau individu yang berdasarkan naskah dari cerita fiksi atau cerita rakyat atau cerita kuno atau babad seperti Jaka Sembung, Si Buta dari Gua Hantu, Fatahillah, Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara, atau yang terbaru dalam bentuk serial Laksamana Cheng Ho.
Di pengujung 2006, saya pernah membaca sebuah wawancara di Koran Tempo tentang seorang produser kenamaan Indonesia yang berupaya mengangkat novel tetralogi (Bumi Manusia, Rumah Kaca, Jejak Langkah dan Anak Semua Bangsa) karya Pramoedya Ananta Toer ke layar lebar. Baginya, ikhtiar itu adalah iimpian gila sekaligus kerja raksasa yang membutuhkan dana miliaran rupiah untuk mewujudkan. Kendati pernah ditawarkan kepada Ang Lee (yang tahun itu meraih penghargaan Piala Oscar sebagai sutradara terbaik) agar berkenan menyuteradarainya, entah mengapa sampai sekarang rencana besar iktu tak terdengar lagi kabarnya.
Sejak itu saya berharap besar (jika bukan berkhayal), bahwa kita juga memiliki warisan karya sastra yang bisa digarap secara serius oleh ssutradara-sutradara muda. Bertolak dari itu, kita bisa mengambil contoh sejumlah film manca yang digarap dengan cemerlang dan berbobot seperti Ben Hur, Helen of Troy, Spartacus, Nero, The Lion of the Desert, Lawrence of Arabia, Gladiator, Brave Heart, The Last Emperor, The Last Mohigan, Dawn Fall, Schandler’s List, The Passion of the Christ, atau Kingdom of Heaven.
Kiranya kita juga patut melongok sejenak pada Jepang yang memiliki sutradara tangguh semacam Akira Kurosawa yang memfilmkan novel Rashomon karya Yasunari Kawabata. Film besutannya yang lain adalah Ran, Kaghemusa, Mamadayo atau Dersu Uzala. Konon, menurut sebagian kritikus film dunia, film-film garapan Kurosawa telah mengilhami sejumlah sutradara Hollywood seperti David Lean, Sergio Leone, Steven Spielberg, Oliver Stone, Martin Scorsese atau Clint Eastwood dalam berkarya. Film-film mereka pun kerap mendulang pujian dan apresiasi yang prestisius di kancah penghargaan Piala Oscar.
Saat membayangkan kiprah Kurosawa, saya jadi balik bertanya: bagaimana kabar sederet novel bermutu kita bila disinggungkan dengan sejauh mana respons kreatif para sutradara mutakhir Indonesia terhadapnya?
Ketika film Daun di Atas Bantal-nya Garin Nugroho muncul pada 1997, sontak saya melonjak girang sosok baru sutrada film Indonesia telah lahir. Film-film karya Garin sebelumnya: Cinta dalam Sepotong Roti (1991), Surat Untuk Bidadari (1993), Bulan Tertusuk Ilalang (1995), Puisi Tak Terkuburkan (1999), Aku ingin menciummu Sekali Saja (2002), Rindu Kami Padamu (2005), dan terakhir Opera Jawa (2006). Saya curiga, apa motivasi dan gagasan mendasar Garin dalam menggarap tema-tema alternatif ihwal fenomena krisis sosial-budaya kekinian Indonesia selain film Puisi Tak Terkuburkan yang mengangkat pertarungan batin seorang penyair pada masa kolonial di Sumatera.
Ihwal lain yang cukup disayangkan adalah naskah skenario film karya Sjumandjaya berjudul Aku, yang bercerita tentang perjalanan kepenyairan Chairil Anwar di masa pergolakan kemerdekaan Indonesia yang tampaknya telah diniatkan untuk difilmkan, namun dengan sebab tertentu tak terselesaikan. Karya itu, menurut saya, wajib difilmkan, karena untuk mengetahui era perpuisian Indonesia modern. Chairil Anwarlah yang pertama harus disebut. Memang masih banyak tokoh lain dalam berbagai bidang yang layak digarap mulai Diponegoro, Raden Saleh, Tan Malaka, Soekarno, Affandi, H.B.Jassin, dll. Dalam hal ini kita bisa bercermin pada sejumlah film terkait semisal pada Byron (Lord Byron, penyair Inggris), Surviving Picasso (Pablo Picasso, pelukis Prancis), Patton (Jenderal Patton dari Amerika pada masa Perang Dunia I), A Beautiful Mind (tentang sosok John Nash, peraih Nobel di bidang matematika), dan sebagainya.
Tampaknya kini sutradara-sutradara Hollywood mulai melirik bahkan ada beberapa yang sudah menggarap film dengan mengacu pada setting Asia. Baik yang berdasarkan novel maupun catatan harian seperti film Anne Fank. Sejumlah film berlatar Asia telah dibesut oleh sutradara Hollywood seperti The Legend of Suriyothai dan Heaven and Earth (Oliver Stone), atau Memoirs of A Geisha (Rob Marshall).
Bertolak dari film Laskar Pelangi, alangkah menarik jika sutradara muda kita melirik untuk menggarap novel Kremil (Suparto Brata), Merahnya Merah (Iwan Simatupang), Surabaya (Idrus), Olenka (Budi Darma), Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari), Burung-burung Manyar (Y.B.Mangunwijaya), atau Arus Balik (Pramoedya Ananta Toer). Hal itu pantas dipikirkan para insan perfilman dan pemerintah, untuk merealisasikannya. Kapan lagi kita dapat mengapresiasi secara bermartabat khazanah sastra bangsa sendiri.
Menjamurnya sinetron-sinetron picisan, dan film-film horor tak bermutu yang sekedar berorientasi pada pasar justru menunjukkan indikasi dari rendah-lumpuh dan pudarnya jati diri bangsa dan kian terseretnya generasi muda dalam arus besar leviathan budaya modern. Karena itu, sepakat atau tidak, terasa hambar jika kita menggagas korelasi antara dunia novel dan film Indonesia sekarang. Sebab, televisi, keringnya kegelisahan kreatif, dan kemakmuran yang korup dan menggila, telah mengubur watak dan kemandirian bangsa ini.
*
Dikutip dari
Ruang BUDAYA, Jawa Pos, Minggu, 19 Oktober 2008.