WISATA PETJINAN SOERABAJA SUASANA RAMADHAN
 25 Juli 2012 Mbak Paulina Mayasari mengontak saya, Melantjong Petjinan Soerabaya bulan Ramadhan ini mau mengadakan wisata pecinan yang bersuasana Islam, yaitu ke Klentheng Mbah Ratu dan Masjid Cheng Hoo. Dan sekali gus wisata ke kompleks Ampel. Apakah saya mau ikut? Saya respon langsung saya mau ikut. Sebab saya memang belum pernah mengunjungi Makam Mbah Ratu, dan Masjid Cheng Hoo. Bahkan tentang Masjid Cheng Hoo ada di Surabaya, saya belum pernah dengar. Wisata mau diselenggarakan hari Minggu tanggal 29 Juli 2012, dimulai kumpul di Jalan Bibis 3 (rumahnya Mbak Maya) jam 13.30, dari sana nanti naik bemo yang disewa pergi ke Mbah Ratu, ke Ampel, dan berakhir di Masjid Cheng Hoo diperkirakan tepat pada jam buka puasa. Beaya untuk wisata ini Rp 110.000,00 sudah termasuk takjil dan makan berbuka puasa di Masjid Cheng Hoo. Saya langsung ikut didaftar jadi peserta. Namun saya ragu juga, berapa orang etnis Cina di Surabaya yang berperhatian terhadap suasana Islami Ramadhan ini? Saya kira tidak terlalu banyak. Dan karenanya sangat mungkin Wisata Petjinan Surabaya yang dikelola Mbak Paulina Mayasari ini tidak mencukupi korum. Maka saya sertakan direspon pendaftaran saya jadi peserta: “Kalau batal segera saya diberitahu”.
25 Juli 2012 Mbak Paulina Mayasari mengontak saya, Melantjong Petjinan Soerabaya bulan Ramadhan ini mau mengadakan wisata pecinan yang bersuasana Islam, yaitu ke Klentheng Mbah Ratu dan Masjid Cheng Hoo. Dan sekali gus wisata ke kompleks Ampel. Apakah saya mau ikut? Saya respon langsung saya mau ikut. Sebab saya memang belum pernah mengunjungi Makam Mbah Ratu, dan Masjid Cheng Hoo. Bahkan tentang Masjid Cheng Hoo ada di Surabaya, saya belum pernah dengar. Wisata mau diselenggarakan hari Minggu tanggal 29 Juli 2012, dimulai kumpul di Jalan Bibis 3 (rumahnya Mbak Maya) jam 13.30, dari sana nanti naik bemo yang disewa pergi ke Mbah Ratu, ke Ampel, dan berakhir di Masjid Cheng Hoo diperkirakan tepat pada jam buka puasa. Beaya untuk wisata ini Rp 110.000,00 sudah termasuk takjil dan makan berbuka puasa di Masjid Cheng Hoo. Saya langsung ikut didaftar jadi peserta. Namun saya ragu juga, berapa orang etnis Cina di Surabaya yang berperhatian terhadap suasana Islami Ramadhan ini? Saya kira tidak terlalu banyak. Dan karenanya sangat mungkin Wisata Petjinan Surabaya yang dikelola Mbak Paulina Mayasari ini tidak mencukupi korum. Maka saya sertakan direspon pendaftaran saya jadi peserta: “Kalau batal segera saya diberitahu”.
Ternyata tidak batal. Mbak Maya menelepon saya, kalau pergi ke Bibis 3 lebih jauh daripada Kampus Universitas Petra Siwalankerto, saya disuruh ke Kampus Siwalankerto saja.
Saya datang di Bibis 3 jam 13.00. Sepi. Hanya ada beberapa orang peserta, tidak lebih 7 orang. Tapi sudah ada Debby, Diana, Andy, Ivana, para “relawan” yang selalu membantu Mbak Maya pabila menyelenggarakan Melantjong Petjinan Soerabaya. Saya kenal mereka. Dan langsung menyelesaikan sebagai peserta, dapat kalung nama. Mbak Maya tidak ada. Ditunggu-tunggu sampai jam 14.00 tetap belum datang. Ternyata busnya macet di tengah kota. Mungkin karena hari Minggu, ada car-free-day. Tapi sudah jam 14.00, mestinya car-free-day sudah selesai.
Sementara itu di Bibis 3 ada Mas Gigik, kameraman JTV. Dia giat merekam kami yang ada di Bibis 3. Katanya di JTV ada program menelusuri kampung-kampung di Surabaya, maka moment Wisata Pecinan ini juga dijadikan bahan acara tadi. Saya juga di-shoot khusus. Selain mengenakan kaos Melantjong Petjinan, saya memakai destar (tutup kepala) Jawa tengah. Jelas beda dengan peserta lain.
Yang saya herankan, mengapa tidak disiapkan bemo-bemo (angkutan kota). Biasanya kami melancong diangkut beberapa bemo, sampai 10 bemo, saking banyaknya peserta. Ternyata sekarang angkutannya bus! Yang ikut langsung pergi ke Bibis 3 hanya sedikit, tapi yang dari Universitas Kristen Petra cukup banyak. Karena itu Mbak Maya memerlukan menjemput ke sana, dan menyewa bus pariwisata. Yang ikut adalah para mahasiswa UK.Petra berkebangsaan Jepang, Thailand, dan juga para dosennya.
Jam 14.30 bus masuk ke Jalan Bibis 3, kami semua segera masuk ke kendaraan. Juga sangu-sangu yang disiapkan diboyongi ke kendaraan. Lalu segera berangkat ke makam Mbah Ratu. Sementara di perjalanan, Mbak Maya menerangkan tujuan wisata yang pertama, yaitu makam Mbah Ratu. Menerangkannya dengan bahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin.
Untuk diabsen dan bahasa Mandarin tugas diserahkan kepada Diana, terutama untuk para mahasiswi dari Thailand. Jumlahnya mahasiswi Thailand 7 orang semua perempuan. Mereka itu belajar bahasa Tionghoa (Mandarin) di UK.Petra. Mereka tidak bisa bahasa Inggris, di bus saling bicara bahasa mereka sendiri, riuh tapi ya hanya dimengerti oleh mereka. Ketika Diana mengabsen dengan memanggil nama seorang mahasiswa Jepang terdengar seperti nama “Suzuki”, langsung para mahasiswi Thailand menyambung dengan riuh kata-kata, “Suzuki! Yamaha! Honda!”, sambil tertawa gelak-gelak. Ada ditambah 2 orang Indonesia mahasiswi UK.Petra yang belajar bahasa Tionghoa bergabung dengan mahasiswi dari Thailand tadi. Mahasiswi Indonesia ini yang seringkali menerangkan kepada para mahasiswi Thailand barang-barang asing yang ditemui di wisata ini. Misalnya ketika dibagikan jajanan dalam plastik, terdapat “kue tok” mahasiswi ini yang menerangkan kepada kelompok mahasiswi Thailand, apa nama jajanan itu. Cara mengucapkan “kue tok” terpaksa pelan dengan gerakan bibir dijelas-jelaskan, dan diulang dipertunjukkan kepada para mahasiswi yang duduk di sekelilingnya.
Mahasiswa dari Jepang jumlahnya 8 orang, semua laki-laki. Mereka mahasiswa ASP, belum bisa berbahasa Indonesia.
Dari UK.Petra juga ada 2 dosen wanita yang ikut wisata ini, yang seorang Bu Priskila (dari Jogya) mengajar akunting dan seorang lagi dosen bahasa Jepang ASP. Ada lagi seorang perempuan yang membawa anaknya masih kecil, juga membawa pembantu perempuan untuk menggendongnya. Nyonya ini juga belum fasih berbahasa Indonesia, menurut Mbak Maya dia gurunya Mbak Maya bahasa Mandarin. Baru 4 bulan di Surabaya.
Semula Mbak Maya dan pembantunya memang memang bergantian memberi penerangan kepada para peserta wisata dengan 3 bahasa tadi. Tetapi kemudian rata-rata mengerti bahasa Inggris, jadi lebih banyak digunakan bahasa Inggris.
Makam Mbah Ratu saya kenal sejak lama. Terletak di sisi barat Kota Surabaya, pojok Jalan Demak menatap jalan besar dari Gresik, merupakan makam lama terluas di daerah barat-laut Kota Surabaya. Kata Mbah Ratu saya kenal sebagai seorang yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam masa lalu. Tapi saya tidak pernah mengurus siapa Mbah Ratu tadi dalam cerita sejarah yang sebenarnya. Sebagai makam lama yang luas di Surabaya, saya pernah melayat keluarga saya dimakamkan di situ, yaitu Mbakyu Bagio, ibu Subodro, pesepak bola Persebaya terkenal 1990-an. Rumahnya dulu di Kantor Pos Perak, waktu meninggal dimakamkan di Makam Mbah Ratu situ. Meskipun nama Makam Mbah Ratu sudah sangat terkenal karena adanya rumah yang panjang di situ sebagai tempat makam khusus Mbah Ratu, tapi saya tidak tertarik untuk melihatnya. Ya sudah terkenal, dan saya kenal di situ ada makam Mbah Ratu yang bentuk makamnya panjang, begitu saja.
Namanya sudah terkenal sejak zaman dahulu, sekarang kok jadi tujuan wisata pecinan bernuansa Islami Ramadhan yang dikelola Mbak Mayasari, itulah maka saya antusias untuk ikut. Ingin tahu kisahnya siapakah sebenarnya Mbah Ratu?
Waktu naik taksi dari Rungkut ke Bibis tadi, tahu saya mau bersama rombongan pergi ke Makam Mbah Ratu, sopir taksi yang Arèk Surabaya, bahkan sudah tahu bahwa Makam Mbah Ratu itu juga disebut Klenteng Cheng Hoo. Dan punya nama lain Makam Sapujagad. Saya menjadi lebih penasaran. Karena memang tidak mengerti sejarahnya. Dan keadaannya sekarang, kok disebut Klentheng Cheng Hoo alias Makam Sapujagad, saya juga baru tahu sekarang.
Sampai di Makam Mbah Ratu, saya sudah tidak bisa menandai lagi bahwa kami sampai di Makam Mbah Ratu yang seperti dulu. Bus kami berhenti di tepi jalan persis di depan bangunan klentheng Cina, megah, dan dilengkapi ornamen-ornamen perklenthengan dengan banyak warna merah meriah. Itu terlihat dari pelataran depan, hingga bangunan emper depan dan seterusnya bangunan belakangnya. Penuh dengan ornamen klentheng pada umumnya, termasuk dominasi warna merahnya.
Di ruang emperan depan klentheng yang cukup luas, di sisi tembok kiri tertata meja panjang dengan kursi-kursi yang menghadapi meja. Di situ telah duduk banyak panitia penerima tamu klentheng, baik perempuan maupun laki-laki. Kedatangan rombongan kami tidak segera tampak berduyun masuk emperan, karena sejak di depan klentheng para rombongan sama antusias membuat foto-foto untuk kenangan sendiri-sendiri, hingga masuknya ke klentheng tidak berduyun-duyun. Para penerima tamu, melihat rombongan kami datang sudah pada ingin menyambutnya.
Ada dua orang yang paling giat menyambut kami. Seorang sudah tua, yang lain lebih muda. Suara yang tua sulit saya dengar, maka saya lebih mendekat pada yang muda. Dan dia dengan semangat bercerita kepada saya tentang bagaimana riwayat Cheng Hoo serta apa yang ditinggalkan di tempat itu. Cheng Hoo adalah seorang nakoda dari dinasti Ming di China, mendapat tugas dari Raja untuk berdagang mengelilingi dunia. Bukan untuk menjajah menguasai negeri di mana kapal-kapalnya mendarat seperti orang Eropa, tetapi lebih bersifat mencari persahabatan, pertukaran ilmu dan barang keperluan hidup, serta menggalang peradaban harmoni. Dalam menjalankan tugasnya Cheng Hoo sudah mengelilingi dunia 7 kali, singgah berbagai negeri. Pada suatu ketika pada tahun 1405, waktu sampai di Selat Madura, kebetulan ada perahu armadanya yang rusak, maka kapal yang rusak itu ditinggalkan di situ. Ya di tempat Mbah Ratu yang kemudian berkembang jadi daratan digunakan sebagai tanah makam, tanah makam yang paling tua dan luas di daerah Surabaya barat laut itu.
Bekas kayu kapal rusak itu sampai sekarang jadi salah satu barang tinggalan yang disimpan di klentheng itu. Sebagai buktinya saya ditunjuki sebatang kayu bekas kapalnya tadi, disimpan di belakang tempat persembahyangan. Sebatang kayu tadi disimpan pada suatu kotak atau lemari khusus yang amat panjang. Panjangnya 14 meter. Konon kayu tadi sejak dahulu kala tiap kali dipertunjukkan kepada para tamu yang berkunjung, banyak yang mencukil-cukil keroposannya, disimpan digunakan untuk jimat. Begitu banyak orang Jawa berbuat begitu, sebagai kepercayaannya. Tapi pengelola Klentheng Cheng Hoo atau Sapujagad, tidak melarang orang-orang yang berbuat dan kepercayaannya begitu. Cheng Hoo tidak mempermasalahkan kepercayaan masing-masing bangsa. Yang perlu persahabatan. Ketika armada Cheng Hoo berlabuh di Tanah Jawa, orang Jawa sudah punya kepercayaan (agama) yang kuat. Dan Cheng Hoo menghormati kepercayaan orang Jawa tadi. Maka silakan saja mengunjungi klentheng situ dengan menganut agama apa pun kepercayaannya. Silakan.
Saya tanya tentang nama Mbah Ratu, panitia muda itu menerangkan bahwa yang disebut Mbah Ratu itu dulunya sebenarnya juru kunci, orang yang menunggu makam yang ada tinggalannya kayu kapal rusak tadi. Setelah meninggal juru kunci tadi dikuburkan di tempat penyimpanan kayu tadi. Juru kunci itulah yang mendapat julukan nama Mbah Ratu. Maka kuburannya beserta penyimpanan kayu kapal itu jadi terkenal sebagai Makam Mbah Ratu. Sekarang kuburan Mbah Ratu sudah dipindah. Sedang tempat penyimpanan kayu bekas kapal rusak dibangunkan gedung jadi Klentheng Cheng Hoo tadi. Dikelola baik-baik.
Mendekati jam 16.00 rombongan Wisata Pecinan Surabaya menuju ke Kompleks Masjid Ampel. Dalam perjalanan ke sana, Mbak Maya dibantu para panitia menerangkan tujuan yang kedua wisata itu. Yaitu siapa Raden Rakhmat, dan bagaimana Masjid Ampel dan kompleks sekitarnya. Karena kompleks ini amat luas, dan dihubungkan dengan gang-gang yang sempit, tapi ramai sekali baik dipenuhi oleh orang berjualan sovenir, makanan khas Timur Tengah, serta para wisatawan domestik maupun luar negeri, dan juga wisatawan religius, maka rombongan diharap selalu memperhatikan gerak perjalanan para rombongannya. Jangan sampai terlepas tersendiri. Dan juga dijaga barang-barang bawaannya sendiri-sendiri. Dalam acara Wisata Pecinan ini juga akan mengunjungi tempat yang kaki harus telanjang. Kepada para cewek dianjurkan mengenakan kerudung. Dan nanti juga ada tempat di mana para perempuan yang sedang datang bulan, dilarang masuk. Maka pihak Mbak Maya sudah memberikan kantong plastik kepada para peserta, untuk tempat pembungkus sepatunya masing-masing.
Ampel. Daerah ini sudah saya kenal dengan sangat biasa sekali. Sebab, tahun 1950, ketika saya harus meneruskan sekolah di SMPN 2 Jalan Kepanjen 1 Surabaya, saya masih bisa dan boleh menginap di rumah Bulik Wibisono Gersikan gang 2 nomer 23 Surabaya. Di rumah itu dulu saya, kakak dan Ibu bertempat tinggal, karena Bulik Wibisono sekeluarganya mengungsi ke Madiun waktu perang 10 November 1945. Tapi tahun 1950 keluarga Bulik Wibisono sudah kembali ke rumah itu, jadi saya, kakak dan Ibu harus cari rumah tempat tinggal lain. Ibu ikut keluarga Dokter Subandi ke Tabanan Bali, Kakak dikirim studi ke Eindhoven Negeri Belanda, tinggal saya belum dapat tempat pondokan, masih boleh bertempat tinggal di Gersikan situ. Kamar-kamar yang kosong pada disewakan untuk kost, jadi kalau saya harus tetap di situ ya harus bayar kost. Saya masih sekolah SMP, jadi ya belum bisa bayar kost. Untuk meneruskan sekolah saja saya belum tahu membayar uang sekolah dengan apa. Jadi saya mohon pada Bulik, agar diperkenankan hanya bermalam saja di rumah situ sampai saya lulus dari sekolah SMP Jalan Kepanjen 1 Surabaya itu, yaitu ujian terakhir Agustus 1950. Sambil sekolah saya terpaksa harus cari makan sendiri. Mula-mula saya mengandalkan bisa menjual tulisan ke suratkabar, namun karena tidak punya mesin ketik, karangan-karangan saya tulis tangan, selalu dikembalikan oleh redaksi. Tidak bisa hidup dengan menulis karangan. Maka terpaksa cari pekerjaan lain, yaitu menjadi loper koran Java Post. Yang mengajak saya jadi loper koran teman sesekolah saya di SMPN 2 Jalan Kepanjen 1, yaitu Muslimin. Rumahnya di Setro. Dia ngampiri saya dulu ketika ambil koran di Kembang Jepun. Hasil loper koran itulah penghidupan saya antara Februari – September 1950, dengan kost (tanpa makan) gratis di Gersikan.
Tempat edar meloper koran saya di daerah Ampel. Tiap hari saya blusukan di gang-gang Kampung Ampel. gangnya sempit, tidak boleh naik sepeda, sepeda harus saya tuntun. Rumah-rumah di sana kebanyakan serambinya ditutup dengan keré, jadi orang di serambi depan rumah tidak kelihatan dari gang, tetapi yang di serambi bisa leluasa melihat orang yang lewat di gang. Meskipun begitu, saking seringnya melewati gang-gang itu untuk mengantar koran, saya tahu saja ada gadis-gadis di balik keré serambi depan rumah pada mengolok-olok atau menggoda saya. Dan akhirnya saya juga kenal sama beberapa gadis yang selalu bersembunyi di balik keré itu. Saya yang mengenal mereka atau mereka yang mengenali saya, begitulah. Ini terbukti ketika ada hari besar Sawalan di Surabaya. Dulu kala, tiap bulan Sawal, di pasar-pasar Surabaya, seperti Pasar Pacarkeling, Genteng, Blawuran, Peneleh, lebih-lebih Pabean, banyak dikunjungi muda-mudi dan anak-anak. Anak-anak laki-laki pada beli dan pakai barang mainan seperti pedang-pedangan, topeng-topengan, plembungan. Para pemuda biasanya topeng-topengannya dipakai, sehingga main colek gadis-gadis ya tidak ketahuan wajahnya. Para gadis juga senang berdesakan ke pasar Mulutan, biasanya yang dibeli manten-mantenan, tempattidur-tempattiduran. Nah, waktu pasar Sawalan saya ke Pasar Pabean, bertemu berdesak-desakan, berimpit-impitan sama gadis-gadis yang biasanya bersembunyi di balik keré serambi rumahnya. Saya tidak pakai topeng ataupun pakai topeng, mereka bisa saja panggil-panggil saya si loper koran Java Post. Kalau saya coleki, ada yang cemberut, tapi kalau mereka tidak sendiri lebih berani membalas menyemprot dengan kata-kata. Itulah gadis-gadis Ampel tahun 1950-an. Sekarang tradisi pasar Sawalan sudah hilang sama sekali di Surabaya.
Saya hafal benar gang-gang di kampung itu zaman itu. Saya bahkan sangat kenal dengan keluarga gang Ampel Kedjeron I nomer 20. Temanku di situ namanya Abdul Azis, kakinya pincang karena kena sasaran peluru pada zaman pertempuran 10 November 1945. Saya kenal dengan Abdul Azis di Probolinggo tahun 1945-1947, dia juga mengungsi di sana, dan satu sekolah dengan saya. Dia punya kakak namanya Soejoenoes, juga di Probolinggo jadi teman kakak. Tidak pada waktu mengantar koran, saya sering bermain di rumah Abdul Azis, karena keluarganya berlangganan majalah Mimbar Indonesia. Saya boleh pinjam saya bawa pulang majalah yang sudah kedaluwarsa. Di Mimbar Indonesia itulah (redaksinya HB.Jasin) saya belajar tentang sastra. Tidak bisa beli majalah, ya pinjam-pinjam, meskipun rumah saya di Gersikan, pinjamnya di Ampel Kedjeron. Saya lakoni.
Nah, sekarang saya ikut Wisata Petjinan Suasana Ramadhan kelolaan Mbak Mayasari. Jalan besar Nyamplungan yang melintas di Ampel sangat ramai sekali. Bus pariwisata berhenti di tepi jalan, para penumpang disuruh segera turun agar tidak mengganggu lalu-lintas kendaraan. Turun, yang menyambut para penjual makanan khas Timur Tengah. Penjualnya banyak, pembelinya banyak. Meskipun kini bulan Ramadhan, baru menjelang Asyar. Dan saya tidak tahu lagi bentuk gang-gang pada kampung Ampel ini. Mungkin saya tepat di mulut gang Ampel Kedjeron I gang rumahnya Abdul Azis dulu. Bentuknya sudah lain sekali. Rombongan wisata digiring masuk, serambi rumah di gang itu bukan lagi keré. Bukan lagi model serambi depan rumah yang menyembunyikan wajah-wajah ayu perawan Ampel. Melainkan toko, kios, rumah tertutup tapi juga berjualan benda-benda religius Islamis seperti kopiah, tasbeh, buku berbagai buku. Kian mendalami gang mendekati masjid, kios-kios berjualan keperluan riligius kian marak: baju muslim laki-laki maupun perempuan, sarung, mukena. Orang yang lalu-lalang juga luar biasa ramainya, bukan saja wajah dan berdandan Asia, tetapi juga berbondong wajah Eropa. Saya jadi tidak terlalu merasa asing dengan rombongan saya yang bermata sipit dan perempuannya tidak berjilbab.
Kami datang ke situ memang berwisata. Mbak Maya dengan pembantunya sudah semayan dengan salah seorang pemandu yang punya tempat dan bisa bercerita tentang kompleks serta sejarah Masjid Ampel. Kami temui Pak Sholeh, pak pemandu tadi, di tempatnya, sebelah sisi selatan Masjid Ampel. Dalam keramaian baik orang lalu-lalang maupun suara ceramah masjid, kami disuruh masuk ke suatu ruangan yang cukup luas, kaki harus telanjang. Pak Sholeh agak grogi melihat yang datang cukup banyak, 24 orang, sebagian baik yang laki maupun perempuan wajah orang asing. Dan disebutkan oleh Mbak Maya bahwa mereka itu dari Thailand, Jepang, Indonesia, banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia, maka ceritanya nanti diterjemahkan bahasa Inggris dan Mandarin. Tugas Pak Sholeh hanyalah bercerita tentang sejarah masjid dan para pendiri yang terlibat, dalam bahasa Indonesia. Nanti akan diterjemahkan oleh panitia. Tapi tetap saja, Pak Sholeh grogi, sehingga ceritanya tersendat-sendat. Dan hanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, baik oleh Mbak Maya, Mbak Diana maupun Mas Andy.
Pokok cerita, pembangun Masjid Ampel itu adalah Sunan Ampel, yang dalam bahasa Jawa disebut Raden Rakhmat. Raden Rakhmat adalah putera dari seorang Campa (Cambodia?), datang ke Tanah Jawa karena dipanggil oleh tantenya, untuk mengembangkan diri di Kerajaan Majapahit, sambil memberi pertolongan terhadap orang pribumi, memberi arahan peribadatan Islam. Tantenya itu sudah jadi isteri keluarga Kerajaan Majapahit. Raden Rakhmat beragama Islam, sedang keluarga Kerajaan Majapahit beragama Hindu-Budha. Waktu itu Kerajaan Majapahit sudah mendekati keruntuhannya dengan banyaknya perselisihan kepercayaan dalam negeri. Termasuk putera tantenya Raden Rakhmat yang ada di Demak. Tidak mau dengan kekerasan perang, Raden Rakhmat untuk mengembangkan kepercayaannya meminjam sebidang tanah bernama Denta di sebuah muara sungai kepada Raja Majapahit. Meminjam bahasa Jawanya ngampil, jadi tanah Denta adalah tanah ampilan, atau Ampel Denta. Di sini Raden Rakhmat membangun pemukiman muslim, di mana agama Islam dikembangkan syiarnya. Raden Rakhmat datang di Ampel Denta 1392. Kemudian mulai membangun Masjid Ampel tahun 1396.
Setelah memberi keterangan sejarah, Pak Sholeh memandu para wisatawan menuju ke makam Sunan Ampel. Letaknya di belakang bangunan masjid. Pada pintu masuk arena makam, para wisatawan harus melepas alas kakinya. Yang laki-laki masuk ke arena makam lewat sisi kiri, yang perempuan lewat sisi kanan. Karena ini merupakan rombongan wisata, maka dengan dipandu oleh Pak Sholeh kami laki-laki boleh masuk bersama rombongan lewat pintu sebelah kanan. Tempat ini sebenarnya lebih sempit daripada arena yang sisi laki-laki. Di kedua sisi arena makam Sunan Ampel waktu itu juga sedang banyak para penziarah yang sedang mengaji dan berdoa. Selain makam Sunan Ampel, di sekitarnya, termasuk yang kami injaki waktu itu, terdapat nisan-nisan tanda kuburan orang, yang tanpa tanda identitas. Dalam keterangannya Pak Sholeh salah satu dari makam di situ adalah sahabat yang membantu Raden Rakhmat membangun masjid, yaitu keluarga China marga Tjoa. Oleh karena itu hiasan dalam masjid tidak saja kaligrafi Timur Tengah, juga model oriental lainnya.
Selesai panduan Pak Sholeh, rombongan pamit keluar lingkungan masjid tidak lagi kembali melalui gang di depan masjid yang dilalui tadi, melainkan dari samping masjid sisi selatan langsung masuk gang yang menjurus ke selatan. Di sini sifat gang sudah berubah menjadi lorong dalam pasar. Bukan saja penuh orang buka toko pakaian, tetapi gangnya yang memanjang diberi atap atau payon, sehingga kami tidak lagi berada di bawah langit bebas. Rombongan berjalan berimpitan di lorong toko pakaian. Hal seperti ini sungguh tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, sebab setengah abad lebih yang lalu saya juga sering menelusuri gang-gang di sekitar Masjid Ampel waktu mengantarkan koran kepada para pelanggan, suasananya sangat terbuka bebas, saya menuntun sepedaku lewat gang-gang ini lancar saja dari arah Jalan Nyamplungan sebelah timur masjid menembus Jalan Haji Mas Mansyur sebelah barat masjid. Guru bahasa Mandarin Mbak Maya yang baru 4 bulan di Surabaya, berkata, “I never imagine that Surabaya likes this!”
Dengan sendat karena harus mengawasi keutuhan rombongan menempuh keramaian orang, kami meneruskan perjalanan keluar dari lingkungan masjid, mengarah kembali ke Jalan Nyamplungan, karena bus kami menunggu di sana. Sampai di Jalan Nyamplungan tempat kami turun dari bus tadi, kami masih harus berjalan berimpit-impitan lagi menuju ke terminal bemo, di mana bus kami parkir. Jalan Nyamplungan sudah berubah sama sekali. Dahulu sunyi, menelusuri Kali Pegirikan. Disebut Kali Pegirikan, sebab sisi sana dari Jalan Nyamplungan terdapat Jalan Pegirikan. Sekarang juga begitu, sementara rombongan kami bercampur juga dengan rombongan lain serta lintas pepat lintas kendaraan mengalir ke utara, tampak di seberang kali sana Jalan Pegirikan yang sepi luang, kendaraan melaju cepat ke arah ke selatan. Akhirnya kami juga menyeberang jembatan sempit ke Jalan Pegirikan, sampailah kami di tempat bus parkir.
Kami segera masuk ke kendaraan. Setelah lengkap diabsen, hari sudah mulai rembang petang, Mas Andy memberitahu rombongan bahwa kini kami akan menuju last destination, yaitu Masjid Cheng Hoo. Bus pun berjalan, langsung menempuh perjalanan dari ujung utara Jalan Pegirian tepi sungai lancar ke selatan. Menyeberangi perempatan Jalan Kapasan-Kembangjepun tetap langsung ke selatan mengikuti alir Kali Pegirikan, nama jalan ganti Jalan Gembong. Bus menyeberangi rel keretaapi dekat Stasiun Semut, tetap melaju mengikuti alir sungai, nama jalan berganti nama Jalan Pecindilan. Bus pun melewati Jalan Kalianyar, tetap melaju menyusuri tepi kali, nama jalan berganti Jalan Undaan Wetan. Menyeberangi Jalan Ambengan bus tetap melaju menelusuri jalan tepi sungai, namun sungainya kini menjadi lebih besar, dan itulah bagian dari sungai besar yang membelit Kota Surabaya, bernama Kalimas. Sedang nama jalan yang dilewati bus adalah Jalan Ngemplak.
Baru setelah di ujung selatan Jalan Ngemplak, di perempatan Jalan Walikota Mustajab-Jembatan Genteng Besar dan kalau mengikuti alir sungai nama jalannya Ketabangkali, maka bus baru membelok ke kiri, berpisah tidak menelusuri alir tepi kali lagi. Bus melewati Jalan Walikota Mustajab. Selanjutnya mengikuti arus lalu-lintas, belok ke kiri melewati Jalan Jaksa Agung Suprapto, terus lurus ke utara menyeberangi Jalan Ambengan lagi, tetap melaju lurus. Tadi dari utara (Undaan Wetan) sudah menyeberangi Jalan Ambengan, sekarang dari selatan (Jaksa Agung Suprapto) menyeberangi lagi Jalan Ambengan. Mengapa tadi tidak belok saja dari Undaan Wetan ke kiri lewat Jalan Ambengan? Karena Jalan Ambengan arus lalu-lintasnya satu jurusan ke barat saja.
Pada waktu itulah Mas Andy mengumumkan bahwa sekarang jam 17.30, para peserta wisata yang berpuasa waktunya berbuka puasa.
Di ujung utara Jalan Jaksa Agung Suprapto bus berjalan pelan, dibelokkan ke Jalan Gading. Di situlah letak Masjid Cheng Hoo. Terlalu sempit, dijaga oleh Satpam, bus pengunjung wisata masjid diharapkan mundur dan diparkir di tepi ujung utara Jalan Jaksa Agung Suprapto saja. Di situ para penumpang turun, dan diberitahu oleh panitia langsung menuju ke tempat Masjid Cheng Hoo, tapi jangan masuk ke wilayah masjid, melainkan ke tempat restoran atau warung di emperan masjid, kursinya sebanyak peserta wisata telah disediakan oleh panitia. Peserta wisata akan makan dulu di situ, sebelum melihat-lihat Masjid Cheng Hoo.
Meskipun keadaan sudah mulai gelap, saya masih kenal benar dengan suasana waktu ketika bus tadi berbelok masuk ke Jalan Gading. Setahu saya, di situ dulu tidak ada masjid. Kok sekarang ada masjid yang bernama Masjid Cheng Hoo, dan nama Cheng Hoo pastilah berhubungan dengan sejarah Laksamana Cheng Hoo yang kuna itu. Kok aneh ada masjid peninggalan zaman kuna di situ? Sungguh lebih membuat penasaran saya. Dulu di Gadingstraat itu tidak ada kok, masjidnya. Yang ada tanah lapang yang cukup luas, seperti biasanya cara orang Belanda membangun wilayah realestat, di antara deretan rumah-rumah gedung ada diberi lapangan kosong (tidak dibangun gedung di situ). Dan Gadingstraat juga terbangun di wilayah bangunan realestat Belanda. Artinya di wilayah sekitar situ sudah dibangun gedung-gedung gaya Belanda, bukan kampung tradisional Jawa lagi, tapi loji. Bahkan bukan saja gedung-gedungnya yang berupa loji bernuansa kolonial Belanda, nama jalannya pun sudah dikolonial-belandakan. Misalnya di wilayah situ ada nama jalan Ketoepastraat, Sroenistraat, Kemoeningstraat, Kembodjastraat, Patjarweg, Canalaan, Canaplein. Nama-nama apakah itu kok saya menyebutnya sudah “dikolonial-belandakan”? Ya, maksud saya sudah pada zaman kolonial Hindia Belanda, nama jalan di Surabaya sudah digolong-golongkan dengan nama-nama pahlawan Belanda (misalnya Coen Boulevard, Carpentierstraat, Julianalaan), nama-nama sungai di Hindia Belanda (misalnya Koeteistraat, Kapoeasstraat, Brantasstraat, Tjiliwoengstraat, Bogowontostraat), nama-nama pulau (misalnya Soematrastraat, Soembawastraat, Celebesstraat), nama-nama pohon berbuah (misalnya Tamarindelaan, Palmenlaan, Embong Gayam, Embong Kemiri, Kenariweg), nama-nama bunga-bungaan (misalnya Sedepmalemweg, Melatiweg, Kenikirweg, Canalaan, Canaplein). Nah, Gadingstraat termasuk golongan tanaman yang bunganya berbau, tapi tidak berbuah, misalnya Kemoeningstraat, Kembodjastraat. Lo, gading…..tanaman berbunga berbau apa? Itu sudah pernah menjadi gagasan saya waktu saya menemukan Gadingstraat di situ pada zaman Balatentara Dai Nippon menduduki Pulau Jawa, termasuk Surabaya. Waktu itu sekolah saya di Kokumin Gakkõ Canalaan 121 (Jalan Kusumabangsa 121), jadi juga berada di daerah Gadingstraat situ. Tiap pelajaran olah-raga, berdurasi 2 jam pelajaran, sudah dipastikan kami murid kelas IV, V, VI laki-laki pasti olah-raga kasti di lapangan Canaplein, tidak lain yang sekarang jadi Taman Makam Pahlawan Kusumabangsa. Dulu merupakan taman lapangan yang bernama Canaplein, di situ saya dan teman-teman main kasti (1943-1945). Gadingstraat tentu saja saya dan murid-murid Kokumin Gakkõ Canalaan tidak asing lagi dengan Gadingstraat, ditelusuri ketika kami punya tugas mengumpulkan biji buah jarak. Di tepi-tepi jalan daerah situ bermnya pasti ditumbuhi dan ditanami buah biji jarak. Tapi sungguh, di Gadingstraat tidak kami temukan bangunan masjid yang namanya berbau sejarah kuna Cheng Hoo. Tidak ada bangunan masjid tua di situ.
Memperhatikan nama-nama jalan yang tertulis rapi pada zaman Hindia Belanda, saya berpikir keras, mengapa di situ papan nama jalannya ditulis Gadingstraat. Hubungannya apa dengan penggolongan nama Kembodjastraat, Sroenistraat? Pikir punya pikir akhirnya ketemu juga. Yang dimaksud gading bukan gading gajah, melainkan bunga srigading. Bunga srigading pohonnya juga besar seperti kemuning, bunganya putih-putih dengan tangkai bunganya warna oranye atau kuning kunyit, kalau dipandang bunganya cukup indah, dan baunya menyengat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa bau kembang srigading harum, sebab baunya yang menyengat saya tidak suka menciumnya.
Agaknya Belanda kurang teliti memberikan nama Gadingstraat tidak disempurnakan sebagai Srigadingstraat. Sebab pada zaman itu, di Surabaya sudah ada kampung lama yang juga bernama Gading. Yang sampai sekarang pun namanya juga kampung Gading, yaitu nama kampung tradisional dekat Kedungcowek.
Kami digiring masuk ke Jalan Gading, dan setelah melalui penjagaan satpam yang juga tempat parkir kendaraan, sampailah kami pada bangunan kompleks, yang pastinya itu kompleks Masjid Cheng Hoo! Betul dugaanku. Itu bukan bangunan masjid kuna! Di situ dulu bukan berupa kompleks masjid, melainkan tanah lapang yang cukup luas. Saya masih ingat benar!
Saya berbuka puasa di restoran di serambi bangunan Masjid Cheng Hoo. Masih bersama para peserta wisata Pecinan. Setelah makan buka, saya minta kepada Mbak Maya, di mana jalannya ke masjid, saya mau sholat Magherip. Letaknya di balik bangunan restoran yang juga jadi bangunan tempat kantor Masjid Cheng Hoo. Selesai sholat, saya kembali menemui para peserta wisata. Dan setelah mereka selesai makan hidangan yang disediakan oleh pelayan restoran atas pesanan panitia, mereka pun diajak menuju ke balik bangunan kantor dan restoran masjid tadi. Mbak Maya menghubungi penjaga atau takmir masjid, yang sudah dipesan untuk menerangkan tentang sejarah Masjid Cheng Hoo. Waktu itu keadaannya ramai sekali, ada kelompok yang sedang pendarasan, pengajian, mendengarkan penerangan panduan, ada yang sholat. Mereka tersebar di segala tempat, ada yang di dalam masjid, di serambi, di halaman depan masjid yang luas. Malam terang cuaca, masjid dan halamannya juga didterangi oleh lampu yang menyala terang. Rombongan kami tidak sendirian. Meskipun tidak seramai seperti di gang-gang Masjid Ampel tadi, namun kelompok-kelompok yang ada di sekitar Masjid Cheng Hoo kelihatan lebih khusuk beritual keagamaan daripada hanya sekedar berwisata. Tidak ada penjualan barang-barang sovenir keagamaan seperti di Masjid Ampel.
Selain kami menerima penerangan dari pemandu yang telah dipesan oleh Mbak Maya, kami juga menerima booklet yang menceritakan rinci soal Masjid Cheng Hoo ini. Berikut saya kutipkan dari buku yang kami terima.
Orang Tionghoa masuk Islam bukan merupakan hal yang luar biasa, tetapi merupakan hal yang biasa karena pada 600 tahun yang lalu, terdapat seorang Laksamana beragama Islam yang taat bernama Muhammad Cheng Hoo dan beliau telah turut mensyi’arkan agama Islam di Tanah Indonesia pada jaman itu.
Beliau adalah utusan Raja Dinasti Ming yang menjalani kunjungan ke Asia sebagai “Utusan/Duta Perdamaian”. Sebagai seorang bahariawan dan Laksamana, Muhammad Cheng Hoo berhasil mengelilingi dunia selama 7 kali berturut-turut dan menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara yang dikunjunginya termasuk di antaranya adalah bersilaturahmi mengunjungi Kerajaan Majapahit untuk menjalin hubungan perdagangan. Barang-barang yang dibawanya adalah sutra, keramik, obat-obatan dan teh, oleh sejarah perjalanan ini dikenal sebagai Perjalanan/Perdagangan Sutera.
Guna mempererat hubungan dengan Kerajaan Majapahit, diberikanlah Puteri Campa untuk dipersunting oleh Raja Majapahit. Keturunan Puteri Campa pertama adalah Raden Patah, kemudian Sunan Ampel dan Sunan Giri (termasuk 9 Sunan atau Wali Songo) yang kemudian melakukan syi’ar agama Islam di Tanah Jawa.
Dalam pelayaran Muhibah yang dilakukan oleh Muhammad Cheng Hoo dapatlah diambil pelajaran oleh para penerusnya, bahwa seluruh umat hendaklah bersatu mempererat tali silaturrohim, saling menghormati sesama umat agama, tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan hidup rukun serta damai antarsesama umat (QS.Al-Imron; 112).
“dhuribat alaihimudzdzillatu aina maa tsuqifuu illa bihablimminallah wa hablimminannas”
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (QS.Ali-Imron; 112).
They are covered by humiliation anywhere, unless when they hold to Allah (religion) and (agreement) with men (QS.Ali-Imron; 112).
Sampai sekarang Cheng Hoo dijuluki sebagai ‘San Pau Ta Ren/San Poo Tua Lang’, semua ini karena sifatnya yang sholeh, taat beragama, tidak membeda-bedakan orang lain dan agama. Di manapun Cheng Hoo berlabuh tidak pernah menjajah Negara-negara yang dikunjunginya meski armada beliau dibekali dengan perlengkapan senjata lengkap, bahkan Cheng Hoo banyak membantu kaum miskin dan duafa tanpa memandang suku, agama dan harta. Atas dasar tersebut, banyak yang memberikan penghormatan kepada Cheng Hoo berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing hingga sekarang, terutama mereka yang beragama Budha dan Tao.
Begitulah cerita tentang Laksamana Muhammad Cheng Hoo sebagai utusan Raja Dinasti Ming (dari Tiongkok) sekaligus sebagai pensyi’ar agama Islam di Indonesia.
Tentang bangunan masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia di Jalan Gading, kisahnya begini:
Atas gagasan dari HMY Bambang Sujanto dan teman-teman PITI (Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), pembangunan Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia dimulai dari tanggal 15 Oktober 2001, diawali dengan upacara peletakan batu pertama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh Tionghoa Surabaya antara lain: Liem Ou Yen (Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya), Bintoro Tanjung (Presiden Komisaris PT.Gudang Garam Tbk), Henry J.Gunawan (Direktur PT.Surya Inti Permata Tbk) dan Bengky Irawan (Ketua Makatin Jawa Timur), serta puluhan pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
Seluruh tokoh masyarakat Jawa Timur yang turut hadir di antaranya: HRP.Moch.Noer dan Mayjend. Pol (Purn) Drs.H.Sumarsono,SH,MBA. Sedangkan dari jajaran pengurus PITI dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia sendiri hadir: HM Trisno Adi Tantiono (Ketua DPP PITI), H.Moch.Gozali (Ketua Korwil PITI Jawa Timur), HMY Bambang Sujanto (Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia).
Selesainya tahap pertama pembangunan Masjid ini pada tanggal 13 Oktober 2002, maka dilakukanlah peresmian pembangunan masjid (soft opening). Dengan selesainya tahap pertama ini, Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia sudah dapat digunakan untuk beribadah dan selanjutnya tinggal melakukan beberapa penyempurnaan bangunan masjid. Oleh seluruh anggota Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia dan PITI disepakati tanggal tersebut sebagai hari ulang tahun Yayasan dan Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia.
Jadi, betul dugaan saya sejak semula. Di Jalan Gading Surabaya di seberang Taman Makam Pahlawan Surabaya Kusumabangsa, dulunya tidak ada bangunan masjid peninggalan sejarah zaman dahulu kala. Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia yang nama Cheng Hoo-nya membayangi bahwa itu nama tokoh sejarah zaman dulu, mestinya mesjidnya juga peninggalan zaman itu, memang tidak benar. Karena bangunan masjid tadi ternyata baru dibangun dan diresmikan tahun 2002. Sebagai orang yang berumur panjang dan ingin tahu sejarah serta menulis pengalaman hidup saya, terjawablah teka-teki yang hinggap di pikiran saya mengenai Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia, yang membuat saya antusias untuk mengikuti ajakan Mbak Paulina Mayasari melakukan Wisata Petjinan Surabaja Suasana Ramadhan 1432 H (2012). Sejarah terus berlangsung, kalau tidak saya tulis, generasi masa depan tidak akan tahu ceritanya. Sejarah bukanlah hanya cerita masa lalu, tetapi juga cerita masa kini untuk digunakan membangun masa depan yang lebih baik, jangan sampai kembali melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu yang membuat masa depan semrawut. Sejarah adalah remembering the past, understanding the present, and preparing the future.
Dengan demikian, saya akhiri tulisan ini. Semoga bermanfaat. Surabaya, 10 Agustus 2012.

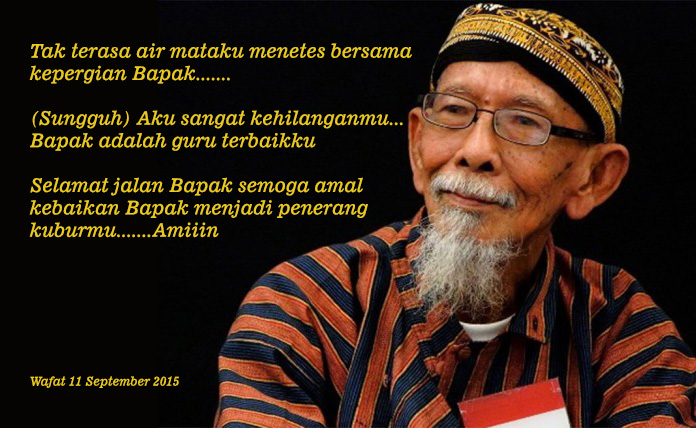



































perjalanan lintas waktu, luar biasa, ditulis dengan indah , membuat saya teringat masa masa 24 tahun hidup di Surabaya