MENCARI SARANG ANGIN
Oleh: Yulitin Sungkowati
Latar Belakang
Mencari Sarang Angin (MSA) karya Suparto Brata ditulis pertama kali pada tanggal 17 Januari – 26 April 1991 dan telah terbit di Jawa Pos sebagai cerita bersambung pada tanggal 23 Oktober – 27 Desember 1991. Sebelum diterbitkan dalam bentuk buku oleh Grasindo pada tahun 2005, MSA telah diubah kembali pada tanggal 17 Januari – 26 April 2004. Novel ini hampir mewakili semua ciri novel Suparto Brata yang banyak dikenal orang selama ini, seperti menceritakan kehidupan bangsawan Surakarta, mewakili tiga zaman (zaman Belanda, zaman Revolusi, dan zaman kemerdekaan/G30S/PKI), berlatar Surabaya dan Surakarta, menyajikan relasi priyayi dan wong cilik, priyayi sentris, serta mengandung unsur detektif. Di samping itu, novel ini memperlihatkan ciri yang kental sebagai kisah perjalanan model Jawa, seperti Ngulandara. Unsur yang dapat dikatakan “baru” adalah tokoh utamanya yang berperan sebagai jurnalis dan mengisahkan “sejarah” kehidupan pers di
Surabaya.
Di samping sejarah kota, sejarah pers, kehidupan sosial budaya masyarakat Surabaya, novel ini juga menarik dilihat dari ambivalensi-ambivalensi dalam kaitannya dengan usaha peniruan atau mimikri yang dilakukan bangsa terjajah terhadap bangsa penjajah, Belanda. Dengan adanya ciri kisah perjalanan, dari segi bentuk, novel ini juga sudah menunjukkan sebuah peniruan atau mimikri terhadap kisah perjalanan model Barat.
Persoalan menarik lainnya adalah munculnya gagasan yang dibawa oleh protagonis Darwan ketika menetapkan diri memilih profesi sebagai penulis, yaitu ingin turut menyongsong rekonstruksi masyarakat Jawa modern. Persoalan ini menyiratkan adanya upaya mencari identitas “baru” dengan jalan mimikri terhadap budaya dominan kolonial Belanda yang terepresentasikan dalam tokoh Darwan. Dalam usaha menunjukkan dirinya itu, Darwan selalu menjadikan Belanda sebagai referensinya sehingga ia pun mencoba melakukan peniruan, baik dalam
gaya hidup maupun cara berpikir. Akan tetapi, sebagai bangsawan Jawa, ia juga tidak dapat melepaskan begitu saja kebangsawanannya sehingga muncul ambivalensi dalam upaya peniruannya itu. Persoalan ambivalensi itulah yang menarik untuk dibicarakan karena tidak hanya tampak pada tokoh Darwan, tetapi juga dalam struktur naratif, ruang, dan waktu. Persoalan ambivalensi ini belum banyak dibicarakan sehingga masih pada dibahas untuk melihat relasi penjajah-terjajah dan memperluas serta memperkaya kajian terhadap karya-karya Suparto Brata. Pembicaraan terhadap karya-karya Suparto Brata selama ini masih terbatas pada pengungkapan alur detektif dan spirit feminis yang terpancar di dalamnya.Kerangka Teori
Ambivalensi merupakan sikap mendua yang dalam wacana pasca-kolonial dipahami sebagai konsekuensi adanya usaha peniruan yang dilakukan oleh bangsa terjajah terhadap bangsa penjajah. Peniruan atau mimikri muncul karena keinginan bangsa terjajah untuk meningkatkan martabatnya agar sejajar dengan bangsa penjajah (Faruk, 2001;75) akibat kolonialisme yang tidak hanya menempatkan tanah jajahan sebagai wilayah yang darinya dapat dieksploitasi sumber-sumber ekonomi, tetapi juga sebagai dunia asing yang berbeda dengan budaya si penjajah dan perbedaan itu tidak dipahami sebagai perbedaan yang netral, horisontal, melainkan hierarkis, vertikal sebagai bangsa terjajah ditempatkan sebagai bangsa yang inferior berhadapan dengan bangsa penjajah yang menempatkan diri sebagai yang superior (Faruk, 2001; 73-74). Kolonialisme Belanda di Indonesia juga disertai serangkaian representasi mengenainya. Oleh karena itu, supremasi Belanda sebagai penjajah tertanam kuat dalam kekuasaan sosial dan psikologis penduduk jajahan, seperti dalam kemampuannya menciptakan mentalitas dan cara berpikir bahwa orang-orang kulit putih adalah yang paling benar, whiteness is rightness, dan panutan bagi orang-orang kulit berwarna. Terhadap dominasi kolonial itu, bangsa terjajah tidak tinggal diam, tetapi melakukan perlawanan meskipun tidak selalu dalam bentuk penegasan identitas nasional sekaligus karena problem pertama masyarakat terjajah dalam menghadapi wacana penjajah sesungguhnya adalah problem emansipasi atau peningkatan martabat diri agar setara dengan bangsa penjajah. Emansipasi itu ditempuh melalui cara peniruan yang ambivalen karena di situ pihak membangun identitas atau persamaan, tetapi di lain pihak mempertahankan perbedaan (Faruk, 2001; 73-75).
Peniruan tidak dapat dihindari lagi ketika terbuka peluang pendidikan di tanah jajahan dengan diberlakukannya politik Etis pada tahun 1899. Kelompok yang paling banyak mengenyam atau memanfaatkan pendidikan Belanda ini adalah kaum bangsawan dan kelas menengah atas. Dengan membuka peluang pendidikan bagi bangsa terjajah, pihak penjajah juga mendapatkan keuntungan dengan terciptanya priyayi baru atau kelas sosial baru yang dapat berlaku sebagai perantara penjajah dalam berhubungan dengan penduduk jajahan. Pihak penjajah menguasai penduduk jajahan tidak secara langsung karena terkendala faktor bahasa dan budaya, tetapi memanfaatkan para bangsawan dan priyayi hasil didikan Belanda yang ditempatkan sebagai Bupati di daerah-daerah kekuasaan Belanda sebagai perantaranya. Strategi Belanda itu telah menempatkan para bangsawan dan priyayi terpelajar dalam posisi ambivalen. Politik Etis yang dicetuskan T. Ch. Van Deventer tampaknya lulus untuk meningkatkan taraf hidup penduduk jajahan, tetapi sesungguhnya untuk mengukuhkan kolonialismenya di Indonesia dengan terbentuknya suatu lapisan sosial yang merasa berhutang budi karena telah ditingkatkan peradabannya menjadi “seolah-olah” sederajat dengan Belanda (Foulcher, 1994).
Peniruan yang paling mudah dilakukan adalah peniruan
gaya hidup orang Eropa yang merebak pada pertengahan kedua abad ke-19 (Sutherland dlm Faruk, 2001;76) dan menurut Adam (dlm Faruk, 2001;76) merupakan perwujudan kehendak zaman untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan diri sederajat dengan bangsa Eropa. Dalam menghadapi gejala mimikri ini, pihak penjajah juga bersikap ambivalen. Di satu sisi membuka peluang pihak terjajah untuk mengenyam pendidikan Eropa, di sisi lain berusaha menghambatnya dengan memberlakukan politik identitas karena takut akan menggoncang struktur kekuasaan kolonial (Faruk, 2001;77). Politik identitas merupakan konsep masyarakat plural, yaitu ideologi pemisahan dan pemeringkatan penduduk berdasarkan golongan, agama, dan juridiksi sehingga tidak saling bergaul. Politik itu mempertajam kontras orang-orang kulit putih sebagai penguasa dan penduduk sebagai jajahan (Furnivali dlm Maemunah, 2005;15). Penduduk jajahan dapat diajar untuk meniru, tetapi bagi penjajah peniruan itu tetap akan terhambat oleh sifat-sifat kodrati yang membedakan mereka dengan Eropa.
Karena wataknya yang ambivalen dalam relasi penjajah-terjajah, mimikri tidak akan menghasilkan gambar yang sama persis, tetapi berupa salinan yang kabur ‘blurred copy’..Berbeda dengan wacana antikolonial yang mengacu pada perlawanan kaum terjajah terhadap penjajah, wacana pascakolonial lebih memperhatikan sifat-sifat dan alam kolonial dan warisannya di alam pascakolonial yang ditandai oleh perebutan, ambivalensi, dan kekaburan makna karena tidak sanggup menghasilkan simpulan yang “konkret”, bahkan mengelabui perlawanan yang menjadi kenyataan “objektif” dalam eksploitasi kolonial yang masih berlangsung (Foukcher, 1994). Menurut Bhabha (Gandhi, 2001;vii) tidak ada budaya atau bahasa baik dari bangsa penjajah maupun yang terjajah, yang bisa direpresentasikan dalam bentuk ‘murni’. Bahasa dan budaya mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga memunculkan hibriditas yang menjadi budaya ketiga, yang sama validnya dengan budaya kolonial dominan.
Pretensi sejarah
Sebagai novel yang memiliki pretensi sejarah, novel ini menunjukkan pentingnya masa lalu agar sejarah yang buruk tidak terulang. Secara jelas, pada awalnya novel ini hendak meninggalkan masa lalu dan membuang semua yang ada di masa lalu untuk menggapai masa depannya. Darwan yang hidup di “masa kini” berusaha menggapai masa depan dengan meninggalkan masa lalu.
Darwan memandang Surakarta adalah kehidupan kemarin, sementara
Surabaya hari esok. Yang kemarin tidak bisa diulang, yang hari esok bisa dirancang. (Brata, 2005;39).
Akan tetapi, novel ini selanjutnya menunjukkan bahwa masa lalu tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena masa depan merupakan rangkaian dari masa lalu dan masa kini. Masa lalu didudukkan dalam posisi penting sebagai cermin agar yang buruk di masa lalu tidak terulang di masa kini dan masa depan. Masa lalu juga tidak harus ditinggalkan karena masa depan yang diinginkan juga belum pasti.
“O, itu lagu lama. Alasan klasik. Menuntut berkuasa karena mengklaim anggotanya paling banyak dan merasa menderita akibat diperlakukan tidak adil. Lalu, mereka membenci penguasa yang tidak sepaham dengannya, berjuang memenangkan segala cara untuk merebut kekuasaan atau sekedar merugikan lawan, melakukan teror, menohok kawan seiring, melumpuhkan kekuatan bangsa sendiri. Tiap orang Jawa hafal dengan lagu itu. Tercermin dalam cerita wayang Pandawa dan Ngastina. Orang Ngastina itu orangnya banyak, mengaku diperlakukan tidak adil, meneror dan membenci orang Pendawa, tetapi selalu kalah. Karena apa? Karena bodoh. Banyak tetapi bodoh, itu akan membuat bangsa jadi terpuruk. PKI itu persis seperti orang Ngastina. Barangkali lagu seperti itu akan terus berulang dan berlanjut, apabila kita tidak mendidik dan mencerdaskan bangsa. Hanya bangsa yang cerdas bisa menolong negara ini adil makmur. Orang PKI sudah lupa jadi orang Jawa maka buta bercermin pada cerita wayang yang begitu mencolok dipagelarkan di depan matanya. Yang diserap dan dianut paham asing, ditonjolkan sebagai paham superior, tidak peduli hal itu cocok atau tidak dengan kebudayaan kita di sini,” kilah Kanjeng Rama.“Nanti dulu, Kanjeng Rama. Nandalem tadi setengahnya meramal cerita klasik perang saudara Pendawa-Ngastina itu mungkin berulang dan berlanjut kalau orang Jawa kehilangan Jawanya, seperti peristiwa yang kini dilakukan oleh orang-orang PKI komunis yang lari ke Madiun itu. Akan berulang kalau bangsa kita tetap bodoh. Apa Musa yang anggota Commintern dan Amir Syarifuddin yang menguasai empat bahasa Eropa itu bukan orang pintar? Apa mereka tidak mendidik bangsa kita menjadi cerdas seperti pemimpinnya?”“Betul, orang pintar. Tetapi, cara mendidik rakyatnya atau umatnya tidak benar. Dididik untuk merebut kekuasaan. Maka, yang terjadi tentu konflik antara bangsa dewek seperti sekarang ini. Perang saudara, seperti Pendawa dan Ngastina. Bangsa tidak akan rukun, sejahtera, dan berdiri tegak, kalau yang dididikkan saling membenci karena berbeda paham dan berebut kekuasaan.”“Kalau Nandalem bisa meramal perang saudara seperti itu akan berulang dan berlanjut, tentunya Nandalem bisa memberi pandangan mengapa bisa berulang dan bagaimana supaya tidak berulang. Sebab kalau perang saudara berulang-ulang, bangsa kita tentulah pecah sebagai ratna.”“Coba kita lihat cerita klasik perang saudara Pendawa dan Ngastina dengan cerdas. Penyebab perang sejatinya adalah perbedaan. Ngastina dan Pendawa itu beda. Celakanya, pemimpin Ngastina, orang pandai seperti Sengkuni, Durna, Adipati Karna, selalu mengasah perbedaan ini menjadi hasutan dendam kesumat. Ngastina umatnya banyak, Pendawa sedikit. Kalau perang pasti menang Ngastina. Ngastina miskin, Pendawa kaya, ini tidak adil. Yang kaya harus direbut kekayaannya. Sama dengan PKI dan Negara Republik kita sekarang ini. Kepercayaan PKI beda sama Republik kita, jadi kekuasaan Republik kita harus ditumpas, direbut, dikalahkan. PKI yang dimenangkan. Itulah kesalahan pemimpin Ngastina. Segala perbedaan ditonjolkan sehingga menimbulkan dendam dan diselesaikan dengan tindak kekerasan. Motif pendidikan seperti itu adalah menghasut. Kalau berlangsung terus, tentu konflik di negara kita tidak akan selesai-selesai. Sebab betapa pun juga Gusti Allah itu tidak pernah menciptakan dua benda, atau manusia, atau kelompok manusia, atau apa saja, yang sama persis satu sama lain. Tidak pernah. Yang tertakdir adalah serbabeda. Jadi, paham atau kepercayaan pun pasti beda. Sedang dalam Ngastina atau PKI, perbedaan itu ditonjol-tonjolkan kepada rakyatnya. Bahwa yang dianutnya itu paham superior benar, superior adil. Maka, harus diperjuangkan agar menang dan pegang kekuasaan. PKI harus mengalahkan paham yang beda dengan cara kekerasan, dengan konflik, dengan teror, dan dengan perang saudara.”“Jadi, supaya tidak berulang perang saudara, bagaimana?”“Ya, rakyat dididik untuk memahami perbedaan, tetapi penyelesaiannya kebangsaan. Tidak perlu dengan konflik dan kekerasan. Jangan menganggap benarnya sendiri yang baik dan yang beda harus diperangi. Biarlah yang beda itu beda seperti kersaning (kehendak) Allah. Mari kita hidup berbeda, tetapi sama-sama makmur. Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan memenangkan paham superiornya sendiri, paham komunis, tetapi sebaiknya dilakukan pembelajaran kepemahaman atau kecerdasan bangsa. Bangsa jangan bodoh, tetapi harus cerdas. Supaya cerdas harus dididik dalam wadah yang saling menghormati paham-paham yang beda. Hanya dengan pendidikan pemahaman begitu maka bangsa kita bisa hidup makmur bersama.” (Brata, 2005; 694-697)
Masa lalu dengan tradisinya dimaknai sebagai sumber teladan kebaikan dan kebajikan yang akan tetap hidup dan berguna untuk masa kini dan masa depan. Pendidikan yang dimaksud dalam kutipan itu tidak hanya pendidikan untuk menghargai dan menghormati perbedaan, tetapi juga untuk menengok dan belajar dari masa lalu sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Rama dengan cerita wayang. Cerita wayang yang berasal dari tradisi atau masa lalu memiliki nilai-nilai dan mengandung pelajaran yang baik serta masih relevan untuk kehidupan masa kini. Oleh karena itu, masyarakat Jawa tidak boleh melupakan ajaran yang ada di dalam wayang agar peperangan dan penderitaan tidak terus menerus berulang.
* * *
Dikutip dari:Buku: AMBIVALENSI DALAM NOVELMENCARI SARANG ANGINKARYA SUPARTO BRATALatar Belakang (halaman 1-3), Kerangka Teori (halaman 6-9),Pretensi Sejarah (halaman 57-59) Pengarang: YULITIN SUNGKOWATIBalai Bahasa
SurabayaJalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo. 2007.

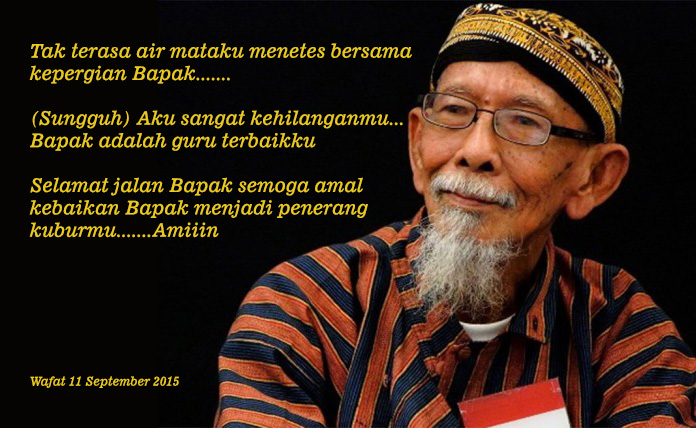



































Saya sudah selesai menamatkan buku Mencari Sarang Angin. Bagus sekali pak. Sayang sungguh disayang mengapa Yayi harus tewas dibunuh kempeitai, padahal saya berpengharapan agar Yayi yang menjadi isteri Darwan, bukan Rokhayah. Saya berandai-andai, setting ceritanya berbelok, saat dalam perjalanan ke pameran, Yayi tak sengaja memeriksa tas dan menemukan emblem yang berbahaya tersebut dan kemudian menginsyafi bahwa Yayi dan Darwan harus lebih waspada.
Saya sampai tidak bisa tidur, kasihan pada Yayi . Jadi ingat buku bapak yang Saksi Mata, yang tokoh sentralnya juga terbunuh diawal cerita.
. Jadi ingat buku bapak yang Saksi Mata, yang tokoh sentralnya juga terbunuh diawal cerita.
Jika membandingkan buku Mencari Sarang Angin dengan buku Mahligai di Ufuk Timur, saya kok mendapat kesan bapak terburu mengakhiri cerita.
Jalinan kisah diakhir cerita kurang sekompleks dan kurang sehalus diawal dan tengah cerita. Mencari Sarang Angin diakhir cerita misalnya, menjadikan Darwan terlalu lemah dan terkesan kurang menghargai pengorbanan Yayi yang harus meninggal karena disiksa Kempetai. Mohon maaf, ini adalah daya tangkap saya, mungkin bapak punya pertimbangan lain yang saya belum dapat memaknainya.
Oh ya, kalau ada pembaca blog bapak yang datang dari Planet Terasi, itu adalah artikel yang saya tulis tentang bapak. Saya ingin lebih banyak orang yang bisa mendengar, membaca dan mengapresiasi tulisan bapak. Sedikit banyak saya yakin akan bisa membantu Indonesia kearah perbaikan.
Salam Hormat dan Terima Kasih
saya sangat senang membaca novel mencari sarang angin. selama ini saya kira yg berjuang itu adalah mereka yang ikut dalam medan perang. ternyata seorang jurnalis dan penulis pun memiliki peranan yg penting….
sangat menginspirasi sekali..
–Terimakasih–
hemmmmmmmmmm terimakasih tulisan ini sangat membantu saya dalam mencari Makna MSA. karena setelah membaca 726 halaman kepala rasanya sakit, cemut-cemut tapi puas.
dimana saya bisa mendapatkan buku MSA….? saya tinggal di Bandung