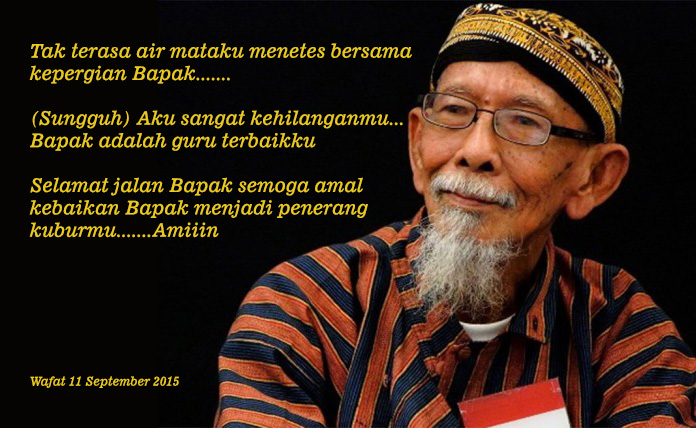CITRA BELANDA DALAM KARYA PROSA SUPARTO BRATA
Yulitin Sungkowati
Balai Bahasa Surabaya.
Abstract
This paper is aimed to study how Ducth is depicted in Suparto Brata’s prose, especially in novel Gadis Tangsi (2004), Mencari Sarang Angin (2005), and Kerajaan Raminem (2006). In the novel, Dutch is not depicted as a colonial that crush and make suffering, but as rescuer, protector, prosperous giver, knowledge/high civilization giver, peace and regularity giver. The image strengthen the view of whiteness is rightness.
Key words: depicted, Ducth, whiteness is rightness.
1. Pengantar.
Kolonialisme Belanda di Indonesia telah meninggalkan jejaknya di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali kesusasteraan. Tidak sedikit karya sastra Indonesia, baik yang ditulis di era kolonial maupun era kemerdekaan, baik yang ditulis oleh pengarang-pengarang keturunan Tionghoa, Eropa, maupun “pribumi” yang menggambarkan kehadiran Belanda dengan berbagai citranya. Pembentukan wacana kolonial Belanda dalam kaitannya dengan penduduk jajahan dalam sastra Indonesia dilatari oleh beragam persoalan dan untuk tujuan atau kepentingan yang berbeda pula sesuai dengan pengalaman dan penghayatan penulisnya.
Pada masa kolonialisme masih mencengkeram, Marah Rusli “membungkus” kritiknya yang tajam terhadap sikap penguasa kolonial dalam kasus pemberlakuan pungutan pajak terhadap masyarakat Minangkabau dalam Siti Nurbaya dengan cara membangun kesan bahwa para pengkritik adalah orang-orang jahat, seperti Datuk Maringgih, sehingga karyanya itu lolos dari sensor Balai Pustaka yang merupakan lembaga penerbitan pemerintah kolonial (Faruk, 2001;94-96). Pada era kemerdekaan, gambaran resistensi terhadap kuasa kolonial tampak jelas pada tetralogi Pulau Buru-nya Pramoedya Ananta Toer: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Keempat novel itu menggambarkan perlawanan pribumi terhadap kolonialisme yang menimbulkan banyak persoalan. Perlawanan yang dipaparkan tersebut bukan sekadar untuk kepentingan individu, tetapi merupakan protes terhadap ketidakadilan supaya rakyat terbebas dari belenggu penindasan (Young Hoon, Koh, 1996;93).
Berbeda dengan karya-karya Pramoedya yang mencitrakan Belanda sebagai penjajah yang menindas dan menyengsarakan rakyat, karya prosa Suparto Brata pada umumnya menunjukkan citra yang berbeda, yang cenderung meniru atau “mengikuti” sudut pandang sang penjajah dalam memproduksi ideologi kolonialismenya, seperti tampak pada karyanya yang berjudul Gadis Tangsi (2004), Kerajaan Raminem dan Mencari Sarang Angin (2005). Sama-sama ditulis di era kemerdekaan, ketiga novel Suparto Brata itu tidak secara jelas menunjukkan resistensinya terhadap kuasa kolonial Belanda sebagaimana tetralogi Pramoedya, tetapi menunjukkan citra Belanda yang positif. Menurut Untoro (2006:53) hal itu dikarenakan karya-karya Suparto Brata ditulis sebagai kenang-kenangan atas masa kecilnya sehingga meskipun pada era kolonial banyak perlawanan, perlawanan terhadap Belanda itu tidak muncul karena masa itu Suparto Brata masih sangat kecil dan tinggal di dalam “tembok istana” sebagai keluarga kraton Surakarta. Suparto Brata tidak melihat dan merasakan penindasan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Belanda sebelum kedatangan Jepang tidak dianggap sebagai penjajah, yang dianggap sebagai penjajah adalah Jepang dan Belanda pada masa perang revolusi. Karya prosa Suparto Brata lebih banyak membicarakan Belanda pada era sebelum pendudukan Jepang sehingga citra yang muncul adalah gambaran Belanda yang baik yang menjadi sumber wacana kemajuan bangsa Jawa. Belanda yang bercitra negatif, yaitu Belanda pada masa perang revolusi hanya muncul pada novel Lara Lapane Kaum Republik yang menggambarkan nasionalisme priyayi sebagai jawaban atas kritik karya-karya Suparto Brata yang menggambarkan kedekatan priyayi dengan Belanda (Untoro, 2006:46). Tulisan ini mencoba membahas bagaimana Belanda digambarkan dalam novel Gadis Tangsi (2004), Mencari Sarang Angin (2005), dan Kerajaan Raminem (2006) dan kemungkinan strategi politik apa yang ada dibalik pencitraan tersebut dengan perspektif pasca-kolonial.
Dari segi budaya, definisi pasca-kolonial seringkali dihubungkan dengan proses konstruksi budaya menuju budaya “putih global”. Kebudayaan kulit putih dipandang sebagai acuan perkembangan dan model bagi budaya lain. Menurut Bhabha (1993;89, Sianipar, 2004:10), proses seperti ini tetap berlangsung meskipun kolonialisme kulit putih telah berakhir. Hal itu terjadi karena kolonialisme Barat atas dunia Timur tidak hanya untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ideologis untuk membuktikannya sebagai manusia superior dan “manusia terpilih” yang berhak menjadi “juru selamat” dunia (Nieuwenhuys dlm. Faruk, 2002:233). Nieuwenhuys (Faruk, 1991:73) menyatakan bahwa representasi tentang Indonesia sudah berlangsung sejak abad XVII berupa cerita-cerita perjalanan yang dicetak dalam bentuk buku-buku murah, tetapi mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Belanda pada waktu itu. Representasi dalam berbagai bentuk itu merupakan upaya Belanda untuk memproduksi ideologi kolonialismenya, misalnya dalam kesusasteraan Belanda. Dalam berbagai cerita nyai selalu terdapat gambaran bahwa pribumi tidak akan pernah bahagia dan aman bila lepas dari Belanda. Belanda adalah pelindung, penyelamat, dan sumber kemakmuran bagi pribumi (Faruk, 2002:234). Citra keunggulan bangsa Eropa yang diproduksi melalui teks-teks kolonial itu menggambarkan dominasi kulit putih sebagai pembawa peradaban dan membenarkan terjadinya kolonialisme sebagai misi suci untuk mengadabkan penduduk pribumi. Produksi teks-teks seperti itu juga merupakan salah satu upaya kolonialis untuk membangun konstruksi whiteness is rightness ‘putih adalah benar’ agar citra itu dapat terpateri dalam benak penduduk jajahan. Berbeda dengan yang anti-kolonial yang secara tegas menarik garis pembatas antara penjajah dan terjajah, yang pasca-kolonial menunjukkan interaksi yang penuh kontradiksi dan ambivalensi (Foulcher, 1999;26,2006).
Bangsa yang pernah mengalami penjajahan tidak dapat menghilangkan begitu saja ideologi bahwa ras kulit putih lebih tinggi daripada ras pribumi yang sawo matang. Oleh karena itu, dalam kata pasca-kolonial sebagai sebuah pendekatan digunakan tanda hubung untuk menunjukkan bahwa pasca-kolonial adalah sebuah sistem yang aktif, hidup, berkelanjutan, dan terjalin dalam interaksi sosial melalui berbagai institusi dalam masyarakat untuk membedakannya dengan istilah pascakolonial (tanpa tanda hubung) yang lebih menunjuk pada periodisasi sesudah kolonialisme berakhir (Aschroft, et.al., 2000:3).
2. Pembahasan
Secara keseluruhan, novel Gadis Tangsi (GT), Kerajaan Raminem (KR), dan Mencari Sarang Angin (MSA) menempatkan Belanda pada posisi superior. Semua tokoh Belanda dicitrakan positif sebagai guru, penyelamat, pemberi kemakmuran, pemberi pengetahuan/peradaban tinggi, pelindung, dan pemberi kedamaian serta keteraturan. Tidak ada gambaran resistensi terhadap Belanda sebagai penjajah, juga tidak ada gambaran masalah yang dihadapi tokoh pribumi di tengah-tengah pergaulannya dengan bangsa Belanda.
2.1 Belanda sebagai Penyelamat dan Pelindung.
Citra Belanda sebagai penyelamat dalam karya prosa Suparto Brata digambarkan melalui berbagai peristiwa. Dalam GT, citra penyelamat itu ditampilkan melalui tokoh Kapten Davenpoort yang menyelamatkan Putri Parasi ketika mendadak jatuh sakit dengan membawanya ke klinik Dokter Winker di Medan. Kapten Davenpoort digambarkan sangat ramah dan sigap ketika menerima Teyi yang mengabarkan sakitnya Putri Parasi. Dokter Winker pun digambarkan menangani penyakit Putri Parasi dengan baik hingga Putri Parasi sembuh kembali (Brata, 2004:158-159).
Dalam MSA tampak ketika Kanjeng Prawirakusuma diselong (dibuang), harus meninggalkan Kerajaan Surakarta Hadiningrat serta keluarganya karena melakukan kesalahan, Belanda memberinya tempat sekolah dan tempat tinggal di Utrecht. Putranya, Darwan, diasuh dan disekolahkan oleh keluarga Jacobus Vollentijn, di Prinseslaan sejak masuk Fröbel sampai hampir lulus ELS. Lingkungan rumah, tetangga, dan sekolahnya adalah orang-orang Belanda totok yang digambarkan sangat baik. Selepas lulus ELS, Darwan melanjutkan HBS di Batavia dan tinggal di internaat Kwitang bersama orang-orang Belanda pula. Selama tinggal di rumah Jacobus Vollentijn, bersekolah di sekolah Belanda, dan tinggal bersama orang-orang Belanda, Darwan diterima dan diperlakukan dengan baik. Setiap ada persoalan, Darwan datang ke Beatrix yang selalu siap membantunya.
Berhubung Kanjeng Rama diselong ke Negeri Belanda, Darwan kecil ditolak masuk sekolah kerabat raja kstrian hingga Darwan dititipkan pendidikannya di rumah Tuan Jacobus Vollentijn di Prinseslaan. Di situ Darwan berkenalan dengan Beatrix, bermain bersama, makan bersama, tidur seranjang, bersekolah bergandengan tangan, masuk gereja bersama. Berpisah benar ketika Darwan bersekolah di Batavia, semasa mereka masih tetap kanak-kanak. Tetapi di sela vacantie mereka bertemu lagi dalam pertumbuhannya yang sama-sama menjadi dewasa. Hingga ketika Darwan mau pergi ke Surabaya pun mereka masih berboncengan sepeda bertamasya menjenguk seorang teman di Pabrik Gula Tasikmadu (Brata, 2005:505).
Citra sebagai penyelamat juga dihadirkan melalui tokoh Steffie van Daal, seperti berikut ini:
Namanya, Steffie van Daal. Ia wartawan suratkabar Het Soerabaiasch Nieuws-Handelsblad. Steffie van Daal baik sekali. Siang hari itu ia mengajak Darwan ke kantornya di Regentstraat (sekarang Jalan Pahlawan). Kelihatannya ia sangat terbuka. Dibawanya Darwan melihat-lihat percetakan suratkabarnya yang berada di belakang gedung. Mesin-mesin serbabaru, besar sekali. Percetakan tadi bukan hand-set atau cetakan tangan seperti yang ada di Dagblad Expres, tetapi intertype. Cara mengoperasikannya dengan diketik seperti mesin ketik, dan keluar secara otomatis gabungan huruf timah per kolom. Semua serbalistrik dan otomatis (Brata, 2005:156).
Steffie van Daal menyelamatkan karier jurnalistik Darwan, ketika rubriknya di surat kabar Dagblad Expres dihapus, dengan memberinya rubrik khusus di suratkabar berbahasa Belanda Het Soerabaiasch Nieuws-Handelsblad. Ketertarikan Darwan pada masalah-masalah sosial budaya mendapat tempat yang baik di suratkabar tersebut hingga dibuatkan rubrik “Poetar Kajoon”. Ia mendapat surat tanggapan dari mantan menteri di Belanda yang tertarik pada persoalan sosial budaya dalam tulisan-tulisannya yang dianggap sebagai rintisan penulisan sejarah sosial Surabaya. Hal serupa tidak ia dapatkan di Dagblad Expres, sebuah koran berbahasa Jawa yang dikelola oleh kaum pribumi. Tulisan-tulisannya di Dagblad Expres tidak pernah dihargai sebagai karya intelektual. Tulisan “Prahara ing Surakarta” sebanyak 38 seri tidak pernah diberi honor.
2.2 Belanda sebagai Pemberi Kemakmuran
Citra Belanda sebagai pemberi kemakmuran tampak dalam kontrasnya dengan masa pendudukan Jepang dan era kemerdekaan. Dalam novel KR, masa pemerintahan kolonial merupakan masa yang makmur karena kebutuhan rakyat tercukupi dan suasana kota hidup oleh kegiatan ekonomi. Dalam MSA, kontras itu juga terlihat jelas: masa pemerintahan kolonial Belanda adalah masa kemakmuran rakyat, sedangkan era pendudukan Jepang itu menyengsarakan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka keadaan bertambah buruk: era revolusi penuh pertumpahan darah dan era kemerdekaan diwarnai pemberontakan PKI Madiun serta perebutan kekuasaan. Narator menarasikan perubahan kota Surabaya pada zaman Belanda digambarkan sebagai “surga” karena kemakmuran dan keteraturannya kemudian menjadi kota kere pada masa Jepang dan porak-poranda pada masa revolusi.
Tahun 1942 tentara Jepang datang di Surabaya. Jepang yang dulu sering disebut Jepun, datang dengan nama baru: Balatentara Dai Nippon.
Zaman berubah! Tatanan yang ada sama sekali jungkir balik. Orang Belanda, kendaraan bermotor, sinar lampu, barang-barang di toko, bahan makanan, semua lenyap dari peredaran masyarakat. Cahaya kemakmuran kota pun suram. (Brata, 2005:422).
Citra sebagai pemberi kemakmuran juga tampak saat Darwan sedang berjuang mempertahankan hidup dengan gaji setengah rupiah sebagai wartawan Dagblad Expres di Surabaya, Steffie van Daal muncul memberi pekerjaan sambilan sebagai wartawan lepas di surat kabarnya.
Untuk berita kebakaran Darwan menerima honorarium setengah rupiah! Sedangkan muat pertama rubrik “Poeter Kajoon” satu rupiah! Darwan menerima kepingan perak setengah rupiah dan satu gulden! Sungguh, kegembiraannya meledak tak terduga! Dua bundaran kepingan perak sedang dan besar itu rasanya antep sekali. Sudah beberapa bulan ini, selama keluar dari Surakarta, Darwan tidak pernah menggenggam uang logam putih begitu antep. Dan, lebih membanggakan hatinya lagi karena itulah kepingan rupiah yang pertama dari hasil kerjanya, karyanya sebagai wartawan dan penulis! Rasa banggalah menyesakkan rongga dada! (Brata, 2005:164).
Gaji dari suratkabar Belanda itu membuat Darwan dapat hidup lebih layak, tidak jauh dari kehidupannya di Surakarta. Ia dapat membeli pakaian, sabun, sisir, minyak rambut, dan memberi hadiah untuk Rokhayah. Di samping itu, Darwan dapat menyewa rumah yang lebih baik di lingkungan priyayi atau kaum pribumi terpelajar. Darwan bisa lebih sering berkeliling Surabaya untuk melihat-lihat keadaan masyarakat sebagai bahan tulisannya.
2.3 Belanda sebagai Guru/Pemberi Pengetahuan dan Peradaban Tinggi
Di dalam GT dan KR, pencitraan Belanda sebagai bangsa berperadaban tinggi tercermin dari sikap Teyi dan Putri Parasi yang sangat bangga bisa berbahasa Belanda. Bahasa Belanda digambarkan mampu mengangkat derajat seseorang dari kelas rendah ke kelas paling tinggi. Putri Parasi mengatakan pada Teyi bahwa dengan bahasa Belanda yang dikuasainya, ia sudah menjadi perempuan Jawa modern yang berhak dan pantas mendapat jodoh pangeran. Bagi para bangsawan, bahasa dan budaya Belanda menjadi penyempurna kebangsawanannya. Bangsawan Jawa menjadi lebih tinggi martabatnya jika mampu membawa etiket dan ilmu dari Belanda (Brata, 2004:256-257).
Tingkat kebangsawanan Raden Sarjubehi tidak mencukupi untuk mengemban pangkat yang layak di jajaran abdi dalem kraton. Untuk mengangkat martabatnya, Putri Parasi menganjurkan agar suaminya bekerja di tanah Gopermen (Brata, 2004:106).
Tanah gopermen adalah wilayah kekuasaan Belanda. Untuk mendapat derajat yang tinggi, seorang bangsawan saja tidak cukup hanya memiliki darah biru, tetapi harus bisa seperti Belanda atau minimal bekerja di tempat orang-orang Belanda. Belanda diposisikan di atas golongan bangsawan. Oleh karena itu, Teyi naik derajatnya di hadapan bangsawan karena meskipun ia berasal dari kelas wong cilik, tetapi mampu berbicara bahasa Belanda dan menerapkan etiket budayanya.
Kehadiran Belanda sebagai guru juga tampak pada pencitraan kepandaian Beatrix yang melebihi Darwan meskipun usianya lebih muda dalam MSA. Beaatrix sering membacakan atau mendongengkan cerita untuk Darwan dan membuka pikiran Darwan untuk kritis terhadap budaya Jawa yang dianggapnya defaistis. Dengan semua kelebihan dan kecerdasannya itu, Darwan dengan senang hati menganggap Beatrix sebagai gurunya, sebagai sumber pengetahuannya. Pendidikan Barat ditempatkan dalam posisi yang penting sebagai penggerak terjadinya proses transformasi seorang dari kelas terjajah untuk berupaya mencapai derajat yang sama dengan sang penjajah.
Dalam pergaulan itu Darwan harus mengakui bahwa perkembangan jiwa Beatrix, mungkin karena menempuh kehidupan bangsanya sendiri, lebih maju dan lebih luas dalam segala hal. Banyak nasihat, pekerti, dan cita-cita yang dipatuhi dan diteladani oleh Darwan, serta dijadikan pedoman hidupnya.
Beatrix mengajari Darwan bicara sopan, bernyanyi, berdansa, bersembahyang, berciuman. Ketika sesama bocah berbaring seranjang, Beatrix membacakan cerita ‘Prinses die honderd jaar sliep” (putri raja yang tidur seratus tahun). Ketika dewasa Beatrix mengajari makna hidup dengan sentuhan natural anatomi tubuhnya meski pelajaran dilaksanakan dengan perabaan wujud sejatinya, Beatrix pula yang melarang Darwan berbuat melampaui batas. “Jangan! Jangan bersetubuh kalau kita belum melalui sakramen perkawinan. Hormatilah perbuatan yang satu ini untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan!” bisik Beatrix sungguh-sungguh. Dan, si murid Darwan patuh, selalu patuh seperti biasanya. Beatrix adalah gurunya yang paling dipatuhi (Brata, 2005:505-506).
Darwan digambarkan merasa beruntung mendapat kesempatan mengenyam pendidikan Belanda dan mempelajari budayanya. Menurut Darwan, pendidikan Belanda lebih berharga daripada warisan derajat kebangsawanannya karena membuatnya berbeda dengan saudara-saudaranya yang tetap tinggal di istana. Ia merasa sanggup hidup mandiri tanpa mengandalkan warisan kekayaan orangtuanya. Dalam segala hal, pendidikan Belanda telah membuatnya lebih unggul, modern, dan maju dibandingkan dengan bangsawan lainnya.
Darwan menganggap sekolahnya yang bercampur dengan anak-anak Belanda – tidak seperti anak bangsawan Surakarta biasanya – dari Europese Lagere School di Surakarta sampai HBS di Batavia, merupakan modal untuk hidup yang tak terhingga nilainya. Itu melebihi warisan harta benda dan darah biru kebangsawanannya. Darwan memutuskan untuk mengenyahkan serbakebendaan serta martabat keturunan yang ada pada Kanjeng Rama dan menggunakan segala yang diperoleh selama sekolah untuk meniti jenjang kehidupannya. (Brata,2005:27).
……beda Darwan dengan para jejaka bangsawan lainnya mungkin karena pendidikan Darwan dari sejak semula adalah sekolah Belanda. Dan saat sekolah lanjutan atau pada pertumbuhan remajanya, ia hidup di luar Surakarta. Selama di HBS, Darwan masuk internaat di Kwitang, Batavia. Dan itu, Darwan yakin bisa membuat segalanya berbeda dengan saudara-saudaranya yang tinggal dan menetap di Prawirakusuman. (Brata, 2005:75-76)
Pengakuan serupa juga tampak pada relasinya dengan Steffie van Daal. Steffie van Daal adalah seorang wartawan Belanda totok yang baru tiga bulan diterjunkan di tanah koloni untuk menyerap pengetahuan tentang budaya pribumi. Dengan seolah-olah sudut pandang Darwan, narator menggambarkan Steffie van Daal sebagai seorang yang sangat baik dan berpengetahuan luas, khususnya tentang dunia kewartawanan. Bahkan, pengetahuannya tentang dunia pers pribumi digambarkan jauh lebih baik daripada Darwan yang pribumi (Brata, 2005:163, 217).
Van Daal orang berilmu dalam profesinya sebagai wartawan. Darwan bisa banyak belajar dari dia. Orangnya terbuka. Bergaul dengan orang pribumi seperti Darwan, van Daal tidak khawatir ilmunya diserap oleh Darwan, atau curiga Darwan nanti akan mengkhianati dirinya. Tidak. “Memang, sejak semula aku ingin bergaul dengan kaum pribumi tanah jajahan. Banyak hal yang belum terungkap tentang bangsamu, yang patut ditulis dalam bahasa berita yang sederhana. Tentang perilaku, gagasannya, keinginannya, ungkapan budi dayanya. Aku percaya sekaliannya itu tidak akan terbeberkan lepas, kalau cara menggaulinya tidak dengan rasa cinta. Dan, rasa cinta itu tidak bakal terwujud tanpa pendekatan ragawi.” (Brata, 2005:163).
Darwan harus mengakui. Mengenai persuratkabaran, dia hanya sepucuk jari kelingking saja dibanding dengan pengetahuan Steffie van Daal. Darwan tercekam mendengarkan kisah-kisah penerbitan suratkabar semacam itu. Lebih mengetahui seluk-beluknya, kian mantap Darwan menjejakkan kakinya pada alam kewartawanan dan persuratkabaran. Ia percaya, saat ini pengetahuan serta kemampuannya menulis telah melebihi dari siapa saja yang bekerja membantu Dagblad Expres. Ia akan lebih banyak belajar dari van Daal. (Brata, 2005:217).
2,4 Belanda sebagai Pembawa Keteraturan dan Kedamaian
Citra keteraturan ini dalam GT terlihat dari tertibnya kehidupan di tangsi militer Belanda, tempat tinggal Teyi, dan Kampung Landa, tempat tinggal orang-orang Belanda serta keluarga bangsawan Putri Parasi. Setiap hari segala aktivitas kehidupan di tangsi dan Kampung Landa diatur dengan ketat dan setiap orang memiliki tugas sendiri-sendiri dengan jadwal yang tetap. Keteraturan dan ketertiban itu tercipta karena ada ketegasan dalam penegakan aturan dan hukum. Hukum ditegakkan dengan baik (Brata, 2004:1-2).
Dalam MSA, narasi yang menggambarkan keadaan Kota Surabaya yang tertata ruang-ruangnya dengan ciri khas sendiri-sendiri, seperti ruang Plampitan sebagai kampung di tengah kota tempat tinggal para priyayi pribumi yang pada umumnya adalah kaum terpelajar pendatang, seperti Insinyur Soekarno yang mondok di rumah Haji Mas Tjokroaminoto (Brata, 2005:195), Jalan Darmo sebagai ruang tempat tinggal orang-orang Belanda dan Plemahan sebagai perkampungan kelas menengah ke bawah khas Surabaya. Rumah-rumah sangat teratur dan alat-alat transportasinya tersedia, lancar, dan cukup beragam jenisnya, seperti trem, amko, demo, dan ataq (kendaraan bermotor roda tiga dengan mesin kecil). Dengan demikian, tampak bahwa pada zaman kolonial Belanda, Kota Surabaya sudah tertata dan teratur, baik perumahan, perkantoran maupun sarana publiknya..
Wage tidak bisa memberi ancar-ancar berapa jauh letak gedung tempat harian Dagblad Expres terbit. Pokoknya, gampang. Turun dari trem, berjalan arah ke kiri, itu Jalan Embong Malang. Dan, menengoklah ke kiri. Melangkah tidak terlalu payah, tentu ketemu. Urut saja nomornya karena nomor rumah di Surabaya tertib sekali. Yang nomor gasal berhadapan dengan yang nomor genap, dan urut dari nomor kecil. Tiap rumah tentu punya nomor yang urut itu. Darwan tidak usah tanya karena nomor rumah itu pasti dipasang seragam di depan setiap rumah.
Betul juga. Ada nomor urut yang bentuk dan warnanya seragam, besarnya sama, warna dasar hitam tulisan angkanya putih, terpasang pada setiap rumah atau pagar halaman rumah. Kepongahan menginjak kota belum puas, pada urutan nomor 55 Darwan sudah membaca papan nama yang terpampang di sebuah gedung bangunan lama: Dagblad Expres. Dagblad Djawa Oemoem. Embong Malang 55 Soerabaja (Brata, 2005:1-2).
Darwan berlari menuju ke pemberhentian trem Simpang Klok. Trem listrik itu beroperasi sampai jam tujuh malam. Waktu itu jalan tengah Kota Surabaya sudah bergebyar dengan lampion penghias kota. Tapi hanya di tengah kota dan rumah-rumah tepi jalan saja yang tampak terang oleh pijaran lampu listrik. Di kampung-kampung, lampu teplok atau pelita minyak lebih umum terlihat. Lampu listrik, barang yang mewah. (Brata, 2005:71).
Di samping itu, Surabaya juga digambarkan sebagai kota pelabuhan, kota dagang dan kota jasa yang besar, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai daerah dan negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena menjanjikan kemakmuran dari segi ekonomi. Citra keteraturan dan kedamaian di bawah kekuasaan Belanda dikontraskan dengan saat pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, dan era kemerdekaan. Kedatangan tentara Jepang memporak-porandakan keteraturan, kedamaian, dan kemakmuran yang telah diciptakan oleh Belanda.
Berita dalam kota sekarang sulit dicari. Sebenarnya kalau pemberitaan longgar seperti dulu, banyak yang bisa ditulis. Pagi-pagi penduduk antre beras. Surabaya sekarang kebanjiran kere, berkeliaran. Tapi mereka mengemis makanan kepada siapa karena penduduk Surabaya sendiri kelaparan? Catu beras per orang per hari tiga ratus gram. Tentu saja itu tidak cukup. Itu pun hanya diberikan kepada penduduk yang terdaftar di Tonarigumi masing-masing. Sedang para kere itu biasanya orang-orang buron yang tidak mau menjadi romusha, tenaga kerja paksa dari desa. Mereka buron di desa, dan mengembara di Surabaya. Tiap hari ada saja ditemukan kere mati di bungker perlindungan di tepi jalan. (Brata, 2005:467).
Ketika Indonesia merdeka, ruang Surabaya digambarkan bertambah buruk. Surabaya dibumihanguskan oleh tentara Inggris dalam perang kota yang mencekam dan menelan banyak korban jiwa pejuang-pejuang Surabaya. Darwan terpaksa kembali ke Surakarta karena Surabaya sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Setelah perang revolusi usai, kedamaian dan ketenteraman seperti pada era kekuasaan Belanda juga tidak tergambar lagi karena terjadi berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan PKI di Madiun akibat perebutan kekuasaan. Di era kemerdekaan, setiap orang atau kelompok saling memaksakan kehendaknya untuk berkuasa: tidak ada yang mau mengalah dan diatur karena semua ingin mengatur dan menguasai yang lain. Orang-orang keliru memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja, sekehendak hatinya, tanpa mempedulikan hukum dan kepentingan orang lain.
3. Simpulan
Reproduksi ideologi kolonial Belanda untuk membangun citra sebagai bangsa yang unggul dan dengan demikian berhak menguasai bangsa lain tampaknya memang berhasil mempengaruhi penduduk jajahan. Bahkan, pengakuan terhadap keunggulan ras kulit putih itu pun masih tertanam di benak masyarakat jajahan meskipun kekuasaan politik mereka telah berakhir. Pada era kemerdekaan yang masih jauh dari kemakmuran dan ketenteraman akibat berbagai konflik, era kolonialisme Belanda mungkin menjadi kenangan yang “menyenangkan” bagi sebagian orang yang pernah hidup pada zaman itu dan kecewa melihat wajah Indonesia kini. Dengan demikian, citra positif Belanda dalam karya prosa Suparto Brata itu juga dapat dimaknai sebagai kritik dan perlawanan terselubung Suparto Brata terhadap keadaan bangsa yang penuh konflik, penegakan hukum yang lemah, dan perebutan kekuasaan di era kemerdekaan ini. Artinya, kemerdekaan yang sesungguhnya belum terwujud, yaitu kemerdekaan dari kebodohan, kemiskinan, dan saling memaksakan kehendak antarkelompok.
Daftar Pustaka
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, Hellen Tiffin, 2003. Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Postkolonial. Terj. Fati Soewandi dan Agus Mokamat. Yogyakarta: CV.Qolam.
Brata, Suparto. 2004. Gadis Tangsi. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara.
Brata, Suparto. 2005. Mencari Sarang Angin. Jakarta: Grasindo.
Brata, Suparto. 2006. Kerajaan Raminem. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Bhabha, Homi K. 1993. The Location of Culture. Routledge: London and New York.
Faruk. 2001. Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan ideologi. Yogyakarta; Gramedia.
Faruk. 2007. Belenggu Pasca-Kolonial: Hegemoni dan Resistensi dalam Sastera Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foulcher, Keith. 1999. “Mimikri Siti Nurbaya: Catatan untuk Faruk” dalam Jurnal Kalam Nomor 14.
Loomba, Ania. 2003. Kolonialisme/Pascakolonialisme. Terjemahan Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang.
Sianipar, Gading. 2004. “Mendefinisikan Pascakolonialisme: Pangantar Menuju Wacana Pemikiran Pascakolonialisme” dalam Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas. (Ed.) Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisius.
Sunaryo. 2004. “Rasisme dalam Hasrat Kolonialisme: Sebuah Studi Pascakolonial” dalam Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas. (Ed.) Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisius.
Untoro, Ratun. 2006. “Pemikiran Suparto Brata dalam Karya-karyanya”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.